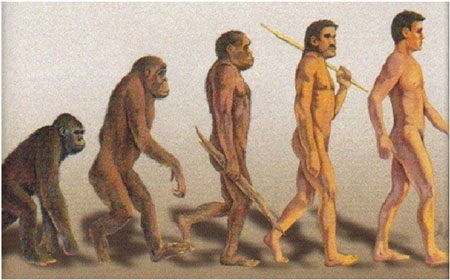“Kami betul-betul memastikan di Jakarta tidak boleh satu pun diterbitkan Perda-Perda syariah. Saya jamin itu nggak boleh ya, ini adalah kota miniaturnya Indonesia…” ~Dajrot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur Jakarta, detik.com, 24 Marer 2017 ~
oleh: Muhammad Iswardani Chaniago
SUASANA agak menegang, Ki Bagus Hadi Kusumo, tiba-tiba menginterupsi rapat: “Saya berlindung kepada Allah dari syetan yang merusak. Tuan-tuan dengan pendek sudah kerapkali diterangkan di sini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisah dari Islam, sebab corak Islam negara dan agama itu sudah diterangkan.. Kalau ideologi negara tidak diterima, tidak diterima!..” (Risalah Sidang BPUPKI, Jakarta: Sekretariat Negara, hal 351)
Itulah penggalan sikap Ki Bagus Hadikusumo dalam BPUPKI soal Islam dan negara. Pernyataan itu keluar menanggapi usul bahwa presiden Indonesia harus beragama Islam. Karena usul itu ditentang sejumlah tokoh, terjadilah perdebatan alot. Muncullah pernyataan tawaran sekaligus sindiran pedas dari Ki Bagus.
Demikian kukuhnya para pendiri bangsa (founding fathers) dari kalangan Islam menghendaki agar Indonesia berdiri berdasarkan Islam. Mengapa demikian kukuh? Jawabannya karena dalam Islam tak ada tempat bagi sekularisme, baik itu gaya anglo-saxon yang dianut Amerika Serikat ataupun french republican seperti yang dibanggakan Prancis. Keduanya tidak pernah terdetik di benak pemimpin Islam awal. Bagi mereka Islam adalah agama secara spritual, emosional maupun norma. Bukan dipecah-pecah, Islam spritual, Islam normatif atau Islam emosional. Persis sebagaimana yang digambarkan Ki Bagus.
Tapi kompromi tetap dilakukan. Singkat cerita, muncullah Piagam Jakarta yang kemudian mengalami sedikit perubahan dengan disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi disertai format Pancasila yang disepakati (Bukan Pancasila Soekarno 1 Juni 1945 seperti yang kerap diaku-aku kelompok sekuler). Tapi menariknya para pendiri bangsa dari kubu Islam tetap bersemangat agar Islam dijadikan dasar negara di forum Konstituante hasil Pemilu 1955.
Apa yang menyebabkan mereka demikian gigih memperjuangkan Islam untuk kali kedua. Apakah mereka tidak menyadari bahwa Indonesia adalah negara majemuk, negara plural, negara beragam? Ataukah para pemimpin Islam itu memiliki hasrat untuk menzalimi agama di luar Islam dengan menetapkan dasar negara adalah Islam?
Pertanyaan sejenis bisa diajukan kepada mereka yang kukuh memperjuangkan syariat dalam lingkup Pancasila. Apakah memperjuangkan klausul dan regulasi islami dalam sebuah sistem nilai Pancasila dapat dikatakan anti keberagaman sebagaimana kerap dituduhkan kelompok sekuler?
Teori Keberagaman
Di Barat teori kemajemukan juga ramai dibahas dan didebat. Adalah Isiah Berlin, filsuf Eropa, yang membuka kran perdebatan saat menulis Four Essays on Liberty. Teorinya tentang value pluralism memancing sejumlah filsuf menanggapi balik, mengkritik atau mendukung.Pertanyaan penting dalam teori keberagaman Barat menyoal bagaimana menyelesaikan masalah kemajemukan yang mengalami konflik konsepsi satu dengan yang lain terutama di ruang pubkik. Padahal keberagaman adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Sejumlah kubu mengajukan teori.
Pertama, kubu liberalis. Sejumlah sarjana seperti John Rawls dan Will Kymlicka menyadari bahwa dunia kontemporer kini semakin plural dan di luar ekspektasi liberalis klasik dulu, sehingga rawan menyuplai konflik ruang publik. Guna mengatasi potensi konflik yang muncul ke permukaan, Rawls menawarkan gagasan reasonable pluralism (atau juga disebut political liberalism).
Adapun Kymlicka menggagas liberal multiculturalism. Inti gagasan keduanya tak jauh beda. Konflik konsepsi yang bisa muncul di ruang publik karena fakta keberagaman harus di atasi dengan cara liberalisme. Hanya saja Rawls tidak menonjol dibandingkan Kymlicka untuk menyebut solusi liberalisme. Tapi yang jelas, doktrin agama, moral dan filsafat tidak bisa masuk dalam ranah politik konstitusional ala Rawls. Yang ada adalah argumen rasional dan penghormatan terhadap hak individu (basic liberties).
Baca: Habib Rizieq: Membenturkan Pancasila dengan Islam adalah
Kedua, Kubu komunitarian juga tak mau kalah. Meskipun awalnya berkonsentrasi pada urgensi nilai-nilai komunal, pengaruh kuat kelompok pada diri individu yang sekaligus mengkritik liberalisme tradisional yang berkutat pada individu. Toh akhirnya, mereka tak bisa membendung efek gagasan mereka yg berdampak pada social pluralism (keberagaman sosial). Terlebih sejumlah tokoh komunitarian juga menggagas hak komunal yang berakibat pada pemberian ruang bagi kelompok guna mengajawantahkan nilai partikular dalam kelompok mereka secara internal. Jelas ini memberikan pengaruh langsung pada ide pluralisme. Lalu bagaimana jika nilai komunal bertentangan dengan nilai-nilai lain? Di negara liberal, para pengusung komunitarianisme menginsafi hal ini. Muncullah gagasan komunitarian baru (new communitarianism). Bagi pengusungnya, seperti Etzioni, nilai-nikai komunal yang beragam tersebut rentan keluar garis dan berubah menjadi relativisme. Untuk itu dibuatlah kesepakatan agar nilai komunal terkontrol. Dibentuklah universalisme, semacam titik temu antar nilai.
Ketiga, kubu liberal petarung. Kubu liberal yang satu ini diwakili Robert Talisse. Ia memandang keberagaman yang tak terelakkan tidak harus disikapi dengan menghilangkan nilai-nilai yang eksis dalam banyak kelompok. Nilai-nilai tersebut malah harus dibiarkan berkontestasi secara sehat dan argumentatif, sehingga tercipta pertukaran argumen di antara para kontestan. Yang perlu diperhatikan hanyalah ciptaan situasi yang dibuat agar tidak terbentuk suasana penghinaan, paksaan, kebohongan dan lainnya.
Yang agak mirip dengan Talisse adalah John Gray. Ia membayangkan dalam lingkungan yang pluralis nilai yang hidup tidak dimonopoli oleh liberalisme, sedangkan non liberal tersingkir. Liberalisme diposisikan bukan sebagai satu-satunya, melainkan salah satu solusi yang tidak bisa sepenuhnya diklaim universalis dibandingkan solusi yang lain. Saat liberalisme mengklaim dirinya universal, maka liberalisme telah merusak pondasi pluralisme.
Baca: Pluralisme Agama
Para penyokong teori keberagaman, baik itu Isaiah Berlin, John Rawls, Ametai Etzioni, Will Kymlicka, Robert Talisse dan John Gray sepakat bahwa bila terjadi benturan antar nilai di ranah publik, maka harus ada solusi penengah. Mereka hanya berbeda dalam rincian solusinya. John Rawls memilih mengosongkan publik dari doktrin (agama, fiksafat dan moral) dan menggunakan kebijakan yang reasonable. Etzioni menggunakan universalisme. Kymlicka memakai prinsip liberalisme sebagai solusinya. Sedangkan Gray cenderung pada modus vivendi.
Negara berbasis Islam dan Teori Keberagaman
Negara berbasis Islam kerap dituduh anti keberagaman hanya karena nilai yang dipakai adalah Islam dan dipandang tidak memberikan ruang pada nilai lain untuk berkontribusi. Tuduhan itu tidak tepat. Karena bila yang dimaksud oleh para penuduh bahwa negara berbasis Islam tidak memberikan ruang pada nilai lain dalam urusan pokok, maka hal itu tidak hanya berlaku untuk negara berbasis Islam. Tapi juga berlaku untuk negara berbasis non Islam, seperti negara berbasis liberal. John Gray, salah satu filosof politik Barat, telah jauh-jauh hari menyadari hal ini. Ia mengkritik liberalisme yang terlalu universalis di tengah beragamnya nilai.
Sikap liberalisme yang memaksa universalismenya ini bisa diraba pada sejumlah gagasan filsuf liberal kontemporer seperti Rawls dan Kymlicka. Ralws menghendaki agar sebuah regulasi dasar kosong dari pengaruh doktrin-doktrin termasuk agama. Hal yang tak terlalu berbeda dengan Kymlicka. Jejak model seperti ini juga bisa ditemukan pada filsuf komunitarianisme. Lalu yang menjadi masalah adalah mengapa telunjuk tuduhan sektarianisme dan anti keberagaman hanya diarahkan kepada negara berbasis Islam dan nyaris tidak pernah kepada negara berbasis liberal?* >> (BERSAMBUNG)