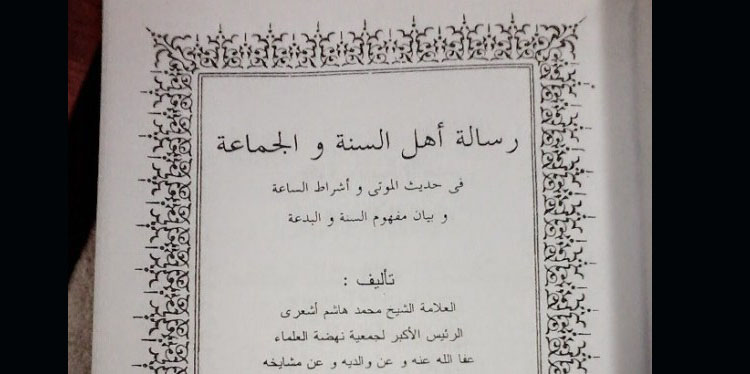Adab bukan sebatas urusan-urusan partikular atau bahkan terkesan “sepele”, melainkan sebuah konsep menyeluruhi pikiran, hati, perasaan, tutur kata serta perbuatan bersifat adil dan pertengahan dikenal wasathiyah
Oleh: Muhamad Ridwan
Hidayatullah.com | ADAB seringkali dipandang sebatas sopan santun atau etika sosial belaka. Misalnya adab mencari ilmu, adab berwudhu dan shalat, adab berteman, adab makan dan minum, adab masuk toilet, dan sebagainya.
Mungkin sebagian dari kita mengira bahwa adab sekadar berkaitan dengan aturan-aturan perkara khusus yang kebanyakan dianggap tak wajib dan bukan syarat sah ibadah, sebagian tidak ada dasar atau dalilnya, cuma tata krama ketika hendak atau sedang beramal, bahkan ada pula. Namun sebenarnya pandangan tersebut kurang tepat.
Oleh sebab itu, kita perlu menyelami bahasan tentang adab untuk menemukan maknanya yang sesungguhnya lantaran konsep ini teramat penting dan mendasar. Menurut Syekh Ibn Manẓūr (t.t.) raḥimahu’llāh dalam Lisān al-ʻArab, kata ini dinamakan “adab ” karena berkaitan dengan mengundang manusia kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat pemuliaan dan mencegah dari apapun yang menyebabkannya tercela. Asalnya dari kata “duʻā’” yang artinya undangan.
Kemudian, suatu jamuan makan dimana orang-orang diundang kepadanya dinamakan “madʻāh” dan “ma’dubah” atau “ma’dabah”, sebagaimana disinggung dalam hadits Ibn Masʻūd raḍiya’llāhuʻanhu:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Sesungguhnya al-Qur’an ini adalah jamuan (ma’dabah) Allah di muka bumi. Maka ambillah ilmu dari jamuan-Nya itu.” (HR: al-Bayhaqī dan ad-Dārimī).
Maksud sabda Nabi ﷺ tersebut yakni al-Qur’an yang kandungannya ilmu, penuh kebaikan serta manfaat adalah ibarat hidangan lezat bagi ruh insan (h. 43). Allah mengundang dan mengaruniakan kita kemuliaan untuk hadir menikmatinya. Namun sebagai tamu dan sifat luhur jamuan tersebut, kita harus datang dengan penuh rasa hormat serta kesucian jiwa raga (Syed al-Attas 1996, h. 57-58). Jadi, dalam suatu adab tersimpul penghormatan.
Sayyid ʻAlī al-Jurjānī (1845, h. 14) raḥimahu’llāh dalam at-Taʻrīfāt-nya mengartikan adab sebagai suatu pengetahuan yang menghindarkan seseorang dari kekeliruan. Imam al-Gazālī (t.t., h. 17) raḥimahu’llāh memaknainya selaku disiplin zhahir dan bathin. Adab juga maksudnya adalah ilmu bahasa dan kesusastraan (Lane 1863, 1: h. 35) karena, kata Profesor Wan Mohd Nor Wan Daud (2003, h. 179)―semoga Allah melindungi dan memuliakan beliau―, di dalamnya terhimpun ajaran-ajaran yang mendidik jiwa manusia dan masyarakat..
Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang sarjana terkemuka abad ini―semoga Allah melindungi dan memuliakan beliau―, melanjutkan faham adab dari ulama pendahulunya sembari menyegarkan tafsirannya. Merujuk penjelasan beliau, adab bersumber dari ilmu yang Allah berikan kepada hamba-Nya mengenai tempat dan kedudukan yang benar dari segala sesuatu. Ilmu inilah yang dinamakan “hikmah” (1996, h. 53) dan jalan untuk mencapai ilmu adalah melalui adab juga (1996, h. 53; az-Zarnūjī 1981, h. 57).
Seorang yang beradab mengejawantahkan hikmah atas dirinya sehingga terpancar hati dan laku berupa pengenalan serta pengakuan akan hakikat susunan derajat semesta wujud secara tepat (al-Attas 1996, h. 53 dan 63). Ia akan menghormati, memuliakan dan mengutamakan setiap yang layak sewajarnya, tidak menyetarakan yang tak sekufu, tidak menempatkan yang berkedudukan rendah di peringkat atas, tetapi juga tidak merendahkan (al-Attas 1993, h. 107 dan 110).
Misalnya, Islam memandang Rasul kemudian ulama memiliki kedudukan tertinggi di antara manusia. Jika ada yang menyejajarkannya setaraf orang biasa atau yang kapasitasnya tak sama, maka pelakunya boleh jadi jahil atau bahkan merendahkan (sombong). Keduanya sama-sama tak beradab (1993, h. 110-111).
Dampaknya bukan main. Ketika mereka yang ilmu dan kemampuannya tak seberapa memandang orang-orang yang lebih unggul dan otoritatif sepadan dengan atau lebih rendah dari mereka, maka muncullah sikap mudah membantah, menyalahkan, mengingkari, bahkan mengorek-ngorek lagi membesar-besarkan khilaf pribadi-pribadi unggul tersebut ketimbang mengangkat jasa-jasanya yang lebih banyak. Keruntuhan adab ini mengakibatkan warisan, tradisi ilmu serta pemahaman orang-orang unggul dan otoritatif itu terkubur dan terputus, digantikan oleh individu-individu yang “sok pakar”.
Ujungnya, merebaklah kerusakan ilmu berupa kebingungan, kesalahfahaman, kesesatan, ekstremisme, kekufuran dan selainnya yang juga memicu kerusakan serta perselisihan di sana-sini. Keadaan ini berlangsung terus-menerus sebab implikasinya adalah kekeliruan memilih pemimpin dan rujukan. Para pemimpin gadungan ini berperan besar dalam melestarikan situasi tersebut (1993, h. 106-132).
Untuk menanggulanginya, pertama-tama kita butuh adab (1993, h. 106). Tetapi, seperti mana telah digambarkan, adab mensyaratkan tertanamnya ilmu yang benar karena pengakuan tanpa pengenalan adalah kejahilan (1996, h. 56). Ilmu ini Allah titipkan pada otoritas yang sah sehingga kita bisa memperolehnya melalui mereka. Kita dapat mengenali mana otoritas yang sah itu bila punya kemampuan membedakan mana yang benar dan yang palsu (1993, h. 106-109).
Kemampuan tersebut berasal dari ilmu pemberian Allah pula yang mengacu kepada hikmah yang melingkupi pengetahuan akan kedudukan diri, orang lain dan segala sesuatu, juga bagaimana menghormati atau memperlakukannya dengan semestinya. Ilmu ini biasanya ditanamkan pada diri seseorang secara bertahap melalui proses yang dinamakan “ta’dīb” (pendidikan/pendisiplinan), maṣdar dari “addaba” (mendidik) (1993, h. 151-152; 1996, h. 60-62). Maka penting sekali kualitas penanam dan apa yang ditanamkannya.
Ilmu itupun harus diamalkan karena pengenalan tanpa pengakuan adalah sama dengan keangkuhan (1996, h. 56). Buahnya adalah keadilan, yakni keadaan ketika segala sesuatu itu berada pada tempat dan kedudukannya yang tepat (1996, h. 53).
Sebaliknya, ketiadaan adab berbentuk kejahilan dan kecongkakan adalah kebiadaban yang akan menghasilkan kekacauan dan kezhaliman (1993, h. 107-108; 1996, h. 75).
Secara singkat, Syed al-Attas menerjemahkan adab sebagai sebuah konsep yang mencakup segenap amalan yang benar (1995, h. 16). Dalam berbagai hal terpancang dua titik batas ekstrem yang pada masing-masing tepiannya terbentang jurang ifrāṭ (terlalu keras) dan tafrīṭ (terlalu abai/enteng/kurang).
Adab atau amalan benar yang telah dicontohkan di atas boleh dikata adalah merupakan suatu pemahaman, tabiat serta perbuatan yang wajar, terletak di pertengahan antara titik ekstrem tersebut dan tidak condong terhadap keduanya. Di antara aqidah, akhlaq dan ibadah ada yang melenceng ke arah salah satu jurang ekstrem itu.
Adab pun adalah menemukan dan memilih posisi seimbang yang terdiri dari aqidah yang lurus, akhlaq mulia, serta amalan ibadah yang sah. Adab juga meliputi epistemologi yang benar, yakni mengetahui dan mengakui sumber-sumber ilmu yang valid, tanpa mengingkari wahyu maupun tanpa mengiyakan agnostisisme, relativisme dan skeptisisme.
Pada tataran ontologi, manifestasi adab adalah meletakkan makna atau hakikat dan kebenaran secara tepat, tidak menganut materialisme, pluralisme agama, maupun dualisme antara wahyu dengan tafsir, sains dengan agama, objektif dengan subjektif, dan sebagainya. Sedangkan dalam wilayah aksiologi, kita beradab jika berpegang pada nilai serta tujuan yang betul, tidak menepikan pesona Tuhan dari alam dan ilmu, tidak pula mengamini doktrin relativisme moral dan etika.
Demikian seterusnya hingga merambah perihal-perihal yang disebut di awal. Bahkan, cara meletakkan al-Qur’an dan buku pun ada adab-nya.
Wasathiyah
Berdasarkan pemaparan serta contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa definisi adab yang diutarakan oleh para ulama, yaitu tindakan yang benar, pengetahuan yang menjaga kita dari kekeliruan, keteraturan zhahir bathin, menempatkan sesuatu secara tepat, serta penghormatan terhadap sesuatu, terutama pada otoritas ilmu, semuanya senafas dan saling terjalin satu sama lain.
Penguraian adab berupa hal-hal khusus adalah penting guna memberitahu kita bagaimana bentuk tindakan yang patut di setiap keadaan. Tetapi, kita mesti melihat adab bukan sebatas urusan-urusan partikular atau bahkan terkesan “sepele” saja, melainkan sebagai sebuah konsep yang menyeluruhi pikiran, hati, perasaan, tutur kata serta perbuatan bersifat adil dan pertengahan yang kita kenal dengan istilah wasathiyah.
Agar insan akhir zaman beradab, Allah menurunkan satu-satunya agama yang wasathiyah, yaitu Islam. Wahyu serta sunnah Rasul-Nya adalah sumber hikmah dan kebenaran. Umat yang memeluk serta menjalankannya disebut sebagai Ummatan Wasaṭan (QS. al-Baqarah 143), menyandang gelar sebagai umat yang adil dan terbaik (QS. Alī ʻImran 110; Ibn Manẓūr t.t., h. 4831-4833; ar-Rāzī 1981, 4: h. 107-108; az-Zuḥaylī 2001, h. 64-65). Sebab itu, apabila kita mau beradab dan termasuk ke dalam Ummatan Wasaṭan alias umat terbaik, jalannya ya berIslam.
Dengan demikian, jelaslah bahwa adab sangat bertalian dengan agama, bahkan bersumber darinya. Lantaran itu boleh kita simpulkan, ketika seseorang menerima kebenaran, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang benar, yaitu Allah Subḥānahu Wa Taʻālā, berakhlaq mulia, berserah diri menaati segala perintah serta menjauhi segala larangan Dia dan Rasul-Nya ﷺ mengikuti tradisi ilmu serta pemahaman ulama, maka ia telah bersikap ilmiah, hormat dan benar alias meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Itulah manusia yang adil dan beradab. Allāh aʻlam bi’ṣ-ṣawāb.*
Manajer program Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN)
DAFTAR PUSTAKA
- Al-Qur’ān al-Karīm
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- 1995. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.
- 1996. Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka-Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam. Diterjemahkan oleh Haidar Bagir. Bandung: Mizan.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas. Diterjemahkan oleh Hamid Fahmy Zarkasyi, M. Arifin Ismail, dan Iskandar Amel. Bandung: Mizan.
- Al-Gazālī, al-Imām Abū Ḥāmid. T.t. Rawḍah aṭ-Ṭālibīn wa ʻUmdah as-Sālikīn. Beirut: Dār an-Nahḍah al- Ḥadītsah
- Al-Jurjānī, Sayyid ʻAlī bin Muḥammad. 1845. Kitāb at-Taʻrīfāt. Editor: Gustavus Flügel. Leipzig: Typis Guil, Vogelii, Filii.
- Lane, Edward William. 1863. Arabic-English Lexicon, Derived From The Most Copious Eastern Sources. Jilid 1. London & Edinburgh: Williams And Norgate.
- Ibn Manẓūr. T.t. Lisān al-‘Arab. Kairo: Dār al-Maʻārif.
- ar-Rāzī, Imam Fakhru’d-dīn. 1981. Tafsīr al-Fakhr ar-Rāzī al-Musytahir bi at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Gayb. Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr.
- Az-Zarnūjī, Burhān al-Islām. 1981. Kitāb Ta‘līm al-Muta‘allim Ṭarīq at-Ta‘allum. Taḥqīq: Marwān Qabānī. Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī.
- az-Zuḥaylī, Wahbah. 2001. at-Tafsīr al-Wasīṭ. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Sayyid ʻAlī al-Jurjānī (1845, h. 14) raḥimahu’llāh dalam at-Taʻrīfāt-nya mengartikan adab sebagai suatu pengetahuan yang menghindarkan seseorang dari kekeliruan. Imam al-Gazālī (t.t., h. 17) raḥimahu’llāh memaknainya selaku disiplin zhahir dan bathin.
- Adab juga maksudnya adalah ilmu bahasa dan kesusastraan (Lane 1863, 1: h. 35) karena, kata Profesor Wan Mohd Nor Wan Daud (2003, h. 179)―semoga Allah melindungi dan memuliakan beliau―, di dalamnya terhimpun ajaran-ajaran yang mendidik jiwa manusia dan masyarakat.