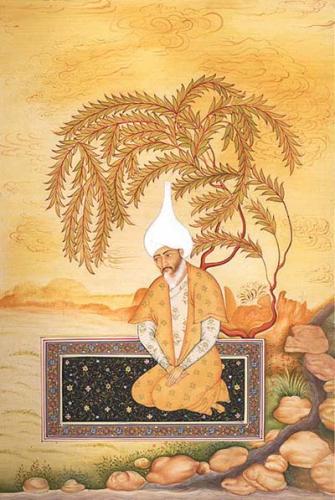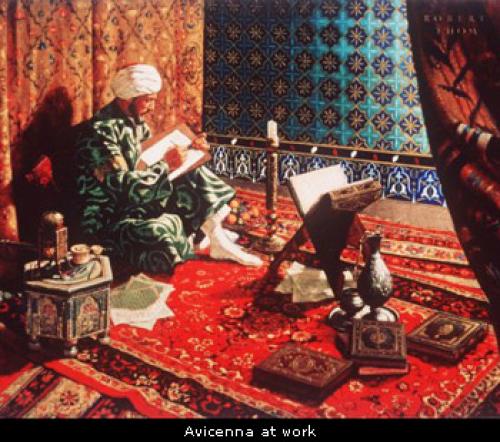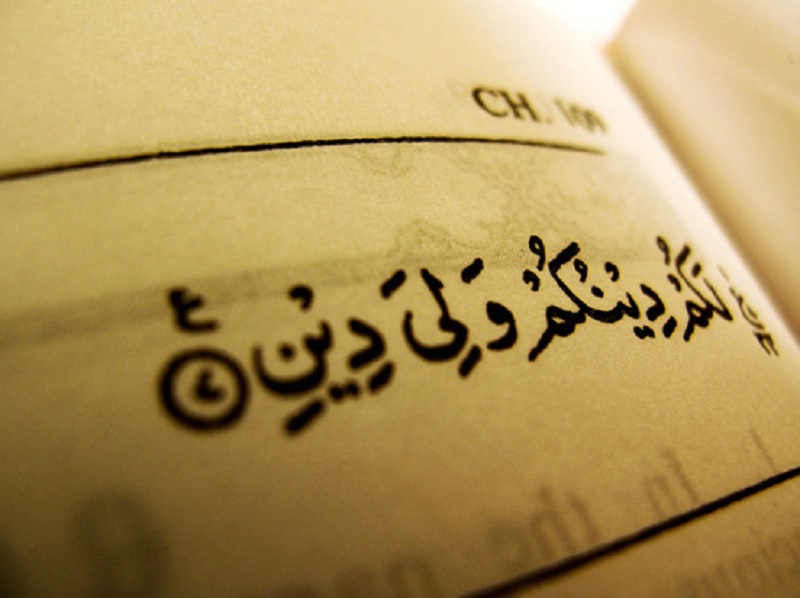Penerapan hukum pembuktian terbalik dalam fiqih tidak bertentangan dengan syari’at Islam; bahkan syari’at mengharuskannya jika hal itu menjadi salah satu langkah politik yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat
Hidayatullah.com | BEBERAPA tahun lalu DPR pernah mengeluarkan wacana pembuktian terbalik sebagai rancangan undang-undang dalam rangka memberantas korupsi. Wacana ini menjadi menarik sekali untuk dikaji dengan mengkomparasikan konsep-konsep Islam sebagai al-nizham wa al-dustur dalam hubungan manusia baik yang bersifat horizontal antar sesama maupun yang vertikal dengan Sang Khaliq seperti yang tertuang dalam disiplin ilmu fiqih.
Persoalan yang perlu dikaji di sini ialah apakah pembuktian terbalik sejalan dengan fiqih Islam sehingga ada legalitas hukum untuk menerapkannya atau bahkan sebaliknya? Atau dalam bahasa yang sederhana, bolehkah dalam pandangan Islam menerapkan undang-undang pembuktian terbalik terhadap pejabat atau eks pejabat – yang dituduh korupsi- untuk tujuan memberantas korupsi, di mana korupsi telah menjadi penyakit yang kronis dan menjalar dalam berbagai institusi negara serta menjadi ancaman serius bagi perjalanan bangsa menuju masa depan yang cerah?
Dari sini ada langkah yang sangat jitu, pejabat atau eks pejabat yang dicurigai korupsi harus membuktikan dirinya sebagai orang yang bersih. Di sini kami diminta untuk menjawab pertanyaan apakah pembuktian terbalik sejalan dengan fiqih Islam?
Dan apakah tidak bertentangan dengan hadits nabi,
“Seandainya manusia diperkenankan untuk menuntut, niscara mereka akan menuntut darah dan harta orang lain. Akan tetapi yang menuntut harus menunjukkan bukti dan orang yang dituntut harus bersumpah.” (HR Bukhari).
Menjawab pertanyaan pertama, apakah pembuktian terbalik yang akan diperlakukan kepada pejabat atau eks pejabat yang dicurigai korupsi itu sejalan dengan fiqih Islam? Ada dua pendekatan yang diberikan oleh al-Madzhaib al-Tsalatsah (Madzhab yang tiga; Hanafi, Maliki dan Hanbali) yaitu pendekatan dengani konsep, “al-qadha’ bima yazh-haru min qara’in al-ahwal wa al-amarat (keputusan hukum yang didasarkan pada indikasi-indikasi kondisional dan tanda-tanda yang zahir)”.
Konsep al-Madzahib al-Tsalatsah ini adalah bermaksud pada keputusan hakim atau jaksa yang tidak didasarkan bukti yang diajukan oleh penuntut (bayyinatu al-mudda’iy) atau sumpah yang disampaikan oleh pihak yang dituntut (yaminu al-mudda’a ‘alayhi); akan tetapi didasarkan kepada qara’in al-ahwal wa al-amarat al-zhahirah (karenah-karenah tradisi dan tanda-tanda yang jelas).
Konsep ini mula-mula berangkat dari al-qa’idah al-ushuliyyah-nya Imam Malik yang menerima munasib mursal atau al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil yang menganggapnya mu’tabar, pula tidak memiliki dalil yang menganggapnya dibuang [mulgha]) sebagai salah satu illat dalam menetapkan hukum.
Akan tetapi meski konsep awal dari sistim ini berangkat dari pendapat al-Imam Malik, konsep ini menjadi termodifikasi secara lebih luas dalam pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Hanbali (wafat 751 H) dalam bukunya al-Thuruq al-Hukmiyyah dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Farhun al-Maliki (799 H) dalam bukunya Tabshirat al-Hukkam, dan lalu oleh al-Tharabulisi al-Hanafi dalam Mu’in al-Hukkam.
Dalam konsep ini, seseorang bisa dijerat dengan hukum tanpa harus ada bukti-bukti yang jelas, akan tetapi didasarkan pada tanda-tanda yang jelas kepada seorang hakim. Termasuk dalam konteks ini adalah kasus yang menimpa Nabi Yusuf as, ia dinyatakan sebagai pihak yang benar dengan karenah apabila bajunya robek di bagian belakang, dan dinyatakan sebagai pihak yang bersalah apabila bajunya robek di depan, tanpa harus ada saksi atau sumpah.
Atau juga seperti penjual minyak wangi apabila berselisih dengan penyamak kulit dalam suatu kulit, maka yang didahulukan adalah tukang samak itu, karena alasan profesi. Contoh ini adalah keputusan hukum yang didasarkan kepada amarat zhahirah.
Bisa dianalogikan dengan contoh di atas, jika ada pejabat atau eks pejabat yang kekayaannya tidak wajar dengan bayarannya, mungkin suatu amarah awwaliyah yang masih perlu diproses lebih lanjut bahwa ia telah menyalahgunakan jabatannya. Kembali kepada pokok persoalan, berangkat dari konsep di atas kami memposisikan pejabat atau eks pejabat sebagai terdakwa korupsi dengan alasan memiliki kekayaan yang tidak wajar dengan bayarannya.
Dengan adanya qarinah atau amarah zhahirah berupa jabatan yang berpeluang menjadi tempat transitnya keuangan negara yang dikeruk untuk kepentingan pribadi dalam status korupsi, maka menjadikan yang bersangkutan sebagai muttaham (dicurigai) menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengeruk keuntungan pribadi tersebut.
Kedua adalah pendekatan politik (al-siyasah al-syar’iyyah). Artinya keputusan hukum atas dasar siyasah syar’iyyah.
Menurut Ibnu al-Qayyim dan kemudian dinukil oleh mazhab-mazhab yang lain, siyasah ada dua macam; pertama, siyasah yang dzalim, maka syara’ melarangnya; dan kedua siyasah yang adil, yang dapat mengeluarkan hak dari seorang yang dzalim, menolak banyak penyelewengan (termasuk korupsi), menakut-nakuti mereka yang senang berbuat kerusakan dan bisa menjadi perantara pada al-maqashid al-syar’iyyah, maka syari’at Islam mengharuskannya dalam upaya menegakkan kebenaran.
Ini adalah pintu yang luas yang banyak menyesatkan pemahaman-pemahaman. Meninggalkannya dapat menelantarkan hak-hak dari pemiliknya, memberikan peluang kepada kalangan gemar berbuat kerusakan untuk menjarah hak-hak orang lain.
Salah satu contoh pendekatan politik ini adalah apa yang dilakukan oleh Sayidina ‘Ali bin Abi Thalib, ketika ada seorang yang melaporkan beberapa orang, “Mereka pergi bersama ayah saya, lalu mereka kembali, sedang ayah saya tidak kembali. Lalu aku bertanya kepada mereka mengenai ayah saya, mereka menjawab, “Ayahmu telah mati”. Lalu aku menanyakan tentang harta ayahku yang banyak, mereka menjawab, “Ayahmu tidak meninggalkan apa-apa”. Lalu kami laporkan mereka kepada Qadi Syuraih, lalu Qadi menyumpah mereka dan kemudian melepasnya karena mereka bersumpah”. Lalu ‘Ali memanggil beberapa polisi untuk menangkap mereka. Tiap-tiap orang dipegang oleh dua polisi. Ali berpesan kepada mereka agar jangan sampai mereka berbincang-bincang dengan temannya. Ali memanggil sekretarisnya, lantas memanggil seseorang dari mereka. Ali berkata kepadanya, “Kamu ceritakan tentang ayah anak ini; pada hari apa keluar bersama kalian; di tempat mana ia beristirahat bersama kalian, bagaimana ia berangkat dengan kalian, dengan penyakit apa ia meninggal, apa yang menimpa hartanya, siapa yang memandikan dan menguburkannya, siapa yang menjadi imam shalatnya, dan dimana dikuburkan?”. Sekretarisnya menulis apa jawabannya. Kemudian ganti satunya untuk ditanyakan sampai akhirnya selesai. Ternyata jawaban mereka berbeda-beda. sehingga pada akhirnya dibunuhlah mereka itu.
Apa yang dilakukan oleh Qadhi Syuraih adalah benar adanya secara hukum syari’at, tetapi secara politik tindakan tersebut tampak sekali kelemahannya dalam upaya mengungkap fakta dan kebenaran. Dari sini al-Madzahib al-Tsalatsah seperti yang dikatakan al-Qarafi memberi keleluasaan dalam pendekatakan politik, “Pemberian keleluasaan terhadap para hakim dalam al-siyasah al-syar’iyyah tidak menyalahi syari’at, bahkah dibenarkan oleh banyak dalil-dalil; yang di antaranya semakin banyak dan meuasnya kerusakan di bumi, berbeda dengan kurun pertama. Konsekuensinya, lahirnya hukum-hukum yang berbeda yang tanpa keluar dari syari’at secara partikular.”
Apa yang dikatakan oleh al-Qarafi ini terbukti dengan penerapan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu. Seperti dalam kasus Ibnu al-Lutbiyyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwasanya Nabi ﷺ mengutus Ibnu al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di kabilah Bani Sulaim.
Setelah datang kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menghitungnya, Ibnu al-Lutbiyyah berkata, “Ini yang untuk kalian, dan yang ini untuk saya sebagai hadiah dari mereka.”
Mendengar ungkapan ini Rasulullah ﷺ bersabda, “Coba saja kamu duduk di rumah ayah dan ibumu sehingga datang hadiah ini jika kamu memang benar”. (calam Fath al-Bari juz 15 hal 98).
Hukum ini mengalami eskalasi (peningkatan) pada masa Sayidina ‘Umar Bin Khaththab, ketika seorang amilnya pulang ke Madinah dengan membawa harta yang sangat banyak sekali. Beliau membagi harta itu secara paruhan, separuh harus diserahkan kepada negara (baitul mal) dan separuh untuk dirinya, hal ini masih dalam konteks pendekatan politik.
Dalam pendekatan politik ini pula al-Madzahib al-Tsalatsah menetapkan hukum al-da’awi bi al-tuham wa al-’udwan (didakwa yang disebabkan tuduhan dan permusuhan). Di sana disebutkan bahwa terdakwa yang disebabkan tuduhan (al-mudda’a ‘alayhi bi al-tuham) ada tiga golongan:
Pertama, terdakwa yang bersih dari tuduhan tersebut; bukan termasuk golongan yang melakukan apa yang dituduhkan itu. Terdakwa dalam status seperti ini tidak boleh disiksa, sedangkan yang mendakwa terhadapnya harus disiksa.
Kedua, terdakwa yang sampai pada status tertuduh dengan perbuatan mesum (fujur) seperti mencuri, merampok, membunuh dan berzina. Terdakwa semacam ini harus diungkap dan diselidiki secara mendalam sesuai dengan kadar tuduhan dan kemasyhurannya dengan tuduhan tersebut.
Bahkan penyelidikan bisa ditingkatkan pada pemukulan dan penahanan, atau ditahan tanpa dipukul sesuai dengan popularitasnya dalam tuduhan itu. Menurut Ibnu al-Qayyim, “Saya tidak mengetahui seseorang dari kalangan imam-imam muslimin berpendapat, bahwa tersangka dalam status ini disumpah lalu dilepas tanpa ditahan atau lainnya. Menyumpah dan melepas orang seperti ini bukanlah madzhab al-A’immah al-Arba’ah dan yang lainnya. Dan seandainya kita menyumpahnya lalu melepasnya, sedangkan ia telah dimaklumi terkenal dengan berbuat kerusakan di bumi serta banyak curian-curiannya dan kita berdalil, “kita tidak menangkapnya kecuali dengan dua saksi yang adil”, maka tindakan ini telah menyalahi al-siyasah al-syar’iyyah. Barangsiapa yang berasumsi bahwa menurut syara’ adalah menyumpahnya lalu melepasnya, maka ia telah bersalah dengan kesalahan yang buruk dan menyalahi terhadap nushush Rasulullah ﷺ, menyalahi ijma’ al-ummah,” demikian kata Ibnu al-Qayyim yang juga dinukil oleh Ibnu Farhun.
Ketiga, terdakwa dengan status tertuduh yang tidak diketahui haliyahnya. Penguasa tidak mengetahui apakah ia baik-baik atau tidak.
Apabila ia didakwa dengan suatu tuduhan, maka harus ditahan sampai terungkap haliyahnya. Ini adalah hukum yang disepakati oleh kebanyakan ulama Islam.
Di sini pihak berwenang bisa menetapkan dakwaan kepada pejabat atau eks pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar; dengan alasan muttaham sebab kekayaannya itu. Vonis muttaham bagi pejabat tersebut adalah pada tempatnya; jika kita melihat bahwa pejabat merupakan transit keuangan negara dan berbagai kepentingan masyarakat; sehingga peluang untuk mengeruk kepentingan pribada sangat besar.
Status ini adalah seperti yang dilakukan oleh Khalifah ‘Umar di atas terhadap amilnya yang kaya itu. Dalam analogi fiqih; seseorang tidak bisa menjadi saksi yang menguntungkan orang tuanya atau anaknya; karena dalam kesaksiannya yang mempunyai hubungan bapak-anak menjadikannya sebagai muttaham.
Di sini kiranya dapat diberikan kesimpulkan bahwa penerapan undang-undang pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan syari’at Islam; bahkan syari’at mengharuskannya jika hal itu menjadi salah satu langkah politik yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat.
Apa yang dilakukan oleh Khalifah ‘Umar dan Khalifah ‘Ali di atas barangkali bersubstansi sama dengan pembuktian terbalik ini. Kiranya tulisan ini sangat singkat serta banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk lebih jelasnya, dipersilahkan membaca referensi-referensi yang tercantum. Wallahu a’lam bish-shawab.*/M Idrus Romli, diambil dari laman sidogiri tahun 2002.
Al-Maraji’ wa al-Mashadir:
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il, al-Jami’ al-Shahih, Dar El Fikr, Beirut. 1993
- Al-’Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Dar El Fikr, Beirut, 1993.
- Ibnu Farhun, Abu al-Wafa Ibrahim bin Muhammad al-Ya’muri, Tabshirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam, Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, Beirut, 1995.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-Hanbali, Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, Rabitah Ma’ahid Islamiyyah, Surabaya, tt.
- Al-Tharabulisi, ‘Ala’uddin ‘Ali bin Khalil al-Hanafi, Mu’in al-Hukkam fima Yataraddadu Bayna al-Khashmayni mina al-Ahkam, Dar El Fikr, Beirut, tt
- Al-Tasuli, ‘Ali bin ‘Abdussalam, Al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah, Dar El Fikr, Beirut, tt
- Al-Wa’iy, Dr. Taufiq, Al-Dawlatu al-Islamiyyah, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1416 H.
- Al-Qarafi, Al-Furuq,
- Al-Maliki, Muhammad ‘Ali bin Husain al-Makki, Tahdzib al-Furuq, Hamisy al-Furuq.
- Al-Zarqa’, Mushthafa Ahmad, Al-Madkhal al-Fiqhiyy al-‘Amm; al-Fiqh al-Islamiy fi Tsaubihi al-Jadid, Dar EL Fikr, Beirut, tt.
- Al-Zuhaili, Dr. Wahbah bin Mushthafa, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus, Dar El Fikr al-Mu’ashir,
- Al-Maliki, Muhammad ‘Ali bin Husain, Qurratu al-‘Ayn fi Fatawa ‘Ulama’ al-Haramayn, Dar Ihya’, Cairo.
- Al-Lubnani, Salim Rustum Baz, Syarh al-Majallah, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, tt
- Haidar, ‘Ali, Durar al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, tt