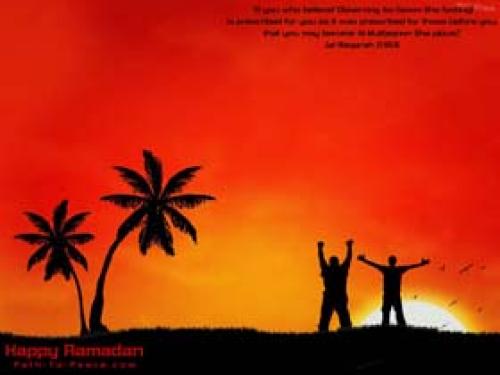Apakah yang menjadikan Fir’aun, Qarun, Abu Lahab dan Abu Jahal mendustakan kebenaran?
Bukan karena mereka tidak cerdas, tetapi seperti yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, mereka telah berdiri di atas prinsip kerasionalan (cocok dengan akal), sehingga menutup mata hatinya dari dekapan cahaya Ilahi.
Qarun misalnya, sebagai sosok yang diceritakan secara spesifik di dalam Al-Qur’an, berani mengatakan bahwa harta benda yang dimilikinya adalah hasil jerih payah dan keahliannya. Jadi tidak ada pihak yang bisa mengatur kehidupannya, apalagi ada peraturan yang mengharuskannya berbagi, peduli dan lain sebagainya, meski itu Tuhan sekalipun.
قَالَإِنَّمَآأُوتِيتُهُۥعَلَىٰعِلۡمٍعِندِىٓۚ
“Qarun berkata: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku.” (QS. Al-Qashshash [28]: 78).
Pernyataan Qarun sepintas benar, padahal mutlak salah. Mengapa?
Dia tidak sadar bahwa kesehatan yang ada pada dirinya bukanlah karena kepintarannya dalam ilmu medis, singkat kata, dokter pun mati. Padahal tanpa kesehatan, ia tak mungkin mampu berniaga menghasilkan banyak harta.
Jika kesehatan diri saja di luar kendalinya, bagaimana dengan hidup, bahagia dan sulit. Sedangkan tidak sedikit manusia yang hidup susah justru karena banyaknya harta yang diperhitungkan terus menerus. Dan, betapa banyak orang yang bahagia tanpa memiliki perbendaharaan harta secara berlebihan.
Tetapi, karena mata hati tertutup, dan kecongkakan telah membumbung di ubun-ubunnya, Allah pun menenggelamkannya. Dan, inilah bukti bahwa rasio benar-benar terbatas, yang siapa saja menjadikan kaki dalam kehidupannya, pasti akan rapuh dan menyengsarakan.
Berbeda dengan pandangan seorang Urwah bin Az-Zubair, pemilik kebun kurma yang sangat rindang lagi lebat buahnya di Madinah. Ia berkata, “Harta ini milik Allah, jika ada ketamakan untuk mendapatkannya maka itu sekadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer saja. Harta ini milik allah, rezeki itu berasal dari-Nya dan akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh-Nya.”
Lebih jauh, putra Zubair bin Awwam itu berkata, “Siapakah orang di atas muka bumi ini yang menanam pohon lalu dia mampu menemtukan jumlah panennya? Sesungguhnya, seluruh umat manusia hanya mampu mengerahkan usahanya saja, sedangkan buahnya berasal dari Allah.”
Di sinilah umat Islam memerlukan pandangan hidup Islam agar tidak terjebak pada apa yang sebenarnya memang dangkal dan sudah pasti mendatangkan keburukan dalam kehidupan, sehingga lahir kedermawanan, bukan untuk mendapat pujian dan pengaruh, tetapi benar-benar ingin ridha dari Allah Ta’ala.
Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anh pernah berpesan melalui surat kepada para panglima perangnya, “Jagalah apa yang kalian dengar dari orang-orang yang taat (taqwa). Sebab sesungguhnya tampak jelas bagi mereka perkara-perkara yang benar.”
Dari sini kita patut merenungkan apa yang disampaikan oleh Abu Yazid yang dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab monumentalnya, Ihya Ulumuddin.
“Orang yang alim itu bukan hanya orang yang menghafal kitab Allah. Lalu apabila lupa terhadap apa yang telah dihafalnya, maka ia tidak serta-merta menjadi bodoh. Sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang mengambil ilmu dari Rabb-nya, dan mengamalkan ilmu dimaksud di seluruh waktu yang dikehendaki-Nya, tanpa harus menghafal atau belajar (secara konvenional).”
فَوَجَدَاعَبۡدً۬امِّنۡعِبَادِنَآءَاتَيۡنَـٰهُرَحۡمَةً۬مِّنۡعِندِنَاوَعَلَّمۡنَـٰهُمِنلَّدُنَّاعِلۡمً۬ا
“Dan ang telah Kami (Allah) ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (QS. Al-Kahfi [18]: 65).
Ibn Hajar Al-Atsqalani adalah satu dari sekian hamba Allah yang mendapatkan ilmu dengan cara yang Allah kehendaki bagi-Nya. Sekelebat pemikiran tentang batu yang berlubang karena tetesan air yang konsisten menjadi sebba terbuka mata hatinya, sehingga muncul keikhlasan atas apa yang selama ini dijalani dengan tanpa mendapat ilmu dari sang guru, ia kembali belajar dan kemudian menjadi seorang ulama yang menyinari kehidupan umat Islam hingga saat ini.
Bisa dibandingkan dengan mereka yang cemerlang sejak belajar, kemudian di kala mereka berbaur dengan masyarakat, alih-alih menghadirkan lentera di tengah-tengah kehidupan umat manusia, adab dan perilakunya pun sudah ditukar dengan beragam gelar dan jabatan dunia, sehingga bukan saja mereka terpental dari jalan kebenaran, malah mereka juga mengatakan tidak ada kebenaran itu. Mereka memahami toleransi dengan menggadaikan agama, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, memaknai kebenaran dengan hawa nafsu, dan melihat Islam seperti orang-orang jahiliyah memandang Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam. Na’udzubillah.
Oleh karena itu, dalam situasi seperti sekarang –bahkan sampai hari kiatam– dimana agama akan dibuat persenda-gurauan, dilecehkan, dinista dan terus-menerus didiskreditkan– kita harus bisa rasional dalam diri kita sebagai kendaraan untuk semakin taqwa, berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Hanya dengan itulah, rasio akan memberikan manfaat terbaiknya.
Jika menggunakan akal kita saat ini, mungkin kita akan mencela junjungaan kita Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam mengapa beliau memerintahkan perang terhadap kaum Yahudi dari Bani Qoinuqa di Madinah terjadi setelah perang Badar hanya gara-gara ada jilbab muslimah di Madinah dilecehkan.
Akibat kasus pelecehan ini Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam mengumpulkan tentara dan memberikan bendera perang kepada Hamzah bin Abdul-Muththalib. Ketika melihat reaksi kaum Muslimin ini, orang-orang Yahudi segera berlindung di balik benteng-benteng mereka. Pasukan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam mengepung mereka dengan rapat selama 15 hari pada bulan Syawal hingga awal Dzulqaidah tahun 2 Hijriah.
Apakah itu rasional? Jika Rasulullah hidup di saat seperti ini, mungkin kita akan ramai-ramai membuat rilis dan pernyaan di media massa, bahwa aksi ini ditunggangi kelompok radikal dan kita mencuci tangan dengan mengatakan, “mereka radikal, kamilah moderat!”
Karena itu, jangan pernah dipahami rasio musuh dalam Islam atau rasio orang-orang munafiq. Sebaliknya, Islamlah yang menjadikan rasio manusia bermanfaat. Seperti nasehat Sayyidina Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu kepada kita semua, “Orang yang berakal itu adalah orang yang meninggalkakn hawa nafsunya dan menjual dunianya dengan akhiratnya.” Wallahu a’lam.*