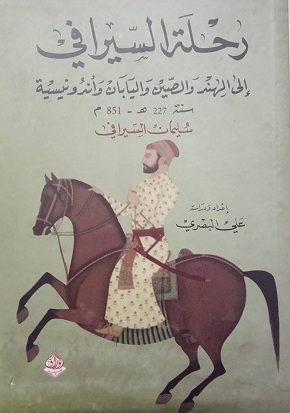Hidayatullah.com | “Tuan-tuan boleh tembak saya, tembak saya, tembak saya! Tetapi, mengakui suatu perbuatan yang tidak saya kerjakan berarti munafik dan ini dilarang Allah!” Demikian teriak Mr. Kasman Singodimedjo, saat diinterogasi berjam-berjam pada bulan Ramadhan oleh polisi, atas tuduhan fiktif yang tak pernah beliau lakukan.
Kejadian lain, S. Soemarsono ketika ditahan dengan tuduhan politis, saat sakit, bukan dirawat di rumah sakit layak, tapi dibawa ke rumah sakit jiwa. Waktu itu, para dokter mengira dia orang gila.
Sebelum Soemarsono, malah Kiai Ma’shum Yogyakarta, saat sakit dalam tahanan juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang sama. Ia tidak dipedulikan, bahkan matinya tak diketahui banyak orang.
Gazali sahlan, pada momen puasa juga, ditahan di Sukabumi. Beliau disiksa sedemikian rupa, hingga pingsan berkali-kali. Bahkan, kemaluannya sempat distroom dengan listrik oleh petugas (tambahan ini bisa dibaca dalam buku: “Hidup Itu Berjuang” [1982]).
Beberapa contoh itu disebutkan Deliar Noer dalam buku beliau yang berjudul “Bunga Rampai dari Kangguru” (1981: 228, 229). Sebuah gamparan singkat tentang penjara zaman Demokrasi Terpimpin, yang mana lawan politik saat itu dihancurkan dengan memberi tekanan spiritual, mental dan fisik.
Tak hanya itu, seorang yang tertuduh bisa diambil tengah malam, subuh pagi, atau siang bolong tanpa berita. Saat dipenjara mereka diinterogasi berjam-jam dan ditempatkan di sell yang tak layak untuk tahanan politik.
Mereka ini adalah tahanan politik, dalam kasus yang belum terbukti bersalah. Bahkan ada yang belum dibawa ke pengadilan kasusnya. Namun, mereka telah mengalami berbagai getir penderitaan yang tak seharusnya didapat. Ini adalah gambaran singkat ketika demokrasi dikebiri dan dijadikan senjata untuk membungkam lawan-lawan politik.
Hal senada, terdapat dalam buku “Kenang-Kenangan di Belakang Terali Besi di Zaman Orla” (1967: 68) karya Yunan Nasution, dikisahkan oleh Yunan Nasution penderitaan rekan setahanannya yang dikenal dengan sebutan “Napoleon Masyumi” (KH. Isa Anshari).
Pada umumnya, saat dipenjara di Jakarta, para tahanan politik waktu itu diperlakukan sebagaimana tahanan biasa. Fasilitas yang diberikan tidak jauh beda dengan tahanan kriminal.
Tak terkecuali dalam fasilitas kesehatan yang disediakan cukup terbatas. Pernah suatu sore KH. Isa Anshary jatuh sakit. Kondisi cukup parah, namun masih dihadapkan dengan brirokasi penjara yang rumit, harus ada surat dokter yang ditunjuk untuk itu.
Ternyata, dokter yang bersangkutan sedang berada di luar RTM, sejauh 2 kilometer (sekitar Kebon Sirih). Akhirnya, KH. Isa ditandu oleh petugas ke tempat itu. Malangnya, hingga malam dokter yang ditunggu tak juga datang. Akhirnya, jam sepuluh malam, beliau dibawa kembali ke RTM.
Bayangkan, kondisi sakit parah dan perlu segera mendapat perawatan yang lekas, malah mendapatkan pelayanan demikian. Anda bisa merasakan betapa susahnya yang beliau hadapi kala itu. Beliaupun baru bisa dirawat esok harinya.
Masih pada Era Demokrasi Terpimpin, Yunan Nasution dkk (waktu itu bersama Mohamad Roem, Prawoto, Sutan Sjahrir, Mochtar Lubis dll) dipenjara oleh rezim dengan kesalahan yang tak begitu jelas dari segi hukum.
Peristiwa ini diceritakan oleh Yunan Nasution dalam buku “Kenang-Kenangan di Belakang Terali Besi di Zaman Rezim Orla” (1967: 37). Pada tanggal 16 Januari 1962, pukul setengah empat menjelang fajar beliau dijemput aparat dan keumudian dijebloskan ke terali besi.
Awalnya beliau ditahan di markas CPM di Jalan Hayam Wuruk (Jakarta), kemudian dipindah ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Cimanggis, lalu LP Madiun (22 Desember 1962), dan dipindah lagindah lagi ke Jakarta (Oktober 1965). Beliau baru bebas pada 15 Februari 1966. Begitulah singkatnya, beliau dipenjara selama empat tahun lebih.
Setelah masa penahanan usai, dan tidak ada bukti kuat, seharusnya Yunan dibebaskan. Namun, untuk menjerat beliau dan kawan-kawan yang waktu dianggap oposisi dan kontra Demokrasi Terpimpin, maka dipakailah pasal 32 PPUUKB disertai pasal 43 yang berbunyi, “Penguasa Perang berhak dengan surat keputusan menundjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petundjuk2 bahwa ia akan mengganggu keamanan, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam untuk sementara dan membawanja ke situ.”
Di situ sudah tidak lagi memakai kata “ditahan” tetapi ditunjuk tempat tertentu sebagai “tempat berdiam”. Terkait hal ini Yunan mencatat, “Alasan atau motif jang dipakai bahwa ‘terdapat petundjuk2 bahwa seseorang akan mengganggu keamanan umum’ adalah suatu sendjata sematjam undang-undang karet, jang dapat diulur-ulur, dapat diperpandjang atau diperpendek, menurut pertimbangan jang berwenang.” (1967: 37)
Di sini kita bisa melihat betapa penguasa ketika sudah menjadi tiran, akan melakukan sapa saja untuk menundukkan lawan-lawannya. Walaupun sebenarnya dirinya tahu bahwa kasus yang dituduhkan adalah mengada-ngada. Dan jeruji besi atau penjara kerapkali dijadikan solusi mereka untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Nama-nama besar seperti Hamka, Natsir, M. Roem, Prawoto pun juga pernah menjadi korbannya.*/Mahmud Budi Setiawan