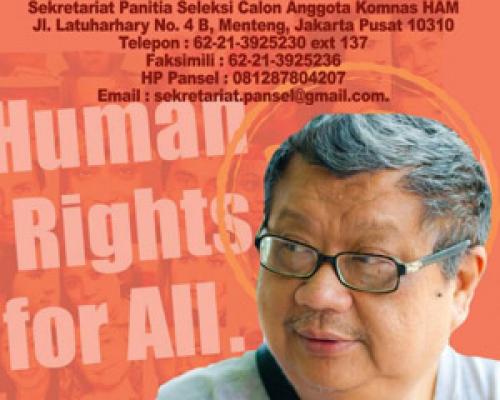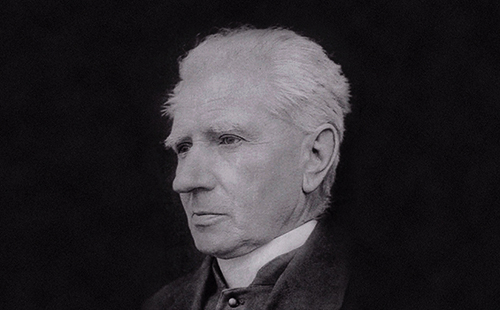Kamis (4 Desember 2003) kemarin, seorang professor di International Islamic University Malaysia, mengirim pesan kepada saya. Ia meminta saya membaca berita di Koran BERITA HARIAN yang terbit di Kuala Lumpur, tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Memang, berita itu menjadi headline di rubrik “Dunia” di Koran Berita Harian. Judulnya sangat mencolok: “NGO INDONESIA BELA KAHWIN BERBEZA AGAMA”.
Seorang anggota Komnas HAM, Zumrotin K. Susilo, yang dikutip pernyataannya, menyatakan: “Undang-undang 1/1974 mengenai perkahwinan mencabuli kebebasan beragama dan mengamalkan kepercayaan masing-masing seperti yang disyaratkan dalam perkara asas hak asasi manusia.”
Berita tentang perkawinan beda agama di Indonesia itu dikutip oleh Berita Harian dari salah satu kantor berita asing, yang juga mengutip beritanya dari Koran The Jakarta Post. Selain Zumrotin, Harkristuti Harkrisnowo, dosen di Fakultas Hukum UI, juga menyatakan perlunya UU Perkawinan diubah. Terutama yang disorot adalah pasal yang menghalangi terjadinya perkawinan antar-agama.
Masalah ini perlu dicermati dan didudukkan persoalannya. Koran The Jakarta Post berkali-kali memuat berita tentang masalah perkawinan antar-agama dan perlunya UU Perkawinan, yaitu UU No 1 tahun 1974 ditinjau kembali. UU itu kini dibenturkan dengan konsep HAM. Sebagai contoh, pada tanggal 28 Agustus 2003, The Jakarta Post menurunkan satu berita berjudul: “Rights activist calls for revision of marriage law.”
Ditulis dalam berita itu: “A noted woman activist and legislator called on Wednesday for a specific revisions to Marriage Law No. 1/1974 in order to promote more equal relations between husband and wife.”
Menurut Nursyahbani Katjasungkana, beberapa pasal dalam UU itu mengabaikan hak-hak wanita dan melegitimasi dominasi laki-laki terhadap wanita.
Misalnya disebutkan, bahwa dalam rumah tangga, laki-laki adalah kepala keluarga dan wanita adalah ibu rumah tangga. Menurutnya, dalam banyak perkawinan sekarang, banyak wanita menjadi kepala rumah tangga dan mencari nafkah untuk keluarga bersama suaminya. Maka, ia menuntut, agar UU itu direvisi, dan dinyatakan, bahwa suami-istri adalah setara dan bersama-sama mengurus rumah tangga. Disamping itu, Nursyahbani juga menentang pasal yang mengiznkan poligami, yang katanya, itu tidak fair bagi wanita. Ia juga menentang pasal 11 tentang masa penantian bagi wanita yang diceraikan untuk dapat menikah kembali.
Katanya, pasal itu menguntungkan laki-laki. Sebab, laki-laki yang bercerai bisa langsung menikah. Sedangkan wanita yang diceraikan harus menunggu sampai batas waktu tertentu untuk boleh menikah kembali. Maka, kata Nursyahbani, yang anggota MPR dari PDIP: “The article should be revised so men also receive the same period of time for reconciliation.”
Berita-berita di berbagai media massa tentang UU Perkawinan itu menunjukan, bahwa telah ada satu gerakan yang serius dan sistematis untuk mengubah UU Perkawinan. Isu yang banyak diangkat adalah seputar pertentangan UU tersebut dengan HAM dan kesetaraan gender (dua isu sakral Mungkin sebab itu, kantor berita asing tertarik untuk mengangkat isu ini menjadi masalah internasional. Nantinya, bisa dibuat laporan, bahwa Indonesia satu negara Muslim terbesar di dunia, tidak menghormati HAM.
Dari isu perkawinan antar-agama dan kesetaraan gender, seperti yang disuarakan Zumrotin dan Nursyahbani, tampak bahwa ada upaya untuk “menyekulerkan” kembali UU Perkawinan. Artinya, merombak pasal-pasal dalam UU Perkawinan, agar terlepas dari ketentuan hukum-hukum dan ketentuan agama. Sejarah mencatat, pengesahan UU No 1 tahun 1974 merupakan satu peristiwa politik yang sangat menghebohkan di masa Orde Baru. Umat Islam ketika itu menentang keras RUU Perkawinan sekuler yang diajukan oleh pemerintah. Sampai-sampai Sidang Pengesahan RUU tersebut di DPR terhenti, gara-gara para demonstran memasuki arena sidang. Akhirnya, setelah terjadi berbagai lobi antara pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, jadilan UU Perkawinan yang usianya kini sudah hampir 30 tahun.
UU Perkawinan No 1 tahun 1974 ini memang bisa dikatakan bercorak keagamaan, karena mendasarkan pengesahan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama.
Ini yang sejak lama menggelisahkan kaum sekuler, yang menginginkan sahnya satu perkawinan, tidak harus berdasarkan hukum-hukum agama. Sebagai contoh, pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 dinyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”
Dengan ketentuan-ketentuan tersebut jelas, perkawinan lintas agama, terutama antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, jelas tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, banyak pasangan kawin campur, yang memilih kawin di luar negeri, lalu mencatatkan perkawinannya di Indonesia. Ketentuan seperti ini, sekarang digugat, dan dipersoalkan, karena dianggap bertentangan dengan HAM. Artinya, kelompok-kelompok penentang perkawinan agama ini akan berusaha keras menggunakan saluran-saluran internasional untuk menekan pemerintah Indonesia, agar mentaati ketentuan HAM, dan mengubah hokum-hukum yang dianggap bertentangan dengan HAM.
Sebab, dalam “Universal Declaration of Human Right”, pasal 16 ayat 1 disebutkan: “Pria-dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untyuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan.”
Jadi, jika mengikuti ketentuan “HAM universal” tersebut tidak boleh ada pembatasan perkawinan karena perbedaan agama. Dunia Islam sudah menolak pasal ini, karena jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Organisasi Konferensi Islam pernah mengeluarkan Memorandum yang menekankan keharusan “kesamaan agama” bagi muslimah dalam perkawinan. Ditegaskan:
“Perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama bagi setiap muslimat.”
Prof. Dr. Hamka pernah mencatat dalam tulisannya berjudul “Perbandingan antara HAM Deklarasi PBB dan Islam”, tentang sikapnya terhadap pasal 16 ayat 1 Universal Declaration of Human Right: “Yang menyebabkan saya tidak dapat menerimanya ialah karena saya jadi orang Islam, bukanlah “Islam statistik”.
Saya seorang Islam yang sadar. Dan Islam saya pelajari dari sumbernya, yaitu Al Quran dan Al Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam tetapi syariatnya tidak saya jalankan atau saya bekukan.”
Gempuran serius terhadap masalah ini sekarang justru datang dari kalangan Islam sendiri, terutama dari sebagian cendekiawan lulusan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka memberikan legitimasi keagamaan – dengan dalil-dalil yang lemah dan dibuat-buat — bahwa perkawinan antara Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah halal. Pada Juni-Juli 2003, seorang doktor bidang filsafat lulusan IAIN Ciputat, menyatakan, bahwa tidak ada masalah, muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Dia katakan, hanya sebagian ulama yang berpendapat, bahwa “muslimah haram menikah dengan non-muslim”.
Pendapat itu jelas-jelas salah. Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah, menegaskan, bahwa semua ulama bersepakat atas hal itu. Tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Selama si laki-laki tidak memeluk agama Islam, maka haram menikahkannya dengan seorang wanita muslimah. Al Quran surat Mumtahanah ayat 10 menyatakan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”
Gempuran oleh sebagian “pakar agama” ini tentu lebih serius daripada gempuran seorang Zumrotin yang meninjaunya dari sudut HAM. Kita hanya mengimbau, siapa pun, sebagai muslim, seyogyanya mengkaji dengan serius masalah ini, dari sudut pandang Islam terlebih dahulu, sebelum melontarkan pendapatnya ke tengah masyarakat. Islam memiliki ketentuan yang tegas dalam soal perkawinan antar-agama. Seperti yang dipaparkan oleh Hamka, dalam soal ini, seorang Muslim ditantang untuk memilih: konsep perkawinan versi HAM atau konsep Islam. Maka, Indonesia pun kini dihadapkan pada persoalan serupa.
Tuntutan-tuntutan kesetaraan gender yang diajukan oleh Nursyahbani Katjasungkana pun sebenarnya satu upaya yang perlu dicermati dan dikaji secara mendalam oleh pakar-pakar hukum Islam. Meskipun secara konseptual, dalam Islam, sebenarnya masalah ini juga relatif sudah selesai. Kedudukan perempuan dalam Islam sangatlah jelas. Memang, perempuan diletakkan dalam posisi “rabbatul bayt” (ibu rumah tangga). Sedangkan laki-laki diberi amanah sebagai “kepala rumah tangga”.
Laki-laki diamanahi sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik tentu yang mengayomi, melindungi, mendidik, dan tidak menindas. Bagaimana pun, laki-laki yang diberi amanah sebagai kepala rumah tangga. Meskipun Megawati adalah Presiden, tetaplah dia adalah istri Taufik Kiemas. Rumah tangga merupakan satu komunitas yang memerlukan pemimpin. Kita tidak tahu, siapa yang bertindak sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga Nursyahbani?
Konsepsi Islam tentang kedudukan wanita ini bersifat sistemis, tidak dapat dilihat sepotong-sepotong. Jika wanita mau menuntut persamaan hak dengan laki-laki–seperti hak talak, hak menikah tanpa masa tunggu (‘iddah), dan sebagainya – maka wanita harus mau disamakan dalam segala bidang dengan laki-laki.
Padahal, itu tidak mungkin. Hingga kini, pun, dunia tetap memisahkan komunitas laki-laki dan wanita.
Berbagai cabang olah raga membedakan kategori antara wanita dan laki-laki. Jika Mike Tyson diadu dengan Lamya Ali, sudah dapat diperkirakan, Tyson yang akan menang. Dunia sepak bola akan kacau, kalau pemainnya merupakan campuran antara laki-laki dan wanita.
Bagaimana pun laki-laki dan wanita adalah berbeda. Biarkanlah mereka berbeda, dan tetap dalam perbedaannya.
Hingga kini, wanita tetap bertugas mengandung dan melahirkan anak. Sampai kapanpun, laki-laki tidak akan bisa menggantikan kemampuan wanita untuk hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Jika Nursyahbani menuntut agar laki-laki juga diberi batas waktu iddah, seperti wanita yang bercerai, apakah dia mau agar wanita juga diwajibkan mencari nafkah. Apakah dia tidak memahami, bahwa masa iddah diperlukan bagi wanita, untuk memastikan apakah si wanita itu mengandung anak dari suaminya terdahulu atau tidak.
Sebab, Islam sangat menekankan aspek nasab bagi si anak. Jika laki-laki diberi peluang untuk berpoligami, apakah wanita akan menuntut untuk poliandri? Jika laki-laki diberi hak talak, apakah wanita juga akan diberikan hak yang sama? Bayangkan, betapa kacaunya, jika suami menjatuhkan talak satu, lalu si istri sekaligus juga membalasnya dengan menjatuhkan talak tiga pada sang suami. Di Afrika Selatan, kabarnya, sudah ada feminis yang menyerukan agar wanita juga diberi hak untuk memberikan khutbah Jumat.
Jika wanita hanya melihat besarnya “hak” yang diberikan kepada laki-laki, tanpa melihat aspek “tanggung jawab” yang dipikulnya, maka bisa memunculkan kecemburuan dan kedengkian. Setiap hak yang diberikan Allah kepada laki-laki sekaligus mengandung beban amanah, bahwa semua itu akan dipertanggung jawabkan. Dimensi keimanan dan tenggung jawab di akhirat inilah yang biasanya hilang dari perspektif feminisme. Seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT, akan yakin bahwa Allah SWT lebih tahu tentang ciptaannya dibandingkan Zumrotin atau Nursyahbani. Allah lebih tahu bagaimana menempatkan posisi wanita dan laki-laki dalam rumah tangga atau masyarakat. Penyalahgunaan “wewenang dan kekuasaan” oleh sebagian laki-laki untuk menindas wanita bukan berarti konsepsi tentang kepemimpinan laki-laki terhadao wanita dalam rumah tangga itu tidak benar.
Jika ada sebagian kyai yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menindas santrinya, bukan berarti lalu dimunculkkan konsep, bahwa santri dan kyai adalah setara dan santri tidak perlu dipimpin kyai. Jika ada pemerintah yang menindas rakyatnya, bukan berarti lalu kita katakan, tidak perlu ada pemerintahan. Sebab, rakyat bisa memimpin dirinya sendiri.
Karena itu, kita mengimbau, semua Muslim yang berkeinginan merevisi UU Perkawinan, seyogyanya mendasarkan pandangannya pada konsepsi Islam, sebelum menoleh kepada konsepsi lain. UU Perkawinan bukanlah kitab suci. Dia mungkin diubah. Tetapi, seyogyanya, perubahannya bukan dilakukan dengan meninggalkan nilai-nilai dan ajaran agama. Jika UU Perkawinan ditarik ke arah sekuler dan dijauhkan dari konsepsi agama, maka bisa diduga – dengan merujuk konsepsi HAM sekuler – perkawinan homoseksual pun nantinya akan dituntut untuk disahkan. Na’udzubillahi min dzalika. (Kuala Lumpur, 4 Desember 2003).