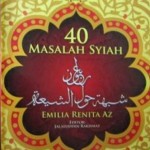~Our goal is a Christian nation. We have a Biblical duty, we are called by God, to conquer this country. We don’t want equal time. We don’t want pluralism.” Randall Terry, Founder of Operation Rescue~
Oleh: Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi
JIKA Christian Nation diganti Daulah Islamiyah, dan Biblical Duty diganti Jihad dan God ditukar Allah, pasti penulisnya jadi buronan. Dalam standar buku When Religion Become Evil karya Charles Kimbal, Randall dan agama Kristen sudah tentu masuk kategori agama jahat (evil) dan melanggar HAM.
Jika Randall pernah membaca tulisan Akbar S. Ahmed tahun 90an bahwa “Postmodernisme dipicu oleh semangat pluralisme”, berarti Randall tengah melawan arus kebudayaan Barat postmodern. Sebab ia pasti tahu bahwa pluralisme menjadi ordo di zaman postmo. Padahal di Barat siapa melawan faham ini, termasuk Randall pasti dapat stigma intoleran, mungkin juga teroris.
Sudah jamak postmodernisme lahir sebagai kemurkaan terhadap modernisme dan kejengkelan terhadap nilai dan kebenaran (nihilisme). Pluralisme menurut Peter Berger, (1967) merupakan alternatif pengganti sekularisme yang telah gagal di dunia Islam.
Kalau al-Attas menganggap sekularisme sebagai program, kita bisa yakin pluralisme adalah proyek postmodernisme.
Dilaksanakan dengan dana, strategi dan agen-agen untuk setiap Negara dan agama. Dipopulerkan oleh tokoh dan didukung tokoh populer. Dipromosikan pada dua wilayah sekaligus yakni sacred, dan profane.
Tidak mudah tapi ini proyek peradaban. Karena itu makna pluralisme dibuat ambigu. Misi umumnya adalah memberangus fundamentalisme, persis seperti postmo. Tapi makna istilahnya dibuat bersayap. Terkadang bermakna toleransi dan disaat lain berarti relativisme.
Tapi kalangan agamawan Kristen telah mencium trik ini. Robert E. Regier & Timothy J. Dailey misalnya dalam Religious ‘Pluralism’ or Tolerance?”, sudah menaruh curiga. Menurutnya, banyak orang hari ini yang dibingungkan oleh istilah toleransi keagamaan tradisional Barat dengan pluralisme agama.
Pluralisme agama berarti semua agama sama-sama valid. Jika demikian, lanjutnya, maka akan terjadi relativisme moral dan ketidakberaturan etika (ethical chaos). Kesan Rick Rood, seorang tokoh Katholik lainnya, juga sama “Dalam pluralisme agama semua agama adalah sama-sama benarnya sebagai jalan menuju Tuhan”.
Bahkan John Stott, teolog Anglican (dalam interview tahun 1998) tidak hanya curiga. Ia menuduh target pluralisme pada akhirnya adalah melarang penyebaran agama, khususnya Kristen (evangelisme). Sudah tentu trik ini tidak dipahami oleh para blind supporter pluralisme. Padahal diantara narasumber mereka yaitu Diana L. Eck, pimpinan proyek pluralisme Amerika, tidak menafikan sayap relativisme itu. Menurutnya agama-agama dan pandangan hidup sekuler adalah sama benar dan validnya.
Benar jika dilihat dari dalam kulturnya sendiri. Untuk itu, kata Diana L. Eck., dalam The Challenge of Pluralism, pluralitas harus digandengkan dengan pluralisme. Pengakuan terhadap pluralitas agama-agama tidak cukup, harusnya juga mengakui realitas kebenaran agama-agama, tegasnya.
Baca: Pluralisme Agama
Kini makna toleransi dan relativisme dalam pluralisme telah dibumikan menjadi makna sosiologis dan teologis. Tapi ini justru merungsingkan pihak gereja. Dr. Dawe Robert L. Dabney dalam Christian Century May 12, 1982 menulis bahwa gaung pluralisme telah memasuki ruang-ruang gereja. “Namun pemahaman kita cenderung sosiologis daripada teologis” tulisnya.
Tapi secara sosiologis sekalipun, menurut profesor teologi di Union Theological Seminary, Richmond, Virginia itu masih terdapat sisi negatifnya. Negatifnya gereja harus menerima berbagai pandangan baik konservatif ataupun liberal, yang saleh atau yang brengsek, feminis atau tradisionalis, aliran kiri atau kanan. Artinya nanti aliran setan sekalipun harus ditolerir.
Jadi sebenarnya mendukung pluralisme sosiologis juga masih riskan secara teologis. Orang diluar gereja merasa aman dari upaya penyingkiran. Tapi secara teologis mengakui keragaman kebenaran termasuk ateisme justru bertentangan secara teologis dengan gereja dan agama manapun.
Itulah sebabnya uskup pertama Baltimore Dr. Dawe John Carroll bingung, jika gereja bersikap terlalu eksklusif Kristen menjadi tidak laku di pasaran yang penuh persaingan. Jika bersifat inklusif atau pluralis maka berarti mengakui semua sebagai sama-sama benar adanya. Ini masalah.
Namun mereka tidak sadar dampak sosial ternyata tidak sebesar konsekuensi religius. Sebab ternyata para peneliti menemukan bahwa pluralisme agama melemahkan keterlibatan masyarakat dalam agama. Penelitian Finke dan Stark (1988) menyimpulkan bahwa pluralisme menghilangkan kegairahan beragama.
Ketika Negara atau lembaga publik tidak lagi mengobarkan kebaikan suatu agama, maka pemeluk agama-agama itu akan kehilangan kualitas atau intensitas keimanan atau kepercayaan pada agamanya. Akibatnya, keterlibatan masyarakat pada agama menjadi turun. Semakin pluralis seseorang semakin rendah semangatnya pergi ke gereja, begitulah simpul Finke dan Stark.
Lebih jeli lagi adalah kesimpulan Kenneth R. Samples, Abad dua puluh telah membawa tantangan yang tidak ada duanya dalam sejarah Kristen. Pada abad ini relevansi Kristen dan kebenarannya yang tertinggi telah dipertanyakan untuk pertama kalinya. Penghinaan terhadap klaim kebenaran Kristen yang sentral datang dari dua kelompok berbeda: humanis sekuler yang ateis dan suasana pluralisme agama yang terus berkembang (The Challenge of Religious Pluralism, Christian Research Journal)
Kesimpulan Sensus Olson and Hadaway (1998) di Kanada juga sama. Pluralisme menggerogoti semangat masyarakat dalam kegiatan keagamaan di Amerika Utara. Stark dan Bainbridge (1987) juga mencatat ketika seseorang berbeda pendapat tentang (ajaran) suatu agama, maka salah satunya akan berkurang keimanannya. Tapi anehnya, Berger, salah seorang konseptor pluralisme, berkesimpulan bahwa secara kognitif pluralisme agama telah menjadikan individu sulit mengimani agama tertentu.
Selain itu kesimpulan Joseph M. Mcshane, S.J., Dosen religious studies di LeMoyne College di Syracuse, New York menarik dicermati. Dalam masa 200 tahun gereja-gereja Amerika menikmati “karunia” pluralisme tapi pada kurun waktu 40 tahun terakhir, gereja akhirnya harus menanggung efek pluralisme yang merusak. Kini di Amerika orang sulit membedakan antara penganut Katholik dan orang awam.
Mengamati situasi diatas Gregory Koukl, rekan John Scott menjadi marah dan emosional mirip Randall. Dengan tegas dan blak-blakan ia mengatakan “Saya rasa konsep pluralisme agama masa kini adalah bodoh (stupid). Konsep bodohnya adalah ide bahwa semua agama pada dasarnya sama-sama benar”.
Emosinya tercermin dari serapah dalam bahasa informal Amerikanya That is just flat out stupid.*
Pemimpin Redaksi Majalah ISLAMIA dan direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)