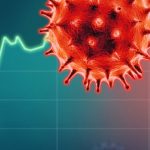Oleh: Amran Nasution *
 Hidayatullah.com–Presiden SBY dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta Selasa, 15 Juli lalu, bersepakat tak meneruskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur, sesudah jajak pendapat tahun 1999, ke pengadilan. Begitu berita yang tersebar di media massa.
Hidayatullah.com–Presiden SBY dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta Selasa, 15 Juli lalu, bersepakat tak meneruskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur, sesudah jajak pendapat tahun 1999, ke pengadilan. Begitu berita yang tersebar di media massa.
Itulah hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk kedua negara. Maka tak ada pribadi atau individu yang harus bertanggung jawab dalam KKP. Semua diambil-alih negara untuk kemudian kedua negeri tetangga itu melakukan rekonsiliasi.
Tapi sebenarnya kerepotan itu tak lebih dari tebar pesona untuk mendongkrak citra Presiden SBY yang terus terpuruk. Lho? Karena apa yang diumumkan kedua Kepala Negara itu sama sekali tak punya konsekuensi hukum di Indonesia. Soalnya Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) – UU nomor 27 tahun 2004 — telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, Desember 2006, sebab bertentangan dengan UUD 1945.
Walau sekarang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berganti nama menjadi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), tetap saja hasil kerjanya tak bermakna apa-apa. Lagi pula siapa yang mau diadili?
Sejumlah pejabat militer, polisi, termasuk Gubernur Timor Timur masa itu, Abilio Soares, dan Panglima Milisi Enrico Guiteres, telah diadili pengadilan Indonesia. Masa mereka mau diadili sekali lagi? Prinsip hukum sama saja di seluruh dunia: orang tak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama.
Agaknya yang dimaksud oleh Presiden SBY dan Jose Ramos Horta dalam komunike itu adalah pengadilan internasional untuk orang-orang yang belum diadili di Indonesia, tapi ditemukan bukti ia harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur.
Ada dua pengadilan internasional. Yang pertama, The International Court of Justice atau lebih dikenal sebagai World Court. Yang satu lagi adalah The Internatio nal Criminal Court.
nal Criminal Court.
World Court adalah organ resmi PBB yang digunakan untuk mengadili sengketa dua negara. Apakah sengketa perbatasan, teritori, dan sebagainya. Dalam kasus ini para pihak yang bersengketa adalah negara, bukan individu. Jadi pengadilan itu tak cocok untuk pelanggaran HAM Timor Timur.
Untuk kasus yang kabarnya melibatkan sejumlah jenderal – paling banyak disebut adalah Jenderal (Pur) Wiranto, Panglima TNI waktu itu — yang pas adalah Pengadilan Kriminal Internasional atau The International Criminal Court, disingkat ICC atau ICCt.
Pengadilan itu ada di Den Hag, Belanda, disiapkan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atau terlibat dalam kejahatan pemusnahan manusia atau genosida (genocide), kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan melakukan agresi (the crime of aggression).
Tapi pengadilan ini pun ternyata tak bisa dipakai untuk kasus Timor Timur. Soalnya, pengadilan yang dibentuk dengan dukungan 106 negara melalui apa yang disebut Statuta Roma (Rome Statute), telah ditetapkan hanya bisa mengadili kasus yang terjadi sejak ICC berdiri 1 Juli 2002. Artinya, kerusuhan Timor Timur yang terjadi sebelumnya, tahun 1999, tak bisa diadili ICC. Pengadilan itu tak berlaku surut (artikel 11 the Rome Statute).
Ia berbeda dengan Pengadilan HAM Adhoc di Indonesia yang bisa mengadili peristiwa pelanggaran HAM dengan berlaku surut, sampai zaman Nabi Adam. Ini adalah produk sebuah kekacauan dalam membuat undang-undang di DPR setelah reformasi. Habis umumnya DPR membuat undang-undang atas pesanan dan pengaruh negara asing, terutama Amerika Serikat. Itu dioperasikan oleh sejumlah LSM tertentu di sini yang dibiayai dollar dari Amerika. Wajar saja kalau sekarang semua kacau di Indonesia.
Jelas? Jadi kesepakatan SBY dan Jose Ramos Horta untuk tak membawa perkara itu ke pengadilan, sesungguhnya sama sekali tak diperlukan. Tampaknya yang ingin dicapai adalah kesan bahwa SBY telah ”berjuang” melobi Ramos Horta dan LSM-LSM, sehingga para mantan petinggi tentara yang terlibat kasus Timor Timur tak diadili. Itu tentu menyenangkan para anggota TNI dan keluarganya.
Sudah lama para anggota TNI terpuruk karena tuduhan pelanggaran HAM masa lalu. Padahal mereka merasa hanya menjalankan tugas di Timor Timur, dan itu semua dilaksanakan sesuai ketentuan pada masanya, demi kepentingan bangsa.
Anehnya, kini yang menjadi pahlawan adalah para pengurus LSM yang mereka ketahui sebagai agen asing, menerima dana asing untuk memojokkan bangsa sendiri, melepaskan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi terbukti dalam tulisan ini selanjutnya bahwa isu HAM hanya untuk kepentingan negara besar dan berpengaruh, terutama Amerika Serikat.
ICC di Den Hag, misalnya, lebih tepat disebut pengadilan pelanggaran HAM khusus untuk Afrika. Sejak dibentuk sampai sekarang kasus yang ditanganinya cuma pelanggaran HAM di Afrika, di negara miskin secara ekonomi dan lemah secara politik.
Tentara Amerika Serikat yang begitu banyak membunuh di Iraq, atau militer Israel setiap hari membunuh orang Palestina, atau menjatuhkan bom dengan sengaja di tempat persembunyian wanita dan anak-anak di Libanon, tak pernah dibahas pengadilan ini.
Hampir 800 tahanan di Teluk Guantanamo, disiksa, dipermalukan, direndahkan martabatnya. Belakangan mereka dilepaskan diam-diam, tanpa proses pengadilan. Segudang bukti sekarang bisa diperoleh dari para mantan tahanan. Tapi ICC tak pernah mau peduli apa yang terjadi di penjara illegal itu.
Milisi Janjaweed
ICC kini menangani kasus pemberontakan di utara Uganda yang dipimpin Joseph Kony. Tokoh pemberontak itu dan beberapa anggotanya dalam pencarian. Kemudian ICC sedang mengadili para pemberontak di Republik Demokratik Congo (Democratic Republic of the Conggo). Mereka dituduh menggunakan tentara anak-anak, perkosaan, pembunuhan massal, dan semacamnya.
Tiga tokoh pemberontak Congo kini ditahan oleh penuntut ICC di Den Hag. Pengadilan itu juga menahan Jean Pierre Bemba, bekas Wakil Presiden yang kemudian memimpin perlawanan bersenjata di Republik Afrika Tengah (Central African Republic). Ia dituduh bertanggung jawab atas sejumlah perkosaan dan pembunuhan.
Yang paling seru tentulah gebrakan ICC untuk Darfur, Sudan. Kalau di Uganda, Congo, dan Afrika Tengah, ICC menuduh atau mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan para pemberontak, untuk Darfur terjadi kebalikannya. ICC justru berhadapan dengan Pemerintah.
Sejak Juni 2005, pengadilan itu telah memerintahkan menangkap Ahmad Haroun, salah seorang Menteri dalam Pemerintahan Sudan, dan Ali Kushayb, pimpinan milisi Janjaweed yang punya hubungan dekat dengan Pemerintah. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Belum cukup. Pada 14 Juli lalu, penuntut ICC menuduh Presiden Omar Hasan al-Basyir bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Darfur. Maka pada hari itu pengadilan memerintahkan menangkap dan menahan Presiden al-Basyir. Ini untuk pertama kali ICC memerintahkan menangkap Presiden yang sedang berkuasa.
Tindakan ini diduga cuma memperburuk kondisi Darfur. Banyak pekerja kemanusiaan meninggalkan Darfur, khawatir pada kemarahan pendukung Presiden al-Basyir. Negara-negara Arab dan Afrika diduga akan membela al-Basyir. Begitu pula China dan Rusia. Itu terlihat dari sikap Tanzania yang kini memimpin Uni Afrika. ”Kalau kau menangkap Basyir, artinya kau menciptakan kevakuman pemerintahan di Sudan. Itu bisa sama dengan apa yang terjadi di Iraq,” kata Bernard Membe, Menteri Luar Negeri Tanzania.
Dalam tiga kasus sebelumnya, pihak pemberi laporan adalah pemerintah, dalam kasus Sudan laporan diberikan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1593. Padahal sebenarnya apa yang terjadi di Darfur, di bagian barat Sudan, tak lain adalah pemberontakan. Sama dengan yang terjadi di tiga negara Afrika lainnya.
Korban yang jatuh di Darfur tak lebih besar dan dramatis dibanding yang terjadi di Congo. Kalau begitu, kenapa sikap ICC berbeda? Tak lain karena Pemerintah Amerika Serikat terlibat jauh di Darfur. Ada kepentingan politik war on terror di sana. Ingat Sudan adalah negara Islam yang menjadi target war on terror, perang melawan terror Presiden Bush. Apalagi hasil minyak Sudan dijual kepada China, bukan Amerika Serikat.
Adalah China yang mensuplai Sudan dengan senjata dan peralatan perang lainnya, termasuk pesawat tempur. Menurut laporan BBC, bulan lalu, 2 pesawat tempur A-5 Fantan Fighter, buatan China, sudah mendarat di Sudan. Malah kini China membangun pabrik senjata di Giat Industrial Complex, di luar ibukota Khartoum, di Kalakla, Chojeri, dan Bageer (lihat The New York Times, 17 Juli 2008).
Profesor Ilmu Politik dari Universitas Columbia, New York, Mahmood Mamdani, telah mengungkapkan masalah itu dengan sangat jelas dalam sebuah esei yang dipublikasikan London Review of Book, 8 Maret 2007.
Esei itu sangat penting karena Mahmood Mamdani, Direktur Institut Studi Afrika di Universitas Columbia, dianggap ahli Afrika terpenting di Amerika Serikat sekarang. Mamdani yang meraih gelar Ph D untuk ilmu politik dari Universitas Harvard, menurut versi majalah Foreign Policy, masuk daftar 100 intelektual dunia 2008.
Dalam esei berjudul The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency (Politik Penamaan: Pemusnahan Manusia, Perang Saudara, Pemberontakan), Profesor Mamdani membandingkan apa yang terjadi di Sudan dengan Iraq.
Menurut penulis buku Good Muslim, Bad Muslim itu, estimasi korban sipil di Darfur dan Iraq selama tiga tahun terakhir adalah sama. Paramiliter juga sama-sama terlibat dalam pembunuhan. Di Darfur ada milisi Janjaweed yang bekerja sama dengan Pemerintah Sudan menghadapi pemberontak, dan di Iraq ada 30.000 pasukan bayaran dari perusahaan swasta Blackwater Worldwide yang disewa Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka sama membunuh. Apa bedanya?
Namun kenyataannya kekerasan yang sama di kedua tempat dinamakan berbeda. ”Di Iraq, ia disebut rangkaian pemberontakan dan penumpasannya. Di Darfur, ia disebut pemusnahan manusia (genocide). Kenapa berbeda? Siapa yang memberi nama? Apa perbedaannya?” tulis Profesor Mamdani. Akhirnya, artikel itu menyimpulkan semua tergantung kepentingan politik Amerika Serikat.
Perang saudara di Congo sejak 1998, sudah menghabiskan nyawa 4 juta manusia. Inilah korban terbesar setelah Perang Dunia II. Semua jenis pelanggaran HAM ada di sini, mulai penggunaan tentara anak-anak, perkosaan, perbudakan seks, pembunuhan massal penduduk tak berdosa, perempuan dan anak-anak.
Tapi milisi di sana dilatih tentara tetangga, Uganda dan Rwanda, teman Amerika Serikat di kawasan itu. Maka kekerasan yang begitu mengerikan di Congo tak disebut genosida dan tak seheboh Darfur. Pemberitaannya pun tak menempati halaman utama koran atau televisi dunia.
Begitu juga bom Israel untuk wanita dan anak-anak di Libanon. Apalagi perang Iraq. Menurut Mamdani, bagi Pemerintah Amerika, persoalan Darfur dilihat dari kacamata perang melawan teror (war on terror).
Masyarakat Amerika Serikat sendiri berbeda melihat Iraq dan Sudan. Mereka merasa punya tanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di daerah pendudukan Iraq. Berbeda dengan Darfur, Sudan, yang sama sekali tak mereka kenali, kecuali di sana terjadi pembunuhan oleh orang Arab terhadap penduduk Afrika. Pemerintahannya oleh Arab, pemberontakannya oleh Afrika, walau mereka sama beragama Islam. Milisi Janjaweed yang didukung pemerintah di Khartoum, adalah suku Arab nomaden. Mereka dituduh banyak membunuh dan memperkosa orang Afrika. [bagian pertama/hidayatullah.com]
* Penulis adalah Direktur Institute for Policy Studies