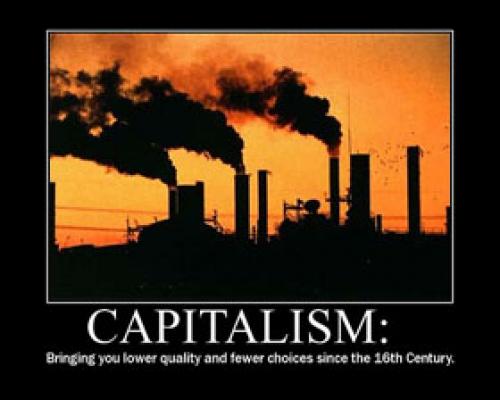Oleh: Amran Nasution*
Yang Muda Yang Koruptor
 Sejak Januari 2007, Mahkamah Agung China (China’s Supreme People’s Court) membuat kebijakan baru bahwa eksekusi mati hanya bisa dilaksanakan bila perkara sudah diuji Mahkamah Agung di Beijing. Sebelumnya, sudah berjalan 23 tahun, hukuman mati bisa dilaksanakan melalui keputusan Mahkamah Tinggi di provinsi. Banyak narapidana dieksekusi ketika baru saja seminggu menerima vonis banding dari Mahkamah Tinggi.
Sejak Januari 2007, Mahkamah Agung China (China’s Supreme People’s Court) membuat kebijakan baru bahwa eksekusi mati hanya bisa dilaksanakan bila perkara sudah diuji Mahkamah Agung di Beijing. Sebelumnya, sudah berjalan 23 tahun, hukuman mati bisa dilaksanakan melalui keputusan Mahkamah Tinggi di provinsi. Banyak narapidana dieksekusi ketika baru saja seminggu menerima vonis banding dari Mahkamah Tinggi.
Sejak kebijakan baru itu, jumlah eksekusi hukuman mati menurun sampai 30%. Seperti dikutip Associated Press, Maret 2008, Ketua Mahkamah Agung China Xiao Yang mengatakan bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan untuk sejumlah kecil kasus ekstrem yang mengancam masyarakat.
Termasuk yang selamat dari eksekusi adalah Liu Jinbao, Kepala Bank of China Cabang Hong Kong. Karena dituduh menggelapkan dana bank serta menerima suap, Liu Jinbao divonis mati. Pelaksanaan hukuman kemudian ditunda. ‘’Dengan begini akan tumbuh keinginan negara lain untuk mengekstradisi para tersangka,’’ kata Profesor Donald Clarke, ahli sistem hukum China di George Washington University Law School.
Banyak para pengamat asing berpendapat korupsi di China tak gampang diatasi hanya dengan mentrapkan hukum yang keras. Hukuman mati untuk para koruptor, misalnya, sudah ditrapkan di negeri itu sejak zaman Dinasti Ming, abad ke-14 sampai 17. Toh korupsi tak pernah menghilang. Sementara itu, seperti dikatakan Profesor Wang Shizhou, ahli hukum di Beijing University, ‘’Terlalu tingginya angka hukuman mati bisa mengganggu kepentingan dan keamanan China.’’
Andrew H.Wedeman, ahli China di University of Nebraska, Amerika, yang membuat studi tentang hubungan korupsi dengan pembangunan di China, menyebut bahwa korupsi merupakan tradisi yang sudah sangat lama di negeri ini. Itu menyebabkan ia tak gampang dihapuskan.
Kemudian China sekarang sedang mengalami masa transisi menuju ekonomi pasar, yang dioperasikan partai di pelbagai level. Artinya, bisnis dan politik tercampur, sementara pengawasan terhadap aparat partai – yang memiliki kekuasaan besar, termasuk membawahkan hakim dan pengadilan – terhitung minim. Itu menyebabkan korupsi merebak. Jadi inti masalah: merebaknya korupsi karena masalah sistem, selain memang sudah lama menjadi tradisi.
Arthur Kroeber, Redaktur China Economic Quarterly dalam sebuah artikel di Financial Times, Februari 2007, mengakui korupsi menyebar di China. Tapi katanya korupsi itu lebih merupakan pelumas yang memperlancar pertumbuhan China, sebagaimana korupsi yang pernah terjadi di Amerika Serikat di masa Gilded Age di ujung abad ke-19, yang terbukti mempercepat pertumbuhan ekonomi Amerika.
Yang terjadi bukan korupsi yang merusak seperti di sejumlah negara di Amerika Latin atau Afrika. Memang di tengah merebaknya korupsi, toh tiap tahun pertumbuhan ekonomi China tetap yang tertinggi di dunia.
Presiden Hu Jintao bekerja keras meremajakan birokrasi China dengan merekrut 200.000 tenaga muda. Mereka dipilih dari jurusan teknik perguruan tinggi yang baik. Ini berbeda dengan birokrasi China yang lebih tua yang umumnya berasal dari jurusan ekonomi, manajemen, sejarah, dan hukum.
Jadi kalau di Indonesia, Rizal Mallarangeng dan kawan-kawan berkampanye sebagai calon Presiden berusia muda, di China kaum muda yang berprestasi sudah mengisi jabatan-jabatan penting birokrasi.
Celakanya, studi yang dilakukan Jinghao Zhou dari Hobart and William Smith Colleges, New York, menunjukkan lebih 60% pejabat yang terlibat korupsi adalah berusia muda, 30 sampai 42 tahun. Mereka, menurut studi ini, kurang memiliki pengalaman kemasyarakatan dan standar moral, tapi memiliki kekuasaan, informasi, dan sumber. Maka ketika memegang kekuasaan, mereka tak mampu menahan godaan (The Journal of Comparative Asian Development, vol.5, no.1).
Apa yang terjadi di China bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata kalau hanya main tangkap – bahkan dengan hukuman mati – tak bisa mengatasi korupsi. Di sini pun korupsi sudah menjadi tradisi dan berlangsung lama, setidaknya sejak zaman VOC, apalagi diperparah oleh sistem politik yang koruptif.
Yang dimaksud, sistem politik kita meniru Amerika Serikat yang biayanya amat besar. Amerika mampu melaksanakannya karena pendapatan perkapita penduduknya 50.000 dollar, sementara Indonesia cuma 900 dollar. Di Amerika, calon Presiden Partai Demokrat, Barack Obama memiliki 1,3 juta donator, maka ia gampang mengumpulkan dana membiayai kampanye.
Sementara di Indonesia rakyat tak mampu menyumbang calon Presiden, Gubernur, atau Bupati dan Walikota. Lalu dari mana dana diperoleh? Di sinilah korupsi terjadi. Para politisi berusaha mengumpulkan dana dari kekuasaan yang dimilikinya. Konglomerat, termasuk konglomerat hitam, menjadi sumber dana politik. Karena itu dengan segala riuh-rendah pemberantasan korupsi, tak satu konglomerat pun yang bisa ditangkap atau diadili (lihat Membuka Topeng Negara Gagal, hidayatullah.com, 17 dan 23 April 2008).
Itulah yang disebut sebagai sistem yang koruptif. Kalau KPK ingin membuktikannya, cobalah sadap telepon para calon Presiden 2009 atau tim suksesnya. Di situ akan diketahui dari mana datangnya biaya kampanye yang teramat besar itu.
Yang sangat mengkhawatirkan, korupsi yang merebak menyebabkan tumbuhnya rasa ketidak-adilan di tengah masyarakat dan bisa mengancam keutuhan bangsa. Sementara itu pemerintah mau pun KPK tak sedikit pun berupaya merancang reformasi sistem politik dan birokrasi kita, sehingga pelan-pelan bisa melawan lajunya korupsi dengan mengganti sistem yang koruptif.
Coba, rekrutmen pegawai, polisi, tentara, atau birokrasi kita selalu diwarnai KKN, terutama suap. Sistem pengawasan tak berjalan, sistem penggajian berantakan, sistem pembinaan (reward dan punishment) tak disiapkan, bagaimana mungkin korupsi dibersihkan? (habis). [hidayatullah.com]
Penulis Direktur Institute for Policy Studies (IPS) Jakarta