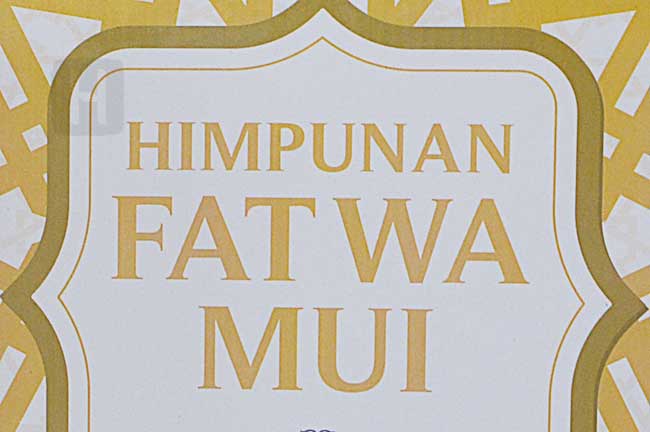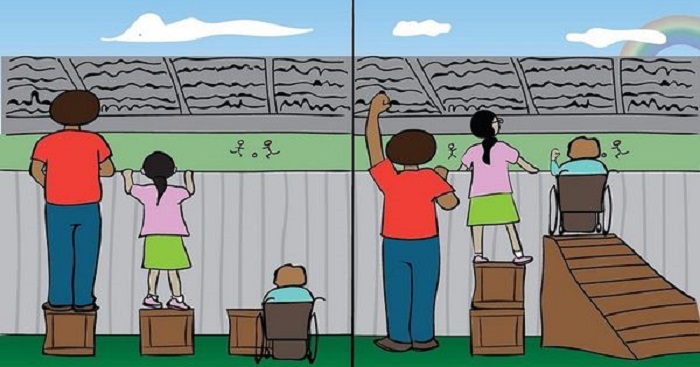Oleh: Muhammad Iswardani Chaniago
SELAMA ini teori yang mengatakan mengapa Barat menjadi sekuler cukup beragam. Salah satu penjelasan yang sering dikutip sebagai penyebab sekularisasi Barat adalah trauma mendalam terhadap agama.
Perang bertahun-tahun, tangan institusi agama yang masuk dalam banyak aspek, dan konflik tafsir. Atau dalam benak sosiolog pro sekularisasi penjelasan ini terdapat dalam eksplanasi rasio. Teori rasio ini menjelaskan mengapa Barat menjadi sekuler, disebabkan proses rasionalisasi yang massif. Dan perang, konflik agama serta kekuasaan agama yang menggurita adalah irrasional, sehingga saat terjadi proses rasionalisasi, agama menjadi terpinggirkan.
Penindasan keagamaan yang demikian keras dan panjang telah menciptakan pengalaman traumatik. Bayangkan, di Eropa abad pertengahan ada ratusan aliran sesat keagamaan yang eksis. Beberapa diantaranya diperangi oleh agama induknya karena dipandang sesat. Perang ini panjang dari satu sekte ke sekte yang lain. Tapi sejarah tidak merekam semua konflik keagamaan itu.
Degradasi agama sebagai salah satu faktor penting sekularisasi Barat banyak diulas para intelektual. Adian Husaini dalam bukunya Wajah Peradaban Barat termasuk cendikiawan yang memandang demikian. Sarjana Barat sendiri seperti Perez Zagorin dengan karyanya How Toleration Come to the West juga mengambil garis yang kurang lebih sama. Ia menggambarkan doktrin toleransi sekuler Barat berkembang disebabkan perlawanan terhadap institusi agama yang kerap berkonflik karena tafsir, memiliki kekuasaan besar dan berperang.
Pertanyaannya adalah jika benar pengalaman keagamaan traumatik menjadi penyebab Barat sekuler, mengapa hal yang sama tidak terjadi pada dunia Islam? Bukankah perang lantaran perbedaan mendasar keagamaan, konflik tafsir, dan kekuasaan agama yang besar juga kerap tejadi di dunia Islam.
Di awal sejarah khalifah pasca Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam wafat, ada perang riddah yang terjadi akibat penolakkan membayar zakat dan konflik dengan nabi palsu yang difatwa sesat. Dalam rekaman peradaban Islam juga ditemukan pertikaian akibat perbedaan tafsir keagamaan yang mendasar, sehingga muncul fatwa kesesatan sejumlah sekte agama. Kekuasaan agama, kala Islam berkuasa juga cukup kuat dan masuk ke dalam banyak sektor kehidupan. Mengapa pengalaman keagamaan yang nyaris tak berbeda, antara Barat dengan Islam, tidak menghasilkan trauma sejarah tersendiri bagi Islam? Kenapa fenomena sekularisasi tidak masif, bahkan bisa dikatakan gagal, pada dunia Islam?
Itu pertanyaan menarik. Jika direnungi setidaknya ada tiga penjelasan atas kegagalan sekularisasi Islam dan keberhasilannya di Barat. Pertama, sikap Islam terhadap hubungan negara-agama cukup tegas sehingga susah dimanipulasi atau ditafsir menjadi pro sekularisasi. Mencari preseden anti sekularisasi sangat mudah, karena bisa mencarinya langsung dari praktik kenabian. Efeknya, meskipun terjadi perang keagamaan, munculnya fatwa kesesatan atas sekte tertentu, dan kuatnya agama masuk dalam ranah kehidupan, sekularisasi nyaris tidak pernah menjadi solusi para ulama. Tapi bukan berarti tidak ada upaya sekularisasi Islam. Sejumlah pihak berupaya demikian.
Namun, upaya yang keras sekalipun bak menghadapi tembok tebal yang sukar ditembus. Kasus paling heboh dari upaya sekularisasi Islam adalah Ali Abdul Raziq. Hakim jebolan al-Azhar yang dihukum akibat argumen sekulernya mengatasnamakan Islam. Tapi gagasan Raziq tidak laku di dunia Islam. Bahkan ia sendiri konon mengubah pendapatnya dan bertobat setelah mendapat hukuman dari institusi al-Azhar.
Baca: Bibit Sekularisme
Argumen sekuler Raziq pernah dipakai Soekarno saat berdebat dengan Natsir, yang diabadikan Soekarno dalam buku tebalnya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi akhirnya, bisa jadi Soekarno paham, memisahakan Islam dengan negara (politik) adalah pekerjaan orang tak punya kerjaan.
Agama di Barat tidak setegas Islam. Masih banyak ambiguitas yang mungkin tak akan pernah selesai seputar sekularisasi. Kalangan Kristen, misalnya, agak kesulitan mencari justifikasi anti sekularisasi dalam diri Yesus. Karena Yesus belum sempat mendirikan komunitas politik. Sehingga wajar tafsir soal sikap kristianitas atas sekularisasi tidak sekuat Islam.
Katolikisme awal menganut doktrin unifikasi agama-negara. Adapun Protestan tak selamanya menganut doktrin tersebut. Bahkan kaum intelektualnya menentang unifikasi dengan menggunakan tafsir lain. Dan kemudian tafsir separasi tersebut laku. Hal ini nyaris tak terjadi dalam Islam. Secara umum kelompok teologis utama Islam (sunni, syiah, mu’tazilah) tidak menganut separasi agama-negara.
Kedua, Barat mengalami subjektifitas nilai yang berujung pada pandangan minor terhadap penyatuan agama dan negara. Bisa jadi ini merupakan efek lanjut dari agama di Barat yang terlanjur identik dengan kemunduran, sehingga penyatuan agama dan negara ikut terseret dalam anggapan ketertinggalan. Jadilah pemberantasan aliran sesat, konflik tafsir dan kekuasaan agama yang besar, disorot Barat sebagai sebuah kejahatan. Dengan penjelasan ini, sekularisasi sejatinya merupakan efek ikutan dari suratan agama yang terlanjur buruk di Barat. Itulah mengapa nyaris semua penganjur sekularisasi awal di Barat akan menyertakan cerita perang, konflik tafsir, tingkah agamawan serta insitusi agama yang menggurita sebagai lampiran dari gagasan sekularisasi pada banyak karya mereka. (BERSAMBUNG)