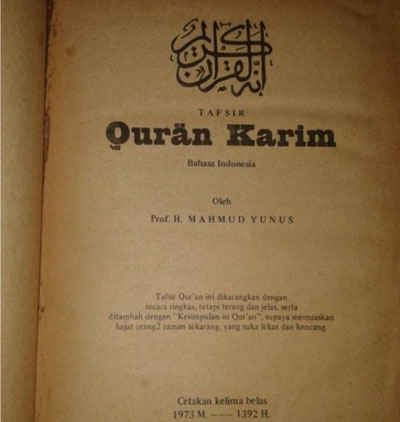Paham relativisme seringkali digunakan untuk mendekonstruksi bangunan-bangunan keilmuan Islam, tidak terkecuali ilmu tafsir
Oleh: Dr. Henri Shalahuddin, MIRKH
Hidayatullah.com | AL-QURAN adalah kitab suci yang diakui dan dihormati oleh segenap orang muslim. Ia adalah hudaa (baca: petunjuk) kehidupan seorang muslim, di dunia dan juga di akhirat. Secara ijma’, Al-Quran adalah sumber rujukan utama kaedah dan hukum yang diikuti oleh seorang muslim.
Para ulama kita terdahulu merumuskan suatu disiplin ilmu yang digunakan secara khusus untuk memhami isi kandungan Al-Quran. Biasanya disebut sebagai ‘uluum at-tafsiir.
Ilmu tafsir adalah salah satu ilmu alat yang paling penting dalam disiplin ilmu-ilmu syar’i. Perannya sebagai metode untuk menyarikan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran menjadikannya tidak bisa begitu saja disamakan dengan konsep tadabbur. Jika tadabbur dimnugkinkan untuk dilakukan oleh setiap mukmin. Maka tafsir Al-Quran harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar kompeten.
Secara umum, kualifikasi seorang penafsir berkisar pada pemahaman yang mendalam akan ilmu-ilmu syar’i dalam Islam, selain penguasaan jiwa dari nafsu dan kebersihan niat. Secara Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sudah pasti seorang penafsir harus menguasai bahasa tersebut. Mulai dari nahw (gramatika), sharf (morfologi), balaaghah (sastra), dalaalah (semantik), ashwaat (fonetik), qiraat, dan tentu saja pemahaman luas tentang kata-kata dna maknanya dalam bahasa Arab.
Pembahasan yang terdapat dalam Al-Quran berkisar pada banyak hal. Mulai dari qashash yang mewajibkan seorang penafsir untuk mengetahui sejarah umat-umat terdahulu. Al-Quran juga termasuk sumber sirah nabawiyah di mana hal itu perlu dicocokkan dengan kronologi yang didapatkan dari sumber-sumber berupa hadis. Hal ini berkaitan dengan pemahaman akan asbaab an-nuzuul beberapa ayat, yang nantinya bisa berpengaruh terhadap istinbath hukum dari ayat-ayat tersebut. Penguasaan terhadap riwayat-riwayat yang bersambung sanadnya sampai Rasul ﷺ menjadi begitu penting.
Tafsir Al-Quran adalah sebuah produk seorang manusia. Dengan begitu, macam penafsiran menjadi beragam tergantung worldview sang penafsir. Adalah sebuah keharusan bahwa seorang penafsir Al-Quran memiliki pandangan alam yang benar terhadap realitas di sekitarnya. Jika ia berasal dari kelompok yang menyimpamg dari Ahlussunnah wal jamaah, bisa dipastikan akan ditemukan catatan-catatan yang perlu diperhatikan dari karyanya. Seperti halnya al-Kassyaaf milik az-Zamakhsyari. Apalagi jika yang menulis tafsir adalah seseorang yang telah terpapar oleh pandangan hidup asing.
Relativisme dalam Tafsir
Singkatnya, relativisme adalah suatu cara pandang bahwa kebenaran bersifat relatif. Ia bisa berubah-ubah pada setiap tempat dan masa. Hasilnya, setiap orang, berilmu atau tidak, bisa menggambarkan dengan apapun tentang apapun sekenanya. Dan itu bisa dianggap benar.
Sejarahnya bisa kita tilik dari kasus munculnya para sofis pada zaman Yunani Kuno. Mereka adalah segolongan ornag yang hidupnya diisi dengan memanipulasi kebenaran untuk kepentingan pragmatis dengan retorika bodong.
Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Menurut mereka, kebenaran hanyalah alat, ia tak perlu diperjuangkan dan dibakukan. Kebenaran yang hakiki tidak mungkin kita capai. Maka tak perlu saling menyalahkan pendapat yang lain
Pada masa kini, paham relativisme seringakali digunakan untuk mendekonstruksi bangunan-bangunan keilmuan Islam, tidak terkecuali ilmu tafsir. Para pengusungnya beranggapan bahwa pembacaan teks suci (baca: Al-Quran) harus terus dilakukan sepanjang zaman, karena ia akan senantiasa berubah
Pada Abad Pertengahan Eropa, muncul disiplin ilmu yang diturunkan dari paham tersebut, ia dinamai hermeneutika. Secara bahasa, ia bermakna tafsir.
Namun objeknya adalah bibel yang memang asalnya sudah kita yakini bermasalah. Meski Al-Quran dan bibel sama-sama dianggap suci oleh orang-orang yang mengimaninya. Tapi tetap saja terdapat perbedaan-perbedaan krusial di antara keduanya.
Al-Quran memiliki otensitas yang terverifikasi sejak empat belas lebih abad yang lalu, sedangkan bibel tidak. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain yang tak kalah pentingnya.
So-called intelektual di Indonesia membawa pemahaman Nasr Hamid Abu Zayd yang memakai hermeneutika dalam wacana pemikirannya. Mereka mencoba mencari solusi atas “ketertinggalan” yang dihadapi umat muslim dengan mengotak-atik qath’iyyaat dan mutasyaabihaat di dalam Al-Quran, yang malah berujung pada ifsaad, walaupun mereka tidak menyadarinya.*
Peneliti INSISTS