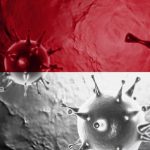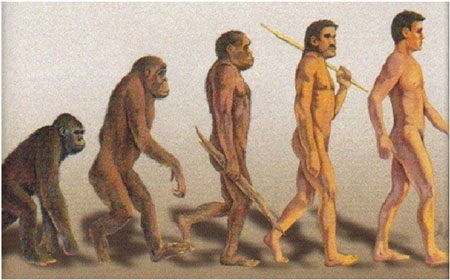Oleh: Dr. Adian Husaini
Hidayatullah.com | DALAM buku Risalah Sidang BPUPKI terbitan Sekretariat Negara RI, dikisahkan sekelumit perdebatan antara Latuharhary, Haji Agus Salim, tentang Piagam Jakarta. Meskipun sudah merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, namun saat dibawa dalam sidang BPUPK, sejumlah anggota BPUPK masih mempersoalkannya. Nama BPUPK – menurut RAB Koesoema –lebih tepat.
Dalam rapat BPUPK tanggal 11 Juli 1945, baik pihak Kristen maupun pihak Islam masih mempersoalkan rumusan Piagam Jakarta itu. Dari pihak Kristen, muncul Latuharhary dari Maluku, yang menggugat rumusan Piagam Jakarta. Latuharhary tidak secara tegas menyampaikan aspirasi Kristen, tetapi menyoal, jika syariat Islam diwajibkan pada pemeluknya, maka mereka harus meninggalkan hukum adat yang sudah diterapkannya selama ini, seperti di Minangkabau dan Maluku. Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di Maluku. Jika syariat Islam diterapkan, maka anak yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan warisan. “Jadi, kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adapt istiadat,” kata Latuharhary.
Haji Agus Salim, yang asal Minangkabau, membantah pernyataan Latuharhary, bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan kekacauan di Minangkabau. Malah dia menegaskan: “Wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya.”
Menanggapi Latuharhary, Bung Karno menyatakan: “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat itu tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus.”
KH Wachid Hasjim, tokoh NU, juga menyampaikan tanggapannya. Bahwa, menurutnya, rumusan Piagam Jakarta itu tidak akan menimbulkan masalah seperti yang dikhawatirkan. Malah, dengan tegas, Wachid Hasjim, menyatakan: “Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi, dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang.”
Menanggapi pernyataan Wachid Hasjim itu, Soekarno menegaskan lagi, “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah diterima Panitia ini.”
Piagam Jakarta adalah naskah pembukaan (preambule) UUD 1945 yang disiapkan untuk konstitusi Negara Indonesia merdeka. Ketika naskah pembukaan itu sudah disepakati, maka naskah-naskah rincian pasal-pasal dalam UUD 1945 masih menjadi persoalan. Dalam rapat tanggal 13 Juli 1945, KH Wachid Hasjim mengusulkan, agar Presiden adalah orang Indonesia asli dan “yang beragama Islam”.
Begitu juga draft pasal 29 diubah dengan ungkapan: “Agama Negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan sebagainya. Kata KH Wachid Hasjim: “Hal ini erat perhubungan dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.”
Usul KH Wachid Hasjim didukung oleh Soekiman. Tapi, Haji Agus Salim mengingatkan, bahwa usul itu berarti mementahkan lagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Usul KH Wachid Hasjim akhirnya kandas. Tapi, pada rapat tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus Hadikoesoemo, tokoh Muhammadiyah kembali mengangkat usul Kiai Sanusi yang meminta agar frase “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta dihapuskan saja. Jadi, bunyinya: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.”
Menanggapi permintaan Kiai Sanusi dan Ki Bagus Hadikoesoemo, Soekarno kembali mengingatkan akan adanya kesepakatan yang telah dicapai dalam Panitia Sembilan. Soekarno, lagi-lagi meminta kepada seluruh anggota BPUPK: “Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini suatu kompromis yang berdasar memberi dan mengambil… Pendek kata, inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi, panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin “Djakarta Charter”, yang disertai perkataan Tuan angora Soekiman, gentlemen agreement, supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.”
****
Pandangan Bung Karno bahwa Piagam Jakarta adalah pemersatu seluruh rakyat Indonesia perlu terus direnungkan secara mendalam. Apa yang dipikirkan oleh Bung Karno saat ini sudah terjadi. Cukup banyak syariat Islam yang telah diterapkan dalam kehidupan bermansyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia telah ada Dewan Syariah Nasional, yang saat ini diketuai oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Karena itu, sikap ‘fobia’ (ketakutan yang membabi buta) terhadap syariat Islam terlalu berlebihan. Sikap ‘Islamo-fobia’ atau syariah-fobia yang berlebihan itu mengingatkan kaum Muslim pada ayat al-Quran: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahannam orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.” (QS: Al Anfal:36).
Diantara kalangan Kristen sendiri, ada ‘suara lain’ yang berbeda. Sebagai contoh, pada 2004, Pdt. Dr. Jan S. Aritonang menerbitkan sebuah buku tebal berjudul “Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004). Buku ini menarik karena – disamping dilengkapi dengan data-data sejarah yang melimpah – juga disertai dengan saran dan harapan untuk mengatasi konflik Islam-Kristen di Indonesia.
Diantara sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada golongan Kristen adalah: “Tidak perlu bersikap alergik dan traumatik terhadap kaum Muslim yang berbicara tentang penerapan Syariat Islam.” Jan S. Aritonang juga mengimbau agar kaum Kristen bersikap lebih simpatik dan bersahabat terhadap kaum Muslim: “Memandang mereka sebagai seteru, pihak yang mengancam, atau pun yang harus ditaklukkan demi Injil atau demi apa pun, adalah tindakan bodoh dan tidak terpuji.” (Depok, 23 Juni 2021).*
Penulis pengasuh PP Attaqwa College (ATCO), www.adianhusaini.id