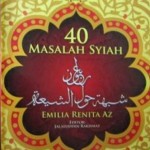Oleh: Reza Ageung
Di satu sisi, kita men-setan-kan Iran. Di sisi lain, invasi kita (Amerika Serikat) ke Iraq telah memberikan Iran sekutu besar dan semakin penting di Timur Tengah
~Araianna Hufftington~
DEMO akbar di Iraq telah hampir sepekan ketika artikel ini ditulis, dan kemungkinan akan semakin panas. Demonstrasi terbesar dengan 10 ribu-an pendemo digelar di Falujjah, kota yang pernah menjadi pusat perlawanan terhadap pendudukan Amerika Serikat (AS) beberapa tahun silam. Para pendemo pada awalnya mengarahkan protes mereka kepada apa yang mereka sebut sebagai “kebijakan sektarian” dari Perdana Menteri Nuri al-Maliki yang Syiah. Pemicu awal dari protes tersebut adalah ditangkapnya sembilan pengawal Menteri Keuangan Rafa al-Essawi yang Sunni dengan tuduhan terkait terorisme. Essawi murka dengan penangkapan tersebut lalu balas menyerukan diturunkannya al-Maliki dari jabatannya
Memang, di tahun ini, aksi kekerasan yang berbau pertikaian Sunni-Syiah semakin meningkat eskalasinya. Media massa menyebut jumlah korban mencapai ratusan jiwa, dan juga mensinyalir bahwa elemen pemerintahan mulai mencurigai bahwa setiap pihak yang Sunni (hatta dari internal pemerintahan) berkaitan dengan aksi-aksi terorisme.
Kondisi ini tentu tidak nyaman di dalam suasana transisi kedaulatan dari pendudukan Amerika Serikat ke pemerintah Iraq yang ditandai dengan ditariknya tentara Obama dari Iraq. Ada lagi satu bumbu yang membuat protes ini serasa lebih menggelora, yaitu “Arab Spring” (Musim Semi Arab) yang selama ini, setelah berkeliling ke Tunisia, Mesir, Yaman dan Suriah, belum menyentuh Iraq.
Analis politik Iraq Sabah al-Mukhtar mengatakan kepada al-Jazeera, “semua masalah ini (kebijakan sektarian, buruknya infrastruktur dan pelayanan publik) membuat semua rakyat Iraq menginginkan perubahan. Dan jangan lupa, kita memiliki Arab Spring. Warga Iraq mengatakan, ‘jika orang lain memberontak, kenapa kita tidak memberontak kepada rezim, yang dipaksakan atas kita oleh kekuatan pendudukan (AS) pada tahun 2003?”
Iran, Syiah dan Penjajahan AS
Nuri al-Maliki adalah PM dari kabinet Iraq baru pasca kejatuhan Saddam Husein yang dilantik pada tahun 2006 di bawah bayang-bayang AS pimpinan rezim George W. Bush. Pada waktu itu dengan semangat War On Terrorism (WOT) dibumbui oleh cerita fiksi bahwa Saddam mengembangkan senjata pemusnah massal, Bush nekat menginvasi Iraq tahun 2003, mengabaikan ketidaksetujuan PBB dan jutaan warganya sendiri yang tumpah berdemo di jalan-jalan New York. Kelak terbukti bahwa perangnya demi ambisi segelintir raja minyak, sehingga perang Iraq sering disindir sebagai “War for Oil.”
Uniknya, kabinet al-Maliki praktis didominasi Syiah, barangkali untuk membujuk dukungan komponen Syiah di negeri 1001 malam itu. Padahal, komunitas Syiah walaupun banyak namun tidak sampai membuatnya mayoritas mutlak sebagaimana Iran. Di Iraq, menurut media, persentase Syiah adalah 60% (namun dalam protes-protes terakhir ini, para pendemo yang Sunni meneriakkan “kami bukan minoritas”).
Memang, konon di masa tiran Saddam yang secara formal Sunni (walaupun lebih tepat disebut sebagai seorang baathist sosialis-sekuler), Syiah ditindas sedemikian rupa. Maka, boleh dikata kebijakan AS yang memberi warna Syiah itu adalah untuk memberikan stempel “pembebasan dari tiran”. Ini khas pendudukan AS di mana pun, kedok dari ambisi imperialis yang sebenarnya.
Semenjak itu, meletus pertikaian sektarian Sunni-Syiah. Pemboman terjadi di mana-mana, bahkan media-media menyorot pemboman di masjid-masjid dan pasar-pasar. Walaupun beberapa analis yang bekeyakinan bahwa konflik dan aksi pemboman itu rekayasa intelejen AS dan dilebih-lebihkan, AS sendiri memanfaatkan kekacauan untuk lebih mencapkan intervensinya. Pun begitu, ada alasan di balik perlawanan kelompok-kelompok Sunni terhadap Syiah, yaitu karena Syiah bersekutu dengan AS untuk mendirikan pemerintahan boneka. Walaupun di awal-awal invasi dulu sering kita dengar bahwa ada satu kelompok Syiah yang dipimpin oleh ulama Syiah populer Muqtada al-Sadr yang melakukan perlawanan terhadap AS, namun toh pada akhirnya terbukti bahwa blok Syiah di negeri itu, dan juga Iran, mendukung kabinet al-Maliki.
Associated Press (AP) pada Juni 2012 melaporkan bahwa Muqtada al-Sadr pergi ke Iran untuk pembicaraan, bahwa Iran menekan Presiden Iraq Jalal Talabani untuk mengurangi tekanan terhadap al-Maliki. Dan ulama Syiah Ayatollah Kazim al-Haeri, yang dianggap sebagai mentor al-Sadr , baru-baru ini mengeluarkan fatwa terhadap dukungan bagi para pemimpin sekuler dalam pemerintahan Iraq.
Hal ini semakin memperkuat gambaran di kelompok-kelompok perlawanan (jihad) Sunni dan di diri para pemrotes di jalanan Iraq hari ini bahwa pemerintahan hasil anak haram penjajahan AS itu berdiri satu barisan dengan kubu Syiah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (baca : Iran).
Perselingkuhan Iran dan AS
George Friedman dalam jurnal Stratfor Global Intelligent, 28 Mei 2004 mengatakan, sebelum America dan sekutunya menginvasi Iraq tahun 2003, Ahmad Challabi, pimpinan Ppartai Kongres Nasional Iraq di pengasingan telah meminta Amerika dan Iran menggulingkan Saddam Hussain. Kala itu, pemerintahan Bush mengharapkan dia bisa menjadi pemimpin baru negara itu.
Chalabi dilahirkan dalam sebuah keluarga Syiah Iraq di Baghdad, tetapi meninggalkan negeri itu tahun 1956. Ia kemudian kembali pada tahun 2003. Sebelum invasi Amerika ke Iraq sekelompok orang Iraq di Washington, membentuk tim analis, ditanggung oleh dana pemerintah Amerika Serikat. Namun hubungan pemerintahan Bush dengan Chalabi mulai renggang manakala AS mencurigai Challabi telah dituduh menjadi mata-mata untuk Iran. Akhirnya tahun 2004 pemerintahan Bush menghentikan bantuan keuangan kepada organisasi Kongres Nasional Irak hingga pasukan keamanan Amerika menyerbu Baghdad.
Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times dan beberapa wartawan Amerika sebelum kembali ke Iraq, mengaku banyak didanai Amerika dan Iran guna merealisasikan dirinya kembali membangun kekuasaan di Iraq dan menggulingkan Saddam.
Dalam wawancara dengan The New York Times, ia mengaku telah beberapa hari tinggal di Teheran dan bertemu dengan para pejabat senior di Garda Revolusi, pejabat keamanan dan intelijen dan melaporkan langsung kepada Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, orang paling kuat di negeri itu. Katanya, para pejabat Iran telah berjanji untuk membantunya memasuki Iraq secara illegal.
Namun seorang pejabat senior Iran mengecilkan kegiatan oposisi Iraq itu dengan mengatakan, “Mereka hanya lewat. Mereka kebetulan punya teman di sini.”
Eskalasi ini semakin menegaskan hakikat posisi Iran di hadapan dunia Arab dan di hadapan AS. Di media-media massa, tensi antara Iran dan AS serta Israel terus memanas seiring memanasnya isu nuklir. Namun, kasus Iraq telah membongkar apa yang terjadi di dunia nyata. Iran tidaklah sepenuhnya memusuhi AS, setidaknya di Iraq ia menjalankan politik hegemoni kawasannya dengan memanfaatkan sentimen sektarian. Dengan kata lain, al-Maliki dan pemerintahannya telah mempertemukan kehendak AS membentuk pemerintahan demokratis pro-AS di satu sisi dengan kepentingan Iran untuk menghegemoni kawasan berdasarkan sentimen sektarian di sisi lain.
Walaupun Obama dengan yakin mengatakan dalam pidatonya di Fort Bragg bahwa dengan ditariknya pasukan dari Iraq, ia telah meninggalkan pemerintahan yang berdaulat, stabil dan mandiri, realitasnya diragukan karena stabilitas dan kemandirian adalah tujuan yang sulit dicapai bagi Iraq. Para pejabat militer sendiri khawatir bahwa kekosongan pasca-AS akan diisi oleh pengaruh Iran yang semakin menguat. Namun, kekhawatiran ini sejatinya tidak beralasan. Sebab, yang sebenarnya terjadi adalah AS dan Iran saling menopang satu sama lain. Arianna Hufftington di hufftingtonpost.com menulis bahwa sebenarnya AS dan Iran sudah “bekerjasama” menopang pemerintahan al-Maliki.
Gambaran lebih jelas mungkin yang ditulis oleh Associated Press pada pertengahan tahun ini yang menyebut Iran sebagai “big brother” untuk al-Maliki karena telah membantunya merancang administrasinya pada tahun 2010 dan kini menyeru kepada semua faksi-faksi (Syiah) sekutunya di Iraq untuk menjaga rezim al-Maliki. “Sidik jari Iran ada di seluruh lingkaran dalam al-Maliki,” kata AP. Maka benarlah ketika Hufftington menegaskan, “di satu sisi, kita men-setan-kan Iran. Di sisi lain, invasi kita (Amerika Serikat) ke Iraq telah memberikan Iran sekutu besar dan semakin penting di Timur Tengah”.
Iraq telah memberi jalan bagi apa yang oleh Tariq al-Hashemi, wakil presiden yang kini buron, disebut sebagai “proyek Safawi” merujuk nama sebuah dinasti Syiah di Iran pada abad ke-16 sampai 18.
Umat Islam seyogyanya menyadari fakta ini, bahwa permainan antara AS, rezim-rezim bonekanya dan kekuatan Syiah yang dipimpin oleh Iran telah membuat umat Islam terombang-ambing tanpa kepastian, seperti bola yang digulirkan dari kaki ke kaki atau bahkan ekstremnya, seperti mangsa yang dilempar-lempar dari harimau ke srigala.
Permasalahannya bukanlah terletak pada apakah Sunni mendapatkan jatah di pemerintahan al-Maliki atau tidak, karena jelas rezim tersebut masih bagian ‘anak haram’ penjajahan.
Persoalannya adalah penjajahan itu sendiri di satu sisi, dan kehendak Iran dengan politik sektariannya di sisi lain. Di sinilah urgensitas umat Islam untuk bersatu di atas akidah yang benar dan memperjuangkan kehidupan yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah saja dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para Sahabat dan generasi Salafus Shaleh.
Umat tidak boleh terpengaruh oleh dikte Barat dan Iran. Akidah dan pemahaman yang benar tidaklah mungkin memberi jalan pada penjajah untuk menguasai sesama umat Islam, walaupun dengan alasan sektarian.
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. An Nisa 141). Wallahu a’lam.*
Penulis tertarik pada masalah politik Iran