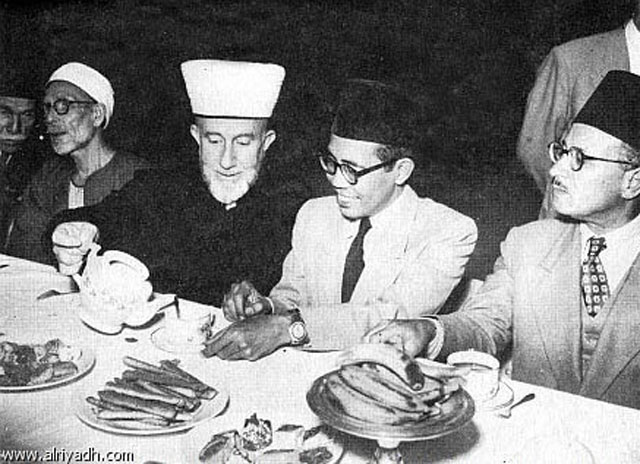Oleh: Fajri M. Muhammadin
PERDEBATAN Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih sangat panas, antara lain menyangkut persoalan zina fornikasi dan LGBT.
Dari sekian banyak poin perdebatan, salah satu kritik terhadap kriminalisasi LGBT dan zina fornikasi adalah soal privasi. Menurut kritik ini, zina fornikasi dan LGBT ini tidak boleh dikriminalisasi jika tanpa paksaan. Pasalnya, walaupun dianggap amoral, tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, hal ini tidak boleh diikut-campuri oleh negara.
Bagaimana kita mendudukkan kritik ini?
Sebagai permulaan, unsur kerugian atau harm dalam kriminalisasi masih panjang diperdebatkan oleh para ahli hukum. Memang sebagian ahli beraliran legal instrumentalism mutlak mensyaratkan adanya kerugian sebagai alasan kriminalisasi, misalnya Claus Roxin. Sehingga, menurut aliran ini, perbuatan amoral tanpa kerugian tidak bisa dikriminalisasi. H.L.A. Hart menegaskan posisi ini. Sebagian ahli misalnya A. P. Simester dan Andreas von Hirsch, menyebut LBGT sebagai perbuatan amoral tapi tidak merugikan.
Tapi, bukan sedikit ahli beraliran legal moralism yang sedikit atau bahkan tidak mensyaratkan adanya kerugian sebagai alasan kriminalisasi.
Joel Feinberg, misalnya, mengatakan bahwa bisa saja dilakukan kriminalisasi sebagian perbuatan tanpa kerugian tetapi sangat amoral. Lebih tegas, Patrick Devlin, menegaskan bahwa perbuatan yang menentang moralitas di masyarakat harus dikriminalisasi walau tidak dilakukan di ruang pubilk. Menurutnya, ini demi menjaga struktur masyarakat.
Bagaimana posisi hukum Indonesia? Secara umum didapati bahwa tidak semua ahli bersifat condong pada salah satu saja posisi secara ekstrim. Hukum Indonesia nampaknya berada pada posisi yang mengintegrasikan keduanya.
Baca: Dr Dinar Kania: ‘Homo Politic’ Sarana Promosi LGBT Di Berbagai Dunia”
Pancasila, sebagai ideology negara dan sumber segala sumber hukum, mencantumkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sebagai Sila Pertama dan Kedua. Jelas, tidak bisa memisahkan hukum dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada pertimbangan mencegah keburukan. Barangkali serupa dengan hukum Islam: hukum bersifat moral karena Allah-lah penyandang Asmaul Husna yang merupakan standar moralitas objektif, dan juga hukum Islam juga mengandung maqashid Syariah (tujuan Syariat Islam) yaitu melindungi lima hal dasar: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana pendapat M. Saifullah Rohman, Islam berpengaruh besar pada perumusan Pancasila. (M. Saifullah, Kandungan Nilai Syariat Islam dalam Pancasila)
Karena itulah, pendekatan integratif ini tampak pada pendapat para ahli hukum Indonesia. Misalnya Sudarto, mensyaratkan kerugian tapi kerugian tersebut bukan hanya materil tapi juga spiritual dengan memperhatikan Pancasila. Muladi pun menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dan penerapannya harus merepresentasikan nilai-nilai sosial.
Dari perspektif moralitas, zina fornikasi dan LGBT jelas bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Argumen sebaliknya juga ada, berlandaskan HAM ala Barat yang sekuler.
Sekulerisme ini bukan sekedar posisi politik untuk ‘memisahkan Negara dan agama’, melainkan ia merupakan sebuah worldview dengan epistemologi yang murni materialistic dan absen spiritualitas-religiusitas. Pola pemikiran seperti ini tidak relevan di masyarakat berkarakter religio-magis dan berideologi Pancasila seperti Indonesia.
Baca: “RUKHP Perlu Dikawal, Agar Liberalisasi Seksualitas dan LGBT Tak Marak’
Dari perspektif pragmatis, ternyata ada yang lolos dari pengamatan para legal instrumentalist Barat. Masalah seksualitas ini tidak dapat dilihat secara terisolasi. Malah, harus dilihat dari gambar lebih besar yaitu masyarakat dan peradaban untuk dapat melihat potensi kerugiannya. Sebuah peradaban akan kuat jika ditunjang antara lain oleh sebuah masyarakat madani dengan struktur sosial yang kuat.
Masyarakat yang kuat adalah sebuah unit sosial terbesar, harus ditunjang oleh keluarga sebagai unit sosial terkecil yang juga kuat. Ini ditunjang antara lain oleh adanya institusi pernikahan.
Soal LGBT, masalahnya jelas. Di samping masalah penyakit menular seksual yang besar, pasangan LGBT tidak dapat membentuk sebuah keluarga dalam institusi pernikahan yang dapat menunjang peradaban suatu masyarakat madani.
Ronald Bayer dan Jeffery Satinover menegaskan ‘normalisasi’ homoseks bukanlah masalah saintifik melainkan hasil tekanan politis ideologis. Tidak ada salahnya melakukan tekanan serupa untuk mengadvokasi sebaliknya.
Terkait zina fornikasi, pembatasan hubungan seksual agar hanya dalam ikatan pernikahan adalah salah satu faktor untuk menguatkan pernikahan itu sendiri.
Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak menjaga dirinya akan cenderung berkurang gairah seksnya ketika menikah karena ter-‘desensitize’.
Realistis saja, ketidakpuasan seksual ternyata dapat menjadi faktor besar dalam meruntuhkan rumah tangga. Dampaknya bisa langsung atau tidak langsung karena menyebabkan masalah-masalah lainnya. Penelitian oleh Joan R. Kahn and Kathryn A. London pada tahun 1991 mengkonfirmasi dampak hubungan seks pranikah terhadap tingginya perceraian. Secara makro, ini berdampak pada masyarakat.
Masalah bergulir bak bola salju. Di Amerika Serikat, statistik 2015 menunjukkan 40% bayi lahir dengan single parent. Jelas, salah satu faktor utamanya adalah berkurangnya angka pernikahan dan preferensi untuk fornikasi. Hubungan fornikasi ini bisa mendapatkan enaknya hubungan seksual, dan dapat menghindari komitmen terlalu besar sehingga lebih mudah pergi kalau sudah bosan atau tidak cocok. Apalagi, sebagaimana penelitian Kahn dan London tadi, pernikahan pun jadi lebih rawan cerai. Tanpa mengatakan bahwa single parent tidak dapat berhasil, atau bahwa pasangan menikah tidak dapat gagal. Tapi, berbagai penelitian, misalnya oleh Sarah McLanahan dan Gary Sandefur menunjukkan bahwa anak yang lahir dari single parent lebih berresiko terjerumus narkoba, kejahatan, gagal Pendidikan, dan lain sebagainya. Ini pun berdampak besar pada angka kriminalitas.
Belum lagi Wendy Shalit menunjukkan bahwa fornikasi termasuk penyebab dari meningkatnya banyak gangguan psikologi pada perempuan, misalnya depresi, anoreksia, keinginan bunuh diri, dan banyak lagi. Ungkapnya, perempuan kini justru berhadapan dengan budaya masyarakat yang terseksualisasi pasca ‘sexual revolution’, dan secara mental ini ternyata sangat opresif terhadap perempuan.
Tentu ini tidak boleh disimpulkan secara berlebihan. Kriminalisasi ini bukan sekonyong-konyong menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, masyarakat madani yang kokoh dan angka kejahatan nol. Banyak unsur lain, misalnya: edukasi agama dan moral, pengelolaan konflik rumah tangga, pemerataan ekonomi, dan lainnya. Perlu penguatan institusi pernikahan secara holistik, dan kriminalisasi penyimpangan seperti zina fornikasi dan LGBT bukan satu-satunya tetapi merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Sebagaimana salah satu kritik Majelis Ulama Indonesia terhadap HAM ala Barat, bahwa konsep HAM terlalu fokus pada hak individu saja dan melupakan hak kolektif masyarakat. Tidak mengherankan jika mereka tidak melihat ruginya fornikasi dan LGBT. Tentu, masyarakat Indonesia lebih baik dari itu.*
Penulis adalah dosen pada Departmen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada