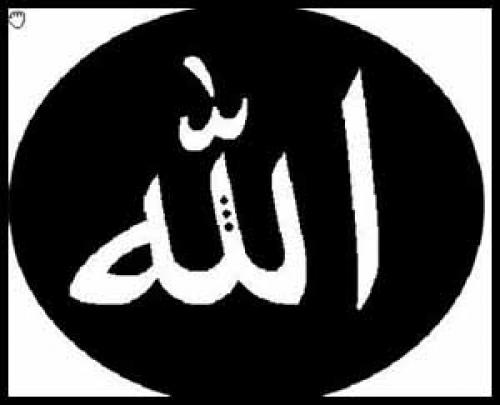Hidayatullah.com–Mohammad Ali Salih, wartawan yang bekerja untuk media Timur Tengah, setiap akhir pekan berdiri sendirian di depan Gedung Putih, Washington DC. Tangannya mengacungkan sebuah poster. Pada salah satu muka poster tertulis: “What is Terrorism?” (Apa itu Terorisme?). Di muka yang lain: “What is Islam?’” (Apakah Islam?). Poster itu sebagai wujud protesnya terhadap pemerintah Amerika Serikat yang tampaknya menyamakan Islam dengan terorisme, sehingga perang melawan teror adalah perang melawan Islam.
Hidayatullah.com–Mohammad Ali Salih, wartawan yang bekerja untuk media Timur Tengah, setiap akhir pekan berdiri sendirian di depan Gedung Putih, Washington DC. Tangannya mengacungkan sebuah poster. Pada salah satu muka poster tertulis: “What is Terrorism?” (Apa itu Terorisme?). Di muka yang lain: “What is Islam?’” (Apakah Islam?). Poster itu sebagai wujud protesnya terhadap pemerintah Amerika Serikat yang tampaknya menyamakan Islam dengan terorisme, sehingga perang melawan teror adalah perang melawan Islam.
Aksi diam itu dilakukannya menjelang akhir pemerintahan Presiden Bush. Seperti ditulisnya di The Washington Post, 16 Januari lalu, ia merasa sedih, marah, dan frustrasi, setelah peristiwa 11 September 2001, ketika kemudian Presiden Bush melancarkan perang terhadap Islam. Presiden Barrack Obama sebagai penggantinya, di mata Ali Salih, tak mengubah apa-apa.
Memang dalam masa kampanye Pilpres yang lalu, wartawan ini menaruh harapan pada Obama. Paling tidak Obama berbicara tentang perlunya Amerika berbicara dengan negara-negara Islam untuk menyelesaikan masalah yang ada. Maka sejak Obama terpilih, Ali Salih sempat menghentikan aksinya. Tapi setelah setahun, Januari lalu, ia mulai lagi berdiri diam di depan Gedung Putih setiap akhir pekan. Kenapa?
 “Ternyata Obama adalah seorang politisi yang berusaha terpilih dalam Pemilu. Setelah terpilih, dia berusaha untuk terpilih lagi,’” tulis Ali Salih di koran tadi. Artinya, di mata wartawan ini, prospek perdamaian dari Obama di musim kampanye hanya sekadar untuk meraih suara.
“Ternyata Obama adalah seorang politisi yang berusaha terpilih dalam Pemilu. Setelah terpilih, dia berusaha untuk terpilih lagi,’” tulis Ali Salih di koran tadi. Artinya, di mata wartawan ini, prospek perdamaian dari Obama di musim kampanye hanya sekadar untuk meraih suara.
Memang pada kenyataannya sejak terpilih menjadi Presiden, Obama justru terus-menerus meningkatkan jumlah pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Hal itu menyebabkan korban yang jatuh pun meningkat, maka perdamaian yang diharapkan semakin jauh.
Seperti diketahui, pada 11 September 2001, sekelompok teroris menyerang Menara Kembar WTC di New York, mengakibatkan gedung kebanggaan Amerika Serikat itu rata dengan tanah. Sekitar 3000 orang terbunuh.
Pemerintah Amerika menuduh serangan dilakukan kelompok Al-Qaeda dipimpin Usamah Bin Laden, putera konglomerat Arab Saudi. Beberapa hari setelah peristiwa, Presiden Bush memproklamasikan perang terhadap teror (war on terror). Tapi perang itu disamakannya dengan Perang Salib (crusade), yaitu perang antara tentara Kristen melawan pasukan Islam 1000 tahun yang lalu untuk memperebutkan Jerusalem. Maka kemudian banyak orang menafsirkan war on terror sebagai war on Islam, perang terhadap Islam.
Dan memang itulah yang terjadi. Dengan dalih tak bersedia menyerahkan Usamah Bin Laden, Afghanistan, negeri miskin itu, diserbu secara keroyokan oleh pasukan Amerika Serikat dan NATO, akhir 2001. Rezim Taliban yang berkuasa dijatuhkan, namun anehnya Usamah tak pernah tertangkap. Lalu dengan alasan mengejar Usamah, sejak itu sampai sekarang, Afghanistan dijajah pasukan Amerika dan sekutunya, NATO.
Padahal kalau membaca buku House of Bush, House of Saud (Scribner 2004), yang ditulis wartawan Amerika Craigh Unger, keluarga Usamah Bin Laden dan keluarga Bush saling kenal. Malah ketika menjalani masa mudanya di Texas (saat itu ayahnya George Howard W. Bush menjadi Wakil Presiden dan kemudian Presiden Amerika Serikat), George Bush, sang anak, menjalankan Arbusto Energy, perusahaan minyak yang dimodali keluarga Bin Laden.
Pada masa itu, di tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan dan Wakil Presiden George H.W.Bush mendukung pejuang Mujahidin untuk mengusir tentara Uni Soviet dari Afghanistan. Badan intelijen Amerika Serikat, CIA, aktif memfasilitasi para pemuda Muslim dari seluruh dunia (termasuk dari Indonesia) untuk berperang di Afghanistan.
Ketika itulah Usamah Bin Laden mulai mencorong. Namanya meroket dengan cepat, karena selain memberikan bantuan fasilitas dan uang kepada Mujahidin, putra konglomerat ini turut langsung memanggul senjata bertempur bersama pejuang Mujahidin melawan tentara Soviet. Sudah tentu Usamah berhubungan akrab dengan para operator CIA. Yang hendak dikatakan di sini bahwa Usamah Bin Laden bersama pasukannya pada waktu itu adalah kawan dekat CIA atau Amerika Serikat.
Seperti sama diketahui di pengujung 1980-an, akhirnya Uni Soviet bertekuk lutut kepada Mujahidin dan meninggalkan Afghanistan. Sejumlah pengamat menganalisa, kekalahan perang ini menyebabkan negeri beruang merah itu mengalami demoralisasi dan kemudian terpecah-pecah seperti sekarang. Akibatnya Amerika tak lagi punya saingan, dan menjadi satu-satunya super-power dunia.
Sekarang dua sekutu itu (kelompok Usamah Bin Laden dan Amerika Serikat) bermusuhan. Tapi anehnya yang menjadi korban adalah rakyat Afghanistan. Belum cukup. Pada 2003, giliran Iraq diserbu dan dijajah (sampai sekarang) oleh pasukan Amerika Serikat. Sudah lebih sejuta rakyat Iraq menjadi korban, apakah mati karena peluru dan rudal, atau oleh kelaparan dan penyakit yang berkecamuk karena perang.
Selain itu, Amerika mengebom Somalia, negeri kecil berpenduduk Muslim dan terbelakang di Afrika, mengancam-ancam Suriah dan Iran, serta melakukan intervensi militer di Yaman, negeri kecil dan miskin lainnya. Dengan semua alasan ini, wartawan Mohammad Ali Salih dalam tulisannya tadi, menyimpulkan bahwa Amerika Serikat memang melakukan peperangan terhadap Islam (war on Islam).
Ditembak Senapan Jesus
 Maka banyak pasukan darat dan Marinir Amerika yang bertugas di Afghanistan dan Iraq dilengkapi senapan berukiran ayat-ayat Bible. Seperti diungkapkan ABC News, tengah Januari lalu, salah satu ukiran pada senapan itu adalah JN8: 12, singkatan dari John bab 8 ayat 12. Yang lain ada yang diambil dari surat Corinthians dan Matthew.
Maka banyak pasukan darat dan Marinir Amerika yang bertugas di Afghanistan dan Iraq dilengkapi senapan berukiran ayat-ayat Bible. Seperti diungkapkan ABC News, tengah Januari lalu, salah satu ukiran pada senapan itu adalah JN8: 12, singkatan dari John bab 8 ayat 12. Yang lain ada yang diambil dari surat Corinthians dan Matthew.
Senapan itu dibuat pabrik senjata Trijicon di Michigan, negara bagian di belahan utara, berdasarkan kontrak bernilai jutaan dollar yang diperoleh perusahaan itu dari Angkatan Darat dan Marinir Amerika Serikat. “Dengan demikian, pasukan Mujahidin, Taliban, al-Qaeda, kaum pemberontak dan jihadis lainnya yang tertembak oleh senapan itu, boleh mengklaim bahwa mereka ditembak senapan Jesus,” ujar Michael Weinstein dari MRFF (The Military Religious Freedom Foundation), LSM penganjur kebebasan beragama di kalangan militer Amerika Serikat. (The First Post, 19 Januari 2010).
Sikap Amerika Serikat itu telah menjalar ke berbagai negara Eropa sekutunya. Belum lama ini, Swiss menetapkan di dalam konstitusinya, larangan membangun menara masjid di negeri itu. Ini pertama kali terjadi di dunia sebuah negara melarang pembangunan menara masjid.
Di banyak negara Eropa, seperti Jerman dan Inggris, sekarang sangat sulit mendapat izin membangun masjid. Di beberapa negara terjadi penghinaan terhadap Islam atau Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan sebuah koran Denmark dalam kasus kartun Nabi itu.
Di Perancis, pertengahan Januari lalu, parlemen merekomendasikan pelarangan wanita menggunakan kain penutup wajah (burqa dan niqab) di tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan angkutan umum. Pelarangan ini tampaknya sesuai keinginan Presiden Nicolas Sarkozy. Sebelumnya Sarkozy secara terbuka sudah mengatakan: wanita yang menutup seluruh tubuh tak diterima (not welcome) di Perancis.
Editorial koran The New York Times 27 Januari 2010, menuduh sikap parlemen dan Presiden Perancis itu sebagai tindakan menyebarkan kebencian (hate-mongering). Pemerintah Perancis sekarang sama saja dengan pemerintahan Taliban dulu di Afghanistan. Maka apa yang ternjadi di Perancis sekarang, sama dengan apa yang dilakukan pemerintahan Taliban dulu di Afghanistan: mewajibkan perempuan menggunakan burqa. Bagi koran ini, mewajibkan atau melarang burqa sama saja: berarti pelanggaran hak azasi manusia.
Di bulan Maret nanti Perancis menghadapi pemilihan umum. Para politisi Perancis pun mengalihkan isu pengangguran yang menerpa negeri itu dan tak bisa diatasi pemerintah, dengan isu anti-Islam. “Adalah sulit menciptakan lapangan kerja, jauh lebih mudah menciptakan prasangka anti-Muslim,” tulis editorial itu. Padahal Islam adalah agama kedua terbesar dalam jumlah pemeluk di Perancis setelah Katolik. Terdapat lebih 5 juta Muslim di antara 65 jutaan penduduk negeri itu.
Bersyukurlah kita di Indonesia. Sekalipun mayoritas penduduk negeri ini Muslim, tapi tak pernah ada larangan untuk lonceng gereja, sebagaimana di Swiss ada larangan untuk mendirikan menara masjid. Pabrik senjata PINDAD tak pernah membuat senapan dengan ukiran Sabilillah , sebagaimana senapan buatan pabrik Trijicon dihiasi ayat Bible dan digunakan pasukan Amerika di Afghanistan dan Iraq. Penganut Sikh tak dilarang menggunakan serban di kepala, sekalipun mereka minoritas di Indonesia, sebagaimana wanita Muslim yang minoritas di Perancis dilarang memakai burqa.
Maka adalah sangat menarik untuk mengamati gugatan yang diajukan sejumlah LSM dan pribadi ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Gugatan itu kini sedang disidangkan Mahkamah Konstitusi. Para penggugat adalah IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, SETARA, Yayasan Desantara, YLBHI, serta pribadi seperti K.H.Abdurrahman Wahid (kini almarhum), Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq.
Dari satu sudut pandang, gugatan itu sebagai upaya kaum liberal melaksanakan ide-idenya. Bagi mereka kebebasan harus mutlak, bebas sebebas-bebasnya. Maka undang-undang tentang penodaan agama itu di mata mereka bertentangan dengan ide kebebasan. Aliran sesesat apa pun boleh saja eksis di Indonesia , tak boleh ada undang-undang yang menghambat.
Bagi mereka, orang bebas mengaku Tuhan orang Kristen, Nabi umat Islam, atau Dewa Hindu. Mereka tak peduli kalau kelak ada ratusan orang mengaku Jesus atau Nabi Muhammad, membuat upacara tengah malam dengan tumbal anak perawan, atau sesajen uang dollar dan semacamnya.
Ahli sejarah kebudayaan dari Inggris, Richard Webster, dalam bukunya A Brief History of Blasphemy: Liberalism, Cencorship and the Satanic Verses (The Orwel Press, 1990) menulis bahwa konflik yang terjadi di pengujung 1980-an, menyusul terbitnya novel Salman Rusdhie, the Satanic Verses (Ayat-ayat Setan), bukan antara otoriterianisme dengan kebebasan, tapi antara dua bentuk kekakuan sikap (rigidity). Antara agama Islam versus agama Liberal.
Di mata Webster, kaum liberal pun memiliki sikap represif dalam doktrinnya. The Satanic Verses yang dengan sengaja dan sangat kasar dan brutal menyerang Islam adalah demi doktrin kebebasan yang mereka percayai. Itu menjadi bukti adanya sikap represif di dalam doktrin kebebasan yang sayangnya seringkali gagal dipahami oleh kaum liberal.
Dari persoalan ini, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu harus dilihat sebagai “pertarungan” kaum liberal melawan Islam. Di sini tak ada urusan dengan demokrasi, hak asasi, atau kebebasan, yang selama ini selalu didengung-dengungkan kelompok liberal.
Lagipula di mana pun di dunia ini, kebebasan selalu ada batasnya, termasuk di Eropa atau di Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai surga kebebasan. Larangan menampilkan iklan rokok di televisi di Amerika Serikat adalah sebuah contoh konkret. Larangan mengajarkan cara membuat bahan peledak, bom, atau senjata pemusnah masal adalah contoh yang lain. Banyak lagi contoh yang serupa. Coba bayangkan, memboikot Israel saja di Amerika Serikat adalah perbuatan terlarang. Sudah banyak orang dihukum karena menganut paham komunisme.
Maka salah seorang intelektual Amerika terkemuka dari New York University, Irving Kristol, punya pernyataan yang amat terkenal dalam soal kebebasan: “Bila Anda peduli pada kualitas hidup di dalam demokrasi Amerika, harus ada sensor.” Jadi kebebasan yang sebebas-bebasnya seperti dimaksudkan para penggugat undang-undang penodaan agama itu adalah kebablasan.
Tapi bisa pula masalah ini diteropong dari sudut pandang lain. Bahwa gugatan itu adalah dalam rangka war on Islam atau perang melawan Islam, atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan dari gerakan menghancurkan Islam di Amerika Serikat yang diproklamasirkan Presiden George Bush. Kalau gugatan tadi melibatkan LSM yang hidupnya dari donatur badan bantuan pemerintah Amerika Serikat (seperti US-AID dan turunannya), maka semakin kuat dugaan bahwa gerakan itu adalah perluasan dari “war on Islam”.
Islam memang sedang diperangi di Amerika dan Eropa – sebagaimana yang diprotes oleh wartawan Ali Salih di Washington — dan boleh jadi kemudian ia telah merambat ke Indonesia. Coba ikuti saja. [hidayatullah.com]
 Penulis adalah Direktur Institute for Policy Studies (IPS) dan kolumis hidayatullah.com
Penulis adalah Direktur Institute for Policy Studies (IPS) dan kolumis hidayatullah.com