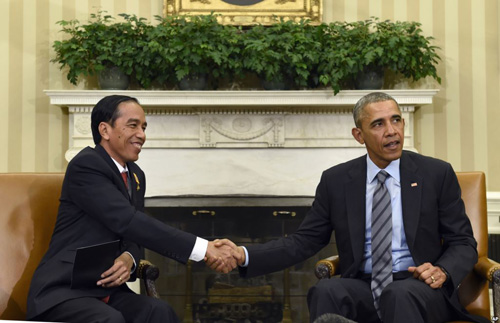Oleh: Syahrullah Asyari
BELAKANGAN ini, hangat dibicarakan tentang karakter. Sebenarnya ada apa dengan karakter? Apakah karena karakter dan akhlak itu sama saja?
Dalam tulisan ini, saya membedakan istilah ‘karakter’ dan ‘akhlak’. Tidak banyak yang menelusuri apa sebenarnya makna kedua kata tersebut.
Banyak yang hanya sekilas memandangnya, lalu berkesimpulan bahwa kedua kata itu bermakna sama. Saya sendiri tidak setuju dengan penggunaan istilah karakter, apalagi dimasukkan dalam konteks pendidikan, lalu disebut pendidikan karakter. Mengapa? Alasannya adalah sebagai berikut.
Pemikir dan pengusung terminologi pendidikan karakter kontemporer, Thomas Lickona, adalah seorang sekuler–liberal. Sejak tahun 1990-an terminologi ini mulai ramai dibicarakan. Melalui karyanya yang berjudul, ‘The Return of Character Education’, Thomas Lickona menyadarkan dunia Barat secara khusus di mana tempat Lickona hidup, dan seluruh dunia pendidikan secara umum bahwa pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Inilah awal kebangkitan ‘pendidikan karakter’. Namun demikian, pemikirannya tentang pendidikan karakter sangat keliru.
Thomas Lickona membedakan secara tegas antara pendidikan agama dan pendidikan karakter. Menurutnya, pendidikan karakter dan pendidikan agama mestinya dipisahkan dan tidak dicampuradukkan.
Tuturnya lagi, agama bukanlah urusan sekolah negeri, sementara pendidikan karakter tidak ada urusan dengan ibadah dan do’a-do’a yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah, atau tidak ada urusan dengan promosi anti-aborsi oleh kalangan agama tertentu, atau tidak ada urusan dengan penerapan ajaran-ajaran liberal dalam diri anak didik.
Baginya, agama memiliki pola hubungan vertikal antara seorang pribadi dengan keilahian (individu dengan ilahi), sedangkan pola hubungan pendidikan karakter adalah horizontal antarmanusia di dalam masyarakat (individu dengan individu lain).
Karenanya, menurut Lickona, jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja secara damai, maka nilai yang berkaitan dengan pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati. Lebih lanjut tuturnya, bahwa nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab pribadi, perasaan senasib sependeritaan, pemecah konflik secara damai, merupakan nilai-nilai yang mestinya diutamakan dalam pendidikan karakter.
Pandangan Lickona ini didasarkan pada pendapat filsuf Yunani, Aristoteles, yang menyatakan bahwa “… good character as the life of right conduct – right conduct in relation to other persons and in relation to oneself.”
Padahal dalam konteks ajaran Islam, pemisahan pendidikan agama (Islam) dan pendidikan karakter (baca: pendidikan akhlak) dalam lembaga pendidikan patut dipertanyakan keshahihannya. Sebab, jika pemisahan itu terjadi, maka pendidikan karakter yang dijalankan itu ‘memungkinkan’ terjadinya pertentangan dengan prinsip pendidikan Islam, yaitu tauhid. Berdasarkan konsep tauhid uluhiyyah, seorang muslim tidak boleh mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman.
Maksudnya, mereka tidak boleh mencampuradukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dengan pemaknaan pendidikan karakter seperti yang dikemukakan Thomas Lickona, maka dengan alasan kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, toleransi dan tanggung jawab pribadi, maka seorang Muslim bisa saja mengadakan kemusyrikan umum melalui upacara tolak bala seperti larung laut, larung sesaji untuk setan laut. Mungkin juga, seorang muslim turut serta merayakan natal dan tahun baru dan sebagainya. Intinya, dengan pandangan Lickona ini, seorang muslim bisa saja dianggap berkarakter baik, sekalipun ia seorang yang melakukan perbuatan syirik. Ini jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan Islam. Ini adalah bentuk akhlak paling tercela, kezhaliman terbesar karena melanggar hak Allah ‘azza wajalla sebagai satu-satunya Dzat yang berhak diibadahi secara benar.
Sebenarnya, kalau pemerintah ingin konsisten mengikuti undang-undang, mestinya tidak perlu ikut-ikutan menggunakan istilah Thomas Lickona, ‘character education’ yang kemudian populer disebut ‘pendidikan karakter’ di Indonesia. Hal ini karena dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”
Jelas, salah satu tujuan pendidikan nasional kita adalah berakhlak mulia. Mengapa kita tidak konsisten saja terhadap penggunaan frase ini dalam proses pendidikan, lalu menyebutnya sebagai ‘pendidikan akhlak’ yang tentu berangkat dari ajaran agama. Mengapa justru cenderung pada penggunaan istilah ‘pendidikan karakter’ oleh Thomas Lickona yang sebenarnya hanya didasarkan pada pendapat filsuf Yunani, Aristoteles. Seorang yang tidak beragama (ateis) yang tidak dibimbing melalui wahyu.
Kalau kita telusuri asal kata, ‘karakter’ dan ‘akhlak’, memang sangatlah berbeda. Sehingga maknanya pun berbeda. Kalau ada yang mengatakan sama, itu karena dipaksakan sama. Ditinjau dari sisi ajaran Islam, kata ‘akhlak’ ini adalah sebuah kata yang agung. Bila ditelusuri asal kata ‘karakter’, kata ini berasal dari bahasa Latin: ‘kharakter’, ‘kharassein’, ‘kharax’, dalam bahasa Inggris: ‘character’, dan Indonesia ‘karakter’, Yunani: ‘character’ dari ‘charassein’ yang berarti membuat tajam, membuat dalam.* (bersambung)
Penulis adalah Dosen Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Makassar, [email protected]