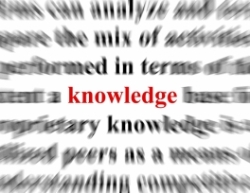Oleh: Mahmud Budi Setiawan
SALAH satu argumen pembela pluralisme agama di Indonesia dalam menjustifikasi kebenaran konsep pluralisme agama ialah dengan mengangkat tema toleransi(seperti: Zuhairi Misrawi, dalam bukunya, Al-Qur`an Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Abd. Muqsith Ghazali dalam, Argumen Pluralisme Agama, Musthafa Ali Ya`qub dalam, Toleransi antar Umat Beragama, Media Zainul Bahri dalam, Satu Tuhan Banyak Agama). Dengan toleransi -menurut mereka-, keberagaman agama bisa disinergikan sedemikian rupa untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, -bahkan pada titik paling ekstrim merelatifkan kebenaran agama-agama – yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian antarumat beragama.
Di antara contoh singkat, bentuk justifikasi pembela pluralisme agama dalam melegitimasi toleransi ialah sebagai berikut. Pertama, Biasanya dari al-Qur`an diambil sepenggal ayat dari surat al-Baqarah ayat: 256 yang artinya, ‘Tidak ada paksaan dalam agama …..”; ada pula ayat lain dalam surat al-Kahfi ayat: 29 yang artinya, ‘….barangsiapa menghendaki (beriman), maka berimanlah, barang siapa menghendaki(kekufuran), maka kafirlah’. Kedua ayat itu dianggap sebagai dasar normatif dari al-Qur`an yang mengandung nilai toleransi yang dijadikan dasar bagi konsep pluralisme agama.
Kedua, Hadits yang biasa dipakai ialah riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Bukhari yang artinya, ‘Agama yang paling dicintai Allah adalah ajaran yang lurus-toleran’. Hadit ini juga –dianggap- sangat menganjurkan sikap toleransi dalam beragama. Ketiga, dari sejarah Nabi Muhammad, biasanya diambil rujukan perjanjian Piagam Madinah sebagai cikal bakal justifikasi pluralisme agama (baca: Aksin Wijaya, Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah, hal. 44).
Bertolak dari realita tersebut, pada tulisan ini, penulis merasa perlu membahas secara kritis terkait masalah toleransi beragama dalam perspektif sejarah Nabi Muhammad. Secara khusus dipilih pendekatan sīrāh nabawiah (sejarah hidup Nabi), karena sudah banyak yang mengambil rujukan dari al-Qur`an dan Hadits, terkait masalah toleransi. Pendekatan historis dari sīrāh nabawiah sangat diperlukan untuk mengetahui obyektivitas mereka dalam mengambil rujukan dari sejarah.
Terkait dengan masalah toleransi agama dalam perspektif sīrāh nabawiah, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek, yaitu: akidah, ibadah, dan interaksi sosial.
Pertama, dari aspek akidah toleransi agama yang dipraktikkan Nabi sangat jelas dan tegas (lihat: al-Bararah, 256) yaitu tidak ada paksaan sama sekali dalam memasuki agama. Nabi pun melarang sahabatnya membunuh pemuka agama ketika berperang, sebagaimana hadits: “Berangkatlah dengan nama Allah, berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah, jangan melampaui batas, jangan berkhianat, jangan mencincang dan jangan membunuh anak-anak serta penghuni-penghuni gereja (orang-orang yang sedang beribadah)”(Ahmad, Juz: IV, hal. 461). Ini sebagai bukti betapa Islam adalah agama yang sangat toleran.
Tak hanya itu, beliau ketika di Madinah sangat menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan agama. Namun yang perlu ditekankan di sini ialah, toleransi Nabi dalam bidang akidah, ialah menghormati dan tidak memaksa pemeluk agama lain masuk Islam. Toleransi agama yang dipraktikkan beliau, tidak sampai mengarah pada relativitame kebenaran agama, yang menganggap semua agama benar, bahkan sama.
Kedua, dalam peribadatan pun beliau toleran dalam arti, menghormati pemeluk agama lain menjalankan agama masing-masing, bukan dalam pengertian meyakini bahwa ibadah pemeluk agama lain juga benar.
Suatu saat, ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam berada di depan Ka`bah, beliau didatangi oleh al-Aswad bin al-Muthallib, al-Walīd bin al-Mughīrah, Umayyah bin Khalaf dan al-`Āsh bin Wāil(Ibnu Katsir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, Maktabah al-Ma`ārif, Bairut, Juz. III hal. 90).
Pada intinya, mereka menginginkan agar Muhammad mau bergantian dalam menjalankan agama masing-masing supaya terjadi kerukunan dan perdamaian. Namun -bertepatan dengan itu-, turunlah surat al-Kafirun(1-6) yang secara tegas menyatakan bahwa dalam masalah akidah dan peribadatan tidak ada toleransi. “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”. Ini membuktikan bahwa dalam masalah akidah dan ibadah tidak ada yang namanya toleransi.* (Bersambung)
Penulis adalah peserta PKU VIII UNIDA Gontor 2014