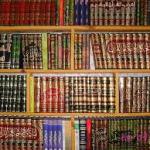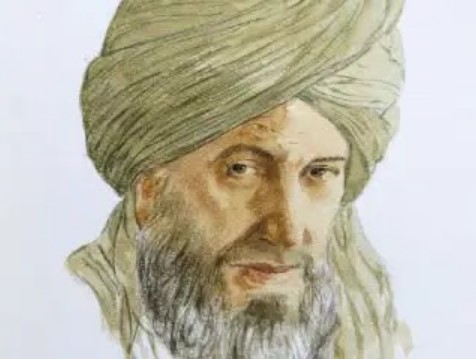oleh: Mahmud Budi Setiawan
DENNY JA dalam web inspirasi.co (15/01/2018) menulis artikel yang menyulut kontroversi. Dalam tulisan kategori agama yang berjudul “Islam di Era Google: Akhirnya Wanita Arab Saudi Menonton Bola di Stadium” ini ada banyak poin terkait wacana keislaman yang tak bisa ditelan mentah-mentah.
Setelah memaparkan “fakta panas” yang terjadi di Saudi Arabia di mana para wanita dibolehkan menonton sepak bola di stadium (12/01/2018), pada paragraf keenam dan ketujuh ia melontarkan pertanyaan yang cukup menukik:
Pertama, “Apa yang abadi dan apa yang bisa berubah dari aturan agama? Ketika aturan itu melarang wanita menonton bola di stadium, lalu kini membolehkannya, ini aturan agamakah?” Kedua, “Ataukah ini hanya interpretasi saja dari agama? Atau ini hanya kultur lokal saja? Atau ini hanya aturan pemerintah yang tak ada hubungan dengan agama? Atau ini hanya cabang kecil dari aturan agama yang boleh berubah? Lalu apa inti dari agama yang tak boleh berubah?”
Pertanyaan-pertanyaan ini –yang akan terlihat secara jelas pada bagian paragraf-paragraf setelahnya- mengandung poin yang biasa dipakai oleh intelektual liberal dalam membicarakan wacana agama Islam dengan nuansa relativisme yang cukup kental, misalnya: Al-Qur`an dan interpretasi tentang Al-Qur`an. Al-Qur`an memang betul perkataan Allah, tapi penafsiran Al-Qur`an itu relatif dan masing-masing tidak boleh merasa benar sendiri. Al-Qur`an benar perkataan Tuhan, tapi yang mengarti maksudnya hanya Tuhan sendiri, dan lain sebagainya.
Padahal, dalam paradigma keilmuan Islam, mengenai yang tetap dan berubah, sudah dibahas dengan istilah: al-Tsawâbit (konstan, permanen) dan al-Mutaghayyirât (dinamis). Buku yang berjudul “al-Tsawâbit wa al-Mutaghayyirât fî Masîrati al-‘Amal al-Islâmi al-Mu’âshir” karya Prof. Dr. Shalah Shawi misalnya, bisa dijadikan referensi bagi yang mau mengetahui lebih mendalam mengenai dua konsep tersebut.
Setelah mengamati “Islam in action” atau lebih umum “agama in action” pada paragraf kedelapan, mulailah pada paragraf kesembilan dan kesepuluh ia menajamkan opininya: “Tak bisa terhindari masalah agama adalah masalah interpretasi. Dua ahli yang sama sama mengerti kitab suci, yang sama sama meyakini satu agama, yang sama sama berniat tulus menjalankan agama karena tanggung jawab individu pada Tuhan, bisa berakhir dengan interpretasi yang berseberangan.”
Jika masalah agama hanya sekadar masalah interpretasi, ada gilirannya, akan mempersoalkan otoritas, karena toh kebenaran agama dianggap sekadar interpretasi individu. Persis seperti yang dilakukan oleh Khaled Abou El Fadl dalam buku “Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women” yang dalam versi Indonesia berjudul “Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif” (2004: 123) di sini ia mempermasalahkan otoritas bahkan mengganggapnya sebagai otoritarianisme.
Pandangan ini juga beraroma postmodern yang menganggap kebenaran tidak pasti karena terus berubah sebagaimana ajaran Nietzsche. Bahkan prinsip utama postmodern yang dihimbau Kevin J. Vanhoozer -sebagai dikutip oleh Dr. Hamid dalam “Misykat” (2012: 67)- adalah jangan percaya pada yang absolut. Dengan demikian, masing-masing tidak bisa menganggap dirinya paling benar.
Lebih dari itu, pernyataan ini bila ditelan mentah-mentah akan berimplikasi serius pada konsep Islam. Mestinya sebelum membahas lebih jauh, diklasifikasikan terlebih dahulu mana yang masuk pada sektor interpretasi atau kalau dalam istilah fikih ranah ijtihadi; dan mana yang masuk kategori ushûli sehingga tak terkesan mengeneralisir dan gebyah uyah.
Dalam ranah “ijtihadi” misalnya antar Imam Madzhab Empat misalnya sudah biasa berbeda. Namun mereka tidak akan berbeda dalam masalah-masalah yang sudah “qath’i” (pasti seperti rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya).
Kalaupun misalnya itu ranah interpretasi, ada persoalan yang mesti dijawab: apakah interpretasi ulama dalam masalah agama selalu relatif sehingga tidak mungkin bernilai kebenaran? Selanjutnya, tipe ulama seperti apa yang otoritatif untuk dijadikan standar? Bila ini tidak terjawab, dibiarkan campur-aduk maka beragama akan menjadi liar. Masing-masing dengan interpretasinya sendiri merasa berhak memodivikasi agama yang dianutnya. Sehingga kalau itu dibiarkan, apa lagi yang tersisa dari Islam?
Baca: Kampanye Homoseksualitas: Antara Toleransi dan Relativisme
Selanjutnya, pada paragraf sepuluh dia menanyakan, “Bagaimana pula memisahkan agama dengan kultur lokal setempat ketika sudah bercampur dalam praktek budaya yang panjang? Itu agamakah? Itu kulturkah? Itu gabungan keduanyakah? Itu bolehkah dari kaca mata doktrin agama?” lagi-lagi pertanyaan tidak akan terlontar jika sudah memahami secara gamblang konsep “tsawâbit” dan “mutaghayyirât”. Ini penting karena, kalau konsep ini tidak jelas, maka nanti dalam memberikan contoh akan tumpang tindih dan silang-sengkarut antara ranah “Ushul” dan “ijtihadi”.
Selanjutnya penulis ini membandingkang kasus perbedaan ulama Kanada yang pernah kuliah di Universitas Madinah yaitu: Said Ahmad Al-Kutty dengan Ulama Saudi Abdul Rahman Al-Barak terkait mengenai perempuan bercampur dengan laki-laki di tempat umum (gender segregation). Al-Kutty berpendapat bahwa tidak ada aturan dalam Islam mengenai hal ini sedangkan Al-Barak mengeluarkan fatwa mati bagi yang membolehkan laki-laki bercampur di depan umum. Setelah dicek, ada artikel yang sesuai dengan contoh yang dikemukakan Denny –entah dia mengambil dari situ atau tidak tapi contoh yang diberikan identik dengan artikel ini- yaitu: https://wiki2.org/en/Gender_segregation_and_Muslims.
Lagi-lagi Denny JA belum terlalu memahami letak perbedaan keduanya. Apakah dalam ranah ‘furu’ (cabang) atau ‘Ushul’ (pokok) perbedaan antara keduanya. Kalau sekiranya perbedaan itu terletak di ranah ‘Ushul’ maka tak mungkin terjadi karena dalam persoalan ‘Ushul’ yang ada adalah kesepakatan. Kalau terjadi perbedaan, berarti masuk dalam ranah ‘ijtihadi’. Lebih dari itu, benarkah fatwa mati yang dikeluarkan Syeikh Al-Barak terkait orang yang membolehkan laki-laki dan wanita di depan umum atau pada konteks Ushul orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Terlebih, fatwa ini adalah untuk semua individu apa secara umum? Itu perlu dijawab.
Tulisan bermuatan relativisme kembali diangkatnya, “Nabi Muhammad memang hanya satu. Kitab suci Quran memang hanya satu. Islam memang hanya satu. Namun ketika ia masuk dalam peradaban dan pikiran manusia, tak terhindari tercipta spektrum. Semua agama bahkan semua paham dan ideologi terkena hukum besi itu. Selalu ada perbedaan interpretasi (bahkan scism) dengan spektrum ultra moderat sampai ultra konservatif.” Tidak ada yang menentang bahwa perbedaan itu sudah menjadi fitrah manusia, namun yang menjadi masalah adalah dengan adanya perbedaan bukan berarti merelatifkan semua pendapat sehingga menafikan kebenaran absolut bahkan menihilkan kebenaran. Sebab dalam Islam, ranah ‘Ushul’ dan ‘furu’ sudah dibahas secara jelas.
Semakin jelas kelemahan pandangannya ketika memberikan contoh-contoh yang diambil dari praktik umat Islam “in acation” sebagai berikut: Pertama, Saudi melarang laki-laki dan perempuan bercampur kemudian secara bertahap membolehkan nonton bercampur pria di depan umum. Pertanyaannya, apakah ini ranah ijtihadi apa bukan? Kemudian, yang memutuskan itu pemerintahan apa ulama? Ini harus digalih lebih jauh sebelum mengeluarkan statement.
Kedua, bercampurnya shalat antara perempuan dan laki-laki dalam satu masjid bahkan menjadi khatib Jum’at. Diambillah kasus Aminah Wadud (2005), Raheel Razza (2010), Sherin Kankan (2016) yang kesemuanya pernah menjadi imam bagi jamaah campur baur laki-laki perempuan dan pernah jadi khatib Jum’at. Contoh-contoh ini memang tidak umum dan termasuk anomali. Empat madzhab sepakat bahwa tidak sah wanita menjadi imam laki-laki (Al-Jaziri, 2003: 372), apalagi shalat bercampur, dan menjadi khatib Jum’at bagi jama’ah laki-laki atau campur. Artinya, para ulama tak ada perselisihan atas larangan ini.
Padahal, mereka yang mempraktikkan ini (seperti Aminah Wadud dkk) ada beberapa kelemahan, di antaranya: Pertama, memahami agama dengan sudut pandang feminisme yang diadopsi dari pengalaman wanita di Barat. Sehingga, apa yang tidak cocok dengan wordlview feminisme, maka akan ditolak atau disesuaikan dengannya. Kedua, anti otoritas. Pendapat jumhur ulama diabaikan, malah pendapat yang nyeleneh diagungkan. Ketiga, tidak memahami ranah tsawabit (hal permanen) dan mutaghayyirat (bersifat dinamis) dalam agama sehingga pendapatnya diramu sesuai dengan syahwat sendiri yang penting Islam harus disesuakan dengan zaman
Bahkan, masjid-masjid yang friendly dengan LGBT di Amerika dan Eropa juga tak lupa diangkat oleh Denny yang disebut sebagai komunitas progresive muslim. Semua contoh-contoh yang dikemukakan sama sekali tidak mewakili pemahaman Islam yang sesungguhnya.
Sebelum akhir pembahasan ia menulis, “Jika hak asasi manusia adalah syarat minimal, apakah yang maksimal bagi individu? Jika aturan yang dipengaruhi agama boleh berubah, apakah yang abadi dalam agama?” Kemudian dijawab, “Pertanyaan ini pun bebas dijawab dan dipilih oleh setiap individu. Saya pribadi menyadari dan memilih: La Ilaha Illallah adalah prinsip hidup paling dahsyat untuk membebaskan batin manusia.”
Di sini yang dijadikan syarat minimal bagi individu dalam berinteraksi di ranah publik adalah HAM (Hak Asasi Manusia) bukan agama, ia juga mereduksi yang tidak berubah-rubah dalam Islam adalah kalimat “La ilaha illallah”.
Padahal, itu adalah bagian pertama dalam rukun Islam, masih banyak lagi yang merupakan bagian yang tak berubah-rubah, misalnya rukun Islam berikutnya, rukun iman dan bagian-bagian lain yang masuk dalam kategori “tsawâbit”.
Denny JA terjebak pada persoalan yang membingungkan. Di satu sisi dia mengakui adanya berbagai tafsir yang kebenarannya relatif, di sisi lain ia juga menyampaikan pendapat yang menurutnya benar. Jadinya, tulisannya bukan malah mencerahkan umat, tapi malah membingungkan.*
Penulis alumni Al Azhar, Mesir dan Pendidikan Kader Ulama (PKU)-Gontor