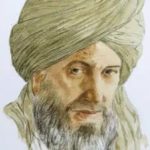Oleh: Faris Ibrahim
Hidayatullah.com | PESATNYA kemajuan teknologi tentu merupakan sebuah berkah tersendiri bagi manusia. Tak terkecuali bagi soalan pendidikannya. Teknologi telah berhasil mengurai segala kerumitan. Dari mulai memotong jarak, sampai melipat tempat. Hanya bermodalkan koneksi internet saja, kini pelajar bisa belajar di mana saja, kapan saja. Dengan gawai pintarnya yang “maha tahu”, pelajar zaman sekarang hampir saja dibuat lupa menyapa guru yang ada untuk membantu.
Itu satu. Harga mahalnya masih banyak lagi. Belajar yang tadinya sepertimana termaktub dalam Qur’an: “Qul sīrū fil ardhī fanzurū.“ Semenjak ada teknologi, pelajar dininabobokan seharian mengunci kamar, ‘berjalan- jalan’ di dunia maya, mengamati cemara, singa, dan Danau Toba, hanya sebatas visualisasinya saja. Proses panjang belajar sembari berjalan- jalan: menjelajah belantara hutan, meresapi alam di pegunungan, mengamati bintang di bukit sambil rebahan bersama teman- teman. Hilang.
Tentu amat disayangkan. Kita tidak ingin generasi ke depan tidak bersambung di pikirannya antara teori (nazharīah) dan realita (wāqi’). Kita tidak ingin apa yang tergambar di film The Teacher’s Diary jadi benar- benar kejadian. Ketika pendidikan di era teknologi menghasilkan mereka yang bisa mengajarkan soal uraian Matematika tentang kereta, tapi tidak tahu kereta itu seperti apa; karena bercerai di kepala mereka antara yang nyata dan maya.
Kebutaan Melihat Kenyataan
Karenanya, nir- kebijaksanaan berteknologi, bisa jadi akan melahirkan generasi yang bingung membedakan apa-apa yang di dunia nyata dan dunia maya. Hari ini mungkin kita masih bisa beramai-ramai menyangkal fenomena itu. Namun, data Childwise ‒sebuah lembaga riset dari Inggris‒ rasanya patut kita renungkan. Di tahun 2015, lembaga riset itu bilang bahwa anak- anak zaman sekarang rata-rata menghabiskan 6,5 jam perhari bermain gadget.
Jika tidak segera ditindak. Jangan heran kalau fenomena yang Mālik bin Nābī sebut sebagai thugyānul afkār (kediktatoran pikiran) akan segera merebak. Ternyata bukan hanya orang- orang (askhōs) yang bisa jadi diktator. Pun ragam pikiran (afkār) bisa jadi diktator. Pikiran menjadi diktator ketika ia berlaku semena-mena di dalam kepala empunya. Teori dijadikannya perkasa. Sampai- sampai realita tak mampu barang sedikit menyentuhnya.
Kediktatoran pikiran bermula, saat suatu pikiran (fikroh) dianggap sudah mapan tak perlu ‘disentuh- sentuh’ lagi. Saking mewahnya pikiran itu, atau saking besarnya pemikir (mufakkir) yang mengusungnya. Akhirnya mereka yang bersekolah di madrasah pemikiran itu, dibuat merasa tidak enak untuk sekadar mengutak- atik pikiran junjungannya itu. Seturutnya, tentu pemikiran atau teori itu mengendap. Kaku untuk sekadar bersentuhan dengan perkembangan zaman.
Ilustrasi Kediktatoran Pikiran
Ketika diktator pikiran berselancar di lalu lintas impuls para guru, jangan heran kalau kelak anak- anak kita malah semakin bingung setibanya di rumah. Sepulang sekolah, pikiran mereka malah terbujur kaku. Karena saat pak guru Biologi menjelaskan tentang anatomi daun, alih-alih membuka jendela, memetik salah satunya dari pohon di dekatnya, pak guru malah bersikeras mensyarah gambar daun yang samar hitam-putih di buku paket. Kukuh sekali.
Pun anak-anak kita‒ akhirnya berpuas diri dengan gambaran daun, ketimbang memetiknya langsung sehabis kelas pas jam istirahat. Toh pikir mereka, ada banyak daun yang Google bisa sediakan di layar gawai pintar mereka. Kebun di Google lebih subur menumbuhkan gambaran daripada kebun di pekarangan kelas. Nanti sajalah pas di rumah. Kan gampang. Tinggal ketik sekian detik sambil rebahan, seluk-beluk daun dari A sampai Z bisa terpampang ribuan pilihan.
Kediktatoran Pikiran dalam Perumpamaan Plato
The Allegory of the Cave, menggambarkan sekumpulan orang yang seumur hidupnya ditawan di gua. Tangan, kaki, leher mereka dirantai menghadap ke dinding. Tikus lewat di belakang, bayangannya yang mereka lihat di dinding, yang dipantulkan api unggun, itulah tikus sebenarnya dalam pandangan mereka. Mereka tidak mau tahu dengan tikus nyata yang ada di luar gua. Tikus yang ada di dinding gua sudahlah cukup nyata bagi mereka.
Mereka sudah tidak lagi peduli dengan realita. Realita yang mereka harus lihat di luar gua menyilaukan mata saja. Cukup selamanya di gua saja. Kira-kira begitulah gelagat mereka yang sudah kerasan ditawan oleh teknologinya sendiri. Gelagat mereka persis seperti tawanan gua yang Plato umpamakan di bukunya itu: Republik. Mereka menganggap yang nyata sebagai bayangan. Yang berbayang malah mereka anggap kenyataan.
Itulah buah dari kediktatoran pikiran. Ia membuat jurang antara yang nyata dan berbayang. Jangan heran, kalau fenomena itu nanti semakin merebak, akan sulit kita temukan gadis kecil seperti Toto- chan di novelnya Tetsuko Kuroyanagi yang senang bukan main bisa belajar di Tomoe Gakuen yang kelasnya gerbong kereta. Wajar memang. Kereta yang nyata, membosankan. Belakangan anak-anak lebih senang dengan animasi kereta di serial Thomas dan Teman.
Kebijaksanaan Berteknologi sangat Dibutuhkan
Teknologi tentu bukan satu-satunya yang menyuburkan kediktatoran pikiran (thugyānul afkār). Namun, teknologilah yang paling rentan. Teknologi adalah produk yang terlampau berguna. Teknologi bisa memotong jarak, melipat tempat. Namun teknologi juga bisa memotong imajinasi kita‒ mengirisnya kecil-kecil agar sukar menyatu dengan realitanya. Kata Karl Marx: “Memproduksi terlalu banyak sesuatu yang kelewat berguna menghasilkan orang-orang yang tidak berguna.”
Karenanya, teknologi harus diasupi kearifan. Dengannya teknologi bisa berguna membantu kita, bukan malah mengguna-guna kita. Tepat sekali judul yang John Naisbitt bubuhkan di bukunya: High Tech, High Touch. Itulah kunci mendayagunakan teknologi. Semakin canggih teknologi, memang harus semakin ‘luhur’ pula sentuhan kebijaksanaannya. Hanya dengan pendekatan seperti itulah fenomena kediktatoran pikiran (thugyānul afkār) bisa dikudeta, agar berhenti menyengsarakan empunya. Allāhu A’lam.*
Penulis adalah mahasiswa Akidah- Falsafah universitas al- Azhar, Kairo