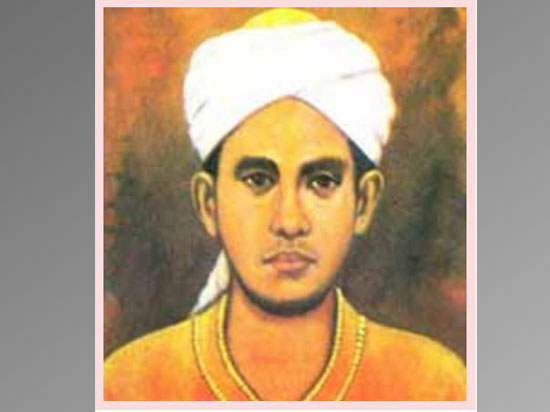Hidayatullah.com | TANGGAL 16 hingga 18 September 1982, sebuah tragedi terjadi di Sabra dan Shatila. Tragedi ini menjadi ingatan pilu yang terus diperingati dunia, khusunya bagi Palestina. Hingga kini 38 tahun kemudian, bersama dengan berbagai kejahatan lainnya atas umat Muslim, keadilan belum juga ditegakkan atas pihak yang bertanggung jawab.
Semua laporan mencatat pelaku utama dari pembantaian itu adalah milisi Kristen Lebanon, Falangis/Phalangis, yang berada di bawah kendali politik dan militer penjajah ‘Israel’. Korban kebanyakan adalah muslim Palestina yang tinggal di Sabra dan Shatila.
Sabra dan Shatila adalah dua kamp pengungsi yang berdampingan dengan Palestina yang terletak di barat daya Beirut. Kini lokasi tersebut tak lagi bisa dilacak dari peta daring milik Google.
Pada tanggal 18 September, setelah sekitar empat puluh jam pembantaian, gambar pertama yang menunjukkan korban sipil muncul di TV. Memicu kemarahan, kecaman dan dukacita di seluruh dunia.
Kezaliman ‘Israel’ yang Terus Memburu
Penduduk Palestina yang terusir mulai menetap di Lebanon setelah berdirinya negara palsu ‘Israel’. “Selama musim panas 1948, sekitar 110.000 orang Palestina diusir dari Galilea dan menyeberangi perbatasan ke Lebanon,” sebuah catatan yang dikutip oleh SciencesPo mengungkapkan.
Kebanyakan dari mereka menjadi pengungsi. Selama tahun 1970-an, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendirikan markas besarnya di Lebanon setelah para pemimpin dan aktivisnya diusir dari Yordania.
PLO bertanggung jawab atas sekitar 340.000 warga Palestina di Lebanon. Menyediakan pelayanan sosial dan prasarana dasar serta membangun kelembagaan di berbagai ranah (ekonomi, budaya, sosial, politik dan militer).
Pada tahun 1975, perang saudara pecah di Lebanon dengan dua kubu: “Kristen-konservatif” dan “Islam-progresif”, sebagaimana dalam laporan Picard tahun 2002. Kelompok pertama terutama termasuk orang Kristen (Maronit, khususnya) membentuk “blok di sekitar kepresidenan untuk pelestarian tatanan tradisional”.
Falangis (atau Kataeb), yang didirikan pada tahun 1936 oleh Pierre Gemayel, menguasai koalisi.
Pada tahun 1976, angkatan bersenjata Suriah mengambil bagian dalam perang saudara Lebanon, menginvasi Lebanon dan memperkuat satu kubu terlebih dahulu dan kemudian, kubu lainnya. Dukungan ‘Israel’ kepada orang-orang Kristen dilembagakan hampir pada waktu yang sama. Disepakati bahwa negara Yahudi itu akan membantu jika eksistensi umat Kristen Lebanon terancam. Menurut Falangis, jumlah pengungsi Palestina, sebagian besar Muslim, mengancam keseimbangan demografis antara Kristen dan Muslim di negara itu.
Mereka juga khawatir hal itu dapat melemahkan posisi menguntungkan mereka dalam permainan politik.
Setelah konflik dengan Suriah, Pasukan Pertahanan ‘Israel’ (IDF) kemudian menyerang PLO sebanyak dua kali pada Maret 1978 dan 6 Juni 1982, di mana tentara Zionis melakukan pengepungan terhadap Beirut.
Negosiasi kemudian dilakukan oleh utusan AS Philip Habib yang mencapai kesepakatan, untuk mengevakuasi pejuang Palestina dan pejabat PLO dari Lebanon dan membongkar kantor serta infrastruktur PLO.
Evakuasi dilakukan dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 1 September 1982 dan diikuti dengan penarikan pasukan multinasional yang datang lebih cepat dari jadwal. Beberapa pengungsi Palestina terutama di Sabra dan Shatila tetap tinggal, dalam keadaan rentan tanpa dukungan kepemimpinan.
PLO yang telah mempertahankan kamp sejak didirikan, setuju untuk meninggalkan Lebanon pada Agustus. Mereka diberi jaminan oleh Amerika bahwa warga sipil yang tertinggal akan dilindungi.
Pembantaian Terencana
Seorang Presiden Lebanon baru dipilih oleh Parlemen setelah evakuasi PLO. Bechir Gemayel, ketua Falangis, memenangkan pemungutan suara pada tanggal 23 Agustus.
Namun, Gemayel dibunuh pada tanggal 14 September sebelum mengambil alih jabatan –hingga kini masih tak jelas siapa aktor di balik pembunuhan tersebut. Pembunuhan politik ini memberi pemerintah Israel kesempatan untuk mengutuk Palestina, dan menjadi alasan untuk memasuki Beirut Barat.
Pembantaian Sabra dan Shatila dimulai dua hari kemudian.
Invasi dimulai pada hari Rabu tanggal 15 pagi, dengan penembakan tank dan kapal perang. Ariel Sharon, Menteri Pertahanan ‘Israel’ saat itu, tiba di lapangan pada pukul 9:00 untuk mengawasi operasi tersebut.
Falangis memasuki kamp Sabra dan Shatila pada sore hari Kamis tanggal 16. Terbukti oleh banyak sumber, pintu masuk mereka dikoordinasikan dengan, dan disahkan oleh IDF. Menurut penyelidikan Komisi Israel (Komisi Kahan, 1983), yang didasarkan pada kesaksian dari hierarki politik dan militer, para pemimpin Israel memutuskan untuk mengirim para Falangis di kamp-kamp selama pertemuan pada hari Rabu tanggal 15.
Mereka yang hadir adalah A. Sharon, kepala staf IDF Jenderal Rafael Eitan, Mayor Jenderal Amir Drori, kepala komando utara Israel, Fadi Ephram, panglima tertinggi Falangis, dan Elias Hobeika, kepala intelijen.
Israel memerintahkan milisi Kristen untuk memasuki kamp untuk mencari “teroris” dan senjata. Menurut mereka, teroris bersenjata 2000 tetap berada di kamp meskipun PLO dievakuasi; mereka harus dipaksa keluar.
Pada pagi hari Jum’at tanggal 17, unit Falangis baru memasuki kamp. Pada puncak penyerangan, anggota milisi berjumlah sekitar 400 orang.
Pembunuhan berlangsung sepanjang hari dengan bagiannya berupa eksekusi singkat, pembongkaran rumah, dan penjarahan barang-barang pribadi seperti uang atau perhiasan. Mayat tergeletak di jalanan, ditinggalkan di bawah reruntuhan atau dibuldoser di kuburan massal.
Tentara ‘Israel’ menembakkan suar sepanjang pembantaian pada malam hari untuk membantu penerangan bagi milis Falangis. Para saksi melihat banyak penduduk menumpuk di atas truk dan dibawa keluar kamp ke tujuan yang tidak diketahui.
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka adalah “yang hilang” dari pembantaian Sabra dan Shatila.
Desas-desus pertama tentang pembantaian mencapai wartawan dari pengungsi yang melarikan diri.
Komisi Penyelidikan Israel (Komisi Kahan, 1983) mengungkapkan bahwa pada pukul 12:00 siang, Jenderal A. Drori memperingatkan atasannya Jenderal R. Eytan di Tel Aviv yang, kemudian, memutuskan untuk terbang ke Beirut untuk memeriksa. Kepala staf IDF bertemu dengan F. Ephram dan E. Hobeika pada jam-jam berikut: mereka menyetujui penarikan anggota milisi untuk keesokan paginya.
Sejarawan Lebanon Bayan al-Hout (2004) melakukan penelitian lapangan antara 1982 dan 1984 tentang korban di Sabra dan Shatila. Dia mengidentifikasi 1.390 kasus: 906 tewas dan 484 “hilang”.
Amnon Kapeliouk, seorang jurnalis ‘Israel’, mengerjakan rekonstitusi kejadian segera setelah pembantaian. Menurut pendapat A. Kapeliouk, jumlah korban mencapai 3.000 – 3.500.
Ia menambahkan ke dalam 2.000 kematian yang secara resmi terdaftar dan diakui oleh otoritas Lebanon tiga jenis korban lainnya:
Pertama, mereka yang dimakamkan di kuburan massal dan tak dapat diidentifikasi setelah penggalian.
Kedua, mereka yang meninggal di bawah reruntuhan rumah mereka.
Ketiga, orang “hilang” yang dibawa hidup-hidup ke tujuan yang tidak diketahui dan tidak pernah kembali.
Menurut Organisasi Palang Merah, jumlah orang “hilang” mencapai 359 antara tanggal 18 dan 20 September. Tidak ada perkiraan jumlah yang terluka diberikan, tetapi kasus mutilasi sangat banyak.
Pada tahun 2004, film dokumenter Jerman berjudul Massaker (diproduksi oleh Monika Borgmann, Lokman Slim et Hermann Theissen, film dokumenter ini dianugerahi penghargaan beberapa kali di festival film), memberikan kesempatan bicara kepada pihak algojo.
Enam Falangis yang tidak disebutkan namanya tak hanya menceritakan tentang bagaimana mereka membunuh warga sipil di Sabra dan Shatila, tetapi juga bagaimana mereka telah dilatih oleh IDF selama perang saudara dan bagaimana mereka berada di bawah perintah mereka ketika mereka melakukan pembantaian (Mandelbaum, 2006).* (BERSAMBUNG)