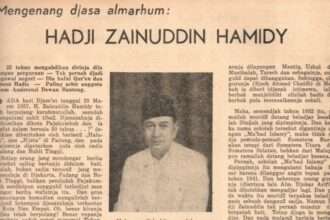Di awal ekspansi Muslim, masyarakat di Syam dan Irak yang beragama Kristen yang sebelumnya bagian dari peradaban kompleks akhirnya dipimpin masyarakat Arab Muslim dengan peradaban sangat sederhana
Oleh: Dr. Alwi Alatas
Hidayatullah.com |SEJAK awal era Khulafa’ al-Rashidin, proses ekspansi kaum Muslimin berlangsung dengan cepat. Di pertengahan era tersebut, Kekaisaran Persia runtuh dan sebagian wilayah Byzantium jatuh ke tangan kaum Muslimin.
Masyarakat di kawasan itu, yang tentunya belum mengenal dan belum beragama Islam, sejak saat itu hidup di bawah pemerintahan yang baru.
Gesekan antara masyarakat Muslim di satu sisi dengan peradaban Romawi (Byzantium) dan Persia di sisi lain sebetulnya sudah mulai terjadi sejak akhir era kenabian. Namun, selepas wafatnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, sempat terjadi riddah di Jazirah Arab.
Orang-orang Arab yang baru masuk Islam berbalik murtad dan memberontak terhadap Madinah sebagai pusat pemerintahan Muslim. Untuk sementara, kaum Muslimin harus memusatkan perhatian mereka pada ancaman internal ini.
Bagaimanapun, Sahabat Abu Bakar al-Shiddiq dapat mengatasi keadaan tersebut. Bahkan setelah berakhirnya riddah, Khalifah yang pertama itu langsung melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kekuasaan Byzantium dan Persia.
Pada era khalifah yang berikutnya, Umar bin al-Khattab, wilayah Mesir dan Syam (mencakup kurang lebih wilayah Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah modern) dapat direbut sepenuhnya oleh kaum Muslimin dari tangan Byzantium. Adapun wilayah Irak yang menjadi pusat pemerintahan Persia juga berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin pada masa yang hampir bersamaan.
Masyarakat di Syam dan Irak banyak yang beragama Kristen dan sebelumnya merupakan bagian dari peradaban yang lebih kompleks. Kini mereka dipimpin oleh masyarakat Arab Muslim yang peradabannya masih sangat sederhana.
Kesederhanaan orang-orang Arab Muslim ketika itu tidaklah mengherankan. Banyak di antara mereka yang menyertai futūḥāt (penaklukan) berasal dari suku-suku semi nomadik yang cara berfikir dan cara hidupnya masih sangat bersahaja. Maklum jika orang-orang Kristen melihat fenomena itu, sebagaimana ditulis oleh Maximus the Confessor antara tahun tahun 634 dan 640, sebagai penyerbuan “bangsa barbar dari padang pasir” (Brock, 1982: 9).
Ini bukan pertama kalinya peradaban yang lebih kompleks ditaklukkan oleh “bangsa barbar”. Dalam kasus semacam itu, biasanya bangsa penakluk akan terserap ke dalam kebudayaan bangsa yang ditaklukkan, karena kebudayaan yang terakhir ini lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh para penakluk.
Namun, penaklukkan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Muslim di abad ke-7 itu, “tidak berakhir dengan para penakluk diserap ke dalam masyarakat yang mereka kuasai, tetapi mengarah pada penciptaan kerangka sosial dan intelektual baru di mana budaya orang-orang yang ditaklukkan dapat ditafsirkan ulang dan dikembangkan” (Juynboll, 1982: 1).
Kesahajaan suku-suku Arab penakluk dapat dilihat dalam kasus-kasus tertentu. Pada satu kesempatan, ketika orang-orang Arab Muslim baru saja mengalahkan Kekaisaran Persia, beberapa anggota suku menemukan sekantong kamper. Mereka mengira itu adalah garam dan menggunakannya untuk masakan mereka.
Seorang Kristen (Nestorian) yang ada di situ memberitahu mereka bahwa itu bukan garam dan menawarkan untuk menukar kamper itu dengan sepotong pakaian. Orang-orang Arab itu setuju.
Mereka kemudian mengenakan pakaian itu pada salah satu rekan mereka dan mengagumi keindahannya. Belakangan mereka mengetahui bahwa harga pakaian itu ternyata hanya 2 dirham saja (al-Ṭabarī, 1992: XII/32). Padahal harga kamper dari kualitas yang bagus biasanya sangat mahal (“Camphor,” 1990).
Tentu saja ini bukan berarti semua orang Arab pada masa itu tidak bisa membedakan antara kamper dan garam, terlebih mereka yang hidup di kawasan urban. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menyuruh Ummu ‘Atiyah untuk menggunakan kamper (kāfūran, aw shay’an min kāfūr) saat memandikan jenazah puteri beliau yang wafat (Muslim, 2007: II/466-467; hadits no. 2168).
Walaupun bersahaja, mereka secara umum tunduk pada adab peperangan yang diatur di dalam Islam. Selama proses penaklukkan, para komandan Muslim biasanya memberikan tiga pilihan kepada pihak lawan: apakah mereka masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang.
Menghadapi pilihan semacam itu, sebagian masyarakat Kristen memilih untuk membayar jizyah. Tokoh di al-Hirah yang bernama ‘Amr bin ‘Abd al-Masīḥ bin Buqaylah (Ibn Buqaylah), misalnya, berkata kepada Khalid bin al-Walid saat pasukan Muslim masuk ke wilayah itu; “Kami tidak ada keperluan untuk berperang denganmu.” Maka mereka pun sepakat untuk membayar jizyah kepada kaum Muslimin (al-Ṭabarī, 1993: XI/6-7; pada bagian tersebut namanya tertulis sebagai ‘Abd al-Masīḥ ibn ‘Amr, tetapi pada bagian selebihnya di dalam buku ditulis sebagai ‘Amr ibn ‘Abd al-Masīḥ).
Ibn Buqaylah sempat membantu menjadi penunjuk jalan bagi rombongan yang membawakan makanan ke tenda kaum Muslimah yang menyertai para mujahidin (tentara Muslim). Saat rombongan mendekat, para Muslimah mengira mereka telah diserang oleh musuh. Maka mereka pun berteriak dan melempari rombongan yang datang itu dengan batu dan kayu untuk melindungi diri mereka dan anak-anak yang ada di situ.
Melihat hal itu, Ibn Buqaylah berujar, “Beginilah keadaannya kaum perempuan dari tentara (Muslim) ini” (al-Ṭabarī, 1993: XI/210). Para Muslimah itu rupanya juga sangat pemberani dan sigap dalam membela diri.
Ada juga orang-orang Kristen yang memilih untuk berperang, walaupun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan. Al-Ṭabarī (1993: XI/88) misalnya menyebutkan bahwa saat pasukan Byzantium terdesak oleh pasukan Muslim di kawasan Yarmuk, mereka berlindung di balik parit, “sementara para pendeta, diakon, dan biarawan mendesak mereka dan meratap pada mereka [akan nasib] Kekristenan.”
Di tempat lainnya di Irak, Bani Taghlib yang beragama Kristen berperang bersama pasukan Persia dalam menghadapi pasukan Muslim. Namun ada anggota Bani Taghlib yang sudah merasa muak dengan kekuasaan Persia dan memutuskan untuk berpihak kepada pasukan Arab Muslim.
Pimpinan pasukan Persia yang bernama Mihran lantas dibunuh oleh seorang pemuda Kristen Bani Taghlib. Karena tindakannya itu, si pemuda disambut oleh kaumnya bak pahlawan (al-Ṭabarī, 1993: XI/206).
Penduduk al-Quds atau Yerusalem – ketika itu dikenal dengan nama Iliyā – merasa khawatir saat mendengar tentang masuknya pasukan Muslim ke Syam. Pemimpin komunitas Kristen di kota itu adalah Uskup Sophronius.
Pada akhir tahun 634, 2 atau 3 tahun sebelum jatuhnya al-Quds, Sophronius berpidato di kota itu sambil menyebut-nyebut Betlehem yang jatuh ke tangan Muslim. Ia antara lain berkata, “Kita hanya perlu bertobat, dan kita akan menumpulkan pedang orang-orang Ismail … serta mematahkan busur panah orang-orang Hajar [Ibu Ismail], dan melihat Betlehem kembali” (Brock, 1982: 9).
Al-Quds akhirnya dikepung oleh pasukan Muslim, sementara penduduknya berjuang mempertahankan kota itu. Beberapa sumber Muslim menyinggung tentang adanya nubuwat di kalangan umat Kristiani yang menyebutkan bahwa al-Quds tidak akan jatuh kecuali secara langsung ke tangan Umar.
Setelah adanya informasi itu, Umar bin al-Khattab berangkat ke al-Quds. Ia menyerahkan kepemimpinan sementara di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Saat Umar tiba, kota itu membuka tembok benteng bagi kaum Muslimin dan penduduknya setuju untuk membayar jizyah (aṣ-Ṣallābi, 2007: II/291-292).
Pada masa itu agama Islam dapat dikatakan belum dikenal oleh penduduk Syam dan Irak, sehingga kecil kemungkinan mereka mau langsung menerima pilihan pertama yang ditawarkan oleh pasukan Muslim (yaitu untuk masuk Islam). Walaupun begitu, rupanya ada juga yang masuk Islam di tengah pertempuran.
Salah seorang pimpinan pasukan Byzantium di Syam, Jurjah (George?) putra Tawdhura (Theodore), meminta dialog khusus dengan Khalid bin al-Walid. Perbincangan di antara keduanya menggerakkan hati Jurjah untuk mempelajari Islam lebih jauh. Khalid mengajak Jurjah ke tendanya, membimbingnya untuk wudhu dan shalat dua raka’at.
Tiba-tiba pecah pertempuran di antara pasukan Muslim dan Byzantium. Khalid keluar untuk bertempur, ditemani oleh Jurjah yang kini ikut berperang di pihak Muslim. Jurjah akhirnya gugur di dalam pertempuran itu, padahal ia baru saja masuk Islam (al-Ṭabarī, 1993: XI/95-97).
Masyarakat Kristen lainnya ada yang memeluk Islam tidak lama setelah Muslim menguasai Syam dan Irak. Di antara yang melakukan hal ini adalah Bani Ghassan.
Bani Ghassan merupakan kabilah Arab yang memimpin sebuah kerajaan di selatan Syam sebagai vasal dari Byzantium. Pusat pemerintahan kerajaan itu berada di Buṣa. Mereka adalah penganut Kristen Monophysite, berbeda dengan keyakinan Kristen Chalcedonian yang dipegang oleh Kekaisaran Byzantium (al-Ṭabarī, 1993: XI/57).
Bersama Byzantium, mereka telah terlibat konflik dengan kaum Muslimin sejak era Nabi ﷺ. Ketika terjadi ekspansi Islam di era Khulafa’ al-Rashidin, mereka pada awalnya berperang melawan Muslim, tetapi kemudian memutuskan untuk masuk Islam bersama dengan pemimpinnya yang terakhir, Jabalah bin al-Ayham.
Jabalah pergi ke Madinah, yang disambut baik oleh Umar bin al-Khattab. Tetapi saat ia pergi haji beberapa waktu kemudian, ia memukul seorang pria Bani Fazar yang menginjak pakaiannya. Pria Fazari ini menuntutnya di hadapan Umar.
Jabalah yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari orang Arab badui itu tidak bisa menerima keputusan Umar yang memproses tuntutan tersebut. Maka ia melarikan diri pada malam hari ke Konstantinopel dan murtad kembali ke agama Kristen (aṣ-Ṣallābi, 2007: I/197-198).
Konversi ke agama Islam sangat digalakkan dan mereka yang baru masuk Islam biasanya disambut dengan hangat. Namun, pelanggaran seperti pada kasus di atas tetap harus diselesaikan secara adil.
Dalam contoh kasus di Mesir, mereka yang kalah berperang dan menjadi tawaran perang ditawari untuk masuk Islam. Mereka yang setuju masuk Islam disambut dengan gembira oleh kaum Muslimin. Sebagian lainnya yang tetap dalam agama lama mereka dibiarkan dan mereka tidak dipaksa untuk pindah agama (aṣ-Ṣallābi, 2007: II/337). Hal semacam ini kemungkinan berlaku juga di Syam dan Irak.
Ayah dari Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi’in yang sangat menonjol di eranya, dahulunya adalah seorang tawanan perang Kristen yang kemudian masuk Islam (al-Ṭabarī, 1993: XI/18). Para mualaf lainnya pun ada yang keturunannya di kemudian hari menjadi tokoh penting di dunia Islam.
Saat menaklukkan ‘Ayn al-Tamr yang sebelumnya berada di bawah kendali Persia, Khalid bin al-Walid menemukan sebuah gereja. Di dalamnya dijumpai empat puluh anak lelaki yang menganggap diri mereka sebagai sandera. Mereka mempelajari Injil di dalam ruangan terkunci, yang dibuka paksa oleh Khalid. Khalid kemudian menyerahkan mereka kepada beberapa anggota pasukan Muslim.
Di antara anak-anak itu ada Abū ‘Amrah, yang cucunya ‘Abd Allah bin ‘Abd al-A‘lā merupakan seorang penyair kenamaan yang memiliki hubungan rapat dengan para khalifah Bani Umayyah. Selain itu ada pula Nuṣayr, yang anaknya Mūsā kelak menjadi gubernur Ifriqiya (Afrika Utara). Musa inilah yang menginstruksikan Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia pada tahun 711. Nama lainnya yang penting untuk disebutkan adalah Sīrīn. Puteranya Muhammad bin Sīrīn kelak menjadi seorang ulama besar di kota Basrah (al-Ṭabarī, 1993: XI/55).
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat di kawasan itu banyak yang masuk Islam. Namun, ada pula yang tetap mempertahankan agama asal mereka. Di masa sekarang ini pun masih dapat dijumpai komunitas-komunitas Kristen lokal di Suriah, Palestina, Irak, dan kawasan Timur Tengah lainnya, yang secara umum hidup berdampingan dan saling bertoleransi dengan masyarakat Muslim.*/Kuala Lumpur,19 Dzul Hijjah 1443/ 19 Juli 2022
Penulis adalah staf pengajar di bidang Sejarah dan Peradaban pada International Islamic University Malaysia (IIUM)
- Daftar Pustaka
- Brock, S. P. 1982. Syriac Views of Emergent Islam. Dalam G. H. A. Juynboll. Studies on the First Century of Islamic Society. Southern Illinois University.
- Camphor. 1990. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/camphor-npers
- Juynboll, G. H. A. 1982. Introduction. Dalam G. H. A. Juynboll. Studies on the First Century of Islamic Society. Southern Illinois University.
- Muslim, Imam Abul Hussain ibn al-Hajjaj. 2007. English Translation of Sahih Muslim, Vol. II (Trans. Nasiruddin al-Khattab). Riyadh: Darussalam.
- Aṣ-Ṣallābi, ‘Ali Muhammad. 2007. ‘Umar ibn al-Khattāb: His Life and Times, Vol. 1. International Islamic Publishing House.
- Aṣ-Ṣallābi, ‘Ali Muhammad. 2007. ‘Umar ibn al-Khattāb: His Life and Times, Vol. 2. International Islamic Publishing House.
- Al-Ṭabarī. 1992. The History of al-Ṭabarī, Vol. XII (Trans. Yohanan Friedmann). New York: State University of New York Press.
- Al-Ṭabarī. 1993. The History of al-Ṭabarī, Vol. XI (Trans. Khalid Yahya Blankinship). New York: State University of New York Press.