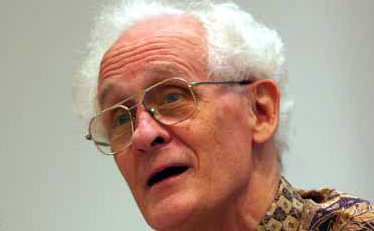Oleh: Dr. Adian Husaini
PADA 1 Mei 2015, saya memulai perjalanan darat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Yogyakarta menjadi tujuan pertama. Di sini, pada 1-3 Mei 2015, diselenggarakan Silaturrahim Nasional Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) ke-4. Acara tiga bulanan MIUMI kali ini memiliki makna penting, di tengah situasi carut-marut isu-isu politik dan keagamaan tingkat nasional dan internasional.
MIUMI dibentuk pada 2013 dengan niat utama ikut berpartisipasi dalam membangun peradaban Islam di Indonesia, dengan semboyan: “Mewujudkan Indonesia yang Lebih Beradab”. Para perumus Dasar Negara Indonesia telah bersepakat membangun kemanusiaan yang adil dan beradab; bukan kemanusiaan yang zalim dan biadab.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam memerintahkan umatnya untuk mencegah orang yang berlaku zalim maupun yang terzalimi. (Unshur akhaaka zhaaliman au madzluuman). Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima’iyyah) bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ironisnya, meskipun tahun ini usia kemerdekaan kita sudah 70 tahun, kita masih menyaksikan begitu banyak kezaliman berlaku. “Adil”, maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan ketentuan Allah. Tauhid jangan disamakan dengan kemusyrikan. Iman tidak sama dengan kekufuran. Orang taqwa jangan disamakan kedudukannya dengan orang fasik (jahat). Orang taqwa itu mulia. Orang fasik harus diragukan ucapan dan pengakuannya. Pezina seharusnya ditetapkan sebagai pelaku kejahatan, bukan dijadikan bintang pujaan.
Prof. Naquib al-Attas menekankan, bahwa tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan pada diri seseorang sebagai manusia. Dan tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang baik. Ada pun elemen paling mendasar dalam konsep pendidikan Islam adalah penanaman adab dalam diri seseorang. (The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a good man… the fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab).
Mewujudkan Indonesia yang lebih beradab bukan hal mudah. MIUMI memiliki strategi memberdayakan para ulama muda secara keilmuan dan akhlak, sehingga mereka mampu menjadi teladan dan pemimpin bagi masyarakat. MIUMI menyadari, ini bukan perkara ringan. Karena itu, MIUMI meletakkan program pemberdayaan ulama ini sebagai program utama. Dalam Silatnas di Yogya itu, para aktivis MIUMI yang datang dari Aceh sampai Papua mendiskusikan masalah ini dengan serius. Tradisi yang baik dari MIUMI selama ini, para delegasi datang ke Silatnas dengan biaya mereka sendiri.
Esoknya, 4-10 Mei 2015, saya memulai perjalanan di berbagai kota untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemikiran Islam, Bedah Novel KEMI, dan Dialog Peradaban. Acara berawal di Yogyakarta, lalu berturut-turut ke Solo, Ponorogo, Malang, Surabaya, dan Semarang. Alhamdulillah, semua acara berlangsung dengan baik, dan saya diberi keselamatan dan kesehatan sampai tiba kembali di Jakarta pada 11 Mei 2015.
Pada 4 Mei, masih di Kota Yogyakarta, Pelatihan Pemikiran Islam diselenggarakan di Penerbit Pro-U Media. Meskipun diumumkan sehari sebelumnya, melalui media sosial, peserta yang hadir mencapai sekitar 200 orang. Pelatihan berlangsung sekitar 6 jam, mulai jam 09.00-15.00. Sebagian besar peserta adalah mahasiswa, disamping sejumlah dosen di beberapa perguruan tinggi di Yogya. Ada juga seorang polisi yang sedang mengambil studi S-3 Pendidikan Islam di sebuah Universitas di Yogya.
Saya memaparkan peta penyebaran paham liberalisme dan pluralisme, setelah 10 tahun lalu, MUI mengeluarkan fatwa tentang Sekularisme, Pluralisme, dam Liberalisme (Sipilis). Meskipun hanya sebuah pendapat hukum (legal opinion), fatwa MUI itu sempat membuat para aktor penyebar paham liberalisme tersengat dan sebagian melampiaskan kekesalannya. Beberapa buku dan disertasi telah diterbitkan untuk membantah fatwa MUI tersebut. Sayangnya, beberapa tokoh ikut-ikutan mendukung penyebaran paham pluralisme, tanpa memberikan klarifikasi makna yang memadai.
Tapi, pada kesempatan tersebut, saya lebih banyak membahas penanggulangan paham liberalisme dalam kurikulum pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai Pendidikan Tinggi. Sejumlah buku ajar di sekolah-sekolah masih didominasi paham sekularisme. Al-Quran belum dijadikan rujukan utama dalam penyusunan buku ajar, khususnya yang dikategorikan sebagai “pelajaran umum”.
Berikut ini beberapa contohnya.
Misalnya, dalam buku Sejarah Indonesia, Kelas X SMA/MA, SMK/MAK, Kurikulum 2103, Kemendikbud, hlm. 9-10, ditulis: “Salah satu diantara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah Teori “Dentuman Besar” (Big Bang), seperti ditemukan oleh sejumlah ilmuwan, seperti ilmuwan besar Inggris, Stephen Hawking. Teori ini menyatakan, bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagad raya…“.
Sebenarnya, lebih tepat jika paparan tentang terbentuknya bumi itu disebut “hipotesis ilmiah” atau “dugaan ilmiah”, karena itu masih dalam taraf dugaan. Sementara, pada saat yang sama, ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta disingkirkan, dan tidak dianggap layak sebagai dasar rujukan ilmiah. Seolah-olah, penyusun buku ajar itu berpesan kepada para guru dan orang tua, “Silakan kalian ajarkan anak-anak kalian untuk membaca dan menghafal al-Quran, tetapi jangan coba-coba untuk membawa-bawa al-Quran ke dalam pelajaran sejarah, Biologi, dan sebagainya.”
Saya teringat kata-kata seorang guru, ketika duduk di bangku SMA, saat saya membantah teori evolusi Darwin, “Adian, ini pelajaran Biologi; bukan pelajaran agama!” Saya pun terdiam, meskipun saya tahu, kata-kata guru itu tidak betul, berdasarkan beberapa buku yang sudah saya baca ketika itu. Saat lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, saya memilih menjadi guru Biologi. Dengan itu saya bebas mengkritik teori evolusi, yang memang tidak memenuhi standar tahapan metode ilmiah: observasi, hipotesa, eksperimen, dan kesimpulan.
Contoh lain, pada buku yang sama, hlm. 31-32, ditulis: “Dalam publikasinya itu, Dubois menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan dari kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia… Saat ini Pythecanthropus diterima sebagai hominid dari Jawa, bagian dari homo erectus.”
Begitu kuatnya dominasi sekulerisme-materialisme dalam buku ajar ini, sehingga untuk mencari asal-usul manusia pun, para siswa dipaksa untuk berpegang pada paham empirisisme. Mereka dipaksa untuk mengakui keilmiahan teori Darwin bahwa moyang manusia adalah kera. Sementara itu, pada saat yang sama, pada mata pelajaran Agama Islam, para siswa diajarkan bahwa manusia berasal dari Adam.
Wajar, jika kemudian, ada siswa yang bertanya, pendapat mana yang benar? Apakah Adam itu juga kera, atau Adam itu berasal dari kera juga? Ada yang kemudian berpikir praktis, bahwa memang ada dua kebenaran; yaitu kebenaran agama dan kebenaran sains. Kedua kebenaran itu tidak bisa disatukan, karena memiliki dua wilayah yang berbeda. Apakah memang benar begitu?
Tentu saja, cara pandang sekuler semacam itu tidak sesuai dengan cara pandang tauhidik dalam Islam. Anggapan bahwa kera adalah moyang manusia, sama sekali tidak bisa dibuktikan secara empiris-ilmiah. Itu masih merupakan praduga. Hingga sekarang, manusia tidak bisa mengubah kera menjadi manusia; dengan cara apa pun. Silakan para pakar evolusi berkumpul! Pilihlah kera yang paling cerdas; lalu kawinkan dengan manusia yang paling cerdas! Lihatlah hasilnya! Atau, kera yang supercerdas itu kasih beasiswa sampai tingkat S-3! Lalu, lihat hasilnya, apakah kera itu bisa berubah menjadi manusia?
Dalam acara Pelatihan Pemikiran Islam di Yogyakarta itu, seorang mahasiswa Biologi bertanya, bagaimana menghadapi profesornya yang sangat memaksakan teori evolusi kera merupakan asal-usul manusia itu. Saya jawab, bahwa, “Anda harus menggantikan professor itu. Belajarlah yang baik sampai anda mampu menggantikan professor anda! Setelah itu, ajarkan ilmu yang benar kepada mahasiswa; bahwa manusia adalah keturunan manusia dan kera juga keturunan kera!”
Sebab, perbedaan hakiki antara manusia dan kera bukan pada aspek-aspek jasadiah yang menjadi fokus penelitian pada ilmuwan sekuler, tetapi perbedaan hakiki antara manusia dan kera adalah pada akalnya. Akal manusia itu merupakan fungsi dari Ruh yang secara khusus ditiupkan Allah kepada manusia. Akal bukan hasil evolusi biologis. Karena dunia ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi masih menolak wahyu sebagai sumber ilmu, maka mereka tidak dapat menerima al-RUH sebagai objek ilmu.
Akibat hegemoni epistemologi ilmu yang sekuler tersebut, mereka kehilangan pemahaman manusia yang utuh dan komprehensif. Manusia hanya dipahami sebagai entitas jasadiah sebagaimana monyet, yang tujuan utama hidupnya hanya untuk mencari makan untuk kesenangan. Kuliah hanya ditujukan untuk supaya lulus dan kemudian bisa cari makan.
Saya katakan pada para mahasiswa:
“Jika kalian kuliah, tujuannya hanya untuk cari makan, maka pikirkanlah, kambing dan monyet itu tidak usah kuliah sudah bisa cari makan! Jika hanya itu tujuannya maka, kalian rugi! Sebab tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik adalah yang kenal Tuhannya, tahu tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan, dan memiliki kemampuan untuk mandiri melaksanakan kewajiban pribadi dan sosialnya.”
Contoh buku ajar lain yang kurang tepat dalam memahami realitas sejarah adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemendikbud, kurikulum 2013, SMP/MTS kelas VIII. Dalam buku ini tertulis: “Secara umum, kegagalan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam mengusir penjajah adalah:… Bersifat lokal/kedaerahan… lebih mengandalkan kekuatan senjata… tergantung pada pimpinan… belum terorganisir secara nasional dan modern (hlm.91)
Buku ini memberikan cara pandang tentang “kegagalan perjuangan” para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Sepatutnya, kita berhati-hati memberikan istilah “gagal” untuk perjuangan para pahlawan tersebut. Sebutlah perjuangan Pangeran Diponegoro. Apakah Diponegoro gagal? Apakah perjuangan Syekh Yusuf Maqassari, Cut Nya’ Dien, Teuku Umar, Antasari, Sultan Hasanuddin, dan sebagainya, bisa dikatakan gagal?
Mari kita bandingkan dengan cara al-Quran dalam menggambarkan perjuangan para Nabi. Meskipun perjuangannya berakhir dengan pembakaran dan pengusiran dirinya, Ibrahim (a.s.) tidak dikatakan gagal perjuangannya. Ibrahim telah berhasil memberikan keteladanan dalam perjuangan, meskipun harus melawan keluarga dan masyarakatnya sendiri. Iblis – meskipun sukses melengserkan Adam dari sorga – tidak dikatakan sebagai sosok yang berhasil. Tapi, Iblis dilaknat oleh Allah. Nuh a.s. pun tidak dikatakan gagal, meskipun hanya sedikit saja kaumnya yang mau mengikutinya. Jangan dikatakan, bahwa Nuh a.s. tidak menguasai teknik komunikasi massa, sehingga kalah hebat dengan para selebritis!
Sepatutnya, pelajaran sejarah memberikan pemahaman yang baik kepada para siswa, bahwa para pahlawan kita tidak gagal dan tidak kalah. Mereka telah menunjukkan keteladanan dalam pengorbanan. Dan itulah kunci kemajuan suatu bangsa, yakni kecintaan rakyatnya untuk berkorban. Jika nilai-nilai pengorbanan itu sudah dikecilkan maknanya, jangan heran jika dari sekolah-sekolah itu akan lahir lulusan-lulusan yang bermental serakah, materialis, dan individualis; enggan berkorban untuk perjuangan menegakkan kebenaran.
Di sinilah pentingnya buku-buku ajar untuk anak-anak dan murid-murid kita disusun dengan perspektif yang benar, agar tujuan pendidikan nasional untuk melahirkan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, bisa terwujud. Wallahu a’lam (bersambung).*
Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com