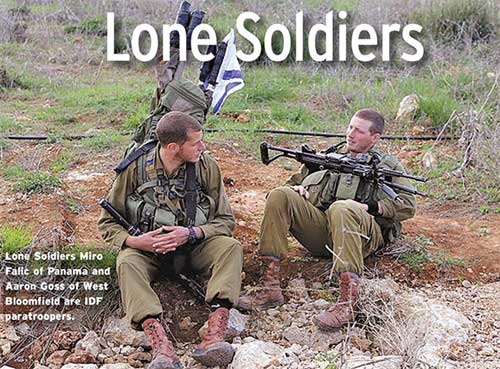Oleh Anu Sukhla
Hidayatullah.com–Kudeta militer di Myanmar telah dikecam sebagai penghinaan terhadap demokrasi oleh kekuatan global. Tetapi para analis mengatakan bahwa tentara telah melakukan penembakan sebelum pemerintah sipil digulingkan dan akan terus melakukannya sekarang, membuat sedikit perbedaan pada penderitaan Muslim Rohingya.
“Bagian dari masalah bagi organisasi seperti saya adalah bahwa hak asasi manusia telah jatuh ke dalam agenda internasional. Jauh lebih sulit daripada sebelumnya bagi kami untuk menghasilkan tekanan dan memaksa pemerintah untuk bertindak,” Mark Farmaner, direktur Kampanye Burma Inggris mengatakan kepada The New Arab. Geopolitik terus menjadi pusat perhatian, kata Farmaner, terlepas dari fakta bahwa “genosida” telah terjadi.
Meningkatnya kekerasan militer baru-baru ini yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi juga tidak boleh diabaikan, kata Ana Colins, fasilitator pendidikan yang sebelumnya bekerja dengan pengungsi dari Myanmar di Cox’s Bazar dan di kota perbatasan Mae Sot, Thailand.
“Sementara kudeta akan membuat sedikit perbedaan bagi Rohingya, kekerasan terang-terangan terhadap warga sipil di daerah perkotaan juga belum terlihat sejak puncak Revolusi Saffron pada 2007,” ungkapnya kepada The New Arab.
Dipuji sebagai wajah demokrasi yang tersenyum, Aung San Suu Kyi sibuk berpacaran dengan dunia yang kontras yang hampir mencopotnya dari hadiah Nobel Perdamaian. Pemimpin Myanmar yang sekarang digulingkan mendukung pendanaan UE dan AS untuk proses demokrasi Myanmar sementara juga menolak tuduhan genosida militer di Mahkamah Internasional pada 2019.
Dinamika serupa sedang bermain dalam kecaman kekuatan Barat atas kudeta Myanmar dan tuntutan untuk “kembali ke demokrasi”, kata para analis, yang menempatkan prioritas ekonomi dan geopolitik di atas pelanggaran HAM massal.
Menurut Profesor Azeem Ibrahim, direktur di Pusat Kebijakan Global di Washington, visi mantan presiden AS Barack Obama selama kunjungannya tahun 2017 ke Myanmar adalah untuk menyegel warisannya sebagai “presiden pembuka gerbang”. Dengan kata lain: mencabut sanksi dan menjauhkan Myanmar dari pengaruh China. Puluhan juta dana AS untuk “proses demokrasi” Myanmar selama bertahun-tahun “hanyalah sandiwara untuk menunjukkan ini adalah demokrasi yang berfungsi bergerak ke arah yang benar,” pungkasnya.
Sejak 2012, AS telah menyediakan hampir $ 1,5 miliar dalam pendanaan untuk “mendukung transisi demokrasi dan transformasi ekonomi Burma,” sementara UE telah menyediakan sekitar € 700 juta. Menurut Ibrahim, “menginvestasikan uang ini sama sekali hanya membuang-buang waktu karena Anda tidak dapat mengadakan pemilihan di mana sebagian besar penduduk tidak diizinkan untuk memilih”.
Pendanaan semacam itu berusaha untuk bersaing dengan proyek-proyek ekonomi China seperti Belt and Road Initiative dan String of Pearls Project, yang membuat Myanmar tetap dekat dan menarik bagi negara-negara seperti Pakistan, yang “tak seorang pun ingin menyentuh tiang tongkang sampai China menginvestasikan $ 62 miliar,” ujar Ibrahim.
Baca juga: Respon Barat terkait Kudeta Myanmar Bongkar Kemunafikan Dukungannya terhadap Demokrasi
AS gagal begitu saja “menaruh uangnya di mana mulutnya berada”, mengirim lebih banyak negara ke pelukan China. Namun dia mengatakan negara-negara seperti itu juga harus membayar harga untuk menjadi “bagian dari Proyek Beijing”. Kudeta atau tidak ada kudeta, itu hanyalah “lapisan demokrasi di Myanmar, yang sekarang telah disingkirkan”.
Anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi telah menyuarakan keinginan untuk dipenjara untuk membela hak asasi manusia namun menolak untuk mengakui penganiayaan terhadap Rohingya.
Menurut Ibrahim, sikap Suu Kyi sendiri terhadap Rohingya tidak muncul karena ketakutan akan militer, seperti yang dituduhkan banyak orang. “Saya telah bertemu orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya dan ketika mereka mengungkit kasus Rohingya, dia meledak karena marah. Itu bukan karakteristik seseorang yang membawa senjata di kepala.”
Demokrasi nyata di Myanmar “tidak selalu penting bagi kekuatan Barat selama pemungutan suara berlangsung,” kata Ibrahim, karena hal itu memberi lampu hijau pada perdagangan dan hubungan keuangan. “Itu berarti mereka dapat mengatakan kami tidak memerlukan sanksi dan kami harus terus berdagang – itulah yang dibayar jutaan dolar.”
Uni Eropa khususnya, katanya, telah didorong oleh masalah ekonomi. “Ada banyak pembicaraan di tingkat UE tentang mandat demokrasi dan hak asasi manusia Myanmar. Tetapi jika Anda melihat substansinya, mereka [UE] sebenarnya jauh lebih buruk daripada entitas Barat lainnya; lebih buruk daripada Inggris, dan jauh lebih buruk daripada Amerika Serikat.”
Dinamika ini tercermin dari kesepakatan perdagangan UE-Cina, yang didorong meskipun pelanggaran hak asasi manusia dilakukan terhadap Muslim Uighur. Terjebak dalam baku tembak dinamika geopolitik yang beracun, Ibrahim mengatakan Rohingya “tidak cocok di mana pun dalam kesetaraan”.
Dan dengan perlindungan ekonomi dan militer China atas Myanmar “hanya sedikit yang dapat dilakukan komunitas internasional”. Dia mengatakan itu “tidak mungkin” terjadi, tetapi jika ada negara dengan kekuatan untuk mengakhiri penganiayaan terhadap Muslim Rohingya, itu bisa jadi adalah China.
Hingga saat ini, upaya China untuk menengahi antara Myanmar dan Rohingya dengan diskusi panel dan dialog tidak membuahkan hasil. Tetapi Ibrahim mengatakan kebijakan non-campur tangan China berarti upaya semacam itu tidak cukup serius. “Anda dapat ikut campur dan tetap netral tetapi dengan tidak ikut campur dalam genosida ini, Anda secara definisi mendukungnya dengan diam.”
Di luar dinamika geopolitik kontemporer ini, Profesor Pemikiran Global di SOAS, Arshin Adib-Moghaddam, berpendapat bahwa sangat penting untuk mengakui dampak historis kolonialisme setelah aneksasi Inggris atas wilayah yang luas seperti Negara Bagian Rakhine.
“Ada faktor sejarah di sini: penggambaran kekaisaran oleh Inggris sebagai bagian dari dekolonisasi India; periode partisi berdarah; dan dilema sejarah penting yang ditimbulkan oleh periode brutal sejarah manusia ini,” ungkapnya kepada The New Arab.
Baca juga: Akhir Kisah Cinta Amerika dengan Timur Tengah
“Seperti banyak komunitas lainnya, Rohingya digunakan sebagai pion di papan catur kekaisaran. Mereka bekerja sama dengan Inggris dengan harapan mencapai semacam otonomi atau kemerdekaan. Ketika pasukan Inggris pergi, Rohingya ditinggalkan tanpa pertahanan terhadap pembalasan dan datang untuk dilihat sebagai kolom kelima di Burma.”
Menurut Omair Anas, asisten profesor di Universitas Yildirim Beyazit, Ankara, warisan sejarah ini bisa dihindari jika struktur kekuasaan seperti Dewan Keamanan PBB mengambil tanggung jawab.
“DK PBB dibentuk sebelum kemerdekaan sebagian besar koloni Asia. Hak kewarganegaraan orang-orang yang tinggal di koloni ini harus menjadi subjek DK PBB dan anggota kolonial konstituennya, Inggris, dalam hal ini,” katanya kepada The New Arab. Dia mengatakan Muslim di wilayah tersebut yang bekerja untuk Inggris sebagai buruh seharusnya ditawarkan hak yang sama untuk kewarganegaraan Inggris seperti komunitas India setelah pengusiran mereka dari Uganda pada tahun 1970-an.
Dia mengatakan Inggris “sepenuhnya menyadari” nasib yang menunggu sekutu Rohingya mereka ketika mereka meninggalkan mereka di Burma tanpa menyelesaikan perselisihan antara Burma dan Rakhine. Mereka juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan menjadikan Rakhine bagian dari kediaman Bengal, yang saat itu dikenal sebagai Pakistan Timur.
Kudeta militer baru-baru ini “harus dilihat dalam konteks meningkatnya persaingan antara China dan AS untuk memperebutkan Samudera Indo-Pasifik,” ujar Anas. Ini juga dapat dilihat sebagai “langkah pencegahan” yang diambil oleh China untuk “membuat India dan AS sibuk dalam krisis Myanmar” setelah aliansi militer pemerintahan Biden dengan India dalam pendiriannya melawan China.
“Kudeta itu sepenuhnya atas perintah China karena itu juga akan berusaha untuk memblokir kebijakan Asia Timur India sebelum serangan Asia Pasifik oleh pemerintahan Biden.”
Analis lain seperti Ibrahim mengatakan kita tidak akan pernah benar-benar tahu sejauh mana peran China dalam kudeta tersebut. Namun, bagi militer, kemenangan pemilihan NLD mungkin telah memicu peringatan tentang kapasitas partai untuk menjadi “sangat berpengaruh”. Kemenangan pemilihan NLD yang tegas mungkin juga membuat jenderal militer Min Aung Hlaing rentan terhadap penuntutan ICJ, mengancam untuk membahayakan kepentingan dan kekayaan keluarganya.
Sementara itu, minoritas Muslim Rohingya terjebak pada hubungan dinamika geopolitik yang kompleks di mana mereka telah digagalkan oleh kekuatan internasional, baik dengan tidak adanya campur tangan China, penjualan senjata Inggris ke Myanmar, pendanaan Uni Eropa dan AS untuk proses demokrasi negara tersebut, atau kegagalan bersejarah kekuatan kolonial untuk melindungi kelompok minoritas di bawah kekuasaan mereka.*
Penulis adalah jurnalis lepas The New Arab yang tinggal di London