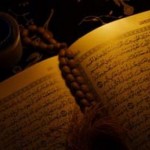Oleh: Dr. Tiar A. Bachtiar
Hidayatullah.com | KATA “emansipasi wanita”, kini sudah nyaris tak terdengar! Lebih sering digaungkan gagasan “kesetaraan gender”. Padahal, kata emansipasi itu sendiri telah memicu banyak pertanyaan. Benarkah perempuan Indonesia memerlukan emansipasi?
Kata “emansipasi wanita” mencuat sejak Armin Pane menerjemahkan surat-menyurat RA Kartini dengan teman-teman Belandanya yang ia beri judul Habis Gelap Terbitlah Terang (Door Dusternis tot Licht) pada tahun 1930-an. Buku Kartini itu menginspirasi kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia untuk menyemangati agar kaum wanita pun turut serta berjuang menegakkan kemerdekaan negeri ini.
Namun, yang tadinya dianggap sebagai penyemangat ternyata di kemudian hari menyimpan masalah krusial bagi para wanita dan keluarga di negeri ini.
Dalam surat-suratnya, Kartini memang menceritakan apa adanya yang dialami para wanita priyayi di Jawa. Misalnya, ia mengisahkan tentang adat istiadat yang mengurung dirinya.
“Kami, anak-anak perempuan yang terantai dengan adat istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pengajaran itu. Bahwa sebagai anak perempuan, setiap hari pergi meninggalkan rumah untuk belajar di sekolah, sudah merupakan pelanggaran besar terhadap adat kebiasaan negeri kami. Ketahuilah, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Pergi ke tempat lain kami tidak boleh…. Pada usia 12 tahun saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk “kotak”, saya dikurung di dalam rumah, sama sekali terasing dari dunia luar…”
Cerita-cerita Kartini hampir sepanjang bukunya itulah yang kemudian menjadi asumsi bahwa nasib para wanita di Indonesia pada umumnya seperti itu hingga kesimpulannya adalah bahwa wanita Indonesia harus dikasihani. Emansipasi wanita adalah suatu keharusan.
Memang, dalam kasus Kartini bisa saja ia diperlakukan seperti itu. Tetapi, apakah semua perempuan di masanya diperlakukan sama RA Kartini?
Jangan-jangan kasus itu hanya menimpa RA Kartini dan beberapa kalangan kaum priyayi seperti Kartini. Sebab, perempuan di Aceh dan di beberapa daerah lainnya, tidak mengalami nasib seperti yang dialami Kartini.
Munculnya Cut Nyak Dien sebetulnya cukup mengherankan. Bagaimana bisa dalam masyarakat yang—katanya–sangat didominasi laki-laki (patriarkhi) dapat muncul seorang panglima perang perempuan. Jelas itu membutuhkan suatu revolusi sosial untuk munculnya seorang seperti Cut Nyak Din dalam masyarakat patriarkhi. Namun, nyatanya Cut Nyak Dien bukan tokoh rekayasa. Jelas dia bukan tokoh ciptaan Belanda.
Harap maklum, Aceh tidak pernah tunduk pada Belanda sampai tahun 1904. Kalaupun akhirnya ditaklukkan, para ulama Aceh tidak mengakui bahwa mereka tunduk pada Belanda. Oleh sebab itu, perlawanan terhadap terus dikobarkan. Jadi tidak mungkin munculnya sosok Cut Nyak Dien dipengaruhi ide feminisme Barat.
Lebih menarik lagi, tradisi perempuan berkiprah di ruang publik, bahkan menjadi pemimpin negara bukan barang baru di Aceh. Pemimpin kerajaan Aceh antara tahun 1641 sampai tahun 1699 adalah perempuan. Mereka masing-masing Sri Ratu Tajul Alam Safiatudin Johan Berdaulat (1641-1675), Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688), dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699) (Ali Hasymi, 1977).
Pada awal abad ke-17 saat Eropa baru memasuki zaman yang mereka sebut “pencerahan” (renaissance, enlightenment), nasib perempuan Eropa tidak lebih baik dari budak. Kalaupun mereka menjadi bangsawan perannya tetap berada di bawah sub-ordinasi laki-laki.
Struktur masyarakat yang patriarkhi sangat dominan di Eropa saat itu. Kenyataan ini pula yang menjadi sebab munculnya gerakan-gerakan feminis di Eropa yang sangat memusuhi dan membenci struktur patriarkhi.
Walaupun umumnya diklaim bahwa gerakan ini mulai diperkenalkan Lady Mary di Belanda tahun 1785, namun gerakan sesungguhnya baru muncul menjelang abad ke-19.
Kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Aceh, tidak mungkin bahwa munculnya raja-raja perempuan di Aceh ini adalah pengaruh dari Eropa. Lagi pula pada masa-masa berikutnya, ketidaksenangan dan permusuhan rakyat kerajaan Aceh terhadap Belanda (baca: Barat) begitu kuat.
Inilah salah satu yang membuat Belanda harus berjibaku selama lebih dari satu abad untuk menaklukkan negeri ini. Namun, itupun tidak sepenuhnya. Hanya kemenangan simbolik dan politik yang didapatkan Belanda. Sisanya Aceh masih seperti sedia kala, terutama dalam masalah keyakinan dan budaya yang dipegang.
Dalam soal relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat “cacah” (rakyat biasa) Jawa ketimpangan seperti yang diceritakan Kartini juga tidak ditemukan. Lihat saja saat menggarap sawah atau kebun yang sejak berabad-abad menjadi mata pencaharian rakyat Jawa.
Selalu saja sawah akan digarap bersama antara laki-laki dan perempuan. Selalu ada pembagian peran.
Misalnya, laki-laki mencangkul, perempuan menyiangi rumput; dan sebagainya. Aktivitas di pasar-pasar pun selalu bercampur antara laki-laki dan perempuan.
Di pesantren-pesantren, ulamanya tidak hanya laki-laki. Istilah “kiai” (ulama laki-laki) dan “nyai” (ulama perempuan) sudah hidup begitu lama. Pesantren pun sudah sejak awal berdirinya selalu diperuntukkan bagi santri putra dan putri.
Kalau melihat kenyataan ini, apakah sungguh-sungguh kaum perempuan Jawa ini termarjinalkan? Jangan-jangan itu hanya terjadi di sekitar lingkungan priyayi saja. Sementara di akar rumput, apa yang diceritakan Kartini tidak terjadi.
Soal pendidikan pun sepertinya itu hanya berlaku di lingkungan Kartini. Mungkin benar para priyayi Jawa lebih senang menyekolahkan anak-anak laki-laki daripada anak-anak perempuan seperti yang diceritakan Kartini. Namun, klaim ini patut dipertanyakan jika digunakan untuk memotret kaum “cacah” (rakyat biasa).
Salah satu bukti adalah tradisi di pesantren-pesantren yang memberikan ruang seluas-luasnya, bahkan khusus, bagi kaum perempuan. Selain itu, masalah buta huruf sesungguhnya tidak hanya dialami kaum perempuan.
Laki-laki pun menghadapi problem yang sama. Jadi, kalau perempuan saat itu tidak banyak yang bersekolah, bukan masalah disriminasi, melainkan karena memang sekolahnya tidak ada.
Jangankan perempuan, laki-laki pun sama-sama tidak pergi ke sekolah. Kebodohan ini merata di kalangan laki-laki dan perempuan. Sama sekali bukan monopoli kaum perempuan saja.
Sederet fakta lain seperti munculnya tokoh seperti Rohana Kudus dan Rahma el-Yunusiah di Sumatera Barat, juga Dewi Sartika di Bandung, semakin memperkokoh argumen bahwa sesungguhnya di negeri ini kesadaran akan kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah sejak lama ada.
Kesadaran ini bukan hasil impor seperti yang diklaim para aktivis feminis. Fakta-fakta ini juga semakin menegaskan bahwa sesungguhnya Indonesia tidak menderita sindrom patriarkhi seperti yang terjadi di Eropa.
Oleh karena kesadaran ini bukan impor, jelas pula prinsip kesetaraan yang dipegang masyarakat Indonesia sama sekali berbeda dengan kesetaraan gender yang diajarkan Barat-sekuler. Kesetaraan gender yang digadang-gadang para aktivis perempuan melabrak norma-norma budaya dan agama. Pada akhirnya, konsep yang tidak sesuai dengan fitrah perempuan itu pun, akan menyengsarakan perempuan itu sendiri. Wallahu A’lam bish-shawab. (*)
Dosen STAIPI Garut