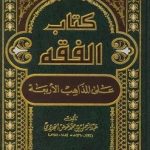Sambungan artikel PERTAMA
Oleh: Dr. Syamsuddin Arif
Kembali ke pertanyaan di atas, umat Islam kini harus berhenti sejenak. Berhenti mengekori orang lain. Berhenti untuk introspeksi mau kemana sebenarnya kita ini. Mau maju kemana, mengapa dan untuk apa? Di sinilah pentingnya kita kembali menengok, menggali, dan mengkaji tradisi leluhur kita, warisan intelektual peradaban kita sendiri, agar bisa berkata seperti Jacques Ellul dengan bangganya berkata: “I see no other satisfactory model that can replace what the West has produced” (Lihat bukunya: The Betrayal of the West, New York 1978, hlm. 19).
Sains memang penting untuk membangun sebuah peradaban, tetapi dengan itu saja tidak cukup. Peradaban berdiri di atas kekuatan metafisis, yaitu iman dan ilmu –orang Barat menyebutnya faith and knowledge, dan tentu saja kerja keras yang dalam perspektif kita adalah amal sholih dan jihad fi sabilillah. Dan ini dibenarkan oleh orang Barat yang mengakui bahwa peradaban mereka dibangun atas fondasi kepercayaan Yahudi-Kristen dan warisan intelektual-kultural Yunani-Romawi kuno. Sains hanya satu dari banyak komponen peradaban.
Dalam buku “Orientalis dan Diabolisme Pemikiran” (2008) disebutkan beberapa teori para ahli tentang nasib sains di dunia Islam. Salah satunya menurut Profesor Sabra dari universitas Harvard. Ia melihat perkembangan sains di dunia Islam setelah melewati fase keempat yang disebutnya sebagai ‘appropriasi’, lebih banyak mengarah pada pemenuhan kebutuhan praktis, sehingga peran sains menyempit sekadar menjadi pelayan agama (handmaiden of religion). Namun, bagi saya penjelasan ini tidak terlalu tepat. Sebab pada banyak kasus, asas manfaat justru berperan penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sains. Teori kedua dikemukakan oleh David C. Lindberg dari universitas Wisconsin Madison. Menurutnya ada tiga faktor penghambat kemajuan sains dalam dunia Islam: pertama, oposisi kaum konservatif. Kedua, krisis ekonomi dan politik. Dan ketiga, keterasingan. Lindberg menyebut sebagai contoh kasus pembakaran buku-buku sains dan filsafat di Cordoba yang menyebabkan saintis Muslim ketakutan. Di sini memang kerap bercampur antara fakta dan fiksi, antara realitas dan imajinasi.
Saya sendiri berpendapat setidaknya ada tiga hal faktor yang menghambat kemajuan sains di dunia Islam sebelum zaman modern. Pertama, banyaknya saintis Muslim yang secara diam-diam telah meninggalkan Islam. Tren yang berlaku pada saat itu pun adalah free-thinking alias berpikiran liberal. Sebagian bahkan mengingkari kenabian Rasulullah. Ada juga yang terang-terangan minum khamar. Faktor kedua adalah krisis ekonomi dan politik. Konflik berkepanjangan seringkali disertai perang saudara yang mengakibatkan disintegrasi dan hancurnya ekonomi. Belum lagi serangan tentara salib yang memakan ribuan korban. Demikian pula invasi pasukan Mongol yang memporak-porandakan Baghdad pada tahun 1258 M. Faktor ketiga adalah gerakan sufi palsu yang menyebarkan dan menyuburkan irrasionalitas, sehingga masyarakat lebih tertarik kepada aspek-aspek mistis dan magis, kesaktian dan keajaiban daripada aspek ubudiyah, ilmiah, dan akhlak.
Kebangkitan dan Isu Khilafah
Lalu, apakah peradaban Islam bisa bangkit kembali? Seperti saya katakan di muka, peradaban Islam belum mati dan tidak beku. Peradaban Islam masih terus bergerak meski sebagai entitas masih berserak. Peradaban Islam kini belum berdiri sebagai satu entitas tunggal yang solid dan utuh. Salah satunya karena umat Islam yang menjadi penyangga peradaban tersebut sedang berusaha mengatasi krisis epistemologis, misorientasi, dan disorientasi teleologis, ndak jelas dan ndak tegas maunya ke mana. Mau ikut al-Qur’an takut dibilang ketinggalan zaman. Mau ikut Nabi takut dimusuhi. Mau melawan atau menolak takut dicap fundamentalis, ekstrimis, atau teroris. Mau mengekori Barat takut kebablasan. Pendek kata, harapan bangkit kembali bukan tidak ada. Optimisme kita didukung oleh hadis Nabi saw: layaghlibanna hādzal-amru! –bahwa peradaban Islam akan menang dan jaya. Juga dipacu oleh firman Allah dalam al-Qur’an: la tay’asū min rawhillāh! –jangan pernah putus harapan kepada pertolongan Allah.
Dan memang sudah tampak beberapa indikator ke arah itu. Sebutlah sebagai contoh perubahan demografi penduduk dunia sekarang ini. Kemudian fakta bahwa sumber-sumber energi dan kekayaan alam terdapat di negara-negara Muslim. Begitu pula proses desekularisasi yang berjalan sama kencangnya dengan proses Islamisasi di banyak belahan dunia. Maka insyā Allah akan tiba saatnya nashrun minallāhi wa fathun qarīb. Kita hanya disuruh berbuat dan bekerja, dan tidak dituntut akan hasilnya. Waqul i‘malū fasayarallāhu ‘amalakum! (Laksanakan tugas kita sesuai dengan profesi dan kapasitas diri masing-masing).
Ada yang meyakini bahwa kejayaan dan kejatuhan peradaban Islam itu bergantung pada atau bahkan disebabkan oleh tegaknya dan runtuhnya ‘khilafah’ (sistem politik dan tata negara yang dipimpin oleh seorang ‘khalifah’). Memang benar, khilafah itu hanya istilah. Di dalam al-Qur’an sendiri, istilah khalifah itu lebih bernuansa teologis ketimbang politis. Khilāfah atau istikhlāf itu adalah pelimpahan kuasa Tuhan kepada manusia untuk mengatur kehidupan di bumi. Adapun dalam koleksi hadis Nabi, seperti kitab Sahih Muslim, yang kita temukan adalah istilah imārah untuk kepemimpinan politik, bukan khilafah. Sementara dalam literatur ilmu kalam yang sering dipakai adalah istilah imamah, tentang siapa yang berhak memimpin umat dan negara, syarat-syaratnya, dan sebagainya. Namun menurut saya, yang amat sangat esensial dalam tata kelola negara (siyāsatul madīnah) adalah asas keadilan dan kebaikan (al-‘adl wal ihsān). Keadilan bukan persamaan. Dan kebaikan bukan berarti menuruti kehendak masyarakat atau suara rakyat (vox populi) belaka. Adil di sini membutuhkan ilmu dan hikmah, meniscayakan amal dan adab, dan pastinya bersendikan petunjuk wahyu. Dengan demikian, soal apakah cita-cita menegakkan khilafah itu utopia atau dystopia menjadi tidak signifikan.
Berkenaan gerakan ISIS (Islamic State of Iraqi and Syiria) dan sepak terjang mereka di Timur Tengah, kita tidak boleh gegabah menyebut mereka bagian dari kebangkitan peradaban Islam ataupun mengecam mereka sebagai anasir-anasir perusak dan pengacau umat Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi yang lengkap dan terpercaya. Berita-berita yang kita baca, dengar, atau lihat itu kebanyakan datang dari media orang fasiq. Untuk melakukan tabayyun tidak mudah. Untuk langsung memvonis, takut berdosa karena firman Allah: inna ba’dhaz-zhanni itsmun! Maka dalam hal ini sikap terbaik adalah diam (tawaqquf). Yang jelas, membangun sebuah peradaban –apalagi yang Islami– itu mustahil tanpa melibatkan para ulama, yakni orang-orang yang paham benar seluk-beluk ajaran Islam mengenai aqidah, hukum, akhlaq dan adab politik, ekonomi dan seterusnya. Jika tidak, maka seperti sabda Rasulullah saw: “idza wussidal-amru ila ghayri ahlihi fa’ntazhiris-sā’ah!”
Model Negara Islam?
Seringkali orang bertanya apakah ada negara yang dapat disebut Islami di zaman sekarang ini untuk kita jadikan contoh. Tentu saja hal ini mengandaikan kesepakatan pada tataran definisi. Apakah sebuah negara itu disebut Islami karena penduduknya Muslim (dengan atau tanpa melihat persentase, kualitas, dan posisi mereka di negara tersebut)? Ataukah sebuah negara itu disebut Islami lantaran nilai-nilai Islam terwujud secara fisik dalam tata kehidupan masyarakat dan tata ruang yang rapi, bersih, indah, dan sebagainya? Ataukah sebuah negara itu Islami karena Syariat Islam diberlakukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial, dalam berpolitik maupun berekonomi, dalam sistem perundangan dan peradilan? Ataukah sebuah negara itu Islami sebab undang-undang dasar atau konstitusinya berasaskan Islam?
Meski belum sempurna, Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara modern yang konstitusinya secara eksplisit menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Konsekuensinya, Yang Dipertuan Agung sebagai kepala negara maupun Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memikul amanah konstitusi untuk menjunjung tinggi agama Islam dan memelihara eksistensinya. Warga non-Muslim tetap dijamin hak-haknya untuk menganut dan mengamalkan agama mereka secara aman dan harmonis. Mungkin karena itu sekularisme sukar untuk berkembang di Malaysia.
Kedua, pemerintah Malaysia sangat peduli (concerned) dengan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ini dibuktikan dengan penyediaan bermacam-macam skema beasiswa dan pembangunan serta perbaikan fasilitas umum secara masif dan bertanggung jawab. Korupsi memang terjadi, namun tidak merajalela dan tidak menjalar ke mana-mana bagaikan kanker ganas seperti halnya di negara-negara lain. Ketiga, umat Islam di Malaysia pada umumnya mudah diatur, tunduk pada pemerintah dan patuh pada aturan hukum dan undang-undang. Sifat-sifat ini memudahkan mereka untuk mengelola banyak hal secara efektif dan efisien, dan menyelesaikan konflik secara bijak dan baik. Jarang sekali mengutamakan otot daripada otak. Seperti jawaban seorang diplomat mereka saat terjadi sengketa pulau dengan Indonesia: “We will cross that bridge when we come to it.” Wallāhu a‘lam.*
Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) Jakarta