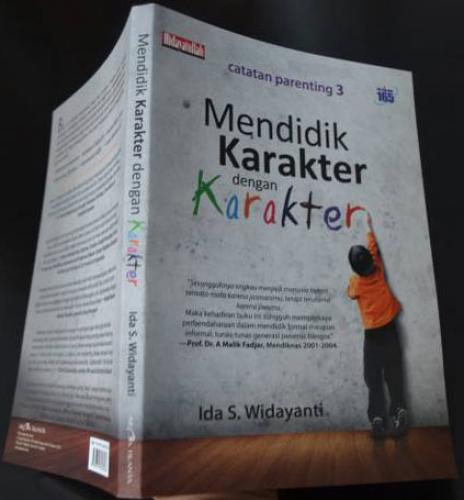Darwinisme Sosial yang mengarah ke suatu bentuk liberalisme radikal, bertentangan dengan teori Islam yang dibawa Nabi Muhammad, gagasan manusia adalah makhluk egois yang selama ini dipercayai ilmuwan Barat hanya mitos
Oleh: Indah Noviariesta
Hidayatullah.com | DALAM hidup ini setiap orang akan menghadapi sesuatu yang cocok dan tidak cocok dengan kehendak dan keinginan. Untuk itu, yang diperlukan untuk menguatkan mental iman kita, bukanlah sibuk meniadakan atau mengelak dari kesulitan dan kegagalan.
Sebab bagaimanapun, sulit dan gagal itu sudah pasti dipergilirkan kepada semua makhluk Tuhan, termasuk hewan dan binatang. Hanya masalahnya, binatang tidak diperintahkan untuk melatih kesabaran dan rasa syukur ketika menghadapi suatu masalah dalam hidupnya.
Keinginan untuk sukses dan menang, adalah manusiawi. Masalahnya, sebagaimana Rasulullah ﷺ, persoalan menang dan kalah pun dipergilirkan juga.
Perang Uhud misalnya, dengan keyakinan akan menang karena infrastruktur sudah cukup mapan, tetapi faktanya Allah kalahkan. Tetapi pada Perang Badar, di saat kekuatan musuh begitu banyak dan tangguh, justru para pengikut Nabi Muhammad ﷺ yang masih minim dimenangkan Allah Swt.
Itu membuktikan, ada faktor Allah dan faktor manusia. Selain ada takdir, faktor pada manusia, bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabat sekalipun bisa keliru dalam memprediksi segala sesuatu.
Yang disangka menang tahu-tahu kalah, sebaliknya yang disangka kalah tahu-tahu menang. Lalu, bagaimana manusia harus mampu menyikapi menang dan kalahl dengan cara-cara terbaik, nah itulah yang diperintahkan dalam ajaran Islam dan diteladankan dalam hidup Nabi Muhammad ﷺ.
Karena itu, bagi pihak yang menang tak perlu eforia dengan gegap-gempita kemenangan, (apalagi) sampai-sampai bersikap angkuh dan sombong. Bagi yang kalah, jangan terlampau berduka, sampai-sampai mengalami frustasi dan putus asa.
Sabar di saat menghadapi ujian kalah, kadang lebih berhasil ketimbang gembira dan melonjak kegirangan ketika menghadapi kemenangan.
Ketika hegemoni politik sudah berada dalam kekuasaan Baginda Nabi ﷺ dan para pengikutnya (Fathu Makkah), justru keputusan politik Baginda Nabi membuat banyak orang tercengang dan geleng-geleng kepala.
Apa yang belau cari ternyata bukan sekadar kemenangan dari persaingan sengit berpuluh-puluh tahun. Tetapi, justru meraih keadilan yang berpangkal dari rasa syukur dan takwa.
Para musuh politik yang dulu menghasut, mencaci-maki, bahkan menyakiti dirinya dan para sahabatnya, tetap dibiarkan hidup, dan menjadi bagian dari proses semesta. Baginda melarang para pasukannya agar jangan menyakiti maupun membunuh lantaran amarah dan dendam masa lalu.
Yang menjadi perhatiannya justru membersihkan sekitar Ka’bah dari sesembahan-sesembahan mereka (patung-patung) yang selama ini menganut dan mempercayai kekuasaan Dewa Hubal, Latta, Manat, Uzza dan lain-lain.
Baginda Nabi menyodorkan tongkatnya, hingga terjengkanglah dewa-dewi pagan yang disimbolisasi patung-patung ukiran dan pahatan kayu, batu, perak hingga emas itu.
Baginya, segala sesuatu yang disimbolisasi sebagai “tandingan” Yang Maha Esa (Allah) itulah yang menjadi biang perkara munculnya berbagai perbedaan yang menimbulkan saling gontok-gontokan, sikut kiri-kanan, bertikai saling berebut dan mengambil hak sesamanya, serta maraknya segala ketidakadilan dan kesewenangan di mana-mana.
Pilihan kebijakan Nabi Muhammad ﷺ untuk tidak menumpaskan para pesaingnya adalah bagian dari sikap dan karakteristiknya sejak usia muda. Ia dikenal sebagai orang jujur dan bicara apa adanya, bahkan istrinya sekalipun (Siti Khadijah) sangat mengakui kejujurannya.
“Tenanglah suamiku, apa-apa yang engkau alami itu bukanlah suatu kejanggalan, karena kami semua tahu bahwa engkau orang yang senang berkunjung (silaturahmi), senang membantu sesama, menghormati tamu dan bicara jujur apa adanya,” demikian Khadijah menenangkan Baginda setelah menghadapi sosok misterius (Jibril) dalam kesunyiannya di Goa Hira.
Di puncak perjuangan yang menentukan jalan sejarahnya, Baginda Nabi justru ditinggal orang-orang yang mencintai dan mendukungnya. Setelah kematian pamannya Abu Thalib, menyusul istri yang sangat dicintainya Khadijah, hingga ia sempat terlarut dalam suasana perkabungan (amul huzni).
Ditinggalkan seorang istri yang baik dan salehah, membuat Baginda Nabi senantiasa berpikir, bahwa hidup manusia dibatasi oleh durasi waktu, kelemahan dan kekurangan. Jika yang dikejar adalah kemenangan duniawi, maka bersiap-siaplah bahwa kehidupan manusia akan terlindas oleh sang waktu hingga mengalami kepunahan dalam catatan sejarah.
Hal ini bertentangan dengan teori Richard Dawkins akhir-akhir ini, mengenai “Gen Egois” (selfish gene), seakan-akan manusia terlahir sebagai makhluk egois dan ingin menang sendiri. Namun, konsep Islam yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ, telah bicara mengenai penciptaan Adam dan pasangannya Hawa, yang terkandung unsur hewani (secara anatomis) tetapi secara rohani mengandung unsur malaikat dan iblis.
Jika kecenderungan iblis yang lebih dominan, ia akan menjelma binatang dari segala binatang buas. Tetapi, jika unsur malaikat yang dominan dalam dirinya, ia akan menjelma makhluk Tuhan yang kasatmata secara inderawi, namun berkedudukan lebih mulia dari para malaikat.
Allah Swt berfirman, bahwa manusia dipercayakan menjadi “khalifah” di muka bumi, yang akan melestarikan kehidupan dan kemaslahatan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Bahkan, dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa manusia lebih mulia ketimbang makhluk-makhluk Allah yang tercipta lebih dulu, seperti malaikat maupun jin.
Lalu, dengan bahasa sebagai alat komunikasi, Allah memperkenalkan nama-nama segala sesuatu agar menjadi pelajaran yang tertancap dalam memorinya. Dalam kaitan ini, para ilmuwan berteori, bahwa perkembangan bahasa manusia merupakan produk sifat sosial Homo Sapiens, yang tak tertandingi oleh genus homo lainnya.
Gen Egois yang gagal
Di masa Jahiliyah (pra-Islam) memang dikenal dengan era persaingan sengit yang saling mematahkan lawan. Barangkali dapat disejajarkan dengan manusia purba (Neandertal), memiliki otak lebih besar dari Homo Sapiens, berpikir logis dan rasional namun tidak mampu mengambangkan akal budi dan hati nuraninya.
Perjuangan yang diprakarsai Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya, seakan dapat mementahkan gagasan Dawkins tentang Gen Egois (selfish gene) sebagai pusat evolusi. Diperkuat lagi oleh hasil penelitian dua ahli kognisi Steven Sloman dan Philip Fernbach, yang menulis buku, The Knowledge Illusions: Why We Never Think Alone (2017).
Ternyata, gagasan bahwa manusia itu makhluk egois yang bersifat individual, yang selama ini dipercayai sebagian ilmuwan Barat, ternyata hanya mitos belaka. Apa yang diperjuangkan Baginda Nabi dan para pengikutnya, membuktikan bahwa manusia berpikir dalam komunitas dan kelompok-kelompok masyarakat.
Fenomena antropologis yang menunjukkan hal itu membawa Sloman dan Fernbach pada kesimpulan, bahwa manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya, serta mampu mengubah dirinya menjadi penguasa planet bumi ini. Hal itu, bukanlah didasarkan rasionalitas individual, akan tetapi karena kecerdasan dan kemampuan mereka dalam memenej dan mengelola komunitas.
Namun demikian, era Nabi Muhammad berbeda dengan era Nabi Nuh, kaum Tsamud, kaum Luth maupun era Firaun (Nabi Musa). Era Nabi Muhammad ﷺ bukanlah era pemusnahan para musuh dan lawan-lawan politik.
Akan tetapi, “mantan musuh” itu pun selayaknya diberdayakan sebagai manusia-manusia yang berproses menuju perbaikan dan pendewasaan iman. Seandainya mereka belum mampu menyadari kekhilafannya saat ini, boleh jadi besok, bulan depan, atau tahun depan mereka akan berubah.
Tetapi bagaimana jika sampai mati belum juga sadar? Tetaplah bersabar, barangkali anak-anak mereka yang akan menjadi orang-orang baik dan saleh yang kelak mendoakan orang tua dan leluhur mereka.
Kita sudah mengarungi fakta. Bahwa tanpa bekerjasama dengan baik, manusia bahkan tak sanggup menghadapi perlawanan makhluk sekecil partikel bernama “Corona” yang mengakibatkan Covid-19 di seluruh dunia.
Dengan sendirinya, Bregman mementahkan teori Darwinisme Sosial, yang membanggakan manusia sebagai makhluk kuat dan kempetitif (termasuk di bidang ekonomi dan politik). Gen Egois yang digagas Dawkins juga hanya berpangku tangan menyaksikan ratusan dan ribuan ambulans yang wara-wiri mengangkuti mayat-mayat korban Covid-19.
Apalagi di sekitar pertengahan tahun 2020 lalu, ketika para dokter kelimpungan menangani pasien, sementara obat dan vaksinnya belum diketemukan. Darwinisme Sosial yang mengarah ke suatu bentuk liberalisme radikal, sangat bertentangan dengan teori Islam yang dibawa Nabi Muhammad.
Teori itu hanya akan dimanfaatkan kaum penguasa modern maupun petualangan politik, untuk membenarkan tingkah laku mereka menguasai dan mengeksploitasi manusia lainnya dalam bentuk penjajahan, kolonialisme, fasisme, rasialisme, yang selama ini menjadi demam-demam imperialisme manusia Barat, yang kemudian dianut oleh sebagian masyarakat Timur (tanpa sikap kritis).
Konsep Darwinisme Sosial bisa menggiring penguasa hingga membenarkan kemenangan harus diraih dengan jalan apa pun, sambil berpegang pada pemikiran bahwa sifat dasar manusia adalah jahat. Inilah yang mendorong World Economic Forum (WEF) 2021 mencetuskan gagasan “Great Reset”, upaya menafsir ulang dan menata kembali kehidupan kita, dengan keharusan mengubah mindset dalam memaknai hakikat kehidupan dunia ini.
Gagasan brillian itu terinspirasi dari pemikiran Bregman yang berdasarkan atas studi sejarah panjang umat manusia. Bahwa manusia sebagai Homo Sapiens, justru memiliki sifat dasar baik, dan keberlangsungan kehidupan manusia bukan dikarenakan kompetisi yang saling menjatuhkan lawan. Bukan karena yang kuat mengalahkan yang lemah, juga bukan karena egoisme yang menutup diri dan bersifat individual.
Namun sejatinya, era post industrial saat ini mesti relevan dengan misi Islam dan teladan iman Nabi Muhammad. Bahwa daya tahan keberlangsungan hidup manusia, karena kecerdasan dan kemampuannya bekerjasama, saling berbagi dan mencintai sesamanya. ***
Pegiat organisasi Gerakan Membangun Nurani Bangsa (Gema Nusa)