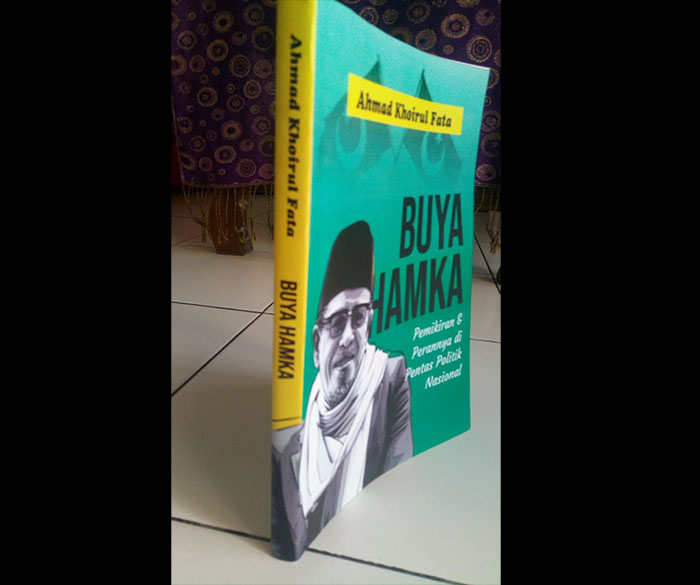Genosida Gaza Palestina menegaskan kegagalan gerakan feminis, mereka sibuk mengomentari penampilan ‘seksi’ Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dibanding pembantaian brutal ‘Israel’
oleh: Maryam Aldossari
Hidayatullah.com | PASCA serangan perlawanan 7 Oktober, bahkan sebelum debu hilang dan penghancuran Gaza dimulai, sejumlah klaim penyerangan seksual dan pemerkosaan dengan cepat disebarluaskan di berbagai surat kabar Barat oleh para feminis.
Tokoh-tokoh terkenal menulis artikel mendengungkan tuduhan “pemerkosaan sistematis” yang dilontarkan oleh pemerintah, pejabat militer Israel dan media Barat, meski tanpa bukti.
Mengungkap fakta-fakta kekerasan seksual selama masa perang merupakan hal yang sangat sulit, terutama karena pemerintah Israel dengan sengaja memperkeruh suasana dengan mengubah narasi, menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan yang dirahasiakan dengan pemerintah, dan mengabaikan praktik investigasi normatif.
Namun, meskipun kita harus selalu percaya pada perempuan dan tetap marah terhadap pemerkosaan, jelas bahwa klaim “pemerkosaan sistematis” digunakan oleh pemerintah Israel untuk menjustifikasi pembantaian warga Palestina.
Oleh karena itu, pertanyaan utamanya adalah mengapa serangan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Palestina tidak memicu kemarahan yang sama.
Selama sepuluh bulan terakhir, empati selektif dari para feminis dan organisasi feminis terkenal di Inggris semakin terlihat jelas.
Sementara pernyataan cepat di media sosial dan artikel-artikel yang mendukung perempuan Israel sangat banyak, ada keheningan yang mencolok terkait kondisi perempuan Palestina yang mengerikan.
Ketidakpedulian yang disengaja atas kerusakan seksual yang dialami perempuan Palestina akibat serangan Israel sungguh memprihatinkan, terutama karena orang akan menganggap hal ini merupakan fokus utama feminisme.
Sejak 7 Oktober, ratusan perempuan Palestina telah ditahan di tahanan Israel dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan seksual, pemukulan dalam keadaan telanjang, ancaman perkosaan, dan dalam dua kasus yang telah diverifikasi, pemerkosaan.
Feminis Barat menutup mata
Bahkan jika dua pemerkosaan dengan bukti valid yang dicatat dalam laporan PBB pada 19 Februari 2024, entah bagaimana diabaikan, bagaimana mungkin sejarah kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh tentara ‘Israel’ terhadap perempuan Palestina selama 76 tahun terakhir dapat diabaikan?
Sejumlah laporan yang merinci kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina, jauh sebelum 7 Oktober, dapat diakses secara online.
Laporan-laporan ini berasal dari kelompok-kelompok HAM besar di Israel, seperti Komite Publik Menentang Penyiksaan di Israel, Pusat Bantuan dan Konseling Hukum Perempuan yang berbasis di Yerusalem, dan B’Tselem (salah satu laporan dari tahun 2009 di antara banyak laporan lainnya), di samping beberapa laporan dari PBB.
Semua laporan ini, berdasarkan protokol yang digunakan dalam sidang pengadilan, pengaduan hukum, dokumentasi pengacara, dan kesaksian tahanan, menggambarkan kekerasan seksual, penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat orang Palestina dalam penjara Israel.
Seandainya wacana feminis benar-benar berusaha untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dalam perang. Dalam hal ini, kekejaman yang sedang berlangsung terhadap perempuan Palestina seharusnya dimasukkan ke dalam semua pasal-pasal tersebut untuk menegakkan integritas gerakan.
Terlepas dari banyaknya bukti dalam 10 bulan terakhir – 40.000 warga Palestina terbunuh, sekitar setengahnya adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 21.000 anak dilaporkan hilang – gerakan feminis belum belajar dari sikap keberpihakan sepihaknya.
Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak Palestina terus terabaikan. Demikian pula, laporan PBB baru-baru ini pada 12 Juni 2024, tampaknya luput dari perhatian, gagal menggugah hati nurani atau mendorong tanggapan yang substansial.
Laporan ini merinci bagaimana Pasukan Keamanan Israel secara sistematis menargetkan dan menjadikan warga Palestina sebagai sasaran kekerasan berbasis seksual dan gender, termasuk penelanjangan paksa di depan umum, penyiksaan dan pelecehan seksual, serta penghinaan dan kekerasan seksual.
Laporan tersebut juga mendokumentasikan bahwa tentara Israel merekam diri mereka sendiri saat menggeledah rumah-rumah, menggeledah laci-laci berisi pakaian dalam untuk mengejek dan mempermalukan perempuan Palestina, menyebut mereka sebagai ‘pelacur’, dan (laporan PBB) menyimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender ini dimaksudkan untuk mempermalukan dan merendahkan penduduk Palestina secara keseluruhan.
Budaya kekerasan seksual
Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender ini juga meluas hingga ke kaum pria. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa para pria berulang kali difilmkan dan difoto oleh para tentara ketika mereka ditelanjangi secara paksa di depan umum, disiksa secara seksual, dan diperlakukan secara tidak manusiawi.
Baru minggu lalu, muncul sebuah rekaman yang memperlihatkan pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang warga Palestina oleh tentara Israel di fasilitas penahanan Sde Teiman. Para menteri Israel, termasuk Bezalel Smotrich, dengan cepat mengutuk bocornya video tersebut dan bukan isinya. Beberapa, seperti Hanoch Milwidsky dari Likud, bahkan bertindak lebih jauh dengan membenarkan pemerkosaan tersebut. Seperti yang sudah diduga, para feminis Barat tetap diam.
Ini meresahkan, tapi bukan hal yang tak terduga bahwa tampaknya hanya ada sedikit simpati untuk pria Arab, yang sering digambarkan dalam stereotip rasis yang mengakar kuat sebagai orang yang secara inheren misoginis dan biadab. Kontras yang mencolok dalam hal empati, baik disadari maupun tidak disadari, memperlihatkan bias yang jelas di antara para feminis terkenal di Inggris dan berkontribusi pada normalisasi tindakan Israel terhadap warga Palestina.
Keheningan yang menyesakkan telinga dari komunitas feminis lainnya juga sama buruknya; mengabaikan gambar-gambar mengerikan dari Gaza selama sepuluh bulan terakhir menandakan dehumanisasi yang begitu dalam sehingga penderitaan yang terjadi tidak lagi memiliki dampak.
Berdiam diri terhadap salah satu kekejaman terburuk terhadap perempuan dan anak-anak dalam hidup kita tidak dapat diterima. Ketika 70% dari mereka yang terbunuh adalah perempuan dan anak-anak; ketika para perempuan Palestina menggali reruntuhan untuk menemukan anak-anak mereka yang hilang; ketika para ibu menggendong bayi-bayi mereka yang sudah tidak bernyawa; ketika keluarga-keluarga dibakar hingga mati di kamp-kamp pengungsian ketika mereka tidur; ketika para ibu menyaksikan anak-anak mereka mati kelaparan akibat kampanye kelaparan yang dilakukan oleh Israel; dan ketika anak-anak menangis minta makan di tengah-tengah kondisi kelaparan, maka sikap diam bukanlah sebuah sikap yang “benar secara politis” – itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip feminis.
Sejumlah kejadian yang terjadi baru-baru ini selama genosida Gaza menegaskan kegagalan gerakan feminis, dan memberikan gambaran yang memalukan terhadap gerakan tersebut.
Selama salah satu minggu paling mematikan di Gaza sejak 7 Oktober, beberapa feminis Inggris malah asyik dan sibuk mengomentari penampilan ‘seksi’ Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Apakah kita hidup di dunia paralel?
Perhatian disengaja pada isu-isu yang dangkal ini, sementara mengabaikan masalah-masalah yang mendesak, menandakan hilangnya arah dalam gerakan ini dan menunjukkan bahwa mereka yang memimpin Feminisme – yang dulunya dipercaya – menyimpan sikap anti-Palestina, rasisme anti-Arab, dan Islamofobia.
Hal ini semakin jelas terlihat ketika beberapa orang yang disebut feminis bersekutu dengan tokoh-tokoh seperti Tommy Robinson, seorang narapidana berideologi sayap kanan dan mempromosikan narasi yang salah tentang Muslim, pencari suaka, dan migran, yang mencerminkan kebangkitan retorika sayap kanan di Inggris.
Meskipun pandangan-pandangan ini telah menyesatkan sebagian orang, sehingga sulit untuk membayangkan kembalinya mereka, gerakan feminis masih memiliki harapan jika dapat kembali ke nilai-nilai dasarnya.
Salah satu pelajaran penting dari kejadian-kejadian baru-baru ini adalah rasisme yang merajalela di kalangan feminis Inggris, bahkan harapan yang paling sederhana sekalipun – untuk mengakui perjuangan perempuan Palestina yang mengalami marjinalisasi sistemik – belum terpenuhi.
Agar gerakan feminis dapat bangkit dari kekacauan ini, harus jelas bahwa tidak ada tempat untuk rasisme. Mengatasi feminisme kesukuan yang hanya melayani kepentingan selektif ini menuntut pengakuan dan penanganan prasangka ketika mereka muncul, dengan meminta pertanggungjawaban setiap orang.
Kekuatan kolektif komunitas feminis tidak boleh diremehkan. Seperti halnya beberapa tokoh yang telah diangkat ke status terkenal, mereka yang mengkhianati prinsip-prinsip inti feminisme harus menghadapi risiko menjadi tidak relevan.
Dengan memilih dengan cermat siapa yang akan didukung dan diangkat, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi feminis, gerakan ini dapat menegakkan integritasnya dan memastikan bahwa nilai-nilainya tetap benar-benar inklusif dan anti-rasis. Tidak ada ruang untuk rasisme dalam feminisme, dan seperti yang dikatakan oleh Angela Davis dengan bijak, “Dalam masyarakat yang rasis, tidak cukup hanya dengan tidak rasis, kita harus anti-rasis”.*
Penulis adalah dosen senior di Royal Holloway, Universitas London. Penelitiannya berfokus pada ketidaksetaraan gender di Timur Tengah. Tulisan adalah opini penulis di www.newarab.com