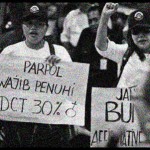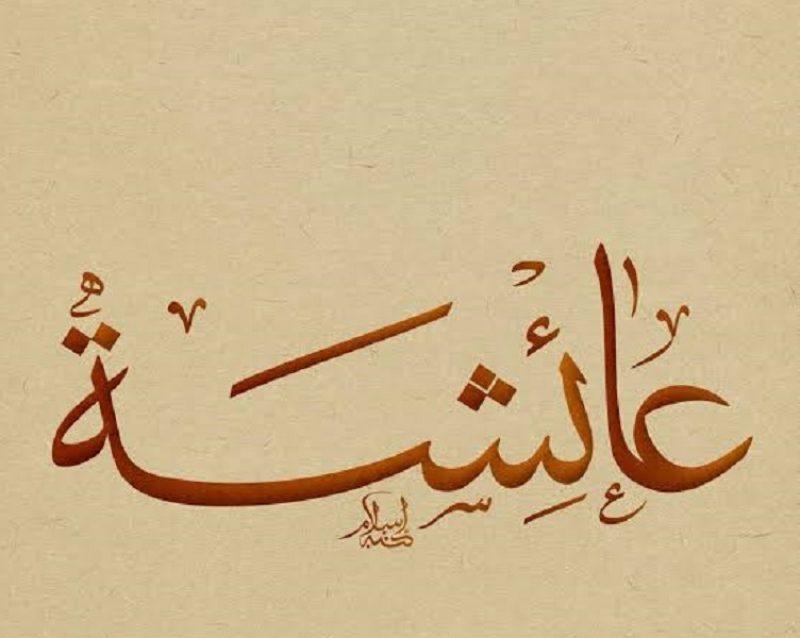Sambungan artikel PERTAMA
Oleh: Sapto Waluyo
SECARA obyektif, kita perlu bandingkan bahaya ISIS dengan isu lain, semisal korupsi yang merasuk ke pusat kekuasaan atau pembelahan (faksionalisasi) politik yang makin marak. Bahkan, jika kita mau jujur dan cermat, kondisi makro ekonomi nasional bisa menjadi ancaman serius, manakala pelemahan kurs rupiah dan defisit anggaran terus melebar.
Pada 2007, ketika kondisi ekonomi Indonesia relatif lebih stabil, Penulis pernah membandingkan isu terorisme dengan korupsi dan bencana alam: mana yang menjadi ancaman serius? Saat itu, sedang marak isu Jemaah Islamiyah (JI) sebagai perpanjangan tangan Al-Qaedah di Asia Tenggara.
Kesimpulannya, perkara korupsi ternyata telah menggerus kepercayaan publik, jauh lebih berbahaya ketimbang terorisme dan bencana. Masyarakat pada umumnya memiliki imunitas terhadap isu terorisme dan membangun soliditas kala bencana, namun mereka frustasi ketika melihat lemahnya penegakan hukum dalam penanganan korupsi. Ketidakpercayaan publik meluas, sehingga warga memandang maraknya terorisme JI sebagai pengalihan isu belaka, dan penanggulangan bencana berlarut-larut (tsunami Aceh, gempa Padang dan Yogya) akibat penyimpangan bantuan.
Proses serupa bisa dilakukan untuk menimbang bahaya ISIS dibandingkan kasus korupsi (yang memunculkan ketegangan Polri versus KPK) dan faksionalisasi politik (mulanya pembelahan kubu KIH versus KMP, kemudian berkembang menjadi pertikaian internal partai politik – PPP dan Golkar).
Stabilitas nasional sangat ditentukan oleh harmonisasi dan efektivitas kinerja lembaga negara, terlebih lagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan termasuk KPK sebagai lembaga yang muncul di era reformasi. Jika lembaga negara bertikai, atau lebih tepat oknum petinggi di tiap lembaga berbeda kepentingan, maka goncangan nasional justru bersumber dari pusat kekuasaan.
Pendukung ISIS
Sementara itu, kelompok yang disebut pendukung ISIS saat ini berasal dari individu atau pecahan kelompok sebelumnya. Belum terdengar suatu konsepsi yang matang dan gerakan yang terorganisasi rapi, kecuali pernyataan (lebih tepat bluffing) di media sosial.
Deklarasi pendukung ISIS yang pertama di Indonesia diketahui berawal dari penjara Nusa Kambangan (18 Juli 2014), ketika 23 narapidana kasus terorisme melakukan aksi baiat dan memasang bendera ISIS. Dua pekan kemudian (4/8/2014), di kota Malang muncul gerakan Ansharul Khilafah, tapi sempat dibubarkan warga setempat.
Abu Bakar Ba’asyir, tokoh sentral Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang dikaitkan dengan kemunculan ISIS membantah eksistensi ISIS Regional Indonesia dan penunjukan dirinya sebagai Amir Daulah atau Presiden ISIS di Indonesia (Merdeka Online, 14/8/2014).
Memang ada tokoh Gerakan Reformis Islam (Garis) dari Cianjur, Chep Hermawan, yang mendeklarasikan ISIS di forum terbuka (Bunderan Hotel Indonesia, 16 Maret 2014). Chep bersama kawan-kawannya itulah yang menemui Ba’asyir di LP Nusakambangan dan mengklaim telah mendapat restu. Tapi, klaim itu dibantah oleh Ba’asyir. Lebih tegas lagi, Ali Fauzi selaku adik terpidana bom Bali (Amrozi) menolak eksistensi ISIS di Indonesia (BBC Indonesia, 27/8/2014).
Anehnya, Chep menyatakan ISIS di Indonesia bukan gerakan radikal, tapi justru ingin menangkal radikalisasi. Chep mengaku membiayai dan mengirim pemuda warga Indonesia ke Suriah untuk bergabung dengan pasukan bersenjata ISIS, tapi tak ingin perang terjadi di Indonesia.
Dengan fakta kontradiksi itu, pendukung ISIS di Indonesia bersifat individual dan sporadik, belum menjadi kekuatan solid. Mungkin saja terjadi aksi kekerasan, seperti di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Namun, hal itu lebih disebabkan dampak konflik di masa lalu, yang sayangnya belum dituntas ditangani aparat keamanan. Ancaman pendukung ISIS terhadap keselamatan Presiden atau petinggi keamanan RI hanya gertak tak berdasar.
Prioritas Ancaman
Buku Putih Pertahanan RI (2008) membedakan ancaman militer dan nonmiliter yang harus diwaspadai. Ancaman militer berupa agresi, spionase, sabotase, pelanggaran batas wilayah, pemberontakan atau konflik komunal.
Lalu, ancaman non militer bisa jadi provokasi politik-ideologis, ekonomi, sosial-budaya, atau serangan teknologi informasi.
Pendukung ISIS memang piawai memanfaatkan sarana teknologi, khususnya media sosial. Tetapi, pesan politik-ideologisnya masih kabur dan tidak terkoneksi dengan jaringan perlawanan bersenjata, misalnya kaum separatis. Senjata yang dimiliki pendukung ISIS itu biasanya berupa rakitan atau hasil rampasan dari aparat.
Sebagaimana diuraikan Tom Quiggin (2007), penanggung jawab keamanan nasional suatu negara, terutama badan intelijen, harus mempertimbangkan lingkungan internasional yang kompleks, disamping faktor-faktor domestik yang rawan. Ancaman global kini bersifat asimetrik dan nontradisional, sehingga bisa datang dari mana saja. Semua faktor strategik harus dipertimbangkan betul berbasiskan data/fakta obyektif, sebelum ditentukan ancaman nasional yang harus dihadapi bersama. Sebab, publikasi terhadap gejala absurd dan belum teruji akan menimbulkan persepsi ambigu, bahkan kontroversial. Justru hal itu menjadi sumber kerawanan baru.
Gencarnya isu ISIS di tengah stagnansi penegakan hukum atas kasus korupsi dan faksionalisasi politik yang semakin tajam, bagai pisau bermata dua. Strategi itu mungkin akan menimbulkan kesadaran (atau ketakutan) publik atas ancaman nasional, atau sebaliknya, membuahkan apatisme massal dan memancing resistensi kelompok yang tidak puas. Karena masalah inti, lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi serta pemantapan stabilitas politik, tidak tertangani. Pemerintah harus fokus menghadapi ancaman nyata (clear and present danger), karena tidak cukup energi nasional yang sedang terkoyak sekarang untuk merespon beragam masalah yang tak jelas arahnya.
Rumuskan masalah prioritas. Hadapi dan selesaikan secara tuntas. Agar rakyat bisa bergerak bersama mencapai tujuan pembangunan nasional yang terbengkalai. Jika gagal, Indonesia akan mengalami setback yang mencemaskan.*
Penulis adalah dosen STT Nurul Fikri, alumni S. Rajaratnam School of International Study, Singapura dan penulis buku “Kontra Terorisme, Kebijakan Indonesia di Masa Transisi” (2009)