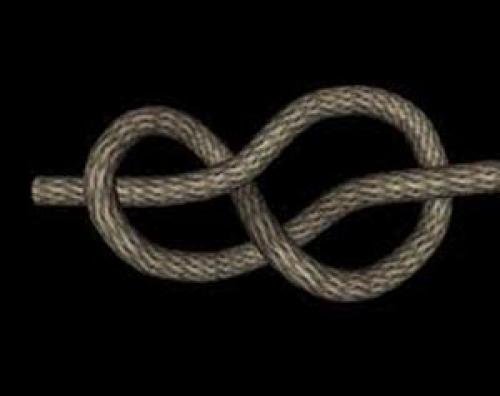Oleh: Fira Admojo
Hidayatullah.com | November 2020, BBC mengeluarkan hasil investigasi terkait pembukaan lahan sawit yang sangat luas di Papua. Hasil investigasi mengungkap perusahaan Korea Selatan ‘sengaja’ membakar lahan untuk perluasan lahan sawit pada periode 2011-2016.
Selain persoalan pembakaran lahan, terkuak pula segala konflik yang melingkupinya, seperti konflik antar warga, maupun konflik dengan aparat (yang berafiliasi dengan perusahaan). Laporan tersebut mendapat tanggapan dari pihak yang terkait, baik dari pemerintah, perusahaan, LSM maupun masyarakat itu sendiri.
Pemerintah mengklaim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan menindak tegas perusahaan manapun yang melanggar ketentuan perundangan. LSM seperti Greenpeace bersama Forensic Architecture menyatakan sudah pernah melayangkan laporan lapangan sejak 2016, namun kasusnya tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Perusahaan telah tegas membantah laporan tersebut, dan menyatakan aktivitasnya adalah legal karena sudah mengantongi izin dari pemerintah. Masyarakat setempat menyatakan tidak puas dengan ganti rugi perusahaan dan menyesali alih fungsi lahan hingga merasakan dampak meresahkan dari segala potensi konflik yang terjadi.
Konflik Eksploitasi Lahan, Cerita Tak Berkesudahan
Kondisi lahan yang luas dan iklim yang mendukung di Indonesia, banyak perusahaan termasuk swasta asing sangat berlomba-lomba untuk berinvestasi di bidang perkebunan, terutama pengembangan kelapa sawit. Selain di Papua, konsesi sawit yang cukup besar juga tersebar di Sumatera dan Kalimantan.
Konsesi lahan yang besar ternyata menyisakan banyak konflik dibaliknya, terutama konflik perebutan lahan hingga gesekan antar warga maupun antar aparat yang berafiliasi ke perusahaan. Catatan konflik lahan memenuhi cerita kelam sepanjang peristiwa pengambilalihan oleh perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan.
Berdasarkan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2019 terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektar berdampak pada 109.042 keluarga. Lima tahun tahun terakhir terjadi 2.047 konflik agraria terutama di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Selama pandemi tercatat ada 35 konflik agraria, diiringi 39 kasus kriminalisasi dan intimidasi, serta 2 petani tewas di wilayah konflik agraria karena mempertahankan wilayah hidupnya. Selama periode pertama pemerintahan Jokowi, menurut KPA sudah ada sekitar dua ribu warga yang menjadi korban konflik agraria. “Selama 2015-2019 ada 55 orang tewas, 75 tertembak, 757 orang dianiaya, dan 1.298 orang dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya” jelas Sekjen KPA, Dewi Sartika.
Sepanjang 1988-2019 konflik agraria mengakibatkan korban jiwa sekitar 673,8 ribu orang di berbagai provinsi di Indonesia. Akankah konflik berhenti sampai disini ketika ekspansi korporasi atas lahan semakin massif?
Sumber Persoalan Eksploitasi Lahan
Luasnya lahan di Indonesia dan potensinya yang besar sebagai sumber utama penghidupan, selayaknya dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang bervisi jangka panjang dan memberikan kemanfaatan yang luas. Terlebih lahan hutan yang berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem, penjagaan iklim, yang pasti akan berdampak terhadap kelangsungan hidup dan masa depan umat manusia. Sayangnya, visi tersebut sepertinya tidak dimiliki oleh pengusa yang menerapkan tata aturan kapitalisme sekuler seperti saat ini.
Setidaknya persoalan krusial yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan antara lain :
Pertama, tidak ada konsep pembagian kepemilikan kekayaan. Mana yang wajib dimiliki negara, mana yang menjadi hak umum dan mana yang boleh dikelola oleh individu maupun korporasi. Konsep menyatakan siapapun bisa memiliki kekayaan apapun selama ia mampu. Jelas, potensi hukum rimba dan tajamnya ketimpangan akan selalu terjadi.
Mengutip data BPS per 2018, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, yaitu 1% penduduk menguasai 68% tanah. Sektor perkebunan sawit terdapat 25 grup perusahaan yang mendominasi penguasaan 16,3 juta hektar tanah, hutan seluas 30,7 juta hektar dikuasai 500 perusahaan dan sektor tambang mencapai 37 juta hektar. Wajar, yang kaya akan semakin berkuasa, yang miskin akan semakin tertindas. Pada titik tertentu, potensi meletusnya konflik akan selalu terbuka.
Kedua, neoliberalisme dan korporatokrasi. Sebuah iklim kebebasan investasi yang dilegalisasi Undang-undang bagi para korporasi besar, termasuk swasta asing, bahkan pada akses kepemilikan publik yang strategis. Termasuk di dalamnya sumber energi maupun sumber daya alam, seperti hutan dengan areal konsesi yang sangat besar dan sangat lama.
Hal ini yang menjadikan para korporasi besar seperti diatas angin, dan tidak mudah tersentuh hukum sekalipun praktik pelanggaran dilakukan, apalagi memiliki kemampuan melibatkan aparat negara. Keberadaan aparat kepolisian, telah diakui menjadi bagian dari anak usaha Korindo di Boven Digoel, Papua. Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal, juga membenarkan karena perkebunan kelapa sawit dikategorikan sebagai obyek vital. “Pihak perusahaan minta untuk kita lakukan pengamanan. Kita kirimkan personel untuk lakukan pengamanan,” jelas Syamsurizal, seraya mengatakan bahwa itu adalah hal yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.
Keterlibatan aparat dalam operasional perkebunan sawit jelas sangat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat adat. Pada Mei lalu misalnya, seorang warga Boven Digoel, Marius Betera, meregang nyawa setelah mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian di kantor PT TSE di Boven Digoel.
Penguasaan konsesi lahan yang besar oleh korporasi juga berdampak pada konflik kepemilikan hingga rawan kecemburuan sosial akibat perebutan akses sumber daya yang semakin menipis. Elisabeth Ndiwaen, perempuan suku Malind, dari Kampung Nakias yang telah lama tinggal di kota Merauke, menuturkan kesepakatan lahan telah menciptakan konflik antarmarga.
Satu marga bertikai dengan marga lain soal batas tanah. Sementara, warga satu kampung yang sama bersitegang soal tawaran ganti rugi perusahaan. “Itu yang terjadi, saudara bunuh saudara. Adik bunuh kakak, akhirnya itu yang terjadi. Itu saya alami dalam saya punya hidup dan saya saksi mata. Saya lihat terjadi konflik ini, adu domba,” ujar Elisabeth.
Konglomerasi perusahaan sawit Korindo mencapai 57.000 hektar, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Jelas perusahaan pun tak bisa langsung disalahkan, karena didukung oleh penguasa dengan segala regulasi melalui sistem korporatokrasi, varian baru dari demokrasi. Manajer humas Korindo ini menambahkan bahwa, “Harus dipahami dengan jelas bahwa kepemilikan legal atas tanah terletak pada pemerintah Indonesia, bukan masyarakat adat. Pemerintah telah memberikan izin untuk jangka waktu 35 tahun dan kepemilikan legal atas tanah tidak ada hubungannya dengan masyarakat adat“.
Ketiga, kekuasaan tanpa visi. Praktik demokrasi juga melahirkan para penguasa yang dipilih hanya berdasarkan elektabilitas dan dukungan para pemodal. Jelas ini bukanlah tanpa kompensasi.
Jangan harap muncul para penguasa dengan visi agung menjadikan negaranya berdaulat penuh, mandiri dan berpengaruh di mata dunia. Sebaliknya, tunduk patuh pada kepentingan korporasi. Terlebih pengaruh korporasi yang semakin kuat pada hampir seluruh partai pengusung penguasa.
Bisa jadi ada yang masih memiliki idealisme kuat, namun tidak akan mudah direalisasikan selama kepungan kepentingan para pemilik modal sudah menggurita. Bahkan dalam iklim ‘demokrasi’pun, akhirnya bisa lahir para diktator konstitusional, demi menjaga kepentingan yang lebih besar. Sayangnya, itu bukan rakyat.
Menggagas Pengelolaan Lahan secara Adil
Manusia tak seharusnya dibatasi dalam upaya mencari solusi terbaik, dari konsep apapun dan dari agama manapun. Selama pengkajian dilakukan dengan jernih dan objektif, tidak ada salahnya mengambil konsep solusi diluar konteks demokrasi saat ini.
Termasuk tawaran solusi pengelolaan lahan dalam konsep ajaran Islam. Terlebih, sebagai sebuah dien, Islam adalah ideologi. Tentu saja menjadi menarik seharusnya, menggali lebih dalam bagaimana konsep Islam dalam menyelesaikan konflik lahan.
Konsep politik ekonomi Islam, juga bicara mengenai pengaturan pengelolaan kepemilikan kekayaan hingga mekanisme distribusinya. Islam, sebagai dien yang diturunkan Allah, Sang Maha Pencipta, dengan tegas membagi bentuk kepemilikan kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu.
Islam tidak membebaskan seperti kapitalisme dan tidak mengekang seperti sosialisme, namun mengaturnya secara tepat dan sempurna. Kekayaan dengan potensi yang luas dan tak terbatas, seperti sumber daya alam dan sumber energi, menjadi milik umum (rakyat) dan haram dimiliki negara apalagi individu termasuk korporasi. Hutan termasuk didalamnya.
Negara wajib mengelolanya dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik umum (yang pastinya akan sangat besar) adalah untuk memenuhi kebutuhan umum, seperti untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan publik. Inilah konsep keberpihakan pada masyarakat yang sesungguhnya. Jelas, ketika penguasa menyerahkan konsesi hutan atau tambang kepada korporasi, itu adalah kedzaliman yang nyata.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, api dan padang rumput.” (HR Abu Daud).
Artinya, barang yang mencakup hajat hidup orang banyak adalah milik bersama, dan haram bagi negara untuk menyerahkannya kepada korporasi. Lahan hutan misalnya, sebagai kepemilikan bersama, pengaturannya tetap dilakukan oleh negara.
Negara berhak menetapkan wilayah konservasi yang artinya tidak boleh ada pemanfaatan selain untuk konservasi, dan wajib memberi sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar wilayah konservasi. Negara juga berhak menetapkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Termasuk dalam menetapkan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan. Seberapa luas, seperti apa pengelolaannya dengan memperhatikan aspek kemaslahatan yang lebih luas, di wilayah mana saja, untuk komoditas apa dan seterusnya.
Negara dalam hal ini, akan melibatkan para ahli yang kompeten di bidangnya. Boleh menggunakan tenaga ahli asing seandainya negara belum memiliki ahli dibidang tersebut, dengan catatan hanya sebagai pekerja, bukan menyerahkan kepemilikan atau konsesi maupun kesepakatan-kesepakatan yang mengancam kedaulatan negara.
Negara haram hukumnya menyerahkan kepemilikan kepada individu atau korporasi dan haram hukumnya menjadikan hasil kekayaan milik umum diperuntukkan bukan untuk kebutuhan masyarakat umum. Dalam konsep Islam, pos pemasukan dan pengeluaran negara sudah ditetapkan berdasarkan hukum syariah.
Pos pemasukan dari kekayaan milik umum hanya digunakan untuk pembiyaan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum, seperti pendidikan, kesehatan, jihad, atau urusan darurat seperti kondisi bencana. Pos zakat misalnya, hanya dikeluarkan untuk kebutuhan 8 asnaf seperti yang tersebut dalam nash. Pos pendapatan negara seperti fa’i, kharaj dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara seperti menggaji pegawai, pembelian fasilitas negara dan seterusnya.
Konsep pemasukan dan pengeluaran yang jelas akan memastikan bahwa sumber-sumber pembiayaan akan selalu menjadi bagian yang diperhatikan pengelolaannya oleh negara. Tidak akan dibiarkan sumber pendapatan diambil oleh siapapun yang tidak berhak.
Konsep politik ekonomi Islam juga mendorong untuk memproduktifkan lahan secara berkelanjutan, tidak sekedar memilikinya. Bahkan negara berhak mengambil paksa kepemilikan lahan ketika ditelantarkan hingga tiga tahun lamanya, dan berhak diberikan kepada siapapun yang mampu memproduktifkannya.
Rasulullah ﷺ bersada, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas tanah tersebut.” (HR at-Tirmidzi). Khalifah Umar ra. pernah berkata, “Orang yang menelantarkan tanah selama tiga tahun dan tidak mengelolanya, lalu datang orang lain dan mengelolanya, maka orang itu berhak atas tanah tersebut.”
Tentu saja, butuh peran negara terutama untuk tanah-tanah marjinal, seperti tanah gambut atau bekas tambang, yang akan sangat sulit dihidupkan oleh individu, karena membutuhkan alat berat dan biaya yang tidak sedikit. Negara dalam konsep Islam, pun boleh membagikan lahan secara cuma-cuma bagi siapapun yang bisa memproduktifkannya sesuai kemampuan.
Inilah konsep pengolaan lahan yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Terhindar dari potensi konflik dan kerusakan yang berkepanjangan. Tentu saja, tak bisa dilepaskan dari sistem politik atau konsep pemerintahan Islam. Karena penerapan aturan ekonomi Islam, tidak akan mungkin berjalan dalam kerangka sistem politik demokrasi sekuler. Jika Islam memiliki seperangkat konsep pengaturan kenegaraan, mengapa tidak dikaji? Selama tidak diperjuangkan dengan anarki, apanya yang ditakuti? Wallahu’alam.*
Pegiat Majelis Taklim