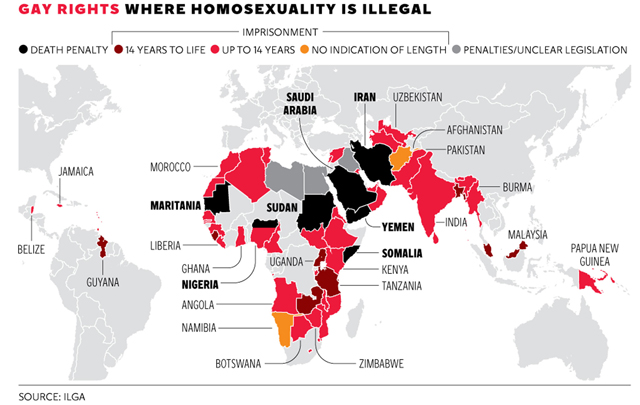Oleh: Beggy Rizkiyansyah
KEMERDEKAAN kita memang sudah menginjak 71 tahun. Namun banyak hal yang belum kita rengkuh, atau setidaknya kita rengkuh sepenuhnya. Salah satunya adalah kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi bukan saja kemerdekaan sebuah negaranya. Namun juga rakyatnya yang dapat berdaulat secara ekonomi. Bebas dari penindasan dan penghisapan.
Seringkali kemajuan ekonomi, atau katakanlah pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai sebuah prestasi. Padahal pertanyaan penting yang perlu dikemukakakn adalah pertumbuhan oleh siapa dan untuk siapa? Pertanyaan ini penting untuk dilayangkan demi menilai seberapa berpengaruh pertumbuhan itu terhadap rakyatnya. Padahal seringkali angka-angka pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah jurus kampanye bagi para pengejar kursi kekuasaan. Nyatanya, jargon pertumbuhan itu perlu kita kritisi, mengingat fakta-fakta yang hadir, menyatakan kondisi yang semakin memprihatinkan untuk sebuah bangsa yang telah 71 tahun merdeka.
Bank Dunia, tahun 2015 lalu merilis laporan yang mencengangkan. Laporan itu menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar. Menurut laporan tersebut, Pada tahun 2002, 10% warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54% warga termiskin. Rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan meningkat dari 30 (tahun 2000 ) menjadi 41 (tahun 2014), yaitu angka tertinggi yang pernah tercatat. Penguasaan kekayaan yang memusat di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, di bawah Rusia dan Thailand. Di Indonesia, 10% orang Indonesia terkaya menguasai sekitar 77% dari seluruh kekayaan di negeri ini. Satu persen orang terkaya bahkan memiliki separuh dari seluruh kekayaan. (World Bank , Ketimpangan yang Semakin Lebar, Executive Summary: 2015)
Dampak dari ketimpangan pendapatan tadi berimbas pada ketimpangan lain yaitu ketimpangan terhadap mendapatkan peluang yang sama sejak lahir, terutama akses terhadap gizi, kesehatan dan pendidikan. Ketimpangan ini juga berimbas pada lapangan pekerjaan. Sementara upah terhadap pekerja terampil semakin meningkat, pekerjaan kurang terampil terjebak pada upah dan produktivitas yang rendah. Ketimpangan ini dirasakan menyayat karena keadaan ini tak ada bedanya dengan tanah air kita di masa penjajahan.
Pemikiran liberalisme klasik menjadi motivasi negara-negara Barat untuk menjajah demi mencari pasar baru produk-produk mereka. Selepas Perang Jawa, Cultuurstelsel (Tanam Paksa) membebani pundak masyarakat Jawa dan menyedot hasilnya habis-habisan. Surplus ekonomi hasil tanam paksa selama 1840-1871 yang menghasilkan 781 juta gulden ini merupakan surplus ekonomi yang nyaris tanpa modal, karena tenaga petani kita dieksploitasi secara brutal. Eksploitasi ini membuat ekonomi petani hancur dan lapisan petani yang mampu akhirnya tumbang, sehingga petani miskin bertambah banyak. Di masa setelahnya, Perkebunan-perkebunan tebu memanfaatkan petani-petani tak miskin dan bermodal tadi menjadi sumber bagi buruh murah perkebunan Belanda di Jawa dan Sumatera. Ketimpangan saat itu menganga luar biasa. Upah Buruh perkebunan hanya 50 sen, sedangkan para pemegang saham perkebunan swasta kolonial menerima deviden lebih dari 40%. Perlu diketahui, selama 1915 – 1920 jumlah surplus ekonomi melonjak menjadi 3,3 miliar gulden. Tentu saja surplus ekonomi ini tak dinikmati oleh rakyat pada masa itu. (Sritua Arief, Kolonisasi Ekonomi Indonesia dalam Negeri Terjajah: 2006)
Jatuhnya rezim orde lama, dan naiknya orde baru memang memberi suasana yang berbeda. Rezim ‘pembangunan’ dan ‘pertumbuhan’ ini di atas kertas memang menunjukkan angka-angka yang mengesankan. Namun di balik itu ternyata pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Dalam satu dekade saja ekonomi orde baru telah menunjukkan angka ketimpangan yang memprihatinkan. Jika kini angka ketimpangan semakin membesar. Ketimpangan itu bahkan semakin kentara tatkala kita melihat pemandangan gedung-gedung mewah pencakar langit di Jakarta yang dikelilingi pemukiman-pemukiman kumuh dan perkampungan padat. Pembangunan di Jakarta yang digencarkan oleh Gubernur Basuki TP (Ahok) justru semakin memperkuat sinyalemen adanya diskriminasi dalam pembangunan di Jakarta. (Beggy Rizkiyansyah, Jakarta untuk Siapa?: 2016). Di Jabotabek ribuan hektar lahan dikuasai oleh segelintir raksasa pengembang saja. Di Karawaci, Tangerang misalnya, 3.222 hektar lahan dikuasai hanya oleh sebuah pengembang saja.
Ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan bukan hanya terjadi di perkotaan saja. Ketimpangan antara kota dengan desa juga sama mengenaskan. Sritua Arief menyebutkan bahwa industrialisasi dan pemusatan ekonomi di perkotaan pada masa Orde baru tak memberi dampak atau pengaruh ke pedesaan. Pendapatan di pedesaan terus tertinggal dibanding perkotaan. (Sritua Arief, Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal: 1978)
Saat ini, Sekitar 40,6% tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Dan tragisnya, sekitar 57,8% penduduk miskin di Indonesia berada di sektor pertanian. Munculnya kemiskinan yang besar di sektor pertanian di Indonesia disebabkan tidak meratanya akses petani terhadap faktor produksi terutama lahan dan modal. Tenaga kerja di sektor pertanian, rata-rata merupakan buruh tani dan petani gurem yang rata-rata hanya memiliki lahan 0.5 hektar. Ini yang menjadi sebab utama rendahnya produktivitas petani di Indonesia yang menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan di sektor pertanian.
(Perkumpulan Prakarsa, Policy Brief : Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pilihan Investasi untuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia : 2014)
Di Pedesaan lahan dikuasai oleh sekelompok kecil pihak. Sementara mayoritas petani adalah petani tanpa lahan. Rumah tangga petani yang menguasai lahan kurang dari satu hektar juga terus berkurang. Jika pada tahun 2003 jumlahnya mencapai 9,3 juta rumah tangga, maka pada tahun 2013 berkurang menjadi 4,3 juta. Menurut laporan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan mengenai regenerasi petani, rumah tangga dengan penguasaan lahan kurang dari satu hektar umumnya merupakan petani berpendidikan dan pendapatan rendah. Ketika usaha taninya tidak memberikan hasil yang baik atau tidak memberikan kepastian maka kelompok ini umumnya beralih profesi dan atau melepaskan aset lahannya. Hal ini sejalan dengan makin maraknya pembangunan infrastruktur terutama di Jawa yang sebagian besar di area pertanian. (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Regenerasi Petani; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menjadi Petani Pada Keluarga Petani Padi dan Hortikultura: 2015)
Sesungguhnya penguasaan lahan adalah hal yang amat penting bagi Indonesia. Sebagai negeri agraris dimana 40% penduduknya masih bertani, penguasaan lahan bagi petani menjadi hal yang krusial. Bung Hatta pada tahun 1943 pernah menyatakan hal ini. Menurutnya, “…karena Indonesia adalah negeri Agraria. Dalam negeri agraria faktor produksi yang terkemuka ialah tanah. Memang tak ada faktor produksi yang mungkin dengan tiada pesertaan kerja manusia dan kapital, banyak sedikitnya. Akan tetapi kedudukan faktor tanahlah yang berpengaruh besar akan kemakmuran rakyat. Hanya sebagai faktor kemakmuran rakyat tanah itu mendapat penghargaan sosialnya. Oleh karena itu segala peraturan terhadap hak tanah hendaklah sesuai dengan tuntutan ‘tanah sebagai faktor produksi yang terutama’ dalam menghasilkan kemakmuran rakyat.” (Sritua Arief, Kebijakan Pertanahan dalam Pemerintahan Orde Baru; Telaah Ekonomi Politik dalam Negeri Terjajah: 2006)
Di tengah ancaman ketimpangan penguasaan lahan, alih fungsi lahan pertanian juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan petani itu sendiri. Harian Republika pada Februari 2016 misalnya, menyebutkan lahan pertanian di Sumatera Utara terus menurun. Pada 2012, luas lahan pertanian mencapai 464.827 ha, lalu menurun pada 2013 menjadi 452.295 ha. Begitu pula di Yogyakarta. Setiap tahun tercatat 200 ha hingga 250 ha lahan pertanian beralih menjadi ruang usaha, industri, hingga permukiman. Salah satu ancaman terhadap alih fungsi lahan pertanian ini bukan hanya ketahanan tetapi juga kedaulatan pangan Indonesia. Maka ancaman impor pangan semakin menghantui pemerintah dan rakyat Indonesia. Jika ini terus terjadi maka ketimpangan akan semakin menganga di antara masyarakat kita.
Di antara segudang persoalan ketimpangan pendapatan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty bagi para ‘pengemplang pajak.’ Mayoritas rakyat yang hidupnya sudah sedemikian sulit ini, dibebani berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi (dan seringkali tak dirasakan manfaatnya). Di lain sisi pemerintah malah melakukan pengampunan terhadap para pengemplang pajak yang sebenarnya adalah orang-orang yang menguasai sebagian besar kekayaan di republik ini. Keputusan pemerintah ini amat mengusik rasa keadilan dan menyakiti hati masyarakat. Ketimpangan rupanya bukan saja terjadi dalam soal pendapatan, tetapi juga ketimpangan perlakuan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.
Peran Umat Islam
Umat Islam di Indonesia dapat bercermin dari sejarah. Salah satu gerakan terbesar dan pelopor kebangkitan di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Kita dapat belajar dari Sarekat Islam yang mendapat dukungan luas dari rakyat saat itu. Dari hanya 4500 anggota tahun 1912, tahun 1919 mencapai dua juta anggota. Sarekat Islam sebelum menjelma menjadi kekuatan politik, adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Dengan dukungan masyarakat kelas menengah khususnya para pedagang batik, Sarekat Dagang Islam menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi bumiputera saat itu. Pun ketika Sarekat Islam menjelma menjadi kekuatan politik, orientasinya bukan pada perebutan kekuasaan. Melainkan menjadi advokasi bagi rakyat, terutama rakyat kecil. Perhatian Sarekat Islam banyak ditujukan pada kaum tani dan buruh yang tertindas oleh kapitalisme di Hindia Belanda. Kritik-kritiknya ditujukan kepada praktik penghisapan rakyat kecil terutama buruh perkebunan dan tani. Hal ini dapat kita dengar dari pidato Tjokroaminoto tahun 1916.
“Tidaklah layak Hindia Belanda diperintah oleh Holland. Zoals een landheer zijn percelen beheert (Sebagai tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya). Hindia Belanda tidaklah layak lagi dianggap sebagai seekor sapi perahan, yang hanya diberi makan demi susunya. Tempat dimana orang-orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan.” (A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?: 1985)
Pembelaan terhadap rakyat kecil, terutama kaum tani dan buruh, kelompok ekonomi yang paling menderita saat itu, menyebabkan meroketnya dukungan rakyat kepada Sarekat Islam. Kita dapat belajar bagaimana gerakan-gerakan umat Islam seyogyanya tak hanya terpaku pada kekuasaan semata, tetapi juga menolak ketimpangan dan penindasan satu kelompok atas kelompok lainnya dalam masyarakat. Agar kata merdeka (dari ketimpangan) bukan hanya sekedar slogan dan mimpi, tetapi menjadi kenyataan.*
Penulis adalah pegiat Jejak Islam untuk Bangsa