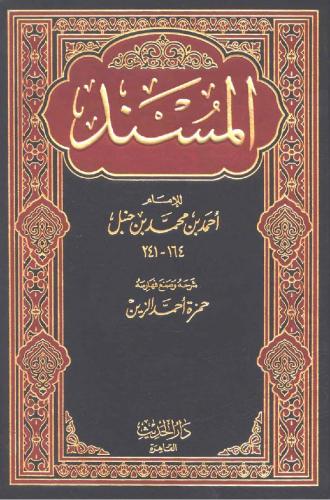Sambungan artikel KEDUA
Oleh: Tiar Anwar Bachtiar
Reproduksi Fitnah Wahabi Abad ke-21
Sejak sekitar awal abad ke-21, seiring dengan tragedi WTC (11/9/2001) dan munculnya isu terorisme yang dialamatkan kepada umat Islam, istilah “Wahabi” muncul kembali menjadi isu hangat. Wahabisme oleh media-media Barat dianggap sebagai basis ideologi gerakan-gerakan yang dianggap teroris seperti Al-Qaeda (al Qaidah), Ikhwanul Muslimin, Hizbut-Tahrir, dan sebagainya. Media-media Barat yang menguasai informasi dunia telah menyebabkan stigma ini sangat tertanam dalam pikiran umat manusia di dunia, yaitu bahwa Wahabisme sama dengan “terorisme”.
Karena penguasaannya yang massif, media-media Barat berhasil membentuk opini mengenai isu ini. Tambahan lagi, menguatnya persaingan antar negara-negara Arab ikut menyulut semakin digorengnya isu Wahabi ini. Dalam hal ini, ekspansionisme Iran semenjak Revolusi 1979 menjadi salah satu pemantiknya dan munculnya Saudi Arabia sebagai negara kaya di Timur Tengah.
Revolusi Iran tahun 1979 cukup berhasil mengeluarkan Iran dari jebakan krisis ekonomi dan politik selama masa kekuasaan Syah Reza. Perlahan namun pasti Iran muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, militer, dan politik baru di kawasan Timur Tengah. Pengaruh Iran semakin membesar sejak saat itu. Pada saat yang sama, Iran mendapat pesaing kuat dari negara Petro-Riyal Saudi Arabia yang pada saat yang bersamaan telah sampai pada tingkat kemakmuran yang cukup untuk Saudi Arabia memperkokoh posisi khasnya di Timur Tengah.
Masalah masing-masing memiliki latar belakang keagamaan dan ideologi tertentu yang berbeda sudah menjadi pengetahuan umum. Di satu pihak, Iran sejak masa Dinasti Safawi hingga Revolusi Khumainiyah tahun 1979 menganut Syi’ah aliran Imamiyah. Sedangkan Saudi Arabia tergolong negara Sunni mazhab Ibnu Taimiyyah atau yang lebih sering disebut sebagai “Wahabi”. Paham ini dipraktikkan dan diajarkan secara massif di Saudi Arabia dan disebarluaskan ke seluruh dunia melalui da’i-da’i yang di-training khusus di universitas-universitas di Saudi Arabia.
Di kalangan Ahlus-Sunnah sendiri sudah dimaklumi lahir berbagai mazhab dan kecenderungan pemikiran, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun muamalah. Perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dihindari sebagai konsekwensi dari diperkenankannya ijtihad dalam berbagai masalah yang tidak ada ketentuan dalilnya di dalam Islam. Walaupun demikian, perbedaan di kalangan internal Ahlus-Sunnah berbeda dengan perbedaan ushulî antara Ahlus-Sunnah dengan Syiah, misalnya. Oleh sebab itu, tidak bisa disebandingkan antara perbedaan Sunni-Syiah dengan perbedaan antara Wahabiyah dengan Asy’ariyah, misalnya. Akan tetapi, dalam konteks politik, perbedaan setipis dan sekecil apapun dapat menjadi alasan untuk munculnya perseteruan politik.
Di tengah persaingan baru Iran dan Saudi Arabia di Timur Tengah, isu ideologi ikut menjadi salah satu alat kontestasi di antara kedua negara ini. Iran dengan Syiah-nya, Saudi Arabia dengan Wahabi-nya. Oleh sebab itu, pasca-Revolusi Iran tahun 1979, isu mengenai Syiah dan Wahabi sebagai ideologi kembali ikut ramai kembali menjadi wacana yang sering dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang. Isu ini bukan hanya menjadi bahan kajian wacana akademik, tetapi juga muncul juga sebagai isu sosial-politik yang berdampak ke dalam hubungan antar-kelompok ideologi ini di seluruh dunia, mengingat ideologi-ideologi ini juga memiliki audiens di berbagai belahan dunia seiring dengan ekspansi para propagandisnya yang sengaja disiapkan di negara masing-masing. Iran dengan terang-terangan menyerang Wahabisme Saudi Arabia, sebaliknya Saudi Arabia menjadi negara nomer wahid penentang Syiisme Iran.
Persaingan politik di Timur Tengah ini dampaknya mau tidak mau juga sampai ke Indonesia yang memberlakukan politik luar negeri bebas-aktif yang menyebabkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah termasuk Iran dan Saudi Arabia sangat terbuka. Kerja sama Indonesia, baik dengan Iran maupun dengan Saudi Arabia, terjalin cukup baik, tanpa menafikan salah satunya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila di Indonesia pendukung-pendukung Iran dan Saudi Arabia, baik secara politik maupun ideologi, cukup banyak. Saudi Arabia sebagai negara Sunni lebih diuntungkan karena mayoritas warga Muslim di Indonesia pun Sunni sehingga hubungan menjadi lebih intensif dan tidak terlau saling mencurigai. Berbeda dengan hubungan Indonesia dengan Iran yang seringkali banyak dicurigai karena Syiah yang dianut mayoritas pendudukan Iran.
Salah satu efek persaingan itu adalah hidupnya kembali isu Wahabi di Indonesia yang selama beberapa dekade sebelumnya sudah mulai pupus dalam ingatan masyarakat Muslim di Indonesia. Apalagi setelah media-media Barat selalu mengait-ngaitkan “terorisme” dengan Wahabisme setelah peristiwa WTC 11/9. Serang Iran terhadap Wahabisme dan sebaliknya serangan Saudi terhadap Syiisme juga terjadi di Indonesia. Para penganut Syiah di Indonesia yang semakin berani menunjukkan jati dirinya sejak Era Reformasi dengan terang-terangan menjadikan “Wahabi” sebagai musuh utama mereka. Begitu pula da’i-da’i yang dididik oleh Saudi Arabia juga menjadi garda paling depan dalam menyuarakan penentangan terhadap Syiah Iran.
Rupanya konflik ini tidak bisa dikanalisasi hanya antara pendukung Wahabi dengan Syiah. Perseteruan merembet juga ke kelompok-kelompok lain. Pasalnya, da’i-da’i Wahabi ini selain sangat bersemangat menyerang Syiah, juga seringkali melontarkan kritik-kritik dengan bahasa yang tidak santun kepada kelompok Sunni lain yang berbeda mazhab. Di Indonesia kelompok yang paling sering menjadi sasaran adalah pengikut NU yang bermazhab Syafi’i dalam fikih dan Asy’ari-Maturidi dalam akidah. Kelompok ini sering diejek sebagai ahlul-bid’ah (pelaku bid’ah), quburiyyûn (suka berziarah kubur), dan istilah-istilah lain yang cukup membuat telingan panas. Tentu saja, karena bahasa ejekan dan setengah cacian, maka muncul reaksi yang juga emosional dari kalangan Nahdhiyyin. Saling serang secara verbal ini bahkan dapat disaksikan secara tebuka oleh seluruh dunia melalui saluran www.youtube.com. Sangat mudah mencari ceramah-ceramah dari dua kelompok ini yang satu sama lain, bukan hanya saling mengritik dan mempertahankan argument, tapi kadang sampai saling mengejek dan mencaci. Bukan hanya ceramah-ceramah terbuka di dunia maya, berbagai buku pun terbit dari kedua kelompok ini dengan tema yang saling serang satu sama lain.
Sebagian kalangan NU yang merasa diserang kemudian melakukan serangan balik dengan membuka kembali lembaran-lembaran sejarah Indonesia pada awal ke-20 saat isu anti-Wahabi mulai muncul di Indonesia. Buku-buku karangan penulis awal abad ke-20 seperti tulisan Ahmad Zaini Dahlan dan yang lainnya dipublikasi ulang. Narasi-narasi di dalam buku-buku tersebut dihadirkan kembali untuk menunjukkan betapa berbahayanya Wahabi sejak dulu. Dengan buku-buku itu para penentang Wahabi ingin menunjukkan bahwa saat inipun bahaya Wahabi masih tidak jauh berbeda, sekalipun objek yang disebut “Wahabi” pada awal abad ke-20 berbeda dengan yang disebut “Wahabi” saat ini.
Isu-isu mengenai Wahabi yang dimunculkan pun cenderung mengulang apa yang disampaikan awal abad ke-20. Tambahannya hanya ulasan mengenai ulama yang dianggap sebagai ideolog Wahabi baru seperti Nashiruddin Al-Albani, Syeikh Utsaimin, Abdullah bin Baz, dan sebagainya. Bahkan “Wahabisme” bagi sebagian kalangan NU diidentikkan dengan “Albanisme” atau Albanisme ini dianggap sebagai perwujudan Wahabisme Baru di zaman ini. Akan tetapi Wahabisme Baru ini setali tiga uang dengan Wahabisme awal abad ke-20, tidak bisa dipisahkan; sehingga tidak mengherankan bila kemudian serangan terhadap Wahabi masa kini pun isinya sama seperti yang dapat kita baca seabad yang lalu.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis-analisis di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan penting yang harus menjadi pelajaran berharga untuk kita.
Pertama, sejalan dengan temuan Rasyid Ridha dan apa yang kita saksikan belakangan ini, isu Wahabi sejatinya bukan isu agama semata-mata, apalagi menyangkut isu aliran sesat. Isu Wahabi adalah bagian dari produk intrik politik untuk melanggengkan atau merebut kekuasaan tertentu. Bila kemudian umat Islam terkecoh dengan isu satu abad ke belakang, berarti umat Islam berhasil dijadikan objek politik musuh-musuh Islam. Saat ini yang paling diuntungkan dengan isu Wahabi ini adalah Syiah-Iran yang sedang sangat berambisi untuk menaklukkan negara-negara Sunni.
Kedua, perbedaan antara Wahabi dan Asy’ari di kalangan Ahlus-Sunnah wal Jamaah harus dilihat dari sudut pandang ikhtilaf furû’iyyah biasa sebagaimana telah banyak dibuktikan oleh para peneliti, termasuk Rasyid Ridha. Tulisan terkahir K.H. Ali Musthafa Ya’kub tentang perbedaan furû’iyyah antara NU dan Wahabi dapat menjadi salah satu contoh yang paling tegas bahwa perbedaan ini adalah sungguh-sungguh hanya perbedaan masalah furû’iyyah ‘aqâ’idiyyah dan fiqhiyyah.
Ketiga, bila demikian kenyataannya maka untuk menyelesaikan kasus persengketaan antara Wahabi dengan yang menyebut diri sebagai Aswaja “asli” adalah dengan memperbanyak dialog, saling pengertian, dan menahan diri untuk tidak saling menghujat satu sama lain. Perbedaan-perbedaan besar yang sifatnya furû’iyyah yang sering dijadikan sebagai penyebab utama persengkataan antara dua kelompok ini sudah saatnya untuk tidak dijadikan alat untuk saling menyerang satu sama lain. Sebab, dari sinilah seringkali konflik horizontal umat Islam. Dalam hal ini, umat Islam juga harus mewaspadai provokasi musuh-musuh Islam yang tidak menghendaki bersatunya umat Islam. Wallâhu a’lam. *
Penulis adalah peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) dan doktor bidang sejarah