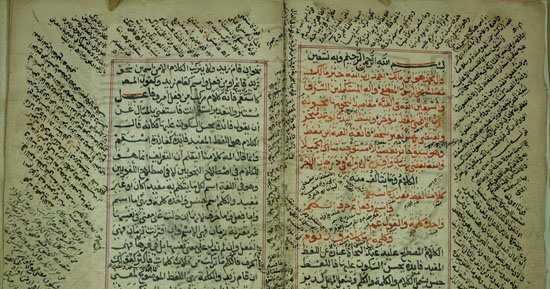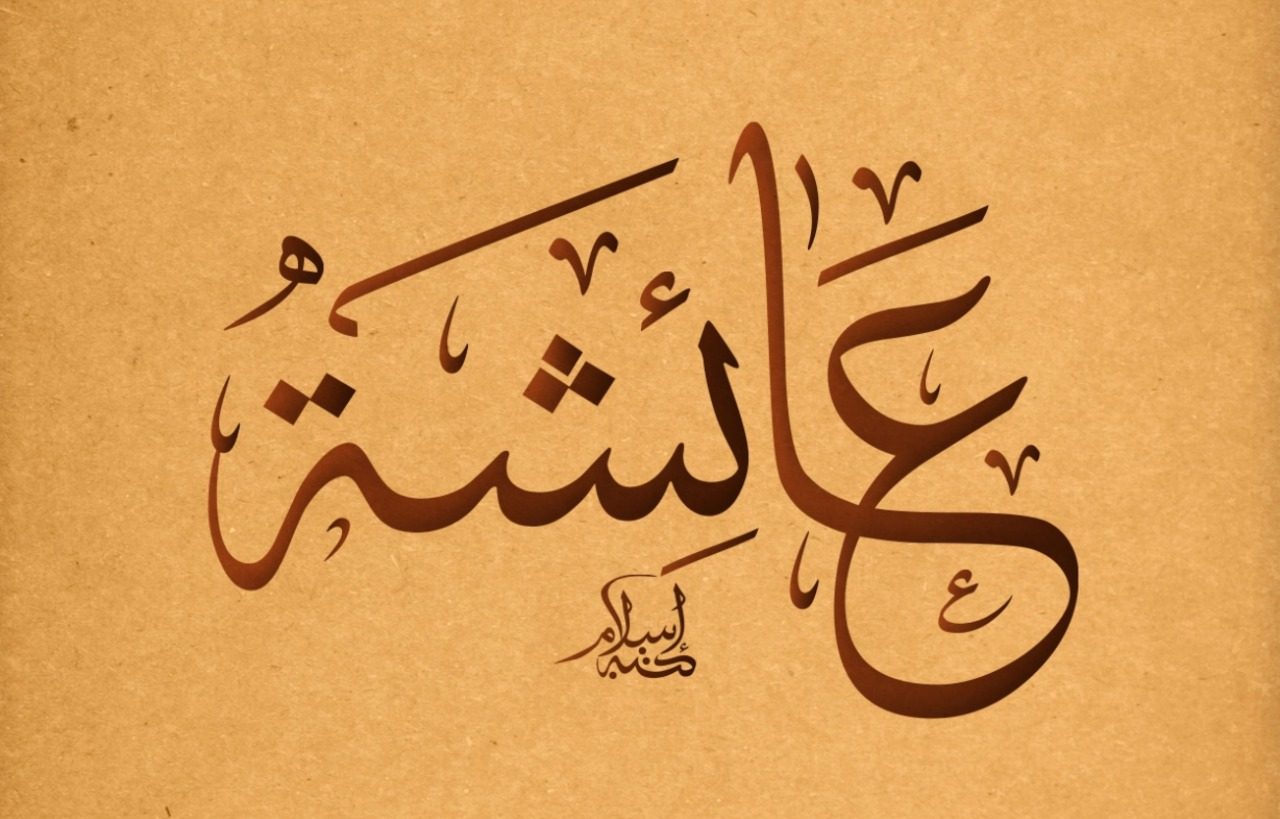Oleh : Bana Fatahillah
DALAM disiplin Ilmu Nahwu, pembahasan kata benda (isim), verba (fi’il), dan huruf (harf) – yang membentuk suatu kalimat (kalam), adalah hal yang mendasar. Imam Hasan al-Kafrawi, dalam Syarh Ajrumiah-nya mengatakan bahwa isim adalah sebuah kata yang mempunyai makna tersendiri dan tidak terikat pada ketiga zaman yang ada: masa sekarang (hāl), masa lampau (mādli), dan masa yang akan datang (mustaqbal).
Berbeda dengan isim, verba (fi’il) adalah sebuah kata yang mempunyai makna tersendiri dan terikat pada ketiga zaman yang ada. Adapun harf adalah sebuah kata yang mempunyai makna bila dihadirkan bersama kata lain dan tidak terkait ketiga zaman yang ada. Setiap perkataan dalam bahasa Arab, tidak keluar dari tiga hal tersebut.
Sebelum membahas tanda-tanda yang menunjukkan pada isim, fi’il, dan harf, Imam Asymawi dalam hasyiyah Ajrumiyyah-nya menyebutkan hukum dari ketiga hal tersebut. Menurut Imam Asymawi, hukum asal dari isim adalah mu’rob. Artinya, keadaan harakat pada akhir kata tersebut dapat berubah – dari fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Sementara hukum asal dari fi’il adalah mabni, yaitu keadaan harakat akhir pada sebuah kata yang bersifat permanen atau tetap dan tidak bisa berubah. Begitu juga dengan harf.
Dalam menulis syarh atau hasyiyah, para ulama banyak yang menyelipkan beberapa pertanyaan terkait kaidah dalam bentuk metodologi dialog (tariqat al-Muqāwalah). Itu untuk melatih para penuntut ilmu dalam memahami teks dan membangun kerangka berfikir yang baik. Biasanya mereka memulai dengan kata “fain qulta”, “qultu”, “fain qīla”, “qulna”, dan lainnya. Selanjutnya, dari kaidah diatas munculah pertanyaan, “kenapa hukum asal pada isim adalah mu’rob? Begitu juga dengan fi’il. Kenapa asal hukumnya adalah mabni?”.
Untuk menjawab pertanyaan diatas, tidak perlu mengundang pakar nahwu, membuka al-Kitab milik Sibaweih, juga kitab-kitab besar dalam nahwu seperti al-Kassyaf, al-Khasais, Al-Mufasshol, al-Tashil, al-Kaafiyah, al-Syaafiyah, dan lainnya, atau berfikir terlalu lama dengan pertanyaan ini. Yang kita butuhkan hanyalah memahami dengan baik sebuah kaidah bahasa (qawaid al-Lughawiyyah) yang berbunyi: Mā jā’a ‘an ashlihī lā yus’alu ‘an majī’i ashlihī, wa’idzā kharaja ‘an ashlihī falatus’alu ‘an sababi khurūjihī. (Jika sesuatu sudah sesuai dengan aslinya, maka jangan kamu tanyakan sebab terjadinya hal tersebut. Taoi, jika sesuatu keluar (menyimpang) dari keasliannya, maka pertanyakanlah sebab dari keluarnya hal tersebut).
Mari kita cocokan kaidah diatas pada permasalahan isim dan fiil. Asal dari isim adalah mu’rob, dan apabila keluar dari keasliannya, maka harus dicari sebabnya. Ternyata benar. Jika diteliti, ada beberapa isim yang bersifat mabni, seperti isim dhomir (huwa, hunna) isyarat (inna), dan maushu (alladziy, allatiy). Dengan demikian, yang perlu dicari adalah sebab keluarnya isim dari keasliannya. Ditemukan, salah satunya karena isim menyerupai fi’il dari segi jumlah huruf dan makna. Karena itu, ia mengambil hukum fi’il yaitu mabni. (Selengkapnya lihat, Ibnu Aqil, Syarh ala al-Alfiyah).
Begitu juga fi’il, yang hukum asalnya bersifat mabni. Jika dicermati, fi’il mudhori yang bersifat mu’rab hadir dan menggugurkan sifat keasliannya. Perlu ditelaah sebab-sebab fi’il keluar dari keasliannya. Alhasil, didapatkan, salah satunya adalah keserasiannya dengan isim dari segi makna. (Selengkapnya lihat Zaini Dahlan, Risaalah fi I’rābi jā Zaidun, Dār el-Adab, Kairo : 2016, hal. 22-23).
Pelajaran berharga
Dari kaedah Ilmu Nahwu yang sederhana “Mā jā’a ‘an ashlihī lā yus’alu ‘an majī’i ashlihī…” barangkali bisa dipetik hikmah berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Sesuatu yang sudah sesuai dengan keaslian atau hakikatnya, tidaklah perlu dipertanyakan. Seorang muslim, misalnya, sepatutnya berpikir dan berperilaku sebagai muslim. Jika seorang muslim berpikir dan berperilaku seperti orang kafir atau munafik, maka itulah yang perlu dipertanyakan. Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian darinya” (H.R Abu Daud).
Kewajiban seorang anak adalah patuh dan tunduk terhadap orang tuanya. Maka, jika ada seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, tidak perlu dipertanyakan. Sebab, itulah kewajiban dasarnya. Sebaliknya, jika ada anak yang durhaka pada orangtuanya, justru itulah yang dipertanyakan sebab mengapa hal ini bisa terjadi.
Tujuan mahasiswa datang ke suatu universitas adalah untuk belajar. Jika ada mahasiswa yang tekun belajar, ikut majlis keilmuan, dan selalu membaca buku, tidak perlu dipersalahkan. Sebab, itu itulah tujuan aslinya. Namun sebaliknya, jika ada mahasiswa tidak pernah belajar, tidak hadir di majlis keilmuan, maka orang-orang inilah yang harus dipertanyakan. Mengapa mereka menjadi seperti itu.
Kewajiban seorang hamba adalah menaati perintah Tuhannya. Apabila ada seseorang yang tidak mengerjakan larangan Allah, jangan dikatakan “sok alim”. Sebab, itu adalah kewajibannya sebagai hamba. Sebaliknya, saat ia melanggar larangan-Nya, ketika itulah ia perlu disoal.
Skeptis
Dalam makalahnya yang berjudul “Ilmu, Kebenaran, dan Keraguan: Refleksi Historis-Filosofis” yang disampaikan dalam orasi ilmiahnya pada peringatan ulang tahun ke-13 Institue for the Study Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Dr.Syamsudin Arif menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari kebenaran dan bersifat negatif terhadap ilmu, secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (i) Skeptisisme, (ii) Relativisme, (iii) Agnositisme. (lihat Orasi Ilmiah Syamsuddin Arif, Ilmu, Kebenaran, dan Keraguan ; Refleksi Historis-Filosofis, Jakarta : 2016)
Ambillah kasus keptisisme dengan mengaitakan pada kaidah nahwu terdahulu. Skeptisisme merupakan sikap meragukan kebenaran suatu peryataaan secara mendasar dan menyeluruh. Orang skeptis atau yang mengaku skeptis biasanya tidak konsisten dalam bersikap. Ia tidak percaya pada perintah Allah, pahala amal baik, surga, neraka, dan lainnya. Pada hal-hal keagamaan, ia mengaku skeptis. Tapi, tidak skeptis pada masalah lain.
Baca: Umat Harus Bermujahadah Serukan Kebaikan Meski Keburukan Seolah Kalahkan Kebenaran
Mengapa mereka hanya ragu pada hal yang berbau agama. Jika ia bersikap “skeptis sejati”, seharusnya meragukan kepada semua hal, termasuk kebenaran kata-katanya sendiri. Menurut Dr. Syam, skeptis itu berbeda dengan sifat mencari tahu. Ia memberi contoh seperti kejadian nabi Ibrahim. Ketika Allah bertanya, “Apakah kau tidak percaya?” Ibrahim menjawab, “Sudah. Tentu [aku percaya] akan tetapi [aku bertanya] supaya hatiku tentram (balā walākin liyathmainna qalbī). Ini sama halnya dengan orang yang bertanya keaslian sebuah madu, ketika membelinya. Bukan berarti ia skeptis. Kelak, ketika ia tenang saat tahu madu tersebut asli, ia akan membelinya. Itu berbeda dengan orang skeptis. Meskipun madu itu sudah dibuktikan keasliannya melalui laboratorium, pun ia tidak akan percaya.
Untuk meruntuhkan gagasan kaum skeptis ini, perlu dikaji kembali kaedah nahwu terdahulu. Jika dikatakan bahwa segala sesuatu yang datang dengan aslinya tidak perlu dipertanyakan, maka segala kebenaran yang didapat dari pengetahuan yang bersifat a priori (al-badihiyyat), indrawi (al-hissiyyat), atau hal yang didengar (al-Sam’iyyat) tidak akan bisa diubah dan tidak perlu dipertanyakan. Pertanyaan seperti, “kenapa api itu panas”, “kenapa garam itu asin”, “kenapa gula itu manis”, atau “kenapa ada surga dan neraka”, seharusnya tidak perlu dipertanyakan.
Jika dikatakan “Allah adalah Tuhan kita”, maka tidak perlu bertanya, “kenapa Allah itu Tuhan kita”. Atau, tidak perlu dipertanyakan, mengapa salat lima waktu itu wajib, dan sebagainya. Jika ada yang mengakui Tuhan-nya selain Allah, itulah yang perlu dipersoalkan. Jika ada orang mengaku muslim tetapi tidak menjalankan shalat lima waktu, maka itulah yang keluar dari sifat asalnya, sehingga harus dipertanyakan, dan dinasehati.
Dari konsep fi’il dan isim, bisa diketahui, bahwasanya kebenaran itu adalah ada dan tidak perlu diingkari. Dengan akalnya, manusia tahu dengan pasti suatu kebenaran. Tentu saja, semua itu dalam batas manusia. Sebab, manusia bukan Tuhan. Dengan mengakui adanya kepastian terhadap kebenaran, maka lahirlah berbagai bidang keilmuan.
Manusia sepakat bahwa rasa cabe itu pedas, rasa garam itu asin, rasa madu itu manis. Dengan pemahaman yang pasti semacam itu, lahirlah ilmu kuliner. Kesepakatan akan karakteristik bebatuan dan logam di alam melahirkan ilmu geologi dan metalurgi. Begitu juga lahirnya berbagai bidang ilmu lain.
Manusia memerlukan kepastian akan kebenaran untuk meraih kebahagiaan. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wata’ala . Al-haqqu min rabbika. Jangan kita ragu dengan kebenaran. Jika manusia ragu dengan kebenaran yang pasti, berarti ada penyakit dalam hatinya. Hati yang tidak yakin, berarti keluar dari sifat asalnya. Itulah hati yang sakit, dan patut dicarikan obatnya. Yakni, keyakinan dan dzikir kepada Yang Maha Kuasa. Wallahu a’lam bil-shawab. *
Mahasiswa Universitas al-Azhar Kairo