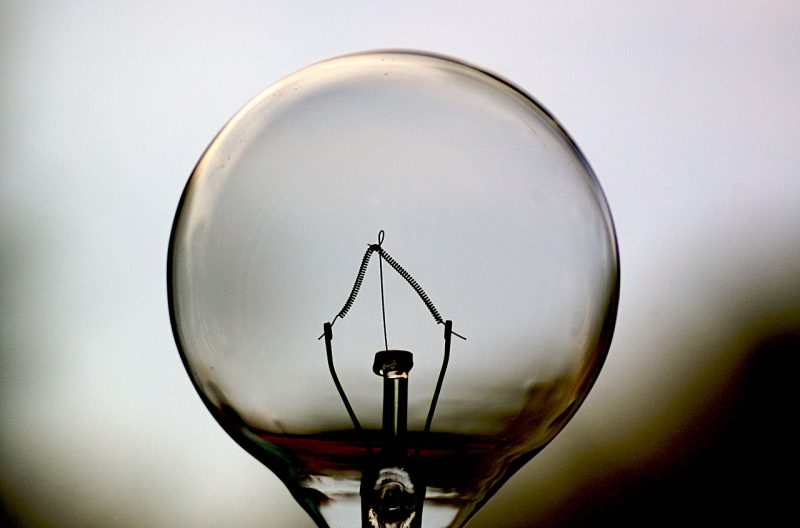Prof. al-Attas menyebut keruntuhan adab melanda kehidupan umat Islam akan mengakibatkan lahirnya pemimpin-pemimpin palsu, tidak bermoral. Inilah anarki intelektual
Oleh: Arif Munandar Riswanto
Hidayatullah.com | DI AWAL tahun 90-an, Prof. al-Attas menulis kata pengantar untuk karyanya yang berjudul Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Di bawah ini petikannya;
The disintegration of adab, which is the effect of the corruption of knowledge, creates the situation whereby the false leaders in all spheres of life emerge; for it not only implies the corruption of knowledge, but it also means the loss of the capacity and ability to recognize and acknowledge the true leaders. Because of the intellectual anarchy that characterizes this situation, the common people become determiners of intellectual decisions and are raised to the level of authority on matters of knowledge. Authentic definition becomes undone, and in their stead we are left with platitudes and vague slogans disguised as profound concepts. (Syed Muhammad Naquib al-Attas)
Bahkan, tulisan-tulisan dengan isi pesan yang sama dengan kutipan di atas telah ditulis oleh Prof. al-Attas pada awal tahun 70-an, tepatnya dalam karya beliau yang berjudul Risalah untuk Kamum Muslimin dan Islam and Secularism. Bukan hanya ditulis dalam karya-karya, penjelasan tentang kutipan di atas pun sering disampaikan oleh Prof. al-Attas dalam kuliah-kuliahnya.
Kutipan di atas yang menjelaskan tentang keruntuhan adab (the disintegration of adab) yang sedang melanda kehidupan umat Islam kemudian diberikan ulasan (sharḥ) oleh Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud dalam kuliah-kuliah dan karya-karyanya—terutama The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas.
Meskipun Prof. al-Attas dan Prof. Wan sudah menerangkan dengan jelas fenomena keruntuhan adab yang terjadi di kalangan umat Islam, tidak ada salahnya kita mengingat kembali nasihat-nasihat penting dari kedua pemikir besar di Tanah Melayu tersebut. Apalagi, situasi yang kita hadapi saat sekarang justru menunjukkan keadaan yang semakin genting daripada keadaan ketika petikan di atas ditulis oleh Prof. al-Attas. Apa yang ditulis oleh Prof. al-Attas pada tahun 70-an semakin jelas terasa pada saat sekarang.
Dalam kutipan di atas, ada istilah menarik yang digunakan oleh Prof. al-Attas untuk menggambarkan situasi umat Islam zaman sekarang, yaitu intelektual anarki (intellectual anarchy). Anarki sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu αναρχία (anarkhia) yang berarti tanpa pemimpin, tanpa otoritas resmi (constituted authority), tidak memiliki aturan (unruliness), tidak teratur (disorder), kekacauan (chaos), ketakutan (terror), dan nihilisme yang menafikan nilai-nilai moral (Peter Marshall, Demanding the Impossible A History of Anarchism [London: Harper Perennial, 2008],ix, 3).
Sedangkan istilah intelektual berasal dari Bahasa Latin, yaitu intellectus, yang berarti pemahaman (discernment) dan kecerdasan (sagacity). Prof. al-Attas menyebut bahwa intelektual adalah hakikat spiritual (spiritual substance) yang terletak dalam organ spiritual pengetahuan manusia yang disebut sebagai hati (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism,(Kuala Lumpur: ISTAC, 1993, 35). Jadi, anarki intelektual yang disebut Prof. al-Attas adalah kondisi kekacauan, ketidakteraturan, dan tanpa otoritas dalam ilmu.
Anarki intelektual yang disebut Prof. al-Attas menunjukkan bahwa umat Islam pada saat sekarang sedang mengalami kekacauan ilmu. Dari kutipan di atas, Prof. al-Attas menyebutkan bahwa salah satu penyebab anarki intelektual adalah ketika masyarakat awam (common people) menjadi penentu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Fenomena yang disebutkan oleh Prof. al-Attas semakin jelas terlihat dengan kemunculan media sosial di tengah-tengah kehidupan kita.
Di media sosial, seluruh manusia duduk setara—baik orang baik, orang jahat, pejabat, ilmuwan, anak kecil, orang dewasa, dll. Dengan media sosial juga kita bisa mendengar, membaca, menonton, dan menyebarkan segala hal yang kita mau.
Padahal, tidak semua hal bisa didengar, dibaca, ditonton, dan disebarkan. Dan itu bukan hanya berlaku untuk hal-hal buruk, hal-hal yang baik pun tidak mesti bisa kita lihat, baca, tonton, dan sebarkan semua. Anak kecil yang baru belajar membaca, misalnya, belum tepat waktunya untuk mendengar isu-isu kalam dalam agama—meskipun itu baik dan bagian dari khazanah keilmuan Islam.
Di dalam Risalah untuk Kaum Muslimin, Prof. al-Attas telah menyebutkan bahwa sikap menyamaratakan adalah salah satu bukti keruntuhan adab. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin [Kuala Lumpur: ISTAC, 2001],146).
Dan ini betul-betul terjadi di zaman media sosial. Munculnya istilah-istilah baru seperti netizen, influencer, selebgram, buzzer, viral, dan trending topic menunjukkan fenomena penyamarataan.
Dalam iklim demokrasi yang menyamaratakan segala hal, fenomena tersebut sebetulnya sudah hidup dengan subur. Tapi, ia kemudian tumbuh dengan lebih ganas lagi dengan munculnya media sosial di era yang orang Barat sebut sebagai post-truth.
Penyamarataan dalam pesta demokrasi untuk mendapatkan suara terbanyak dan kekukasaan politik mungkin bermanfaat, tapi sikap penyamarataan dalam masalah ilmu dan otoritas ilmu justru akan merusak.
Jika telah menjadi penentu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, masyarakat awam akan diangkat ke tingkat pemegang otoritas yang tinggi. Ini yang kemudian sering disebut oleh Prof. Wan dalam berbagai kuliahnya sebagai krisis otoritas (the crisis of authority).
Munculnya fenomena berita palsu (hoax) yang viral melalui media sosial adalah salah satu bukti krisis otoritas. Namun sayangnya, krisis otoritas ini justru menyerang ilmu-ilmu agama.
Dengan kata lain, ketika kita berbicara ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu agama, otoritas masih dipegang kukuh. Bahkan, dalam bidang-bidang olahraga, hiburan, seni peran dll. Otoritas masih terlihat dengan jelas.
Namun, ketika berbicara agama, semua orang berhak berbicara dan memberikan pendapat tanpa mengukur pendapatnya dengan ilmu. Dengan wasilah media sosial, orang-orang yang tidak belajar ilmu-ilmu Islam pun bisa dengan bebas membuat video dan content tentang Islam yang justru mengelirukan Islam serta memecah belah masyakarat Muslim.
Padahal, untuk menjadi ilmuwan Muslim (ulama) yang ilmunya mengakar sangat dalam (al-rāsikhūn fi al-ʿilm), perlu proses panjang yang harus ditempuh. Ulama-ulama besar seperti Imam al-Shāfiʿī (150-205 H/767-820 M), Imam al-Bukhārī (194-256 H/810-870 M), Imam al-Ghazālī (450-505 H/1058-1111 M), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (544-606 H/1149-1210 M), ḤHamzah al-Fanshūrī (1550-1600), Nūr al-Dīn al-Rānīrī (w. 1658) dan lain-lain tidak lahir dari proses yang instant.
Seseorang yang baru lulus belajar dari salah satu perguruan tinggi di Timur Tengah, banyak jadwal ceramah, dan sering menulis status di media sosial hingga memiliki banyak follower tidak serta merta bisa disebut ulama untuk kemudian memegang otoritas di dalam ilmu agama. Untuk mencetak atlet-atlet handal dalam sepak bola Seperti Pele, Diego Maradona, Zinadine Zidane, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi saja perlu waktu yang tidak sedikit dan “pendidikan” yang lama, apalagi mencetak ulama yang memiliki peran sebagai pewaris para Nabi.
Jika masyarakat awam diangkat ke tingkat otoritas ilmu yang tinggi, definisi-definisi yang sudah jelas (authentic definition) akan menjadi kabur. Sebagai contoh adalah istilah metafisika yang saat sekarang hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan membatasi cakupan pembahasan seputar isu-sisu seperti sihir, dukun, dan jin.
Padahal, jika kita membaca khazanah keilmuan Islam, metafisika yang disebut oleh Aristoteles sebagai first philosophy untuk mengkaji being qua being, sangat sedikit membahas isu-isu tentang sihir, dukun, dan jin. Dalam Ilmu Kalam yang menjadi salah satu unsur metafisika Islam, misalnya, isu-isu yang dibahas adalah isu-isu tentang epistemology (al-ʿilm), theology (al-ilāhiyyāt), psychology (ʿilm al-nafs), kenabian (al-nubuwwah), kepemimpinan (al-imāmah), ilmu alam (al-ṭabīʿiyyāt), dan eskatologi (al-ukhrawiyyāt).
Ini yang disebut oleh Prof. al-Attas sebagai kata-kata hampa (platitudes) dan slogan-slogan samar (vague slogans) yang dianggap sebagai konsep yang dalam. Ini juga yang kemudian disebut oleh Prof. al-Attas sebagai kebingungan dalam ilmu (confusion of knowledge).
Prof. al-Attas kemudian menyebut bahwa keruntuhan adab yang melanda kehidupan umat Islam akan mengakibatkan lahirnya pemimpin-pemimpin palsu, yaitu orang-orang yang tidak memiliki nilai moral, intelektual dan spiritual yang baik (al-Attas, Islam and Secularism,106).
Pemimpin di sini tentu saja bukan hanya pemimpin politik, tetapi pemimpin yang menjadi otoritas dan rujukan umat—terutama dalam masalah ilmu. Pemimpin tersebut adalah tempat umat bertanya dan teladan untuk diikuti. Sebagai penerus risalah kenabian, pemimpin yang kemudian didaulat oleh Nabi untuk memimpin kehidupan umat adalah ulama, pewaris risalah para Nabi.
Fenomena munculnya pemimpin-pemimpin palsu yang lahir di tengah-tengah umat bukan hanya fenomena yang terjadi pada zaman sekarang, pada zaman dahulu pun umat Islam pernah merasakan kelahiran pemimpin-pemimpin palsu di tengah-tengah kehidupan mereka. Imam al-Ghazālī, misalnya, telah menulis fenomena pemimpin palsu di dalam muqaddimah karyanya yang berjudul Ihyā’ ʿUlūm al-Dīn.
Imam al-Ghazālī menulis, “Petunjuk jalan adalah para ulama yang menjadi pewaris para Nabi.Tapi zaman ini tidak memiliki ulama seperti itu, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang mementingkan formalitas (al-mutarassimūn).
Kebanyakan mereka telah dirasuki oleh setan dan diperdaya oleh kesewenang-wenangan. Mereka cinta terhadap kenikmatan dunia sehingga melihat yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik.
Ilmu agama kemudian hilang dan cahaya petunjuk di penjuru bumi padam. Mereka menipu orang-orang bahwa ilmu itu hanya fatwa penguasa yang digunakan oleh hakim untuk mendamaikan persengketaan ketika orang-orang berbuat kerusuhan; atau perdebatan yang digunakan oleh orang yang mencari kesombongan dan perselisihan; atau sajak indah yang digunakan oleh penceramah untuk menarik orang awam” (al-Ghazālī, Ihyā’ ʿUlūm al-Dīn, 9. vols. [Jeddah: Dār al-Minhāj, 2011], 1: 8-9).
Di sini Imam al-Ghazālī dengan sangat jelas menyebut tiga golongan yang sering dianggap sebagai ulama tetapi jauh dari orang-orang yang berhak menjadi pewaris risalah para Nabi: orang-orang yang membatasi ilmu agama hanya sebatas hukum; orang-orang yang suka berdebat agar dilihat oleh masyarakat awam sebagai orang berilmu; penceramah yang indah kata-katanya tetapi tidak dalam ilmunya.
Lalu, bagaimana kita menghadapi zaman anarki intelektual yang sedang melanda kehidupan umat Islam? Prof. al-Attas telah menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk keluar dari tiga lingkaran ganas (kekeliruan dalam ilmu, kehilangan adab, dan kemunculan pemimpin palsu) adalah dimulai dari adab terlebih dahulu. Adab di sini berarti disiplin raga, fikiran, dan jiwa. Adab adalah disiplin berupa pengenalan (recognition) dan pengakuan (acknowledgment) bahwa segala sesuatu ada tempatnya yang tepat (al-Attas, Islam and Secularism,105-6).
Ketika segala sesuatu diletakkan di atas tempatnya yang tepat, maka akan tercipta keadilan—lawan anarki. Karena segala sesuatu ada tempatnya yang tepat, berarti segala sesuatu tidak bisa disamaratakan (Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas [Kuala Lumpur: ISTAC, 1998], 162-165).
Ilmu yang harus kit acari, misalnya, ia tidak bisa disamaratakan untuk kemudian disimpan dalam satu tingkatan yang sama. Ada ilmu farḍ ʿain, ilmu farḍ kifāyah, ilmu yang haram dicari, ilmu yang harus segera diketahui, ilmu yang bisa ditangguhkan untuk dicari, ilmu untuk makanan jiwa, ilmu berupa keterampilan (skill) untuk mempertahankan hidup di dunia, dan lain-lain. Ketika ilmu-ilmu tersebut disebut diletakkan dalam tempatnya yang tepat, berarti kita telah beradab dan berlaku adil terhadap ilmu.
Prof. al-Attas pun menjelaskan bahwa al-Qur’ān pada hakikatnya telah memerintahkan kita untuk mengembalikan amanah kepada ahlinya (al-Nisā’ [4]: 58). Amanah yang diberikan kepada ahlinya adalah seperti seorang doktor yang mempunyai keahlian untuk mengobati orang sakit.
Karena ilmu yang dimilikinya, doktor tersebut berhak diberikan amanah dan menjadi otoritas untuk mengobati orang sakit. Demikian juga orang yang sakit, ia harus meletakkan amanah kepada doktor untuk mengobatinya.
Namun, jika orang yang sakit pergi berobat kepada tukang kayu, ia telah mengkhianati dan menzalimi amanah doktor, tukang kayu, dan dirinya sendiri. Sebab, ia telah mengelirukan hak amanah dan tanggung jawab masing-masing (al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, 133-134).
Jika itu terjadi, kekeliruan dalam ilmu, kehilangan adab dan kemunculan pemimpin palsu sudah pasti tidak bisa dielakkan lagi. Ia akan mengakibatkan kezaliman, chaos, brutality, dan anarki di tengah-tengah kehidupan. WaLlāhu aʿlam.*
Mahasiswa Ph.D Raja Zarith Sofiah Centre for Advanced Studies on Islam Science and Civilisation (RZS-CASIS) Universiti Teknonolgi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur