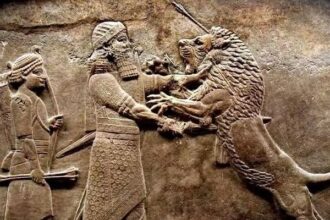Oleh: Beggy Rizkyansyah
MENINGKATNYA pertumbuhan perekonomian di Jawa dengan cepat pada awal abad ke 20, dan terjadinya krisis di pedesaan, menciptakan kondisi baru yang mendorong urbanisasi di perkotaan. Makin meningkatnya penduduk di pedesaan yang tak memiliki tanah, mendorong petani yang menjadi buruh (tani) upahan.
Di lain sisi, perluasan ekspor hasil panen dari Jawa Tengah dan Timur, serta tumbuhnya pelabuhan,perusahaan dagang,dan bank, membuka gerbang urbanisasi lebih besar. Khususnya di Surabaya, Semarang dan Batavia, di mana pelabuhan menjadi titik pengangkutan hasil panen dari Jawa ke seluruh dunia. Pelabuhan-pelabuhan tersambung dengan jaringan kereta api untuk mengangkut hasil gula dari Jawa tengah dan Timur untuk di ekspor. Maka tak mengherankan di kedua daerah tersebut tumbuh penduduk-penduduk yang awalnya berasal dari desa untuk mengadu nasib di perkotaan. Sebuah komunitas pekerja yang seringkali disebut kaum buruh. (Baca: “Perkotaan Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial”, Pengarang/Editor: John Ingleson & Iskandar P Nugraha, Penerbit: Komunitas Bambu)
Buruh perkotaan tidaklah seragam. Ada buruh yang tidak terampil mengisi berbagai pekerjaan dengan bayaran rendah, tanpa jaminan pekerjaan dan kontrak kerja. Contohnya sepert sejumlah besar buruh yang bekerja di galangan kapal di Semarang. Mereka meninggalkan keluargaanya di kampung, dan hidup di pondok kecil diatas perahu, dengan Sembilan buruh lainnya, berhimpit-himpitan tiap malam atau tidur dengan beratapkan langit. Di perkotaan, buruh-buruh lainnya tinggal di lingkungan yang buruk, pemukiman padat, diantara gang-gang yang tidak dapat masuk sinar matahari, sehingga menjadi sarang tikus. Rumah-rumah itu umumnya beratapkan rumbia dan berdinding bambu.
Selain buruh tidak terampil, ada pula buruh-buruh terampil, yang mendapat nasib lebih baik. Mereka antara lain pegawai administrasi, juru ketik, montir, operator mesin, masinis, dan lainnya. Mereka dibayar dengan upah yang lebih baik, kadang-kadang disediakan perumahan dan sejumlah dana pensiun. Merekalah yang nantinya menjadi tulang punggung serikat buruh di Hindia Belanda.
Para buruh pribumi mulai memiliki kesadaran untuk berserikat ketika melihat ketimpangan upah dan perlakuan dengan buruh-buruh Eropa dilingkungan mereka. Ketimpangan ini terlihat dalam keluhan yang dimuat Majalah Volharding.
“Mengapa buruh Eropa menerima gaji lebih besar daripada yang diterima koleganya yang Pribumi dan mengapa para buruh Pribumi menduduki posisi yang sangat tidak terpilih dalam menuntut hak pensiunnya? Bahkan jika mereka melakukan pekerjaan yang sama.”
Perubahan sosial yang terjadi di Jawa, perkembangan media cetak berbahasa Melayu dan daerah, serta kesadaran para lulusan dari pendidikan ala Barat yang dijalankan pemerintah colonial, turut mendorong berkembangnya serikat buruh yang mulai bermunculan di tahun 1910-an.
Membuka kembali lembaran penulisan sejarah buruh saat ini, lebih banyak mencatat peranan gerakan kiri dalam awal perjalanan pembelaan buruh dan cenderung meminggirkan peranan gerakan Islam. Padahal gerakan Islam, khususnya Sarekat Islam (SI), memainkan peranan penting dalam pembelaan nasib buruh di Hindia Belanda (Indonesia). Bahkan begitu besarnya pengaruh Sarekat Islam, sehingga, pada awal mulanya, gerakan kiri pun menumpang dalam bahtera Sarekat Islam (SI) dalam perjalanan mereka bersama buruh.
Pengaruh Sarekat Islam begitu besar dalam hal sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat turut sertanya ratusan ribu petani dan buruh di Jawa yang mendukung mereka, hanya dalam beberapa tahun setelah berdirinya SI.
Pembelaan SI pada nasib buruh tidak terbatas di tanah Jawa, di mana banyak terdapat serikat buruh. Tetapi juga di Sumatera, dimana buruh (Kuli Kontrak) perkebunan di Deli, menerima perlakuan buruk dan cenderung tidak manusiawi. Melalui tokoh SI Jawa Barat, Goenawan, yang melakukan perjalanan ke Sumatera, ia menulis tentang nasib buruk kuli kontrak di Deli.
Majalah Pantjaran Warta yang dipimpin seorang tokoh SI, Abdul Muis, menamakan sistem kuli kontrak di Deli sebagai ‘Perbudakan Industrial.’
Pada awal tahun 1914, Kaoem Moeda menuliskan serangkaian kecaman tentang keadaan kerja di Deli; terutama soal kemerosotan moral. Hal ini mereka anggap sebagai akibat dari politik pengusaha perkebunan yang mendorong perjudian dan menolak dilakukannya perkawinan yang sah di perkebunan. Kecaman juga dilontarkan sehubungan denga rendahnya upah serta pegawai perkebunan yang ringan tangan memberi pukulan. (Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?, .P.E Korver, Grafitipers (Jakarta).
Begitu rendahnya upah mereka, sehingga Buya Hamka menyindirnya dengan; “…pukul lima diterimanya uang, pukul tujuh musnah semuanya. “ [Merantau Ke Deli, HAMKA, Bulan Bintang, 1977 (Jakarta)]
Kongres SI di Bandung, tahun 1916 juga membahas nasib buruh di Deli. Mereka menyoroti soal kerja kontrak dan mengecam calo-calo yang bermain dalam merekrut kuli kontrak tersebut. Calo-calo itu, yang dalam prakteknya sering memberikan janji palsu dan banyak dibela oleh polisi. Buya Hamka dalam roman Merantau Ke Deli, menyingkap adanya praktek penipuan para calo ini;
“Kuli-kuli itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, ada yang bersuami isteri dan ada yang datangnya tidak beristeri, tidak bersuami, datang oleh karena ditipu oleh tengkulak-tengkulak pencari kuli, yang dinamai wervers. Mereka ditipu, dikatakan bahwa pekerjaan di tanah Deli itu amat senang, berteduh tidak kena panas, memang tidak kena panas di dalam rimba karet. Lampunya tidak lampu minyak tanah, melainkan listrik; memang listrik lampu di pondok panjang itu.”
Melihat kenyataan tersebut, SI dalam kongresnya di Bandung memutuskan untuk memohon kepada pemerintah agar mengizinkan wakil-wakil SI untuk meneliti terlaksananya kontrak tersebut secara sukarela dan melarang dikurungnya kuli kontrak ini dalam gudang penerimaan tenaga kerja, sehingga tidak bisa berhubungan dengan dunia luar.