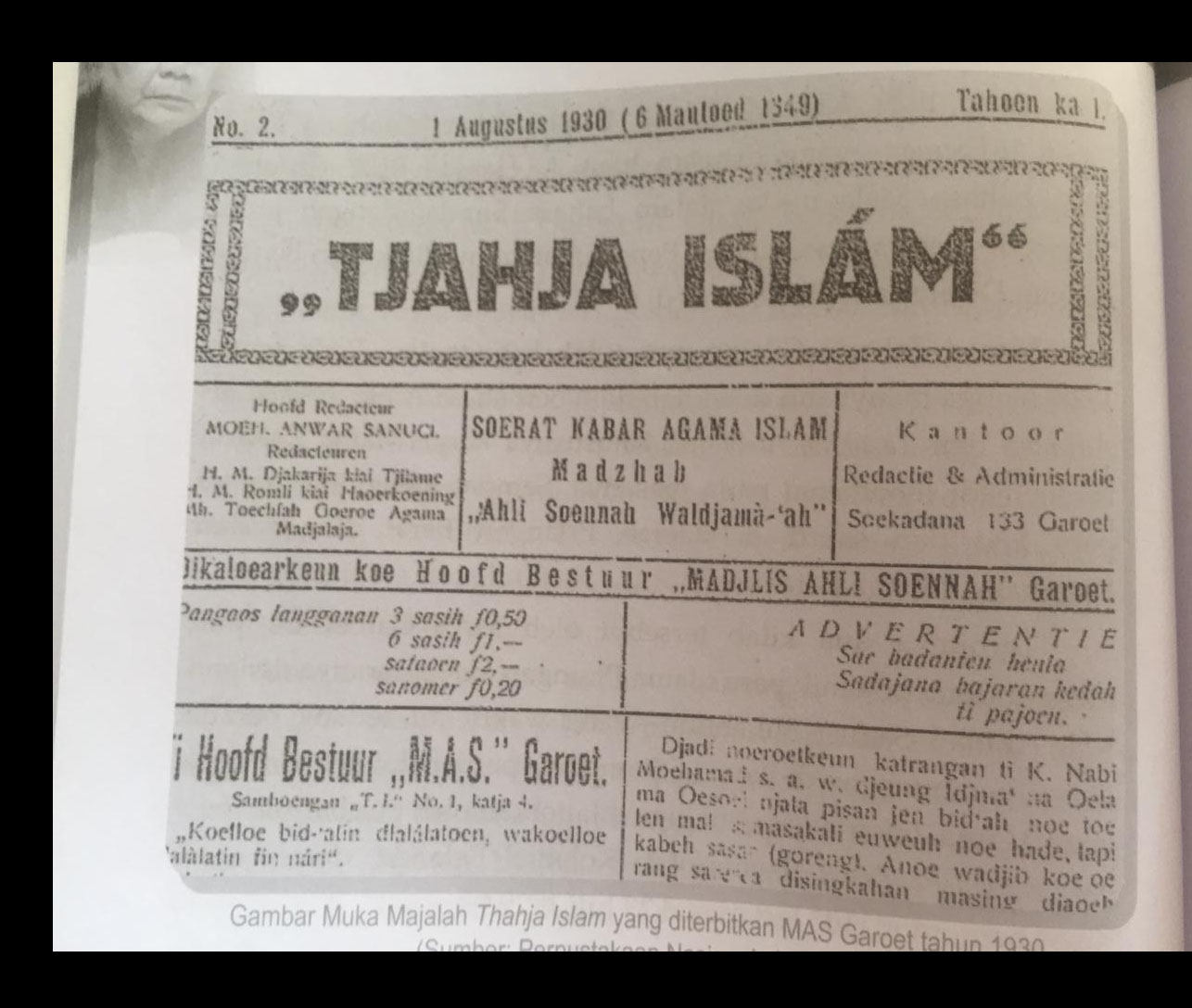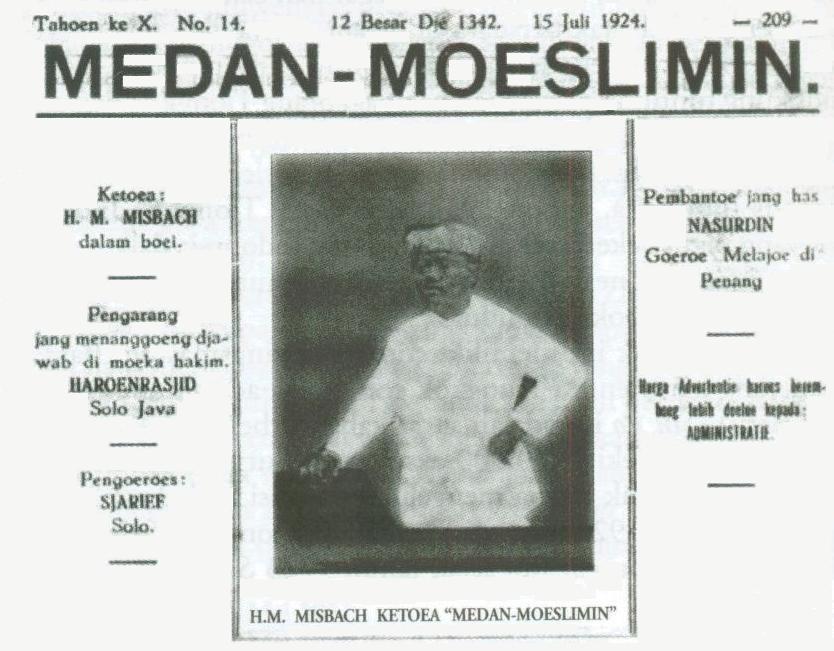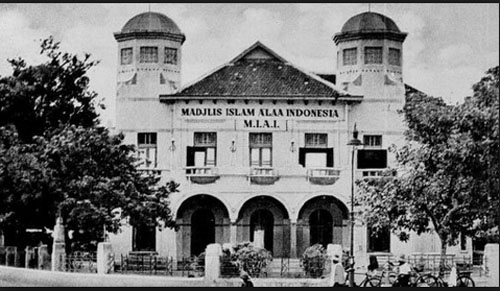Oleh: Alwi Alatas
BEBERAPA tahun lalu saat Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, atau yang biasa dipanggil Pak Lah, beliau meluncurkan satu program bernama Islam Hadhari, atau Civilizational Islam (Islam yang bertamadun). Mungkin ada orang yang tersenyum saat memperhatikan satu kebetulan yang menggelitik betapa Islam Hadhari atau Islam yang berperadaban justru dipromosikan oleh seorang yang bernama Badawi.
Dalam bahasa Arab, badawī bermakna badui, pedesaan, dan nomadic (Wehr, 1966: 47). Orangnya disebut badui, yang perilaku dan cara-cara hidupnya berbeda dengan masyarakat kota dan secara umum dianggap berseberangan dengan apa-apa yang terkandung dalam istilah peradaban. Ibn Mandzur (1966: 235) dalam Lisan al-‘Arab mendefinisikan kata ini sebagai khilaf al-hadhar atau sesuatu yang berlawanan dengan kehidupan kota atau urban. Secara bahasa, kata ini juga berkaitan dengan gurun. Kata bādiyah dan badāwah masing-masing bermakna padang pasir dan kehidupan gurun.
Ibn Khaldun (2005: 92-93) menganggap bahwa pola hidup badui merupakan tahap yang lebih awal daripada kehidupan yang menetap. Mereka merupakan bentuk awal peradaban. Kehidupannya cenderung berpindah-pindah, sederhana secara ekonomi dan biasanya hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi pada umumnya mendamba kehidupan urban dan perekonomiannya yang melampaui tingkat subsisten. Badawī merupakan basis atau awal dari hadharī, dan sebaliknya hadharī merupakan tujuan serta tahap berikutnya dari kehidupan badāwah, begitu kurang lebih yang digambarkan oleh Ibn Khaldun di dalam Muqaddimah-nya. Walaupun kehidupan kaum badui biasanya dipertentangkan dengan budaya urban, tetapi pada era Ibn Khaldun, cara hidup masyarakat sudah sangat kompleks, begitu pula dengan masyarakat baduinya. Sebagian mereka ada yang hidup dalam komunitas kesukuan yang agak besar dan tinggal di kota yang berpenduduk cukup banyak, tetapi statusnya tetap di bawah kota-kota yang lebih maju dan beradab.
Di era Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga dikenal adanya kaum badui, tetapi keadaan mereka masih jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun, sebagaimana kehidupan kotanya juga masih relatif lebih sederhana. Orang-orang badui pada masa ini betul-betul tinggal di padang pasir yang sangat berbeda dengan kehidupan urban. Mereka sesekali datang ke kota, untuk berniaga atau keperluan lainnya, tetapi karakteristik mereka sangat berlainan dengan penduduk kota. Perbedaan karakteristik ini tidak hanya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, tetapi lebih luas daripada itu juga berkaitan dengan ilmu, adab, dan tata krama.
Dapat dikatakan masyarakat badui merupakan orang-orang Arab yang tinggal di gurun secara terpencar dan hidup terpisah dari kabilah-kabilah besar.
Menurut Philip K. Hitti (2002: 23-27), “individualisme … begitu kuat mendarah daging sehingga si Badui tidak pernah mampu mengangkat dirinya ke satu wujud sosial yang bermartabat pada tipe internasional”. Namun ini bukan berarti mereka terputus atau terpisah dari kabilah manapun, hanya saja mereka tidak terlalu suka tunduk kepada otoritas kekabilahan atau hidup dalam kedisiplinan dan aturan sosial yang mengekang kebebasan. Perlu juga diingat bahwa keberadaan Arab badui dan Arab kota bukan sesuatu yang secara mutlak terpisah. Ada hubungan dan proses di antara keduanya. Meminjam kata-kata Hitti, “there are stages of semi-nomadism and quasi-urbanity”.
Dalam konteks inilah kita dapat memahami lebih baik beberapa riwayat yang mengaitkan kehidupan badui dan karakteristiknya dengan kabilah-kabilah tertentu.
Abu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Dari arah sini, fitnah akan datang dari arah Timur. Kekasaran (al-jaf’u) dan kerasnya hati (ghildzu al-qulūb) merupakan karakteristik orang-orang badui (ahl al-wabar) yang sibuk dengan kumpulan unta dan sapi (dan tidak menaruh perhatian pada agama), dari kalangan Rabi’ah dan Mudhar.” (HR Bukhari).
Orang-orang Badui pada hadits itu memang tidak disebut dengan kata badawī atau a’rab, tetapi ahl al-wabar dalam bahasa Arab juga kurang lebih mengacu pada entitas yang sama, yang hidupnya cenderung nomadik dan berseberangan secara makna dengan ahl al-madar, yaitu kaum yang hidup menetap (lihat Wehr, 1966: 33 & 1045). Bani Fazarah juga misalnya masuk pada kategori badui yang pada masa pra-Islam memiliki keharusan untuk mengikuti aturan-aturan Quraisy saat berhaji dan orang-orang Quraisy berhak mengambil dari hewan sembelihan mereka (Kister, 1986: 33-34).
Orang-orang arab badui pada masa Nabi lebih sering disebut di dalam al-Qur’an dan hadits dengan sebutan A’rab. Namun gambaran tentang mereka secara umum kurang positif, tidak dalam arti mendiskreditkan, tetapi lebih kepada realitas yang melekat pada diri mereka. Riwayat-riwayat hadits dan sejarah lebih sering menyebutkan tentang mereka secara anonim, tanpa nama. Ciri-ciri mereka diketahui, tetapi nama dan ketokohan mereka tidak dikenali. Tabiat mereka cenderung kasar dan kurang memiliki adab, tetapi Nabi berinteraksi dengan mereka secara sabar dan menjaga sikap.
Pernah sekumpulan Arab badui datang pada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan tanpa keraguan membanggakan iman. Namun al-Qur’an meluruskan, “Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah Islam’ …” (QS 49: 14). Ini karena iman belum betul-betul masuk ke dalam hati mereka. Pada ayat yang lain al-Qur’an menyifatkan mereka sebagai “lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya” (asyaddu kufran wa nifāqan), “memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian”, dan “menanti-nanti marabahaya menimpamu (Nabi)” (QS 9: 97-98). Mereka itu, tulis Ibn Jarīr al-Thabarī (1374H: 429) saat menafsirkan ayat ke-97 di atas, “paling keras hatinya (aqsā qulūban) dan paling sedikit ilmunya (aqallu ‘ilman) terhadap hak-hak Allah.” Dan mereka tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang baik (ahl al-khayr). Tetapi al-Qur’an juga menyatakan bahwa di antara orang-orang badui itu “ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk mendapatkan doa Rasul” dan kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (Surga)-Nya (QS 9: 99).
Pada masa Perang Khandaq, orang-orang munafik Madinah digambarkan oleh al-Qur’an (33: 20) sebagai berkeinginan untuk pergi ke gurun dan tinggal untuk sementara waktu bersama orang-orang Arab badui sambil memastikan pasukan Ahdzab yang sebelumnya mengepung Madinah benar-benar sudah pergi meninggalkan kota itu. Rupanya kampung-kampung badui adalah tempat yang dianggap aman bagi mereka untuk menutupi nifak yang ada di dalam dada. Dan memang tak lama setelah wafat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, telah terjadi peristiwa riddah di mana masyarakat di luar Makkah dan Madinah banyak yang berbalik keluar dari Islam dan menolak untuk membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar al-Shiddiq radhiallahu ‘anhu. Banyak di antara yang berbalik keluar dari Islam ini adalah dari kalangan orang-orang Arab badui. Namun, Abu Bakar mampu mengatasi keadaan dan dapat mempertahankan cahaya Islam di Jazirah Arab dari ancaman riddah (Haekal, 2003: 97).
Karena itu pula orang kota yang memilih pindah dan menetap di gurun kadang dicurigai ada masalah dengan imannya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Salamah bin al-Akwa’ radhiallahu ‘anhuma memutuskan untuk menetap di satu tempat di gurun yang bernama al-Rabadzah. Ia menikah dan punya anak di tempat itu, dan baru kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kematiannya. Ketika ia bertemu Hajjaj, yang terakhir ini berkata kepadanya, “Wahai Ibn al-Akwa’, engkau telah murtad dengan menetap di gurun bersama orang-orang badui.” Ibn al-Akwa’ menjawab, “Tidak, melainkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberi ijin kepadaku untuk menetap di tengah orang-orang badui.” (HR Bukhari, Muslim). Hajjaj mungkin mencari-cari jalan untuk menuduh Ibn al-Akwa’, tetapi alasan yang digunakannya bukan sama sekali tak berdasar. Jawaban Ibn al-Akwa’ juga mengisyaratkan bahwa kehidupan badāwah merupakan satu kemunduran dan bukan sesuatu yang baik jika dilakukan tanpa ijin dari Nabi.* (BERSAMBUNG)
Penulis buku-buku sejarah pahlawan Islam