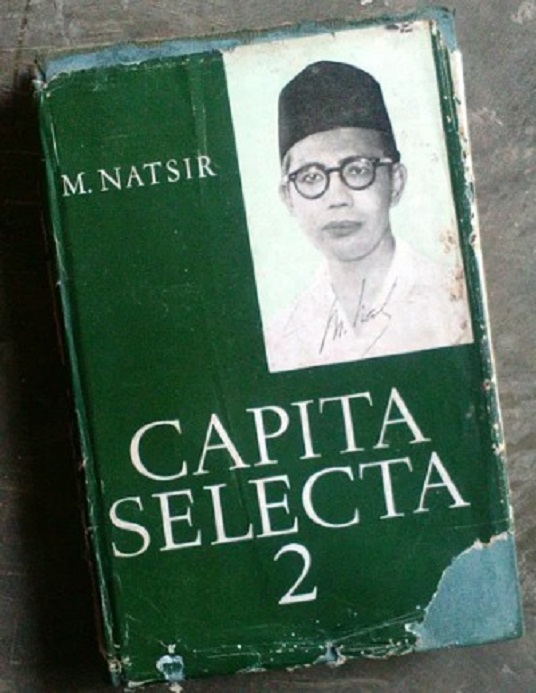Oleh: Muhammad Cheng Ho
TAK sedikit kaum hawa Indonesia yang bercerai dengan masa lalunya. Melompat dari ruang hampa ke masa kini. Jadi merasa asing sendiri, minder, kikuk, linglung, dan merogoh-rogoh identitas semu. Mengekorlah mereka dengan feminisme, misalnya. Dan jadilah mereka seorang yang –dalam bahasa Hamid Fahmy Zarkasyi– feminus alias kurang iman.
Andai mereka bersedia rujuk dengan sejarah, mereka akan menemukan identitas yang jelas dari para pendahulunya. Kaum muslimah yang berpijak, beranjak, dan berjejak membela agama dan negaranya.
Kala itu, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang, kuku-kuku tajam penjajah rupanya masih mencengkeram. Semangat kemerdekaan yang meluap-luap dalam diri rakyat, menggolakkan pertempuran di berbagai tempat. Salah satu Ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) bahkan sampai mengeluarkan resolusi jihad, “bahwa mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum Islam termasuk sebagai suatu kewadjiban mutlaq bagi tiap2 orang Islam laki2 dan perempuan.” Perlawanan rakyat 10 November 1945 pun akhirnya meletus di Surabaya. Kaum Nahdiyyin dan Nahdiyyat ikut mempertahankan kemerdekaan dengan segala apa yang ada. NU bergabung dalam pasukan-pasukan pejuang Hizbullah dan Sabilillah memanggul senjata melawan musuh (Aisjah Dachlan, 1955: 45).
Semangat perjuangan fi sabilillah (di jalan Allah) yang dihidupkan para ulama menerjunkan anak-anak muda dan kaum ibu NU ke gelanggang perjuangan. Jika kaum laki-laki berjuang di garis depan, maka kaum ibu berjuang di garis belakang. Kaum ibu bekerja di di berbagai lapisan seperti dapur umum, palang merah, mengumpulkan pakaian dan makanan, memberi penerangan ke sana sini, serta menghidupkan semangat perjuangan melawan musuh (Aisjah Dachlan, 1955:47).
Sebagaimana organisasi-organisasi perjuangan yang diikuti perempuan Indonesia, sebut saja GPII Putri, Muslimaat Masjumi, BPRI, dan Pesindo, maka NU pun mengorganisir perempuan-perempuannya. Kaum perempuan disusun NU agar menjadi barisan imaadul bilaad karena perempuan itu laksana tiang negeri. Apabila dia baik, negerinya baik. Dan apabila dia rusak, negerinya pun rusak binasa (Moeslimat Soekaradja, 1940:14). Perempuan-perempuan ahlussunnah wal jamaah digerakkan NU menurut ajaran Islam agar turut menyerahkan darma baktinya membela tanah air, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam, “Perempuan memikul kewajiban-kewajibannya seperti kewajibannya laki-laki.” dan “Laki-laki mendapat bagian dari usahanya, perempuan pun mendapat bagian dari hasil kerjanya.” Oleh karena itu, meski negara dalam keadaan diserang, maka Muslimaat NU pun diwajibkan berjuang mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan kodrat dan iradat sebagai perempuan (Aisjah Dachlan, 1955:46).
Setelah kaum ibu Muslimaat NU turut menyingsingkan lengan baju mempertahankan kemerdekaan, tiba masanya mereka menjalani peran dalam organisasi. Maka pada Kongres NU ke XVI di kota Purwokerto, tanggal 23-26 Rabiul Akhir 1365, bertepatan dengan tanggal 26-29 Maret 1946, rencana menjadikan Muslimaat bagian dari NU dimajukan dalam Kongres. Kongres itu secara aklamasi (suara bulat) memutuskan Muslimaat termasuk bagian dari NU dan diresmikan dalam rapat pleno terakhir, 26 Rabiul Akhir 1365/ 9 Maret 1946, dengan singkatan nama NUM (Nahdlatul Ulama Muslimaat) (Aisjah Dachlan, 1955:47).
Ketua NUM Nj. Chadidjah saat itu kemudian menjelaskan dasar perjuangan mereka,
“…. sebenarnya kita perempuan Islam terutama zaman pembangunan sebagaimana sekarang ini tidak boleh tinggal diam, dan tidak boleh menonton para kaum laki-laki yang sedang berjuang untuk meluhurkan agama Allah. Tetapi juga kaum perempuan harus membantu dan memperkuat barisan NU. Karena apa NU harus dibantu? Ya karena memang lapangan pekerjaan itu luas sekali dan berat…
Ketahuilah bahwa setengah dari kekawatiran yang besar ialah orang yang menjauhkan diri dari mengumpuli ‘Ulama, tentu jauh pula ia dari pada agama, sebagaimana orang-orang yang tinggal di desa-desa yang tiada orang ‘Alimnya yang mereka tidak tahu pada orang ‘Alim, pun begitu sebaliknya dan sebagai pula penggembala lembu atau para pekerja-pekerja yang hanya mengetahui pekerjaannya saja serta tidak mau pada lainnya, atau dalam golongan mereka itu terdapat orang ‘Alimnya, tetapi mereka tidak mau mencampurinya, atau mereka tidak mau tunduk padanya dan tidak mau memetik ilmunya.
Sesungguhnya mereka itu dalam umumnya tidak mengetahui Tuhan. Tidak pula Rasul dan tidak pula Agama…maka kewajiban yang dihadapi NU itu besar sekali, minta tenaga yang cukup banyaknya guna beramar ma’ruf dan nahi munkar, dan menuntun ummat Islam yang demikian sifatnya itu… Kalau menilik ummat Islam Indonesia ini begitu besar jumlahnya yang tidak mengerti urusan agamanya, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan kaum perempuan lebih banyak yang kurang perhatiannya pada agama, maka tepat benar Nahdlatul ‘Ulama membentuk bagian perempuan. Al-Mukminuuna wal mukminatu ba’dluhum auliyau ba’di ta’muruna bil ma’rufi wa tanhauna ‘anilmunkar al ayat.” (Tim Penyusun Muslimat NU, 1979: 57-58).
Lahirnya NUM tidak bisa dipisahkan dari KH. Wahab Hasbullah dan KH.M Dahlan. Ibarat bayi yang baru lahir, maka mereka berdualah yang menjadi dokter dan bidan NUM. Mereka mengerti dan terus mengamati kapan bayi itu akan lahir. Maka saat tiba waktunya, mereka mendorong, memimpin, dan membimbing dengan tidak menghiraukan rintangan dari kanan dan kiri. Kini bayi NUM telah lahir sehat dan segar bugar. Sebagai dokter dan bidan, mereka tidak tega meninggalkan bayi NUM yang baru lahir itu sendirian. Maka diasuhlah NUM, diberi petunjuk, dipimpin, dan dibimbing, diluruskan jalannya, ditolong kalau mau jatuh, dibesarkan hatinya, dikobarkan semangatnya, sehingga NUM dapat berjalan sedikit demi sedikit (Tim Penyusun Muslimat NU, 1979:46). Dalam kiprahnya untuk negeri tak sedikit yang telah mereka curahkan. Dari politik sampai pendidikan.* (BERSAMBUNG)
Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)