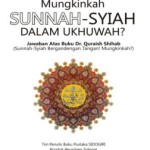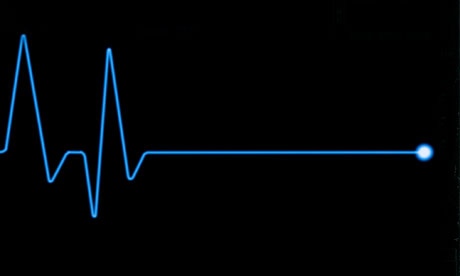Oleh: Shalih Hasyim
SETIAP Muslim harus bersatu dalam kebenaran, berkumpul dalam petunjuk para ulama yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi Shallallahu’alaihi Wassalam tanpa dibatasi oleh sikap fanatik golongan, tidak terbatas oleh keanggotaan ormas, partai atau jama’ah dakwah. Itulah al jamaah.
Islam mewajiban kaum Muslim untuk bersatu sebagai satu umat. Allah SWT berfirman, ”Sesungguhnya umat kalian adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah Aku.”(QS al-Anbiya’ [21]: 92).
Islam melalui A-Quran menetapkan umatnya agar bersatu dalam satu kesatuan umat di bawah naungan satu kepemimpinan. Rasulullah mengatakan, “Berpegang teguhlah pada jamaah kaum Muslim dan imam mereka).” (HR Ibn Majjah).
Hanya saja, kepemimpinan imamah jamaah tidak akan lengkap sebelum membahas produk ketetapan yang dihasilkan oleh Syuro, musyawarah dan istisyarah, sebuah kesepakatan kaum Muslimin.
Pengalaman empiris mengajarkan, setiap keputusan yang ambil mengandung selalu resiko. Tapi, kita meyakini sesungguhnya hasil syura menggambarkan akal kolektif sebuah jamaah.
Masih muncul sisa pertanyaan, apakah yang seharusnya kita lakukan jika kesepakatan syura tidak kita setujui? Kenyataan seperti ini akan kita temukan dalam dinamika (pasang surut) pergerakan kaum Muslim. Dan fenomena (gejala) tersebut hal yang lumrah saja. Karena, implikasai dari fakta yang lebih besar, yaitu adanya perbedaan pendapat yang merupakan cirikhas masyarakat yang mejemuk (heterogen).
Kalangan gerakan Islam hadir dengan latar belakang (kholfiyyah) sosial dan keluarga yang berbeda, level (marhalah) pengetahuan yang berbeda, sekalipun proses tarbawi dan pengkaderan kita berusaha menyamakan cara berpikir kita sebagai aktifis dengan menjadikan manhaj nubuwwah sebagai landasan gerak (muntholaq), namun dinamika personal, keluarga, organisasi dan lingkungan sosial tetap saja akan menyisakan celah bagi semua kemungkinan perbedaan.
Dari sinilah kita harus memperoleh pelajaran “keikhlasan” baru. Tunduk dan patuh kepada sesuatu yang barangkali tidak kita setujui dalam berjamaah. Dan taat dalam keadaan terpaksa bukanlah pekerjaan sederhana dan mudah. Itulah ujian bersikap jiwa besar yang paling berat dalam keseluruhan pengalaman spiritual sebagai aktifis harakah Islam.
Tapi kita meyakini berjiwa besar merupakan pelajaran gratis dari Allah Subhanahu Wata’ala agar karakter kita lebih matang dalam sebuah kepemimpinan.
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ
“Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As Sajdah (32) : 24).
Banyak yang berguguran di jalan perjuangan, disebabkan oleh salah satunya karena mereka gagal dalam mengelola dan menikmati ketidaksetujuannya terhadap hasil syuro. Tidak trampil dalam mengelola sebuah perbedaan. Padahal kualitas kematangan tarbawi kita di antaranya ditentukan oleh kemampuan kita dalam memenej kontradiksi (menejemen konflik), menuju produktifitas amal shalih.
Apa yang sepatutnya kita lakukan dalam menghadapai kenyataan di atas?
Pertama, marilah kita bertanya kembali kepada diri kita, apakah pendapat kita terbentuk melalui suatu upaya ilmiah seperti kajian, perenungan, pengalaman lapangan yang mendalam sehingga kita punya landasan yang kuat untuk mempertahankannya? Kita harus membedakan secara ketat antara pendapat yang lahir dari proses ilmiah yang sistematis dengan pendapat yang sebenarnya sekedar lintasan pikiran yang muncul dalam benak kita ketika rapat berlangsung.
Seandainya pendapat kita hanya sekedar lintasan pikiran, sebaiknya hindari untuk berpendapat atau hanya sekedar berbicara dalam syura. Itu adalah kebiasaan yang buruk. Ngotot atas dasar lintasan pikiran adalah kebiasaan yang jauh lebih buruk. Alangkah menyedihkannya menyaksikan para aktifis Islam yang ngotot mempertahankan pendapatnya tanpa landasan ilmiah yang kokoh.
Tapi, seandainya pendapat kita terbangun melalui proses ilmiah yang intensif dan sistematis, mari kita belajar tawadhu. Karena kaidah yang diwariskan oleh para ulama mazhab kita mengatakan, Pendapat kita benar, tapi mungkin salah. Dan pendapat mereka mungkin salah, tapi mungkin benar.
Kedua, marilah kita bertanya secara jujur pada diri kita sendiri, apakah pendapat yang kita bela itu merupakan kebenaran obyektif atau sebenarnya ada obsesi jiwa tertentu di dalam diri kita yang kita sadari atau tidak kita sadari, mendorong kita untuk ngotot?
Misalnya, ketika kita merasakan perbedaan pendapat sebagai suatu persaingan. Sehingga ketika pendapat kita ditolak kita merasakannya sebagai kekalahan. Jadi yang kita bela adalah obsesi jiwa kita, bukan kebenaran obyektif, sekalipun karena faktor setan kita mengatakannya demikian.
Bila yang kita bela adalah obsesi jiwa, kita harus segera berhenti memenangkan gengsi dan syahwat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Sebab itu adalah jebakan setan yang boleh jadi menggiring kita kepada pembangkangan dan kemaksiatan. Tapi, seandainya yang kita bela adalah kebenaran obyektif dan yakin kita terbebas dari segala bentuk obsesi jiwa semacam itu, kita harus yakin syuro pun membela hal yang sama. Sebab berlaku sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam, “Umatku tidak akan pernah bersepakat atas suatu kesesatan.” Dengan begitu kita menjadi lega dan tidak perlu ngotot mempertahankan pendapat pribadi kita.
Ketiga, seandainya kita tetap percaya bahwa pendapat kita lebih benar dan pendapat umum yang kemudian menjadi ketetapan syura lebih lemah atau bahkan pilihan yang salah, hendaklah kita percaya mempartahankan kesatuan dan keutuhan shaf (barisan) jamaah dakwah jauh lebih utama dan lebih penting daripada sekedar memenangkan sebuah pendapat yang boleh jadi memang lebih mendekati kebenaran. Karena berkah dan pertolongan hanya turun kepada jamaah yang bersatu padu, utuh dan solid.
“Aku (Allah) nomer tiga dari kedua orang yan g bersepakat dalam kebaikan, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Kesatuan dan keutuhan barisan jamaah bahkan jauh lebih penting dari kemenangan yang kita raih dalam peperangan. Jadi, seandainya kita kalah perang tapi tetap bersatu, itu jauh lebih baik daripada kita menang tapi kemudian bercerai-berai. Persaudaraan adalah karunia Allah swt yang tidak tertandingi setelah beriman kepada-Nya.
Seandainya kemudian pilihan syura itu terbukti salah, dengan kesatuan, keutuhan dan kesolidan barisanb dakwah, Allah dengan mudah akan meminimalisir dampak negative dari kesalahan itu, Baik dengan mengurangi tingkat resikonya atau menciptakan kesadaran kolektif yang baru (pencerahan) yang mungkin tidak akan pernah tercapai tanpa pengalaman salah seperti itu. Bisa pula mengubah jalan peristiwa kehidupan sehingga muncul situasi baru yang memungkinkan pilihan syura itu ditinggalkan dengan cara yang logis, tepat waktu, dan tanpa resiko. Itulah hikmah Allah SWT. Sehingga merupakan satu dari sekian banyak rahasia ilmu-Nya. Dengan begitu, hati kita menjadi lapang menerima pilihan syura karena hikmah tertentu yang mungkin hanya akan muncul setelah berlalunya waktu. Dan alangkah tepatnya sang waktu mengajarkan kita panorama hikmah ilahi di sepanjang pengalaman dakwah kita.
Keempat, sesungguhnya dalam ketidaksetujuan itu kita belajar tentang demikian banyak makna imaniyah, makna keikhlasan yang tidak terbatas, tentang makna tajarrud (steril) dari semua hawa nafsu, tentang makna ukhuwwah dan persatuan, tentang sikap tawadhu, tentang cara menempatkan diri yang tepat dalam kehidupan berjamaah, tentang cara memandang diri kita dan orang lain secara tepat, tentang makna tradisi ilmiah yang kokoh, dan kelapangan dada yang tidak terbatas, tentang makna keterbatasan ilmu di hadapan ilmu Allah SWT yang tidak terbatas, tentang makna tsiqah (percaya) kepada jamaah.
Jangan pernah merasa lebih besar dari jamaah atau merasa lebih cerdas dari akal kolektif. Tapi, kita harus memperkuat tradisi ilmiah kita. Memperkokoh kultur perenungan dan pemikiran yang mendalam, Dan pada waktu yang sama memperkuat daya tamping hati kita terhadap beban perbedaan. Memperluas kelapangan dada dan kerendahan hati terhadap begitu banyak ilmu dan rahasia serta hikmah Allah SWT yang mungkin belum tampak di depan kita atau tersembunyi di hari-hari yang akan datang.
Perbedaan adalah sumber kekayaan dalam kehidupan berjamaah. Mereka yang tidak mampu mengelola dan menikmati perbedaan itu dengan cara yang benar akan kehilangan banyak sumber kekayaan. Dalam ketidaksetujuan itu sebuah rahasia akan tampak ke permukaan “Apakah kita benar-benar matang secara pengkaderan atau tidak?”*
Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Kudus, Jawa Tengah