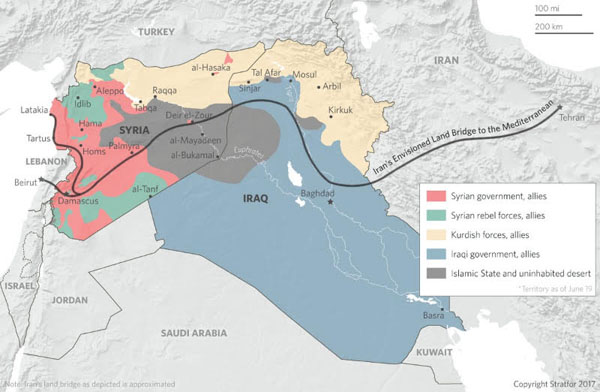Oleh: Vidya Subrahmaniam
Hidayatullah.com | PADA 24 Februari, gerombolan nasionalis Hindu menyerbu bagian timur laut ibukota India, New Delhi, dan menimbulkan kekacauan selama empat hari. Mereka menyerang toko dan rumah milik Muslim.
Lebih dari 50 orang terbunuh dan ratusan lainnya terluka dalam kekerasan.
Setelah serangan tersebut, saya mengunjungi pemukiman yang termasuk paling parah terdampak, Shiv Vihar, dan menyaksikan kehancuran. Sementara toko dan tempat tinggal orang Hindu sebagian besar tampak masih utuh, sebagian besar rumah dan bisnis Muslim hancur tak tersisa.
Bekas benda milik keluarga-keluarga Muslim – lemari es, televisi dan mobil – berserakan di sepanjang jalur-jalur sempit pemukiman itu.
Sementara satu masjid lokal hangus hingga rata dengan tanah, masjid lain bernama Auliya dari luar tampak tidak ada kerusakan. Namun di dalam, saya menemukan bahwa itu, juga, hangus terbakar, berantakan.
Para penduduk Hindu tampaknya melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa, tetapi Muslim tidak terlihat di manapun – mereka telah pergi, mencari keselamatan di kamp-kamp bantuan yang didirikan oleh pemerintah.
Kerusuhan yang menyebabkan Shiv Vihar menjadi puing-puing dipicu setelah aksi demonstrasi duduk berminggu-minggu terhadap Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), yang menurut kritik mendiskriminasi umat Islam, yang diserang oleh para nasionalis Hindu.
Protes anti-CAA di Delhi sejak awal berlangsung damai. Orang-orang berkumpul untuk menyanyikan lagu patriotik, mengibarkan bendera India, membaca konstitusi India dan mendengarkan pidato tentang kebebasan, sekularisme dan solidaritas.
Para demonstran – kebanyakan dari mereka perempuan – tidak menunjukkan apa-apa selain kesetiaan kepada negara mereka, namun ini tidak menghentikan partai penguasa Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk menggambarkan mereka sebagai “pengkhianat” dan membuat mereka target utama untuk serangan main hakim sendiri.
Menjelang pemilihan dewan Delhi 7 Februari, contohnya, BJP menjalankan kampanye keji menarget Muslim kota itu. Anurag Thakur, menteri keuangan junior, menghasut kerumunan orang yang menghadiri kampanye pemilunya untuk “menembak para pengkhianat”.
Menteri lain, Parvesh Verma, bersumpah para demonstran akan “dikirim dalam kemasan” dalam beberapa jam setelah kemenangan BJP, menambahkan bahwa jika dibiarkan, mereka akan “memperkosa dan membunuh”.
Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah, sementara itu, menyiratkan bahwa para demonstran anti-India dan pro-Pakistan.
Modi menyebut demonstrasi yang sedang berlangsung sebuah “konspirasi” yang dirancang untuk melemahkan “harmoni India”. Shah mengklaim para demonstran telah mengangkat slogan-slogan seperti “Jinnah wali azaadi (Kami ingin kemerdekaan bergaya Jinnah)”, mengesankan mereka ingin kehancuran India.
Ketika hal yang tidak terhindarkan terjadi dan para demonstran diserang, kekerasan dengan cepat menyebar ke seluruh Delhi. Pihak berwenang tidak berbuat banyak untuk meredakan ketegangan, sementara polisi menghadapi tuduhan karena bersikap acuh.
Banyak pengamat membandingkan serangan di Delhi dengan episode kekerasan komunal sebelumnya. Memang, sejarah pasca kemerdekaan India penuh dengan insiden semacam itu.
Episode terbaru ini bukanlah yang terbesar ataupun yang paling ganas dalam sejarah India baru-baru ini. Namun, bagi para pengamat India yang cermat, apa yang terjadi bulan lalu berada di kategori yang berbeda.
Untuk memahami apa yang membuat serangan-serangan ini unik dan karenanya lebih menakutkan, mari kita ingat kembali dua episode kekerasan interkomunal di sejarah India baru-baru ini: pembantaian Sikh di Delhi 1984 dan pogrom yang menarget Muslim di Gujarat pada 2002.
Akar kekerasan anti-Sikh 1984 dapat ditelusuri kembali hingga pemberontakan separatis bersenjata yang terbentuk di negara bagian Punjab pada pertengahan 1970an. Ketika gerakan itu tumbuh dalam kekuasaan, para pejuangnya mulai melakukan serangan kekerasan di Delhi dan kota utara lainnya.
Pada tahun 1983, pemimpin gerakan itu, Jarnail Singh Bhindranwale, dan beberapa pengikutnya yang paling terkemuka berlindung di Kuil Emas, kuil suci paling suci di Sikh yang terletak di Amritsar di Punjab, untuk menghindari penangkapan.
Pada Juni 1984, Perdana Menteri saat itu Indira Gandhi memerintahkan militer India untuk menyingkirkan para pejuang Sikh dari kuil. Lebih dari 500 orang tewas dalam operasi itu, termasuk banyak warga sipil Sikh.
Kemudian pada 31 Oktober, 1984, dua penjaga Sikh membunuh Gandhi di rumahnya di New Delhi sebagai pembalasan. Pembunuhannya memicu kemarahan: pada hari ketiga penjagalan tanpa henti, 2.800 Sikh dibunuh.
Pogram Gujarat 2002 mengikuti skenario yang sama.
Pada 27 Februari, 2002, kebakaran di kereta yang mengangkut jamaah Hindu menewaskan 59 orang di Godhra, Gujarat.
Para penumpangnya merupakan jamaah Hindu, yang kembali dari Ayodhya setelah upacara keagamaan di lokasi Masjid Babri. Masjid yang 10 tahun sebelumnya dihancurkan oleh gerombolan Hindu yang mengklaim bahwa masjid itu dibangun di atas reruntuhan sebuah kuil yang didedikasikan untuk Ram, dewa utama agama Hindu.
Salah satu penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa api di kereta itu tidak disengaja, disebabkan oleh seseorang yang memasak atau merokok di dalam gerbong, namun laporan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung disebut “tidak valid”.
Pihak berwenang India pada akhirnya menyimpulkan bahwa kereta itu dibakar oleh Muslim. Insiden kebakaran tersebut menyebabkan ledakan kemarahan masyarakat Hindu dan mengarah pada pembunuhan lebih dari 1.000 orang, kebanyakan dari mereka Muslim.
Pembataian Sikh 1984 dan pogrom 2002 terhada Muslim di Gujarat memiliki banyak kesamaan.
Di kedua kasus, polisi dituduh meninggalkan tugas pengawasan mereka, baik dengan bersikap pasif atau, dalam beberapa kasus, membantu dan bersekongkol dalam pembantaian.
Kedua contoh itu juga ditandai dengan tindakan kekerasan ekstrem yang sebelumnya belum pernah terlihat dalam bentrokan komunal di India.
Pada tahun 1984, pria dan anak laki-laki Sikh dikalungi dengan ban yang kemudian dibakar sehingga kematian mereka sangat pelan dan menyakitkan. Sebaliknya, perempuan Sikh diperkosa berulang kali dan dipaksa menyaksikan suami dan putra mereka mati.
Pada tahun 2002 di Gujarat, banyak pria dan anak lelaki dimutilasi dan dibakar. Ehsan Jafri, seorang mantan anggota Parlemen, contohnya, dimutilasi dan dibakar meskipun dia telah berulangkali meminta bantuan orang-orang yang dia kenal di pemerintahan negara bagian.
Kesamaan penting lainnya antara kedua episode kekerasan mengerikan ini adalah tuduhan keterlibatan pemerintah.
Pada 1984, para pemimpin Kongres lokal di Delhi dituduh membantu dan bersekongkol dengan para perusuh, sementara pemerintah pusat dituduh menutup mata terhadap kekerasan.
Pada tahun 2014, tim pencari fakta gabungan dua organisasi masyarakat sipil terkenal, People’s Union for Democratic Rights dan People’s Union for Civil Liberties, menemukan bahwa serangan terhadap anggota Komunitas Sikh di Delhi dan pinggiran kotanya “adalah hasil dari rencana yang terorganisasi dengan baik yang ditandai dengan tindakan komisi yang disengaja dan kelalaian oleh politisi penting Kongres”.
Empat tahun kemudian, Sajjan Kumar, yang merupakan anggota parlemen terkemuka pada saat kerusuhan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena “menghasut orang banyak untuk membunuh Sikh”.
Di Gujarat, tuduhan serupa diarahkan pada pemerintah negara bagian BJP. Modi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Menteri Gujarat, dituduh gagal menghentikan kekerasan dan secara tidak langsung mendorong beberapa perusuh Hindu.
Selama musyawarah tentang kerusuhan Gujarat, Mahkamah Agung India bahkan menyamakan pemerintahan Modi dengan pemerintahan Nero, kaisar Romawi yang mengutak-atik saat Roma terbakar.
Pada 2012, Modi dibebaskan dari keterlibatan dalam kekerasan oleh Tim Investigasi Khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, tetapi kelompok-kelompok HAM terus menuduhnya diam-diam mendukung para perusuh.
Serangan anti-Muslim bulan lalu di Delhi memiliki semua karakteristik ini.
Namun, ada satu aspek yang membedakan peristiwa bulan lalu dari kasus kekerasan komunal bersejarah.
Baik pembantaian Sikh maupun pogrom Gujarat dimulai sebagai tanggapan atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh anggota masyarakat sasaran. Namun kekerasan anti-Muslim bulan lalu di Delhi, bukanlah “balas dendam” untuk apa pun. Itu tidak didahului dengan pelanggaran besar terhadap mayoritas Hindu.
Komunitas Muslim tidak melakukan apa pun yang bahkan bisa menjamin pembalasan. Satu-satunya hal yang telah mereka lakukan pada minggu-minggu sebelum serangan itu adalah memprotes secara damai terhadap undang-undang kewarganegaraan baru yang diskriminatif.
Dengan demikian, tidak seperti pada tahun 1984 dan 2002, tidak ada alasan nyata untuk kekerasan.
Kali ini, Muslim dihukum, hanya karena menjadi Muslim dan meminta untuk menjadi orang India.
Dan karena ini, serangan bulan lalu menandai awal babak baru yang menakutkan dalam sejarah India. Gerombolan perusuh Hindu, yang diberdayakan oleh pemerintah pusat Hindu-nasionalis, tampaknya tidak lagi membutuhkan alasan untuk menyerang minoritas.
Ini menandakan bahwa bagi komunitas minoritas di India, masa depan sekarang lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya.*