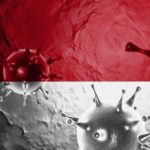“Kami berkeyakinan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan (yang tidak dapat dipisahkan) dengan konstitusi tersebut”
Oleh Muh. Zaitun Rasmin
Hidayatullah.com | KUTIPAN di atas adalah salah satu kalimat penting pada naskah dekrit presiden, yang diumumkan Sukarno pada 5 Juli 1959. Sukarno mengeluarkan dekrit, karena konstitusi yang ideal bagi Indonesia tidak dapat disusun oleh konstituante. Sementara UUD 1945 yang merupakan ‘modifikasi’ dari Piagam Jakarta dianggap sebagai konstitusi yang lebih layak daripada 2 konstritusi lainnya, UUD-RIS 1949 dan UUDS-1950.
Sejarah mencatat, Piagam Jakarta adalah rumusan konstitusi yang disusun oleh 9 tokoh intelektual lintas madzab pemikiran, yang ditunjuk sebagai tim ad hoc BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Penunjukan tersebut diberikan, karena mereka memiliki reputasi intelektualitas yang mumpuni.
Dari 9 orang intelektual anggota tim perumus (sehingga mereka dikenal sebagai Panitia Sembilan), 4 orang di antaranya adalah ulama yang mewakili kaum intelektual santri, yaitu: KH. Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), KH. Abikusno Cokrosuyoso, KH. Agus Salim (SI), serta KH. Wahid Hasyim (NU).
Sementara itu, kaum intelektual abangan diwakili oleh Achmad Subarjo, Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan Sukarno. Seorang tokoh lainnya, yaitu Alexander Andries Maramis, ditunjuk mewakili kaum intelektual minoritas non muslim.
Meskipun sama-sama berlatarbelakang muslim, antara tokoh intelektual santri dan tokoh intelektual abangan sering diperhadapkan pada diskusi yang sengit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tajam tentang pemikiran politik masing-masing. Para tokoh intelektual santri menginginkan agar nilai-nilai agama diintegrasikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Sedangkan bagi tokoh intelektual abangan, politik dan pemerintahan negara ini hendaknya diparsialkan dari nilai-nilai agama. (Firdaus AN, 1993; Anshari, 2005; Woodward, 2011).
Nah, Piagam Jakarta yang dirumuskan sebagai rancangan naskah konstitusi Indonesia merdeka, menjadi simbol konsensus nasional antar para intelektual yang berbeda-beda madzab pemikiran politik tersebut. Selain disetujui Panitia Sembilan sendiri, naskah Piagam Jakarta juga diapresiasi secara positif oleh seluruh anggota BPUPKI.
Berdasarkan catatan sejarah, Piagam Jakarta, memberikan sedikitnya 6 informasi tentang reputasi para ulama sebagai tokoh intelektual sejati, yang dapat diteladani oleh umat.
Pertama, para ulama kita memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kesadaran rakyat untuk meraih, menjaga, serta mengisi kemerdekaan tanah airnya. Ketika tanah airnya dijajah, maka para ulama tergerak untuk berjuang mengusir penjajah agar kemerdekaan tanah airnya dapat kembali terwujud.
Sebagai intelektual sejati, para ulama memahami banyaknya dalil-dalil dalam al-Qur’an maupun al-Hadits yang dijadikan sebagai referensi bagi mereka untuk mengusir penjajah. Penjajahan menimbulkan fitnah (kesengsaraan) bagi kaum yang dijajah, sehingga harus dihapuskan.
Allah swt. berfirman, “Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah….” (QS. al-Baqarah : 193)
Maka tidak mengherankan jika perjuangan mengusir penjajah selalu dipelopori, dimotori, bahkan dipimpin sendiri oleh para ulama. Sebagai intelektual sejati yang berwawasan luas, para ulama memiliki nasionalisme yang tidak sempit. Mereka memandang bangsa manapun yang mengalami penjajahan, harus ditolong agar bisa kembali merdeka.
Seperti ketika pertama kali sebuah kesultanan Nusantara, yaitu Malaka (kini wilayah Malaysia) dijajah Portugis pada 1511, maka seorang ulama sekaligus sultan Demak, Pati Unus memimpin sendiri bantuan tempur ke Malaka. Meskipun perjuangan Pati Unus gagal, bahkan beliau sendiri gugur dalam pertempuran, namun tingginya semangat nasionalisme beliau diwarisi oleh para ulama Nusantara lainnya. Sehingga selama 3,5 abad penjajah sendiri tidak bisa ‘tidur nyenyak’ karena terus-menerus dilawan oleh para ulama beserta pengikutnya.
Begitu banyaknya ulama yang diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah, membuktikan semangat nasionalisme mereka telah diakui sejarah. (Firdaus-AN, 1993).
Sejumlah ulama anggota BPUPKI, seperti KH. Mas Mansur pernah dipenjara oleh tentara penjajah, karena perjuangannya. Bahkan beliau gugur pada 1946 sewaktu dipenjara karena turut berperang melawa Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Kedua, para ulama kita memiliki strategi perjuangan fisik dan diplomatik yang cerdas. Sebagai intelektual sejati, para ulama mampu memadukan dua strategi perjuangan agar tanah airnya dapat dibebaskan dari penjajahan. Mereka berjuang secara fisik dengan bertempur melawan tentara penjajah, dan mereka juga aktif berjuang secara diplomatik melalui pemikiran-pemikiran cerdas yang ditulis pada media massa, bahkan juga disampaikan secara retoris melalui perundingan-perundingan.
Seperti anggota BPUPKI dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, beliau termasuk intelektual sejati dari kalangan ulama, yang pemikirannya banyak disepakati dalam perundingan-perundingan BPUPKI. Sementara itu, beliau juga merupakan tokoh senior Hisbullah (laskar pejuang bentukan Muhammadiyah) yang dikenal merepotkan penjajah Belanda maupun Jepang. Wahid Hasyim, anggota Panitia Sembilan BPUPKI dari NU, selain ‘jago’ berunding secara diplomatis, beliau juga salah satu tokoh terkemuka Sabilillah (laskar pejuang NU).
Ketiga, para ulama kita memiliki semangat persatuan yang kuat. Sebagai intelektual sejati, para ulama menyadari, bahwa tanpa persatuan kuat dari seluruh rakyat yang berbeda-beda latar belakang, kemerdekaan tidak akan bisa dicapai. Mereka pun berbesar hati ‘merangkul’ para tokoh intelektual lintas madzab pemikiran politik lainnya, untuk diajak kerjasama dalam melawan penjajah melalui diplomasi.
Seperti yang dilakukan KH. Ahmad Hassan (pendiri Persatuan Islam), yang bersahabat erat dan bekerjasama dengan para intelektual abangan seperti Sukarno. Pemikiran Hassan sangat bertolak belakang dengan pemikiran Sukarno, bahkan ketika dipertemukan dalam forum-forum dialogis, mereka sering terlibat perdebatan sengit.
Namun perdebatan sengit dan cenderung ‘keras’ tersebut hanya sampai pada tataran kepala saja, sedangkan hati mereka disatukan dengan perasaan cinta yang sama, yaitu sama-sama mencintai tanah air Indonesia. Apalagi sebagai intelektual yang dikagumi Sukarno, Hassan sangat memahami prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, termasuk juga dalam mengikuti madzab politik tertentu.
Allah swt. berfirman, “(Katakan) bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.” (QS. al-Kafirun : 6)
Tingginya Semangat persatuan yang dimiliki para ulama kita. ternyata mendasari para pejuang kemerdekaan di berbagai negara, untuk mencontoh sikap mulia tersebut. Seperti yang dilakukan seorang intelektual kharismatik dari kalangan ulama Afghanistan, Burhanuddin Rabbani. Ketika tanah airnya dijajah Uni Sovyet pada 1979, Rabani ‘merangkul’ para tokoh intelektual dari berbagai madzab pemikiran politik, untuk bersama-sama berjuang mengusir Sovyet. (Azzam, 1992).
Salah satu tokoh intelektual abangan yang dianggap musuh bebuyutan Rabbani adalah Gulbuddin Hekmatyar. Namun Rabbani dengan begitu sabar menghadapi ‘kerasnya’ perdebatan yang dilancarkan Hekmatyar. Sebab Rabbani dan Hekmatyar disatukan oleh persamaan cinta kepada tanah air mereka. Sehingga pada 1989, mereka berhasil mengusir penjajah Sovyet dari Afghanistan, bahkan tidak lama kemudian, Sovyet pun dilanda ‘kehancuran’ dengan terpecah-belah menjadi belasan negara baru. (Abdul Mun’im, 1995).
Keempat, para ulama kita memiliki skill komunikasi dialogis yang baik. Kuatnya semangat persatuan yang dimiliki para ulama, membuat mereka mampu berdialog dengan skill komunikasi yang baik. Sebab dalam dialog tersebut, mereka membuang jauh egoisme pribadi. Mereka bisa adil dalam menghadapi mitra dialog atau oleh publik dikenal sebagai lawan berdebat.
Keadilan sikap mereka dalam berkomunikasi secara dialogis, didasarkan pada firman Allah swt. “…Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa….“ (QS. al-Maidah : 8).
Para ulama yakin, bahwa tidak ada ideologi terbaik di alam semesta ini selain Islam yang diwahyukan Allah swt. melalui kitab suci-Nya. Namun mereka paham, bahwa komunikasi dialogis membutuhkan persamaan (equity) derajat antara pihak-pihak yang berdialog, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa direndahkan citranya.
Seolah para ulama kita memahami teori komunikasi I-Thou, yang dikemukakan Martin Buber pada awal abad ke-20 silam. Dalam teori tersebut, pelaku dialog memandang dirinya dan orang lain (mitra dialog) sebagai manusia utuh, yang tidak dapat dikurangi karakteristis kemanusiaannya menjadi lebih sederhana. Setiap orang memiliki pengalaman hidup penting, yang menjamin adanya hubungan positif, bahkan ketika pengalaman (termasuk pemikiran) orang lain berbeda dari pengalaman atau kita. (Littlejohn & Foss, dalam Nurhidayat, 2018).
Karena memiliki kemampuan komunikasi dialog yang baik, maka para ulama pun dihormati tokoh-tokoh intelektual abangan maupun intelektual non muslim.
Kelima, para ulama kita memiliki visi yang hebat. Sejarah membuktikan, bahwa selama 3,5 abad, perjuangan melawan penjajah selalu dipelopori, dimotori, bahkan dipimpin sendiri oleh para ulama.
Selama 3,5 abad perjuangan mengusir penjajah, tidak sedikit ulama beserta muslim santri yang gugur diterjang peluru-peluru penjajah. Banyak pula di antara mereka yang ditangkap, dipenjara, diasingkan, dianiaya, hingga dibunuh penjajah. Sungguh besar pengorbanan yang diberikan mereka untuk kemerdekaan tanah air ini.
Oleh karena itu, sangat berhak dan layak bagi para ulama sebagai representasi intelektual santri menghendaki agar ideologi mereka yang bersumber dari ajaran Islam, dijadikan sebagai ideologi bagi Indonesia merdeka. Sebab harus diakui, mereka memiliki ‘saham’ terbesar dalam mencapai kemerdekaan tanah air ini.
Namun demikian, setelah melalui berbagai komunikasi dialogis, bahkan sejumlah adu argumentatif yang ‘keras’, para ulama di BPUPKI, khususnya keempat ulama anggota Panitia Sembilan yang menyusun Piagam Jakarta, secara legowo menerima keputusan bahwa ideologi yang ditetapkan bagi Indonesia merdeka adalah Pancasila.
Sikap legowo ini lahir, karena mereka yakin bahwa Pancasila hanyalah akad (konsensus) nasional tentang interaksi antar rakyat yang ber-bhinneka tunggal ika. Pancasila versi Piagam Jakarta sama kedudukannya dengan naskah Piagam Madinah (yang ditandatangani Nabi Muhammad saw. dan tokoh-tokoh berbagai golongan di Madinah), ataupun naskah Magna Charta-nya Inggris yang ditandatangani pada 1215 (Anshari, 1995).
Sila pertama Pancasila berupa kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dijadikan sebagai landasan para ulama dalam memberlakukan aturan-aturan yang secara substansial berasal dari ajaran Islam.
Keenam, para ulama kita memiliki adab yang mulia. Para ulama yang dikenal sebagai intelektual sejati senantiasa menjungjung tinggi adab yang mulia. Hal ini dibuktikan secara jelas sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945, ketika mereka kembali harus legowo, karena tujuh kata pada sila pertama Pancasila, yaitu “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret PPKI (panitia persiapan kemerdekaan Indonesia). Ketujuh kata yang dicoret itu kemudian diganti dengan kalimat “…yang maha esa”, sehingga sila pertama Pancasila versi PPKI menjadi “Ketuhanan yang maha esa”.
Ternyata saat itu, ada sejumlah tokoh intelektual minoritas non-muslim maupun juga sebagian intelektual abangan yang tiba-tiba tidak legowo jika tujuh kata “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tertulis dalam Pancasila. Padahal sebelumnya tujuh kata tersebut diapresiasi positif oleh seluruh anggota BPUPKI. Para intelektual yang tidak legowo dengan tujuh kata tersebut seolah mengancam, bahwa rakyat minoritas non muslim, terutama dari kawasan timur Indonesia, akan memisahkan diri dari negara ini jika ketujuh kata tersebut tidak dicoret. (Firdaus AN, 1993; Anshari, 1995).
Meskipun ide pencoretan tersebut berasal dari segelintir oknum inteletual non-muslim dan intelektual abangan, namun hal tersebut juga tidak disukai oleh sebagian tokoh dari kalangan tersebut. Seperti Maramis, satu-satunya intelektual non-muslim yang ikut mererumuskan Paiagam Jakarta, dia sangat kecewa dengan pencoretan tersebut, karena dia berkeyakinan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari tujuh kata yang dicoret itu. (Firdaus AN, 1993).
Apalagi sasaran yang dimaksud pada tujuh kata tersebut hanyalah umat Islam saja. Bahkan umat agama lain yang minoritas dapat secara internal menjalankan ajaran agama mereka. Namun wacana ini pun tidak disetujui oleh mereka. (Hasan, 2004).
Sebagai intelektual sejati, para ulama pun menunjukkan adab mulia mereka, yang dengan kebesaran jiwa dan kebijaksanaan hati, mereka ikhlas lahir-batin dengan kalimat baru “Ketuhanan yang maha esa” tersebut. Meskipun diakui sejarah, pemilik ‘saham’ terbesar dalam mencapai kemerdekaan Indonesia adalah para ulama dan kaum santri.
Mereka yakin, meskipun kata “syariat Islam” tidak lagi dicantumkan secara tersurat dalam dasar maupun konstitusi negara, namun secara tersirat nilai-nilai syariat Islam dapat diterapkan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Apalagi selain sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan dalam beragama, para ulama diberi kabar gembira oleh naskah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang secara tersirat mengakui reputasi intelektual para ulama.
Dengan demikian, para ulama semakin yakin, bahwa syariat Islam tetap bisa diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak pernah ada pertentangan antara Pancasila dengan nilai-nilai luhur agama, yang salah satunya adalah nilai-nilai luhur Islam. Realitasnya, sejak kabinet pemerintahan pertama dibentuk Sukarno hingga sekarang, Indonesia memiliki kementerian agama.
Selain itu, berbagai produk hukum konvensional di negara ini pun, substansialnya banyak digali dari nilai-nilai luhur pada al-Qur’an maupun al-Hadits. Dalam studi hukum, syariat Islam telah lama diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia (Ali, 1998).
Kini, banyak sekali peraturan perundang-undangan tingkat nasional, provinsi, hingga kota / kabupaten dibuat dengan bersumber dari nilai-nilai luhur Islam. Sekali lagi, Dekrit Presiden telah mengakui reputasi intelektualitas para ulama yang patut disyukuri. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan mereka untuk melahirkan para intelektual sejati, yang sangat dibutuhkan tanah air ini, dalam mencapai cita-cita luhur para pendahulu kita. Wallahua’lam.*
Penulis adalah Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat