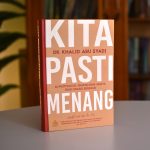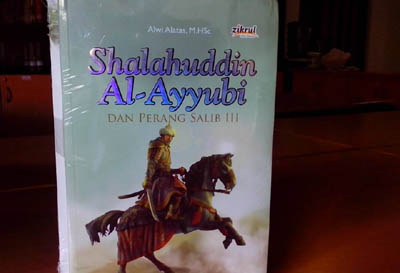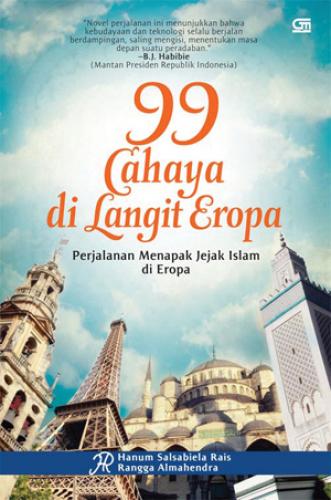ISLAMOPHOBIA memang bukan perkara gampang untuk dipahami. Istilah itu selama ini terbukti efektif membungkam siapapun yang dicurigai membenci Islam atau muslim. Bahkan lebih dari itu, istilah tersebut bisa menjadi pangkal dari proses hukum terhadap para pihak yang terbukti bersikap anti-Islam.
Pascal Bruckner, penulis buku ini, berusaha mengkritisi istilah ‘Islamofobia’. Sejarah timbulnya istilah ini berawal dari pengalaman Prancis menangani koloninya di Afrika Utara. Pada tahun 1910 penulis Prancis, Andre Quillien, yang bekerja untuk sebuah kementerian di Prancis menulis, Islam merupakan sekutu potensial di tanah jajahan. Sekutu ini harus dirangkul, bukan dicurigai. Quillien mengkritik para pejabat kolonial yang cenderung bersikap anti-Islam.
Pendirian Quillien ini sejalan dengan Louis Massignon, pakar mistisisme Islam, yang selalu menganjurkan dialog antara komunitas muslim dengan gereja Katolik Roma. Tentu saja, observasi Quillien diungkapkan dalam laporan-laporannya ke kementerian untuk tujuan kolonialisme Prancis di Afrika Utara. Kelak, dalam perjalanan sejarah, istilah islamofobia ini lantas berkembang menjadi istilah mujarab guna menghentikan segala bentuk upaya kecurigaan apalagi kebencian pada Islam dan muslim.
Selama lebih dari satu dekade silam, Pascal Bruckner telah menisbatkan diri sebagai figur intelektual Prancis yang secara berkelanjutan menyerang istilah ‘Islamofobia’ pada setiap diskusi publik. Bruckner menyoroti bukan saja pada istilah Islamofobia itu sendiri, melainkan juga pada para korban Islamofobia, serta konsekwensinya yang telah terjadi. Judul-judul tulisannya yang telah tersebar di berbagai media menunjukkan penolakannya pada Islamofobia. Ia begitu gigih menguraikan banyak ide-ide yang akan ditemukan pembaca dalam buku ini. Baginya, Islamofobia adalah rasisme imajiner, yakni ketika rasisme menurun tapi para penolak rasis justru menggelontor ruang publik dengan Islamofobia.
Bagi Bruckner, Islamofobia diciptakan untuk melindungi diri dari kritik terhadap Islam plus muslim. Sikap Bruckner ini boleh dikata mewakili sikap para pemikir bebas yang bukan saja merasa kesulitan berbicara bebas tentang realitas muslim, namun lebih dari itu, merasa terancam karena berbicara bebas tentang Islam dan muslim. Walaupun sesungguhnya, dalam buku ini, Bruckner kehilangan fokus ketika membahas gagasan-gagasannya dalam buku ini, lantaran ia memasukkan berbagai pembacaan pada situasi yang dihadapi kelompok neo-konservatif Prancis, manifesto para mantan gerakan 1968, kelompok multikulturalis, dan pendapat para sosiolog, antropolog serta serangan kaum kiri.
Saat ini, tulis Bruckner, Prancis melarang pemakaian burqa dan simbol-simbol agama di ruang publik dengan alasan kesetaraan. Jika orang lain tidak memakai burqa, dan menunjukkan wajah serta tanpa penutup kepala, maka perempuan muslim juga harus berlaku sama. Itu logika kesetaraan Prancis, yang mendasari dilarangnya burqa. Logika ini pula yang sempat ramai diperbincangkan di Indonesia pasca pelarangan cadar beberapa waktu lalu. Alasan utama para pengkritik cadar berpangkal dari kesetaraan ini. Jika para mahasiswi atau dosen lain tidak bercadar, maka mahasiswi atau dosen bercadar harus membuka cadarnya. Pelarangan terhadap burqa dan juga cadar ini pada gilirannya masuk ke dalam ruang diskriminasi. Mereka yang memakai burqa atau bercadar digiring ke dalam satu ruang layaknya mereka bukanlah bagian dari publik yang bebas. Bukan bagian dari publik yang punya hak-hak untuk beraktivitas. Perilaku diskriminatif atas nama kesetaraan ini memang ganjil, seganjil logika yang mendasarinya.
Bruckner secara implisit menunjukkan keberpihakannya pada kesetaraan itu, yang dianggapnya sebagai jauh di atas multikulturalisme sebagaimana dipraktekkan di Inggris. Ironinya, Bruckner tidak mengulas lebih dalam dampak kebijakan bertumpu kesetaraan terhadap komunitas minoritas, seperti minoritas muslim Prancis. Bruckner bangga pada warisan Prancis yang sangat mendukung kesetaraan tapi minim penghargaan pada kemajemukan.
Bahkan di kalangan intelektual Prancis sendiri, perdebatan seputar Islamofobia marak tiada henti. Pada tahun 2008 jagat akademis Prancis ramai diisi perdebatan antara filsuf Alain de Libera lawan Sylvain Gouguenheim. Alain adalah gurubesar pada lembaga akademis paling bergengsi di Prancis, College de France, sedangkan Sylvain merupakan sejarawan yang menolak peran orang Arab dalam transmisi pengetahuan ke Eropa. Sylvain banyak menulis soal ini dan terkesan sangat minor pada kontribusi muslim.
Baca: Bagaimana Islamofobia dan Fakta ‘Alternatif Membentuk Perintah Donald Trump
Bagi Alain, karya-karya Sylvain memperlihatkan karakter Islamofobia, dan bahkan bukan hanya Sylvain, melainkan juga karya-karya Fernand Braudel, Remi Brague serta Dominique Urvoy. Kritik lebih lunak dikemukakan Jacques le Goff, yang menyatakan karya Sylvain sangat menarik tapi layak diperdebatkan. Bruckner sendiri lebih berpihak pada Sylvain dan siapapun intelektual Prancis yang dianggapnya telah menjadi korban tudingan islamofobik. Menurut Bruckner, tudingan seperti itu ibarat ‘senjata pengintimidasi massal’, yang berdampak membungkam kebebasan akademis. Tudingan Islamofobia menjadikan seorang akademis tak berkutik, lalu dimasukkan ke dalam kubu kelompok fasis anti-minoritas. Bahkan, intelektual muslim yang berusaha membela kebebasan pun kemudian harus menghadapi nasib dituding sebagai ‘pengkhianat’. Bruckner berada di pihak membela para ‘pengkhianat’ ini.
Buku ini berisi 19 tulisan terpisah dalam lima bagian. Bruckner sudah menyerang sejak dalam tiga bagian awal. Selain menuding istilah Islamofobia adalah fabrikasi opini berujung kriminalitas, Bruckner juga meragukan keberadaan Islamofobia.
Meskipun sesungguhnya istilah Islamofobia itu sendiri muncul dalam teks-teks Prancis pada awal tahun 1920-an (sesuatu yang diakui oleh Bruckner). Namun, Bruckner berdalih bahwa penggunaannya saat ini tidak dapat dilacak ke dalam upaya kaum Islamis yang sering dianggap gencar menolak Islamofobia.
Kehadiran istilah itu, kata Bruckner, berakar pada kebutuhan konseptual untuk menamakan bentuk permusuhan dan diskriminasi yang dialami oleh umat Islam. Hanya saja, Bruckner tampak mengabaikan fakta, bahwa pemakaian kembali istilah Islamofobia justru pertama kali muncul dari riset lembaga pemikir Inggris pada akhir dekade ’90an tentang rasisme. Sehingga boleh dikata, sebenarnya yang memperlihatkan sisi imajiner justru ketiadaan silsilah istilah tersebut, ketimbang sisi imajiner itu dianggap melekat pada istilah Islamofobia . Inilah kelemahan argumen Bruckner. Ia begitu bergairah mengupas sisi gelap pemakaian istilah Islamofobia , tapi ia lupa atau sengaja mengabaikan bagaimana silsilah istilah itu kembali muncul.
Serangan berikutnya dari Bruckner adalah menyamakan Islamofobia dengan anti-semitisme. Diawali paparan Edward Said yang secara tersirat menyamakan nasib muslim Timur-Tengah yang terpinggirkan usai perang Arab-Israel, dengan nasib Yahudi di masa lampau saat perang dunia kedua. Bruckner membantah hal ini dengan mengutip pendapat Enzo Traverso, sejarawan Italia, yang menyatakan bahwa saat ini Islamofobia memainkan peran mirip dengan wacana anti-semitisme. Dengan kata lain, Islamofobia merupakan artikulasi baru wacana anti-semitisme. Islamofobia identik dengan sikap anti-semit. Islamofobia merupakan kelahiran kembali anti-semitisme, begitu tulis Bruckner. Serangan Bruckner ini tertuju pada siapapun muslim yang gemar menuding Islamofobia kepada pihak yang mengkritisi Islam dan muslim. Tak tanggung-tanggung, Bruckner bahkan menyentil paman Yasser Arafat, yakni mufti besar Jerusalem Haji Amin al Husseini, sebagai pengagum Hitler. Menurut Bruckner, Husseini tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang ikut mendukung ideologi Nazi, bahkan lebih jauh, Bruckner juga menuding Louis Farrakhan, pencetus gerakan ‘Nation of Islam’ di AS, sebagai anti-semit. Indikasinya sederhana. Para tokoh anti-semit itu selalu menebar wacana Islamofobia .
Buku Bruckner ini memang kontroversial. Begitu kontroversialnya, Bruckner juga mengutip pendapat Olivier Roy, ilmuwan politik, yang melihat kebangkitan wacana Islamofobia mengulangi kebangkitan anti-semitisme. Sikap Roy ini tentu saja berkaitan pada upayanya menegakkan kembali apa yang disebut sebagai semangat sekularisme Prancis, yang menempatkan bangsa di atas agama. Walaupun Bruckner berusaha mengulas secara berimbang, namun lagi-lagi ia selalu jatuh pada pembahasan yang sederhana ihwal Islamofobia. Baginya, Islamofobia merupakan barang lama dalam kemasan baru, yang mengancam nilai-nilai kebebasan Eropa.*

Judul buku: An Imaginary Racism
Penulis : Pascal Bruckner
Penerbit: Polity Press, UK
Tebal: vi + 206 halaman
Cetakan: Pertama, 2018
Rosdiansyah, Peresensi alumni FH Unair, master studi pembangunan ISS, Den Haag, Belanda. Peraih beragam beasiswa internasional. Kini, periset pada the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP, Surabaya