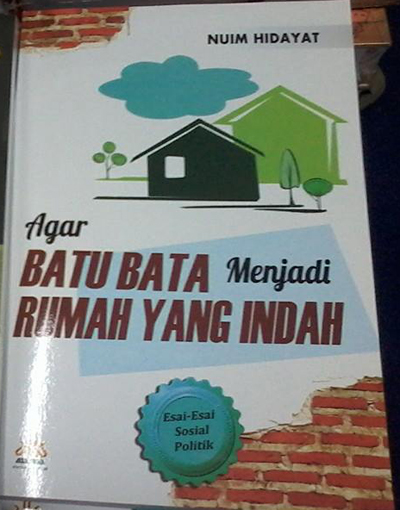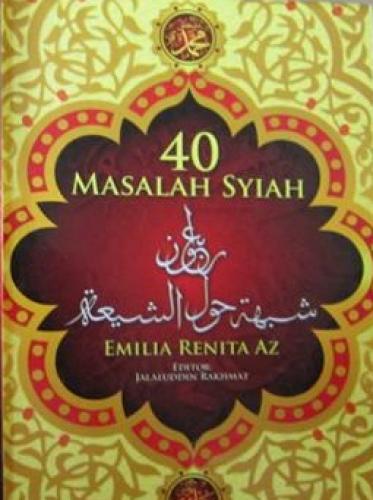Hidayatullah.com—Peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSTISTS), Nuim Hidayat, baru saja meluncurkan buku barunya berjudul “Agar Batu Bata Menjadi Rumah Yang Indah” (Esai-Esai Sosial Politik) diterbitkan oleh Pustaka Al Kautsar.
“Alhamdulillah buku saya akhirnya terbit. Buku ini adalah buku serius yang membahas permasalahan mendasar bagi para aktivis Islam. Mulai dari masalah ketertinggalan umat, politik dalam negeri, perbandingan gerakan Islam, sejarah Masyumi, sejarah UUD 45 sampai dengan nasihat Ali bin Abi Thalib dan Muhammad al Fatih,”terangnya kepada hidayatullah.com, Sabtu (08/03/2014).
Dalam bukunya, Nuim membandingan gerakan-gerakan pemikiran, termasuk gerakan yang dimotori Mohammad Natsir, Hasan Al Banna, Abul Ala Maududi dan Taqiyudin an Nabhani.
Menurutnya, ada kesamaan pemikiran empat tokoh di atas. Mereka sama-sama menginginkan terbentuknya negeri Islam atau masyarakat Islam. Mereka sama-sama menekankan pentingnya pembentukan pribadi Muslim, Keluarga Muslim, Masyarakat Muslim dan Negeri Islam. Mereka juga sama-sama menginginkan jalan damai bagi pembentukan negeri Islam.
Perbedaannya adalah pada cara pembentukan negera Islam itu, struktur negara Islam dan nama negara Islam itu. Dalam pandangan Mohammad Natsir, Islam tidak mengatur nama dan struktur negara Islam. Natsir menyatakan bahwa negara harus berlandaskan Islam dan pemimpin dalam negara itu harus bertekad melaksanakan hukum Islam dalam masalah individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Natsir menyetujui istilah demokrasi Islam dan Natsir menerima negera Indonesia sebagai sebagai negeri Islam yang berdasarkan Pancasila (bagian dari UUD 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta sesuai dengan Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959).
Pancasiladianggap Natsir sebagai sebagian dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam dan ia juga menerima demokrasi parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Meski demikian, dalam sidang-sidang Dewan Konstituante tahun 50-an Natsir dengan partai Masyumi-nya berjuang keras agar landasan negara Indonesia adalah Islam.
Hampir sama dengan Natsir, Hasan al Banna dan Abul A’la al Maududi juga demikian. Meski al Banna dan Maududi menolak demokrasi Barat, mereka masih menerima sistem parlemen. Maududi mengajukan istilah Theodemokrasi, demokrasi berketuhanan atau demokrasi Islam. Begitu juga Hasan al Banna. Pendiri Ikhwanul Muslimin ini, memang semasa hidupnya pernah mengecam habis partai-partai yang berlomba mengejar jabatan dan materi belaka di Mesir. Menurut al Banna, partai atau organisasi-organisasi politik itu dibentuk untuk dakwah Islam dan memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kekuasaan belaka. Karena itu, Ikhwanul Muslimin dulu dan kini di berbagai negara, masuk terlibat dalam kekuasaan pemerintahan yang berdasar demokrasi parlementer. Menurut Al Banna, pembentukan negeri Islam, dimulai dari individu, keluarga, masyarakat dan kemudian negara.
Maududi bahkan memperinci struktur negara dalam Islam, dengan menerima konsep demokrasi modern, legislatif, yudikatif dan eksekutif. Cuma ia mencatat bahwa ketiga lembaga ini mesti memegang teguh Islam, Al Qur’an dan Sunnah, dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maududi yang berjasa besar dalam meletakkan dasar Islam bagi negara Pakistan dan gerakannya Jamaat Islami juga masuk dalam ‘politik parlementer’.
Sedangkan Taqiyuddin an Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menjelaskan bahwa nama dan struktur negara Islam sudah merupakan hal yang baku dalam Islam. Titel kepala negara bernama khalifah dan negara Islam yang bernama khilafah Islamiyah adalah suatu hal yang qath’i bagi Hizbut Tahrir. Bahkan an Nabhani juga mengharuskan nama-nama khusus untuk pejabat dalam struktur pemerintahan khilafah Islamiyah, seperti khalifah, naibul khalifah, muawwin, muawwin tafwizh dan lain-lain.
Selain itu an Nabhani juga menolak keras istilah demokrasi, bahkan demokrasi Islam sekalipun. Menurutnya demokrasi adalah istilah dari Barat dan harus ditolak oleh kaum Muslimin. Pendiri Hizbut Tahrir ini juga mengajukan konsep revolusi (inqilabiyah) dalam penerapan Islam oleh negara. Dengan catatan bahwa perjuangan pembentukan Daulah Islamiyah ini, harus diperjuangkan dengan cara-cara damai.
Begitu juga istilah nasionalisme, Nabhani menolak keras konsep ini. Hal ini berbeda dengan Natsir, Maududi dan al Banna. Ketiga tokoh ini menempatkan nasionalisme dalam bingkai Islam. Menurut ketiganya, Islam memang tidak memandang ras, wilayah geografis dan lain-lain, tapi bila seorang Muslim mencintai negaranya, sebagai bumi Allah dan berjuang agar ditegakkan hukum-hukum Allah, maka itu adalah sebuah kewajiban. Ketiganya juga memandang persatuan dunia Islam (khilafah Islamiyah) bisa diraih, dengan lebih dahulu membentuk negeri-negeri Islam di wilayah masing-masing.
Pesan Sultan al Fatih
Dalam buku baru ini, Nuim juga mengutip nasihat-nasihat politik yang menarik dari Mohammad Natsir, Mohammad Al Fatih dan Sayyidina Ali.
Dalam dialognya dengan Amien Rais, Kuntowijoyo dkk pada 1986-1987, Natsir mengkhawatirkan adanya penyakit bangsa Indonesia, termasuk umat Islamnya, yaitu cinta berlebihan kepada dunia. Kata Natsir: “Umat Islam dihinggapi penyakit wahn, yakni dunia yang berlebihan dan takut mengambil risiko. Keadaan semacam ini pernah terjadi dalam sejarah, pada waktu itu para prajurit yang ikut berperang karena tergiur pada harta rampasan perang, lalu karena kelengahan dan kepongahan ini mereka dengan mudah dikalahkan musuh. Hal ini terjadi pada saat Islam mengembangkan sayapnya di daratan Eropa.
“Di negara kita penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang “baru”, tidak kita jumpai pada masa revolusi, dan bahkan pada masa Orde Lama (kecuali pada sebagian elite masyarakat). Tetapi gejala yang “baru” ini, akhir-akhir ini terasa pesat “perkembangannya, sehingga seperti sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, maka bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi bagi bangsa kita umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius.”
Penyakit cinta dunia ini, menurutnya memang bukan semata-mata permasalahan dakwah, yang harus dihadapi para mubaligh dan dai, tetapi sudah merupakan permasalahan nasional.
“Dalam konteks yang terakhir ini masalahnya menjadi lebih sulit ( complicated) karena bukan saja merupakan masalah ekonomi, tetapi masalah sosial, budaya, dan bahkan politik. Untuk ini terpulanglah kepada para pengambil keputusan untuk mengatasinya.”
Nasehat Natsir ini selaras dengan nasehat Mohammad al Fatih, pemimpin besar Islam yang menaklukkan Konstantinopel menjelang wafatnya:
“Tak lama lagi aku akan menghadap Allah Subhanahu Wata’ala. Namun aku sama sekali tidak merasa menyesal, sebab aku meninggalkan pengganti seperti kamu. Maka jadilah engkau seorang yang adil, saleh dan pengasih.
Rentangkan perlindunganmu terhadap seluruh rakyatmu tanpa perbedaan. Bekerjalah kamu untuk menyebarkan agama Islam sebab ini merupakan kewajiban raja-raja di bumi.
Kedepankan kepentingan agama atas kepentingan lain apapun. Janganlah kamu lemah dan lengah dalam menegakkan agama. Janganlah kamu sekali-kali memakai orang-orang yang tidak peduli agama menjadi pembantumu. Jangan pula kamu mengangkat orang-orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar dan larut dalam kekejian…
Oleh sebab ulama itu laksana kekuatan yang harus ada di dalam raga negeri, maka hormatilah mereka. Jika kamu mendengar ada seorang ulama di negeri lain, ajaklah dia agar datang ke negeri ini dan berilah dia harta kekayaan. Hati-hatilah jangan sampai kamu tertipu dengan harta benda dan jangan pula dengan banyaknya tentara. Jangan sekali-kali kamu mengusir ulama dari pintupintu istanamu. Janganlah kamu sekali-kali melakukan satu hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebab agama merupakan tujuan kita, hidayah Allah adalah manhaj (pedoman) hidup kita dan dengan agama kita menang.
Ambillah pelajaran ini dariku. Aku datang ke negeri ini laksana semut kecil, lalu Allah karuniakan kepadaku nikmat yang demikian besar ini. Maka berjalanlah seperti apa yang aku lakukan. Bekerjalah kamu untuk meninggikan agama Allah dan hormatilah ahlinya. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta negara dalam foya-foya dan senang-senang atau kamu pergunakan lebih dari yang sewajarnya. Sebab itu semua merupakan penyebab utama kehancuran.”
Menurut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Depok ini, para pemimpin juga perlu mengambil ibrah dari surat-surat Sayyidina Ali r.a. yang sangat berharga. Nasehat khalifah keempat ini adalah surat-surat yang dikirimkannya kepada Gubernur Mesir Malik bin Harits al Asytar, pada tahun 655M. Nasihat ini berisi prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan atau manajemen sebuah pemerintahan, organisasi dan lain-lain.
Di antara nasehatnya adalah: “Ketahuilah wahai Malik bahwa aku telah mengangkatmu menjadi seorang Gubernur dari sebuah negeri yang dalam sejarahnya berpengalaman dengan pemerintahan-pemerintahan yang benar maupun tidak benar.
Sesungguhnya orang-orang akan melihat segala urusanmu, sebagaimana engkau dahulu melihat urusan para pemimpin sebelummu. Rakyat akan mengawasimu dengan matanya yang tajam, sebagaimana kamu menyoroti pemerintahan sebelumnya juga dengan pandangan yang tajam. Mereka akan bicara tentangmu, sebagaimana kau bicara tentang mereka.
Sesungguhnya rakyat akan berkata yang baik-baik tentang mereka yang berbuat baik pada mereka. Mereka akan (dapat) ‘menggelapkan’ semua bukti dari tindakan baikmu. Karenanya, harta karun terbesar akan kau peroleh jika kau dapat menghimpun harta karun dari perbuatan-perbuatan baikmu. Jagalah keinginan agar selalu di bawah kendali dan jauhkan dirimu dari halhal yang terlarang. Mereka adalah makhlukmakhluk yang lemah, bahkan sering melakukan kesalahan. Bagaimanapun berikanlah ampun dan maafmu sebagaimana engkau menginginkan ampunan dan maaf dari-Nya. Sesungguhnya engkau berada di atas mereka dan urusan mereka ada di pundakmu.
Sedangkan Allah berada di atas orang yang mengangkatmu. Allah telah menyerahkan urusan mereka kepadamu dan menguji dirimu dengan urusan mereka. Jangan katakan:”Aku ini telah diangkat menjadi pemimpin, maka aku bisa memerintahkan dan harus ditaati”, karena hal itu akan merusak hatimu sendiri, melemahkan keyakinanmu pada agama dan menciptakan kekacauan dalam negerimu.
Bila kau merasa bahagia dengan kekuasaan atau malah merasakan semacam gejala rasa bangga dan ketakaburan, maka pandanglah kekuasaan dan keagungan pemerintahan Allah atas semesta, yang kamu sama sekali tak mampu kuasai. Hal itu akan meredakan ambisimu, mengekang kesewenang-wenangan dan mengembalikan pemikiranmu yang terlalu jauh.”* /Abu Zidni Taqiyudin