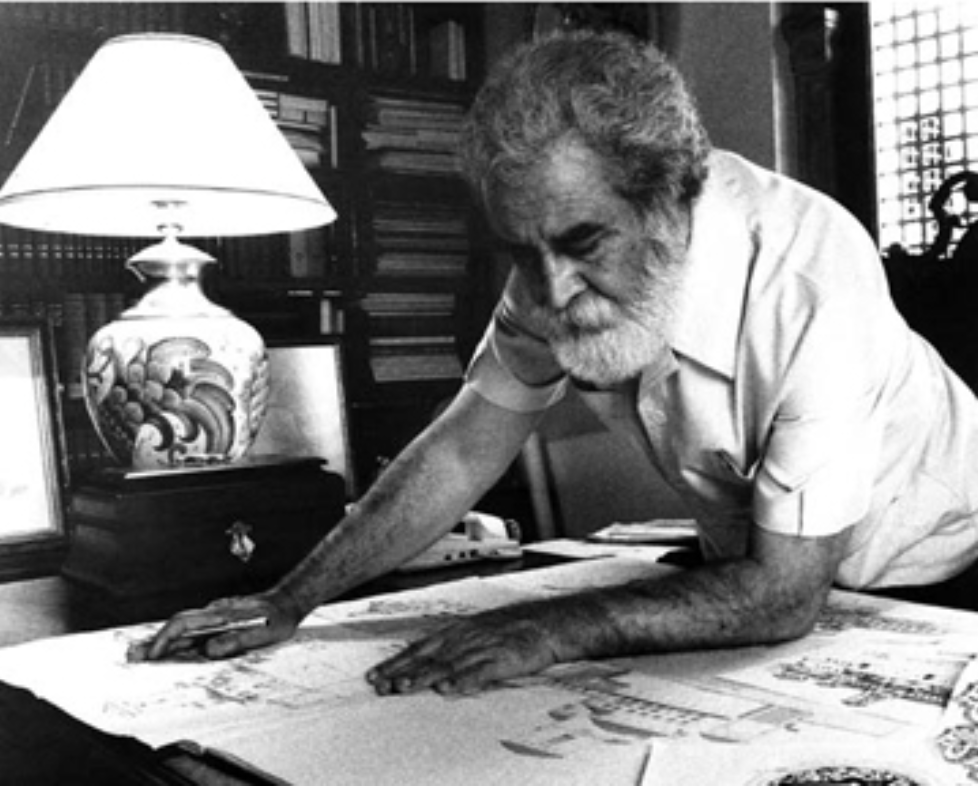Oleh: Rahmat Hidayat Zakaria
KEBERLANGSUNGAN dan kebertahanan suatu bahasa sungguh tidak dinafikan bahwa di baliknya tentu terdapat unsur-unsur yang mempengaruhinya, di antaranya adalah kitab suci. Ini karena kitab suci memiliki andil atauperan yang begitu besar dan merupakan otoritas yang dimiliki oleh manusia serta dianggap sebagai pondasi terhadap kebertahanan suatu bahasa. Walaupun terdapat pelbagai macam kitab suci di dunia, namun yang penulis maksudkan di sini adalah kitab suci al-Qur’an.
Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an diturunkan berbahasa Arab. Bahasa Arab yang dipilih sebagai bahasa wahyu disebabkan oleh bahasa tersebut mempunyai kekuatan dan keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab dengan tuntunan Allah Subhanahu Wata’ala dan wahyu mampu mengubah kedudukannya menjadi satu-satunya bahasa yang masih hidup di antara bahasa-bahasa manusia. Al-Qur’anlah yang berperan menjadikan bahasa Arab terpelihara dari perubahan-perubahan, tetap hidup dan kekal sebagai bahasa yang baku. Setiap makna dari perkataan-perkataan yang ditimbulkannya ditentukan oleh perbendaharaan kata semantik dari al-Qur’an dan ia bukan ditentukan oleh perubahan sosial (SMN Al-Attas, Islam and secularism, 1993, 46).
Bahasa Arab disinyalir sebagai bahasa yang tertua di muka bumi, sebab bahasa ini telah dipilih Allah Subhanahu Wata’ala sebagai bahasa wahyu yang telah diturunkan semenjak 1400an tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam dan bahkan amat jauh dari masa diturunkannya itu, al-Qur’an sudah ada sebelum manusia pertama Adam a.s. diciptakan, karena hal tersebut dapat diamati dari redaksi surah al-Raḥmān: 1-3. Hingga sekarang bahasa ini tetap digunakan dan masih hidup di saat bahasa-bahasa dunia lainnya telah punah seperti bahasa Amerindian yang pernah digunakan oleh penduduk asli Amerika, bahasa Sumeria, Galia, Koptik, Aramaic, Slovania, Sanskerta, Pali, bahasa Chamicuro yang sekarang telah digantikan dengan bahasa Spanyol, Ongota yang pernah digunakan di daerah Ethiopia, Njerep Bantoid di daerah Nigeria dan Kamerun, Dumi di Nepal, Chemehuevi di California, Uru di Bolivia, Mescalero-Chiricahua Apache di Oklahoma dan New Mexico, Onandaga yang pernah dipakai di Kanada dan Amerika Serikat danbahasa Irlandia, Kornisy serta bahasa-bahasa di kepulauan Hawai pun demikian yang sekarang telah digantikan dengan bahasa Inggris.
Demikian pula dengan bangsa seperti di Afrika, Amerika Selatan dan Asia Pasifik sudah tidak menggunakan bahasa ibu mereka lagi karena telah digantikan dengan bahasa-bahasa yang menjajah bangsa-bangsa tersebut. Betapa pun, bahasa-bahasa tersebut dinilai tidak memiliki sandaran kuat yang dapat memelihara keutuhannya. Oleh sebab itu, apabila bahasa telah punah maka tidak mustahil jika budaya dan tradisi suatu bangsa juga akan punah.
Bahasa Arab sebagaimana difahami selama ini adalah bukan bahasa yang hanya digunakan sebatas untuk beribadah atau digunakan untuk aktivitas yang bersifat keagamaan saja, akan tetapi di samping itu bahasa ini merupakan atau dikategorikan sebagai bahasa saintifik (ilmiah) disebabkan oleh kalimat-kalimatnya mempunyai akar kata (the root of word) tersendiri.
Akar kata tersebut saling berkaitan, sehingga dari akar kata yang sama ia melahirkan kalimat yang baru dan memberikan definisi, kata kunci, makna dan penekanan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perkara yang demikian dapat kita perhatikan dari keterkaitan dan keterikatan oleh beberapa perkataan sebagai berikut:
Dunia, Agama, Hutang, Hakim/Penguasa/Pemerintah, Kota dan Peradaban.
Perkataan dunia pada awalnya terambil dari perkataan danā yang berarti membuat sesuatu itu menjadi dekat. Dunia diciptaan Tuhan untuk dibuat dan dijadikan agar dekat dengan manusia. Lawan kata dari dunia adalah Akhirat. Itu sebabnya Akhirat atau hari kemudian diposisikan di akhir, karena penentuan perkataan tersebut adalah selaras dan tidak menyalahi tata bahasanya. Namun apa hubungannya dengan Agama? di dalam Islam dan dalam bahasa Arab agama dinamai dengan dīn. Perlu diketahui bahwa dīn tidak serta-merta bermakna agama, akan tetapi dīn pula mempunyai makna sebagai penyerahan diri; keadaan berhutang; kuasa peradilan; dan kecenderungan alami, (SMN Al-Attas, Prolegomena to The Metaphysics of Islam, 1995, 42).
Konsep dīn (agama) di dalam Islam tidaklah sama dengan konsep agama yang dilahirkan dari Barat yaitu religion. Religion merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Latin yaitu religiõ yang berarti mengikat. Pada hakikatnya sikap yang “diikat” maupun dasar-dasar “pengikatan” tersebut kesemuanya tidak jelas terkandung di dalam istilah tersebut. Pengikatan di sini dalam sejarah agama Barat, itu dilakukan secara paksa oleh paderi (pendeta) terhadap masyarakat luas yang tidak rela. Itu sebabnya agama bagi mereka dianggap sebagai belenggu yang menafikan “kebebasan”, karena pengikatan diri tersebut tidak didasari oleh kerelaan dan kesadaran di dalam diri.
Oleh karena itu baik agama Kristen, agama Barat maupun agama-agama lain yang bukan Islam kesemuanya adalah agama yang bersumber dari kebudayaan, lahir daripada produk manusia yang terbina dari pengalaman sejarah, yang dilahirkan, dibela, diasuh dan dibesarkan oleh sejarah, (SMN Al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, 2001, 36-37).
Seakar dengan perkataan dīn (د – ي – ن) adalah dayn yang bermakna keadaan berhutang. Manusia dianugerahi nikmat yang melimpah dari yang sekecil-kecilnnya hingga yang sebesar-besarnya. Dianugerahi nikmat berupa udara, hujan yang diturunkan dari langit, matahari yang menyinari alam raya, diciptakannya malam dan siang, dianugerahi sungai dan lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Akan tetapi, nikmat terbesar yang dianugerahi Allah Subhanahu Wata’ala kepada manusia adalah nikmat kewujudan atau keberadaanya di dunia.
Dengan nikmat terbesar dan melimpah yang dianugerahkan kepada manusia itu, tentu mereka mempunyai hutang (dayn) yang wajib untuk ditunaikan. Hutang terbesar yang wajib manusia tunaikan adalah hutang kewujudannya di dunia, karena nikmat-nikmat yang melimpah tadi tidak dapat dirasakan dan dinikmati apabila manusia tidak dilahirkan atau tidak wujud di muka bumi.
Oleh sebab itu, hutang kewujudan tersebut sampai kapan pun tidak mampu mereka tebus dan lunasi, kecuali dengan cara menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan penyerahan yang penuh kerelaan dan tanpa adanya unsur paksaan (lā ikrāha fī al-dīn), yaitu suatu penyerahan yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan diajarkan oleh Rasulullah bukan penyerahan diri berdasarkan budaya, sejarah dan hasil pemikiran manusia. Media untuk menyerahkan diri tersebut adalah dengan cara keberagamaan (dīn) yang benar. Oleh karena itu, hutang kewujudan manusia dapat terlunasi apabila ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan penyerahan yang sesungguhnya, tidak berubah-ubah dan tidak beribadah mengikut kehendak nalar manusia.
Dunia maupun agama (dīn) mempunyai ikatan yang amat erat dan keduanya adalah berasal dari akar kata yang sama. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa agama atau keberAgamaan itu hanya dilaksanakan di dunia dan bukan di tempat yang lain.
Dari akar kata di atas yaitu dunyā (dunia), dīn (agama) dan dayn (dalam keadaan berhutang) tidak mustahil apabila ia seakar pula dengan perkataan dāna sehingga dari perkataan tersebut ia melahirkan kalimat baru yaitu mudun atau madā’in yang berarti kota.
Dahulu, sebelum kota Madinah didirikan, kota ini dikenal dengan nama Yathrib. Oleh sebab itu, sebuah kota atau Madīnah tentu memiliki seorang hakim, penguasa atau pemerintah yang mempunyai otoritas untuk mengatur kota tersebut, yang mana itu dinamakan dengan dayyān. Dayyān yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah karena beliau merupakan otoritas tertinggi (dayyān) sebagai seorang hakim, penguasa dan pemerintah yang wajib ditaati oleh penduduk kota tersebut.
Berdasarkan penjelasan ini kita dapat berkesimpulan bahwa kota Madinah dapat berdiri dengan atau atas dasar dīn (agama) atau keber-agamaan yang benar yang diajarkan oleh beliau. Atas dasar dīn dan bermula dari kota Madinah inilah sebuah peradaban (tamaddun) tercipta. Perkataan tamaddun pula masih seakar dengan perkataan sebelumnya yaitu maddana yang memiliki makna di antaranya adalah membangun atau membina kota, membangun peradaban, memurnikan dan memanusiakan, (berkenaan dengan perbincangan tadi boleh rujuk langsung SMN Al-Attas, Prolegomena to The Metaphysics of Islam, khususnya di bab Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality).
Perkataan peradaban sebagaimana yang disinggung di atas sebelum perkataan tersebut ditambah imbuhan “per dan an”, pada mulanya adalah adab. Jadi peradaban atau tamaddun merupakan istilah yang menggambarkan konsep adab yang menyeluruh yaitu meliputi individu dan masyarakat yang menjangkaui semua bidang dan institusi seperti agama, kebudayaan, sosio-politik, ekonomi, kesenian, senibina dan lain-lain (Wan Mohd Nor Wan Daud, Al-Attas: Ilmuwan Penyambung Tradisi Pembaharuan Tulen, di dalam Adab dan Peradaban, 2012, 58).
Istilah adab tidak sesimpel seperti apa yang difahami oleh masyarakat selama ini yang barangkali maknanya hanya direduksi sebatas sopan santun kepada orang lain saja misalnya. Jika difahami demikian, maka hadith Nabi yang menyatakan, addabanī Rabbī faaḥsana ta’dībī (Tuhan telah mendidikku dan memperindah adabku atau pendidikan itu) tentu tidak memiliki kesan sama sekali di baliknya terhadap kepribadian Rasulullah. Hal yang perlu diketahui bahwa adab adalah potensi seseorang yang mampu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya yang tepat, yang wajar dan yang semestinya. Untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, seseorang perlu dibekali ilmu dan pengetahuan.
Adab terhadap peradaban atau puncak penilaian terhadap suatu peradaban adalah ditempatkan atau dilihat dari aspek manusianya yaitu ilmu, karena ilmu merupakan perhiasan yang ada pada diri manusia dan ia juga menjadi puncak segala yang terhasil dari kreativitas manusia yang dizahirkan dalam bentuk ilmu-ilmu baru seperti penemuan sains, metode berpolitik, ekonomi, bangunan dan teknologi. Peradaban yang maju bukanlah dinilai dari aspek yang bersifat materi seperti bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, peninggalan-peninggalan sejarah, candi-candi, karya-karya persuratan dan lain sebagainya, karena sifat-sifat kebendaan (materi) seperti ini tidak akan kekal dan suatu saat akan pudar seiring dengan berjalannya waktu, (M. Zainiy Uthman, Pemikiran dan Pembinaan Tamaddun, 2012, 18).
Dengan demikian, tidaklah heran apabila Rasulullah dan generasi-generasi beliau atau agama Islam tidak banyak meninggalkan kemegahan-kemegahan yang bersifat fisik atau materi, karena yang Rasulullah bangun itu adalah manusianya dan generasi-generasi yang unggul dan beradab. Kualitas yang ada pada diri manusialah yang menjadikan peradaban mampu bertahan lama.* (BERSAMBUNG)
Penulis mahasiswa Pasca Sarjana di Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, Universiti Teknologi Malaysia. Email: [email protected]