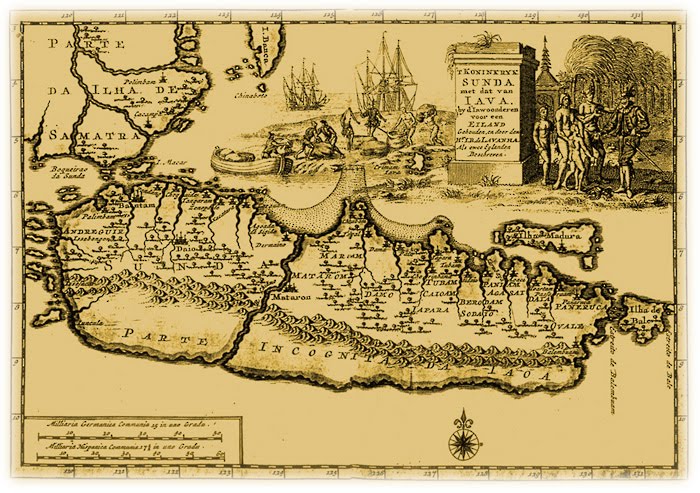Oleh: Usep Mohamad Ishaq
PADA suatu kesempatan ketika menghadiri kuliah filsafat Ilmu di suatu perguruan tinggi bidang sains dan teknologi, saat itu kebetulan bersamaan dengan tugas presentasi dari para mahasiswa peserta kuliah. Setelah beberapa lama berselang para peserta bergantian menyajikan karya tulisnya, salah satu tema yang menarik perhatian adalah makalah yang berkaitan dengan kemunduran sains di dunia Islām, setelah menguraikan fakta dan data sejarah, kemudian ia menyimpulkan dengan meyakinkan dan tanpa ragu-ragu bahwa sosok yang bertanggung jawab atas kemunduran sains di dunia Islām adalah sosok seorang teolog bernama al-Ghazālī, karena ia cenderung pada ilmu agama dan menolak filsafat. Nampaknya tidak ada tanda keberatan dari peserta lain, demikian pula dari profesor pengampu mata kuliah tersebut.
Pada kesempatan lainnya selang beberapa tahun, ketika penulis berkesempatan menjadi panelis dalam suatu acara ilmiah, salah seorang panelis lain juga tanpa ragu-ragu menyalahkan al-Ghazālī terhadap kemunduran sains, alasannya sederhana, senada dan seirama: serangan telak beliau terhadap filsafat yang mengakibatkan orang-orang Islām berpaling dari sains pada ilmu agama.
Demikian juga tidak terhitung tulisan yang memiliki nada serupa baik dalam media cetak maupun jejaring sosial, bahwa al-Ghazālī penyebab utama kemunduran sains di dunia Islām. Nampaknya pandangan seperti ini banyak diterima tanpa direnungkan lebih jauh.
Awal tuduhan
Anggapan seperti ini sebenarnya bisa dilacak jauh ke belakang. Misalnya pendapat seorang orientalis Goldziher, ia menyatakan bahwa kemunduran sains di dunia Islām adalah karena suatu “conservative religious forces”,[ Muzaffar Iqbal, Science and Islam (London: Greenwood Press, 2007),hlm. 125] atau juga ulasan seorang pemenang nobel fisika terkenal Steven Weinberg tahun 1979 yang juga seorang ateis [Dalam Steven Weinberg, “A deadly certitude” (artikel dapat dilihat pada laman http://tls.timesonline.co.uk/article/0,,25349-2552017.htmlhttp://old.richarddawkins.net/articles/531-a-deadly-certitude]
“Alas, Islam turned against science in the twelfth century. The most influential figure was the philosopher Abu Hamid al-Ghazzali, who argued in The Incoherence of the Philosophers against the very idea of laws of nature…After al-Ghazzali, there was no more science worth mentioning in Islamic countries.”
(Sayang sekali, Islām berbalik menentang sains pada abad kedua belas. Sosok yang paling berpengaruh adalah seorang filsuf Abū Ḥāmid al-Ghazālī, yang berargumen dalam “Kerancuan Para Filsuf” menentang gagasan hukum alam…setelah al-Ghazālī, tidak ada lagi sains yang layak diperhitungkan di negeri-negeri Islām.)
Pandangan semacam ini banyak diikuti bukan hanya oleh orientalis namun juga kalangan saintis Muslim yang mungkin tidak memiliki akses untuk membaca langsung pandangan-pandangan Imām al-Ghazālī. Tentu saja pendapat seperti ini tidak berlandaskan argumen yang kukuh dan data yang lengkap. George Saliba seorang sejarawan terkemuka peneliti peradaban Islām bahkan menantang mereka yang bersikukuh dengan tesis tersebut untuk menjawab pertanyaan: jika benar Imām al-Ghazālī menyebabkan kemunduran sains bagaimana menjelaskan tetap munculnya hampir puluhan saintis dalam setiap disiplin ilmu pasca al-Ghazālī? Bahkan dalam beberapa segi lebih hebat dari sebelumnya.[3] Ini mengindikasikan bahwa islamisasi dalam bentuk pembersihan anasir filsafat yang merusak dan konseptualisasi keilmuan yang dilakukan Imām al-Ghazālī bukanlah faktor yang menyebabkan kemunduran sains di dunia Islām.
Ada banyak faktor yang saling memengaruhi kemunduran sains di dunia Islām saat itu seperti invasi militer, penjajahan, perpecahan politik, ekonomi, dan lain-lain. Misalnya bukti yang diajukan Saliba bahwa sekitar abad 16 faktor-faktor luar berperan besar dalam melemahkan kemajuan sains di dunia Islām seperti perpecahan politik di kalangan mereka sendiri, peperangan dengan dunia Barat, kolonialisasi Barat untuk mencari sumber-sumber kekayaan baru di negeri-negeri Muslim dan lain-lain. Akibatnya institusi-institusi pendidikan yang berperan dalam pengembangan sains menyusut dan bergantung sepenuhnya pada penemuan-penemuan saintifik asing.[ Asadullāh ʿAlī al-Andalusi, The Rise And Decline of Scientific Productivity In The Muslim World: A Preliminary Analysis]
Konsep ilmu Imām al-Ghazali
Jika para penuduh ini mau sedikit membuka langsung pandangan-pandangan Imām al-Ghazali dalam berbagai karyanya, akan jelas bagaimana sebenarnya posisi dan sikap beliau pada ilmu-ilmu rasional seperti sains, kedokteran, logika dan matematika. Imām al-Ghazālī raḥimahuʾLlāh dalam Iḥyā‘ mengklasifikasikan ilmu farḍ kifāyah (ilmu yang wajib dikuasai secara mencukupi oleh satu komunitas) pada sharʿiyyah dan ghayr sharʿiyyah.
Ilmu-ilmu farḍ kifāyah yang bersumber dari para nabi yang disebut oleh Imām al-Ghazālī sebagai ilmu sharʿiyyah yaitu yang menyandarkan rujukannya pada al-Qur‘ān, sunnah, ijmaʿ, dll; dan kedua, ilmu ghayr sharʿiyyah–yang sebagaimana dinyatakan beliau sendiri untuk tidak usah heran dengan pernyataan ini– adalah seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung, ilmu pengetahuan alam dan lain-lain.
Ilmu ghayr sharʿiyyah pun diurutkan menurut kepentingannya dalam masyarakat, dan sangat bergantung pada keperluan suatu masyarakat. Contoh ilmu ghayr sharʿiyyah menurutnya yang penting adalah seperti kedokteran, matematika, astronomi, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain.[Abū Ḥamīd al-Ghazālī, Iḥyāʾ ʿUlumiddīn (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), juz 1, hlm 17.]
Jadi jelaslah bahwa Imām al-Ghazali tidak menolak sains dan matematika sebagai disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh umat Islām.
Lebih jauh Imām al-Ghazālī bukan hanya menerima ilmu rasional seperti matematika, ia sendiri menulis beberapa karya logika seperti Miʿyār al-ʿIlm dan Miḥakk al-Naẓar, bahkan Imām al-Ghazālī adalah tergolong sarjana pertama yang menerima logika dan menggunakannya dalam ilmu uṣūl al-fiqh. Bahkan dalam Miʿyār al-ʿIlm, ia sendiri mengulas prinsip-prinsip ilmu geometri Euclid seperti definisi titik, garis, bidang dan luas permukaan benda.[ Lihat: Abū Ḥamīd al-Ghazālī (ed. Sulayman Dunya), Mi’yar al-‘Ilm, (Kairo: Dāru’l Maʿārif 1961), hlm. 307-308]* (BERSAMBUNG)
Penulis peneliti PIMPIN Bandung, alumnus Jurusan Fisika ITB, mahasiswa program PhD di Centre for Advanced Studies on Islām, Science and Civilisation (CASIS)-UTM