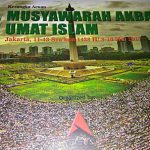PERBEDAAN adalah keniscayaan. Namun, ada dua perbedaan yang harus dipahami dalam fikih Islam agar tidak salah dalam menyikapinya. Pertama, tadhâdh [perbedaan kontradiktif mengenai sesuatu yang sudah final dalam Islam seperti akidah dan ibadah mahdhah]. Kedua, tanawwu’ [perbedaan cabang, multi tafsir misalnya dalam hukum fikih yang teknis] (Yasir Husain Barhami, Fiqhu al-Khilâf, 12).
Dari kedua perbedaan tersebut, memang perbedaan tadhâdh (kontradiktif), tidak ada kompromi sedikit pun. Namun, pada wilayah perbedaan tanawwu’ (cabang, multi tafsir), umat Islam diharuskan berlapang dada dan toleransi. Ironisnya, masih banyak dari kalangan umat Islam yang belum arif dalam menyikapi perbedaan furu’iyah ini. Pada tingkat yang lebih ekstrim, di antara mereka ada yang saling membid’ahkan, merasa pihaknya sendiri yang paling benar, bahkan mengkafirkan orang yang berseberangan. Hal ini tentu bisa menyulut permusuhan dan mengoyak persatuan.
Konflik semacam ini tidak akan terjadi jika perbedaan furu’iyah ini disikapi dengan kearifan. Ada banyak contoh sejak zaman Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam yang bisa dijadikan teladan untuk menyikapi perbedaan demikian secara arif.
Semasa nabi hidup misalnya –tanpa bermaksud membatasi- ada 3 peristiwa yang bisa diangkat dalam menyikapi perbedaan furu’iyah secara arif.
Pertama, pasca Perang Khandak (5H), Rasulullah menginstruksikan sahabatnya, “Jangan shalat Ashar, melainkan di Bani Quraidzah!” (HR. Bukhari, Muslim).
Para sahabat tebelah dua dalam memahami instruksi nabi tersebut. Ada yang memahaminya secara tekstual, sehingga tidak shalat Ashar kecuali sudah sampai lokasi. Ada juga yang memahaminya secara kontekstual, sehingga memahaminya segera melaksanakan shalat tepat waktu. Menariknya, saat kedua kelompok ini mengadu kepada nabi, beliau sikapi dengan arif dengan tidak mencela keduanya.
Kedua, Abu Qatadah menceritakan, suatu saat Nabi bertanya kepada Abu Bakar, “Kapan kamu menunaikan witir?” Abu Bakar menjawab bahwa ia menunaikan witir di awal malam. Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada Umar. Beliau pun menjawab, “Aku menunaikan witir di akhir malam.” (HR. Abu Daud).
Sikap nabi ketika melihat perbedaan antara keduanya bukan dengan menyalahkan, tapi justru menyebutkan sisi positif masing-masing. Abu Bakar, dipuji nabi sebagai seorang yang teguh. Sedangkan Umar bin Khathab, disanjung sebagai orang yang kuat.
Ketiga, ‘Amr bin ‘Âsh bercerita, saat dirinya diutus dalam peperangan Dzâtus Salâsil, pada suatu malam yang sangat dingin, ia bermimpi hingga junub. Saat bangun pagi-pagi, beliau mengganti perintah mandi junub dengan tayamum. Pada saat itu juga, ia menjadi imam shalat Shubuh. Kejadian ini diadukan langsung kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam oleh sahabat yang tak sependapat. Ketika diklarifikasi nabi, Amru bin Ash berargumen dengan Surah An-Nisa [4]: 29, yang intinya tak boleh membunuh diri karena Allah Maha Penyayang (HR. Abu Daud, Ahmad). Setelah mendengar argumentasinya, Rasulullah pun tertawa tanpa mengatakan sesuatu apapun –sebagai taqrir (pengakuan)- bahwa apa yang dilakukan Amru ini bukan perbuatan yang salah.
Jamaluddin al-Qasimi dalam buku Qawâ’idu al-Tahdîts min Funûni Mushthalah al-Hadîts (371) menuturkan bahwa perbedaan di kalangan sahabat dan tabi’in dalam masalah furu’iyah sudah biasa. Di antara mereka ada yang membaca basmalah dalam shalat, ada pula yang tidak; ada yang mengeraskan basmalah, ada juga yang tidak’; ada yang qunut pada waktu shalat Shubuh, ada pula yang tidak melakukannya; ada yang berwudhu setelah berbekam, ada pula yang tidak berwudu. Uniknya, meski terjadi perbedaan, mereka tetap tidak menghalangi mereka shalat secara berjama’ah.
Dikisahkan, Abu Hanifah dan penganut madzhab Syafi’i serta yang lainnya shalat di belakang imam-imam Madinah yang bermadzhab Maliki (meskipun mereka tidak membaca basmallah baik secara lirih maupun keras). Harun Ar-Rasyid pernah menjadi Imam shalat –padahal ia telah berbekam- waktu itu Abu Yusuf menjadi makmumnya dan tak mengulangi shalatnya.
Dalam kisah lain disebutkan bahwa pernah Abu Yusuf dan Muhammad ketika bertakbir dalam Idul Fithri keduanya bertakbir seperti pendapat Ibnu Abbas, ini karena Harun Ar-Rasyid suka terhadap takbir kakeknya (Ibnu Abbas). Lebih dari itu, pernah Imam Syafi’i shalat Shubuh tanpa qunut dekat kuburan Abu Hanifah sebagai wujud adab beliau terhadap Abu Hanifah.
Ada kisah lain yang cukup menarik. Seusai melaksanakan shalat Jum’at, Imam Abu Yusuf diingatkan jama’ah bahwa di sumur dekat kamar mandi (yang beliau pakai mandi sebelum Jum’at), terdapat bangkai tikus. Mendengar ini beliau berkomentar, “Kalau begitu, kita mengambil pendapat saudara kita Ahli Madinah, “Jika air mencapai dua qulla, maka kotor [najis].” (HR. Ahmad).
Lihat bagaimana mereka menyikapi perbedaan furu’iyah, tidak ada yang saling mencela bahkan sinis terhadap pendapat yang berseberangan.
Di Indonesia sendiri, sejak sebelum kemerdekaan perbedaan furu’iyah memang menimbulkan selalu ketegangan. Terbelahlah umat Islam pada waktu itu dengan istilah kaum tradisionalis dan kaum modernis. Perbedaan tersebut dampaknya masih berpengaruh hingga saat ini. Padahal, kalau diamati secara cermat, perbedaan mereka kebanyakan pada masalah furu’iyah bukan prinsipil.
Melihat fenomena demikian, Tjokroaminoto dan Agus Salim menginisiasi Kongres Islam pertama di Cirebon 1922 untuk merajut Ukhuwah Islamiah dan tidak disibukkan dengan Urusan Khilafiyah (Aji Dedi Mulawarman, Jang Oetama Jejak dan Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, 187).
Baca: Salah Menyikapi yang Furu’ Penyebab Rusaknya Persatuan
Contoh lain dari Pahlawan Muslim Indonesia dalam menyikapi perbedaan furu’iyah ialah seperti yang dipraktikkan Buya Hamka. Dalam buku Mengenang 100 tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), disebutkan bahwa Hamka adalah sosok yang mengutamakan silaturahim ketimbang meributkan perbedaan tak prinsip. Ada beberapa contoh yang menunjukkan toleransi hamka dalam menyikapi perbedaan furu’iyah.
Pertama, ketika KH Abdullah Syafi’i menunaikan shalat Jum’at di Masjid Al-Azhar. Waktu itu, Buya Hamka sudah terjadwal sebagai khatib. Melihat kedatangan KH Abdullah Syafi’i, seketika Buya “memaksa” beliau menggantikan dirinya. Buya juga meminta adzan dikumandangkan dua kalisebagaimana tradisi Nahdhiyin yang dipegang Syafi’i.
Kedua, sejak dibukanya Masjid Al-Azhar, Buya sudah mengedepankan tasamuh (toleransi). Waktu itu, Hamka ikut hadir dan duduk bersebelahan dengan tokoh NU KH Idham Chalid. Hamka tak segan untuk ikut berdiri dan membacakan asrakai pada Maulud Diba. (Shobahussurur, 2008).
Ketiga, pada saat Hamka dan Idham Chalid berada dalam satu pesawat menuju Mekah. Masing-masing bergantian menjadi imam shalat Shubuh. Saat Idham menjadi imam, beliau tidak membaca qunut karena ada Hamka di belakangnya. Demikian juga Hamka, saat menjadi imam, beliau membaca qunut karena ada Idham Chalid di belakangnya. (Abdillah Mubarak Nurin, Islam Agama Kasih Sayang, 86).
Ada pula contoh dari tokoh nasional yang masih hidup, yaitu: Amin Rais. Tokoh yang pernah menjabat menjadi Ketua Umum Muhammadiyah ke-12 (1995-2000) ini sangat arif dalam menyikapi perbedaan furû’iyyah.
Baca: Dialog Ukhuwah NU, Muhammadiyah dan Persis Mesir: Tak Perlu Perbesar Furu’
Zaim Uchrowi dalam buku Mohammad Amien Rais: Memimpin dengan Nurani menceritakan bahwa meski lahir dari kultur Muhammadiyah, Amin dikatakan sebagai sosok yang fasih dalam membaca qunut. Ia selalu membaca doa qunut saat menjadi umam penganut Islam ‘kultural’ saat shalat Subuh (2004: 146). Bahkan, masih menurut buku yang sama, beberapa kali saat berkunjung ke pesantren tradisional, beliau diminta menjadi imam shalat Shubuh. Jika kebiasaan di tempat itu memakai doa qunut, maka belia pun juga membaca doa qunut (2004: 85).
Dari beberapa contoh di atas, perbedaan furû’iyah memang harus disikapi secara arif. Perbedaan demikian seyogianya tidak merusak persatuan. Justru umat Islam saling berlapang dada, toleran dan menyikapinya dengan kearifan. Hal ini persis yang dicontohkan nabi, para sahabat, tabiin, ulama hingga tokoh Islam negeri ini.
Sebagai penutup, pernyataan Ibnu Najim (ulama bermadzab Hanafi) berikut bisa dicamkan baik-baik dalam menyikapi perbedaan furû’iyah secara arif, “Jika kita ditanya tentang madzhab kita oleh orang-orang yang berbeda dengan kita dalam masalah furu’ (cabang fikih), kita wajib menjawab bahwa madzhab kita shawab (benar) tapi ada kemungkinan salah, sedangkan madzhab yang menyelisihi kita bisa jadi khatha` (salah) tapi bisa jadi benar.” (al-Asybâh wa al-Nadhâir, Ibnu Najim 330). Wallâhu a’lam.*/Mahmud Budi Setiawan