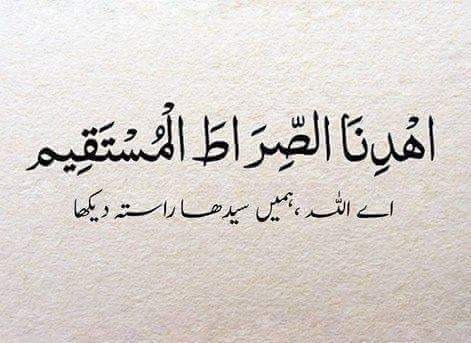HUBUNGAN antara ulama dan umara (penguasa) dalam sejarah Islam memang bervariatif. Sebagai contoh, bisa dilihat dari Imam Empat Madzhab yang masyhur: Hanafi, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal Rahimahumullah. Imam Hanafi, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai ulama yang menjaga jarak dengan penguasa, bahkan pernah mendapatkan perlakuan represif dari penguasa akibat tidak mau menuruti kemaunnya.
Sementara Imam Malik rahimahullah, dikenal memiliki kedekatan dengan penguasa bahkan sempat menerima hadiah dari mereka. Hanya saja, yang menjadi catatan penting, Imam Pengasas Madzhab Maliki ini bukanlah ulama penjilat. Interaksi beliau dengan penguasa tetap pada koridor syariat yang jelas, bukan karena ingin mengeruk harta. Beliau juga bersikap obyektif dan konsisten terhadap kebenaran yang diyakininya sehingga tidak menjadi jongos penguasa.
Meski demikian, bukan berarti ulama yang dikenal dengan buku ‘Al-Muwaththa’-nya ini, tak pernah kontra dengan penguasa. Wahid Abdussalam Bâli dalam buku “Ulamâ wa Umarâ`” (1410: 181) menceritakan konflik Imam Malik dengan penguasa.
Alkisah, Ja’far bin Sulaiman –sepupu Abu Ja’far Al-Manshur- berniat buruk kepada Imam Malik. Dituduhkan rumor bahwa beliau tidak mengakui kepemimpinan Ja’far Al-Manshur. Mendengar berita itu, kuping Abu Ja’far panas, lalu memerintahkan kepada tentaranya untuk mencabuk beliau. Sungguh ironis, cambukan ini sampai membuat tulang pundak beliau lepas. Imam Ibnu Jauzi menyebut dalam buku “Syudzûr al-‘Uqûd” bahwa beliau dicambuk sebanyak tujuh puluh kali akibat mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan kepentingan penguasa di zamannya.
Dari kedua posisi tadi –baik yang sedang memilih menjadi oposisi atau bersama mendukung penguasa– para ulama yang empat itu tetap tidak kehilangan harga diri dan marwah. Izzah mereka di hadapan penguasa begitu tinggi. Saat dekat tak kehilangan martabat dan tak mau menjilat; saat jauh mereka tetap teguh pendirian menjadi suluh, menjaga marwah dan menjadi yang terdepan dalam hal mengingatkan penguasa.
Para nabi pun –bila dilihat berdasarkan paradigma al-Qur`an—di antara mereka ada yang sedang bekerjasama dengan penguasa, sebagaimana Nabi Yusuf dengan Aziz; ada yang oposisi dengan penguasa, seperti Musa dan Fir’aun dan ada yang murni menjadi nabi sekaligus penguasa, seperti halnya Nabi Sulaiman ‘alaihimussalam.
Menariknya, di mana pun posisi mereka, marwah sebagai seorang nabi tetap terjaga dengan baik. Mereka tidak akan mengorbankan marwah kenabian hanya gara-gara perkara dunia yang sangat kecil. Apa pun posisinya, mereka tetap memberi pencerahan, menjadi suluh dan lentera bagi sekitarnya. Seharusnya, ulama yang menjadi pewaris para Nabi harus terdepan dalam meneladaninya.
Berkenaan dengan hal ini, dalam kitab “Ghurar al-Khaṣā`iṣ al-Wāḍihah wa ‘Uraru al-Naqā`iḍ al-Fāḍihah” (243, 244), Abu Ishaq Jamaluddin al-Wathwath memberikan contoh menarik bagaimana marwah ulama di hadapan penguasa. Kisah antara Hisyam bin Abdul Malik dengan ‘Atha` bin Abi Rabbah bisa dikemukakan di sini.
Suatu ketika ‘Utsman bin ‘Atha’ al-Khurasani mengisahkan. Saat dirinya bersama sang ayah hendak pergi menemui Hisyam bin Abdul Malik, keduanya bertemu dengan syeikh yang menunggangi keledai hitam, bajunya lusuh, jubahnya kotor dan penutup kepala yang tak sedap dipandang mata. Utsman pun saat melihatnya langsung tertawa. Ia langsung diingatkan ayahnya, “Diamlah! Ini adalah penghulu para ahli fiqih di wilayah Hijaz, Atha’ bin Abi Rabbah!”
Setelah bertemu, ayah Utsman berpelukan dengan Atha`. Kemudian, bersama-sama menuju istana Hisyam bin Malik. Tak perlu menunggu lama, keduanya segara diizinkan masuk. Mengenai cerita keduanya dalam istana Hisyam, Utsman tidak tahu sama sekali. Hanya saja, ia mendapat cerita itu dari ayahnya.
Saat masuk istana, Atha’ disambut dengan sangat hangat hingga duduk bersama Hisyam di singgasana. Ayah Utsman bisa masuk dengan cepat pun karena sosok Atha’. Mereka berdua berbincang, dan para pembesar berikut orang yang hadir dalam istana waktu itu diam. Tak ada yang berani bersuara kala itu.
Uniknya, semua permintaan ‘Atha bin Abi Rabbah –terkait kepentingan umat– tidak ada yang ditampik. Bahkan, Hisyam segera menginstruksikan bawahannya agar secepat mungkin melaksanakannya. Pada momen ini ada pemandangan luar biasa, marwah ulama sekaliber Atha’ begitu terjaga di hadapan penguasa, izzahnya begitu tinggi, sampai-sampai duduk bersama di singgasananya.
Tak cukup sampai di situ, pada kesempatan itu, Atha’ sebagai ulama juga tak melupakan tugasnya untuk mengingatkan penguasa. Beliau memberi nasihat kepada Hisyam, “Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya kamu diciptakan sendirian, mati sendirian, dibangkitkan sendirian dan dihisab di akhirat sendirian. Saat itu, tak ada seorang pun yang menemanimu!” Mendengar nasihat yang berdiksi kuat dan menyentuh itu, Hisyam tersungkur dan tak kuasa menahan air mata.
Setelah urusan selesai, Atha’ undur diri. Rupanya, di belakangnya ada pegawai Hisyam yang mengikuti yang membawa kantong berisi uang banyak. Ketika diberikan kepada Atha’, ulama karismatik ini dengan ringan menjawab, “Aku tidak meminta upah pada kalian, biarlah Allah saja yang memberi upah kepadaku.” Lebih dari itu, menurut cerita ayah Utsman, pada pertemuan itu Atha’ tidak meneguk air sedikit pun yang dihidangkan.
Di Indonesia, ulama seperti HAMKA juga bisa dijadikan contoh dalam hal menjaga marwah di hadapan penguasa. Dalam buku “Buya Hamka: Pribadi dan Martabat” (2016) karya Rusydi Hamka misalnya, ditulis bahwa pernah Hamka oleh Soeharto diundang untuk berkhutbah di istana negara. Dalam kesempatan itu, beliau tetap bisa menjaga marwah dengan baik. Saat berkhutbah pun, tak ada narasi yang berisi penjilatan kepada penguasa. Demikianlah seharusnya marwah ulama di hadapan penguasa.*/Mahmud Budi Setiawan