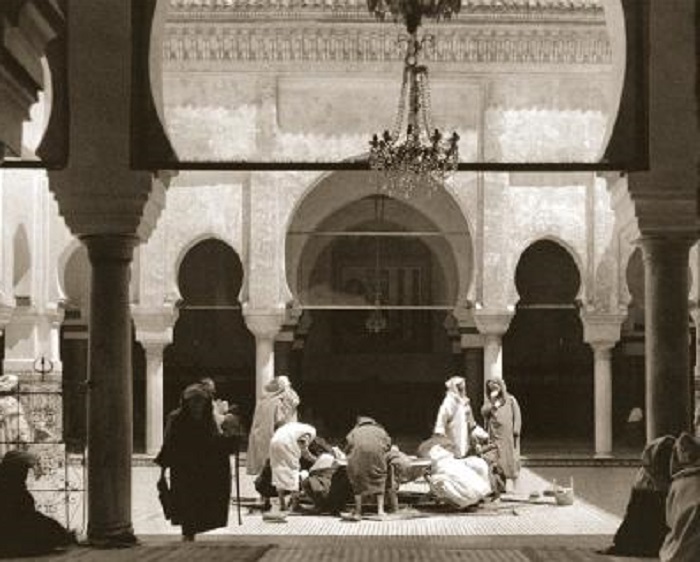Oleh: Alwi Alatas
SEJAK awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menerapkan sebuah kebijakan baru, yaitu Politik Etis, setelah pada dua periode sebelumnya memberlakukan kebijakan Tanam Paksa (1830-1870) dan kebijakan Liberal (1870-1900). Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dipandang terlalu eksploitatif dan telah menyebabkan merosotnya ekonomi pribumi. Oleh para pengkritiknya, pemerintah kolonial dianggap memiliki ‘hutang budi’ dan karenanya perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan masyarakat pribumi (Husken 1994: 217).
Maka pada tahun 1901, bersamaan dengan pidato Ratu Wilhelmina di depan parlemen Belanda, dimulailah kebijakan Politik Etis di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki keadaan masyarakat pribumi pada umumnya. Bagaimanapun, cukup menarik untuk dicermati betapa di dalam pidatonya Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa ‘sebagai kekuatan Kristen, Belanda berkewajiban, di kepulauan Hindia Timur, untuk mengatur secara lebih baik posisi hukum kaum pribumi Kristen, untuk memberikan dukungan, secara tegas, kepada misi Kristen, dan untuk mengilhami seluruh perilaku pemerintah dalam kesadaran bahwa Belanda memiliki kewajiban moral yang harus dipenuhi, sehubungan dengan orang-orang yang berada di wilayah-wilayah tersebut’ (Schmutzer 1977: 14). Dalam pidatonya itu sang Ratu Belanda telah menyisipkan nilai-nilai moral Kristen sebagai tenaga pendorong bagi dijalankannya kebijakan baru ini.
Kebijakan yang berlangsung pada fase terakhir pemerintahan kolonial ini terkenal dengan slogan ‘edukasi, irigrasi, dan emigrasi.’ Sekolah-sekolah dibuka untuk memberi peluang karir yang lebih luas bagi kaum pribumi. Irigasi dimajukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian penduduk pribumi. Emigrasi dijalankan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan penduduk Jawa dan luar Jawa serta untuk menyebarluaskan sistem penanaman padi yang lebih baik yang sudah lebih dulu berkembang di Jawa (Moon 2007: 20).
Namun demikian, kebijakan politik etis tidak hanya terbatas pada ketiga aspek di atas, tetapi juga pada bidang-bidang lainnya, seperti pada upaya mengembangkan industri pribumi dan membuka akses perbankan bagi masyarakat pribumi hingga ke masyarakat pedesaan (Van der Kroef 1994).
Bersamaan dengan dilancarkannya kebijakan ini, pemerintah kolonial juga membentuk sebuah panitia untuk menyelidiki kemunduran kesejahteraan masyarakat pribumi (Mindere Welvaarts Onderzoek).
Panitia ini dibentuk pertama kali pada tahun 1902, dipimpin oleh residen Pekalongan, H.E. Steinmetz, dan mulai melakukan penyelidikan pada tahun 1904 dengan cara menyebarkan sejumlah besar pertanyaan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Penelitian ini baru selesai sekitar sepuluh tahun kemudian dan menghasilkan laporan sebanyak lebih dari 30 jilid.
Laporan ini memberikan segudang data yang mendetail tentang kehidupan dan perekonomian masyarakat pribumi, tetapi sayangnya tidak berujung pada sebuah kesimpulan yang jelas tentang sebab-sebab kemerosotan ekonomi masyarakat. C.J. Hasselman, yang bertugas menulis bagian kesimpulan penelitian ini, menyebut laporan-laporan tersebut sebagai ‘seperiuk dugaan’ (a stewpot of surmise) (Furnivall 1944: 393-394).
Lebih disayangkan lagi, laporan ini cenderung menganggap mentalitas pribumi sebagai penyebab utama di balik kemerosotan kualitas kehidupan mereka. Laporan tersebut ‘tidak menunjuk kepada sistem kolonial, tetapi pada gaya hidup pribumi sebagai penyebab dari kurang sejahteranya kehidupan mereka’ (Hellwig and Tagliacozzo 2009: 260-261).
Seorang akademisi lainnya menyimpulkan bahwa, ‘laporan akhir tersebut tidak terlalu menjadi survei terhadap kondisi ekonomi yang ada, tetapi lebih sebagai upaya menafsirkan karakteristik etnis pribumi dalam konteks dorongan-dorongan ekonomi dan psikologi Barat’ (Van der Kroef 1994: 259-260).
Politik Etis secara umum memberikan peningkatan dan perbaikan pada kehidupan masyarakat pribumi. Pada periode ini, semakin banyak masyarakat pribumi yang dapat mengakses pendidikan modern dan pada gilirannya tumbuh menjadi kelompok elit baru yang berperan sebagai pemimpin Indonesia di akhir masa kolonial dan di masa kemerdekaan. Pertanian dan perkebunan penduduk di berbagai daerah menjadi lebih baik dengan semakin tersebar luasnya teknik pengairan yang lebih maju. Industri dan perdagangan pribumi juga tumbuh lebih baik pada periode ini.
Tidak perlu diragukan bahwa sebagian pegawai kolonial Belanda bekerja dengan tulus dan sungguh-sungguh untuk memajukan kehidupan masyarakat pribumi. Namun demikian, politik etis juga memiliki banyak kekurangan dan menimbulkan beberapa persoalan bagi masyarakat pribumi.
Di balik wajah etisnya, kebijakan ini tetaplah bersifat kolonial, yaitu kebijakan yang menempatkan sebagai penguasa dan penduduk pribumi sebagai bangsa yang dikuasai.
Melalui sekolah-sekolahnya, pemerintah kolonial tidak kehilangan maksudnya dalam mempertahankan hegemoni atas penduduk pribumi melalui penanaman nilai-nilai Barat yang sekular. Pendidikan yang dicanangkan pemerintah kolonial juga telah menciptakan jarak yang sangat besar antara kaum terdidik baru, khususnya dari kalangan priyayi, dengan nilai-nilai dan pendidikan Islam yang selama ini merupakan sumber rujukan utama masyarakat Nusantara.
Pendidikan sekular membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang diidamkan pemerintah kolonial, yaitu masyarakat yang terasing dari Islam (Woodward 2011: 53-54). Sebagaimana telah diketahui, hal ini pada gilirannya memicu percabangan serta konfrontasi ideologi dan pergerakan di tengah masyarakat Indonesia, antara kelompok yang nasionalis-sekular versus Islam.
Dalam upaya memajukan ekonomi pribumi, pemerintah kolonial cenderung bersikap tanggung-tanggung. Dalam bidang industri, pemerintah hanya memberikan dorongan bagi kaum pribumi pada aspek-aspek yang tidak dimasuki oleh masyarakat Eropa. Dengan kata lain, walaupun tampaknya mustahil, pemerintah sejak awal telah menutup pintu bagi kemungkinan terjadinya kompetisi antara kaum pribumi dan kaum industrialis Eropa (Van der Kroef 1994: 285).
Di samping itu, pemerintah kolonial hanya berusaha memajukan sektor non-pertanian di tengah masyarakat pribumi sejauh hal itu tidak mengganggu kehidupan pertanian yang telah menjadi kebiasaan penduduk pribumi (Van Eeghen 1937: 130 & 133).
Artinya, pemerintah kolonial hanya berniat mengupayakan perubahan yang terbatas di kalangan penduduk pribumi, kebijakan yang mungkin akan dibaca oleh sebagian orang sebagai tindakan setengah hati. Pada akhirnya agak sulit untuk menilai apakah dengan mengambil langkah tersebut pemerintah kolonial telah memberi perlindungan terhadap adat dan kebiasaan masyarakat pribumi seperti yang dikatakannya, atau sebenarnya ia hanya ingin melindungi dan melanjutkan hegemoni kekuasaannya semata.
Sikap yang tanggung-tanggung tentunya akan memberikan hasil yang tanggung juga. Dalam hal pertanian, pemerintah kolonial tidak mentransfer ilmu pertanian modern secara lengkap kepada penduduk, tetapi hanya memberikan teknik-teknik yang sesuai dengan kebiasaan lama penduduk. Dampaknya cukup signifikan. Walaupun ada perbaikan dalam pertanian masyarakat pribumi, pada akhir jaman kolonial masih terdapat kesenjangan yang besar antara produktivitas pertanian dan perkebunan yang dimiliki pribumi dibandingkan dengan yang dimiliki orang Eropa (Van der Kroef 1994: 262-263).
Berbagai celah pada kebijakan politik etis, sebagaimana yang dijelaskan di atas, telah menimbulkan kritik terhadap pemerintah kolonial. Kebijakan yang terdengar indah dan penuh moralitas sebenarnya tidak se etis yang dibayangkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial mungkin sedikit banyak telah berusaha membalas budi atas eksploitasi yang telah dilakukannya, tetapi pada saat yang sama juga terus mempertahankan hegemoninya dalam menjajah dan mengeruk keuntungan dari bangsa yang dijajah. Sebagian pengkritik, memberikan sebuah definisi yang menarik tentang politik etis, bahwa ia sebenarnya merupakan ‘Kapitalisme yang berbaju Kristen’ (Furnivall 1944: 392).
Mungkin ini memang kalimat yang sesuai untuk menggambarkan politik etis, karena kebijakan ini mengekspresikan semangat penuh moralitas pemerintah Belanda, ‘sebagai sebuah kekuatan Kristen,’ seperti dikatakan Ratu Wilhelmina’, untuk membantu bangsa yang dijajah, tetapi jiwa dan substansi tindakannya tetaplah kapitalis dan kolonialis.*/Singapura, 14 Sha’ban 1433/ 4 Juli 2012
Penulis adalah penulis buku “Nuruddin Zanki dan Perang Salib” kolumnis hidayatullah.com, kini sedang mengambil program doktoral bidang sejarah di Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia
Daftar Pustaka
Furnivall, J.S. Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge: Cambridge University Press. 1944.
Helwig, Tineke & Eric Tagliacozzo (eds.). The Indonesia Reader: History, Culture, Politics. Durham: Duke University Press. 2009.
Husken, Frans. ‘Declining Welfare in Java: Government and private inquiries, 1903-1914,’ in Robert Cribb (ed.). The Late Colonial State in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942. pp. 213-227. Leiden: KITLV Press. 1994.
Moon, Suzanne. Technology and Ethical Idealism: A History of Development in the Netherlands East Indies. Leiden: CNWS Publications. 2007.
Schmutzer, Eduard J.M. Dutch colonial policy and the search for identity in Indonesia 1920-1931. Leiden: E.J. Brill. 1977.
Van der Kroef, Justus Maria. Dutch Colonial Policy in Indonesia, 1900-1941, submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philisophy in the Faculty of Political Science, Columbia University, Michigan: UMI Dissertation Services, 1994.
Van Eeghen, Geertrui M. “The Beginning of Industrialization in Netherlands India,” in Far Eastern Survey, Vol. 6, No. 12. Pp. 129-133. 1937.
Woodward, Mark. Java, Indonesia and Islam. Dordrecht: Springer. 2011.