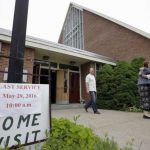Oleh: Faizal Adi Surya
ISLAM pada masa pemerintah Kolonial selalu menjadi penghalang, yang selalu menyusahkan kuku kolonial leluasa menancapkan kekuasaan di Bumi Nusantara. Pemberontakan yang dipimpin para ulama dan haji, selalu diwaspadai oleh para gubernur jenderal, hingga kemudian dipikirkan cara terbaik untuk meredam semangat perlawanan Umat Islam.
Pendirian Kantoor voor Inlandasche Zaken atau kantor urusan nasehat untuk masalah Pribumi pada 1899, menandai keawaspadaan Total pemerintah Kolonial terhadap gerakan Islam. Sebab mayoritas Pribumi adalah beragama Islam, maka otomatis, Islam menjadi fokus garapan kantor ini.
Nama Snouck Hurgronje cukup dikenal sebagai kepala komisaris kantor tersebut, selain nama besarnya dalam studi Islam di Hindia Belanda. Rekam Jejak Snouck cukup istimewa, ia berhasil membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda meningkatkan kewaspadaan kepada Politik Ummat Islam. Snouck meyakinkan Pemerintah Belanda agar mereduksi Islam sekedar berkembang menjadi agama ibadah saja. Politik Islam yang menjadi inspirasi perlawanan terhadap pemerintah Kolonial, sedikit banyak dikurangi.
‘Kejeniusan’ Snocuk tidak lepas dari kenyataan dirinya adalah seorang Muslim, dengan menyamar sebagai Abdul Gaffar, Snouck telah mempelajarai Islam di Mekkah. Dan yang tidak kalah penting, Snocuk didampingi seorang ulama, yaitu Sayyid Utsman. Rekam jejak Sayyid Utsman, terbilang kontroversi pada zamanya. Disaat para Ulama lain, gigih menentang pemerintah Kolonial. Ia justru ada dalam kubu seberang, tak jarang Sayyid Utsman menjadi santapan empuk kritik ulama saat itu, ia dituduh menjual agama kepada Pemerintah Kolonial. hal ditambah kenyataan bahwa Sayyid Utsman adalah seorang mufti di wilayah Batavia.
Namun Sayyid Utsman juga tidak sedikit mendapat pujian, terutama karena keuletan Sayyid Ustsman dalam menentang Bid’ah yang berlindung di balik baju tradisi dan budaya. Oleh sebab itu, tidak sedikit yang menyebutnya sebagai “Ulama Pembaharu”.
Sekilas Sayyid Utsman
Sayyid Utsman dilahirkan di Pekojan, Betawi, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 (1822 M). Ayahnya, Abdullah, dan kakeknya ‘Aqil, dilahirkan di Makkah, tetapi kakek ayahnya, Umar, dilahirkan di Hadramaut tepatnya di desa Qârah Âl Syaikh. Mengenai kakek Sayyid Utsman, ‘Aqil, informasi dari Snouck hanya menjelaskanbahwa dia adalah seorang yang cukup terhormat di Makkah. Jabatannya sebagai syaikh al-sâdah (pemimpin para sayyid) disandangnya selama 50 tahun. Ia kemudian meninggal dalam penjara Syarif Akbar. Sedangkan ibu Sayyid Utsman bernamaAminah adalah putri dari Syekh Abdurrahman al-Mishri, seorang ulama keturunanMesir yang sudah ada di Indonesia.
Sayyid Utsman pun diasuh oleh kakeknya, Abdurrahman al- Mishri. Melalui kakeknya,pula Sayyid Utsman mendapatkan pengajaran membaca al-Qur`an, akhlak, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, nahwu sharaf, tafsir-hadis dan ilmu falak.Sayyid Utsman berangkat ke Makkah ketika usianya 18 tahun. Ia berada di sanadalam rentang waktu antara tahun 1840 sampai 1847. Selain untuk menunaikan ibadahhaji, perjalanan ini juga dimaksudkan untuk mengunjungi ayahnya.
Ia melanjutkan Setelah tujuh tahun di Makkah, Sayyid Utsman melanjutkan kembaliperjalanannya ke Hadramaut pada tahun 1264 (1848) dan mengambil pengetahuan kepada para ulama Hadramaut. Hasrat Sayyid yang masih lapar akan ilmu, membuat ia melancong ke Madinah, Mesir, Tunisia, sampai ke Istanbul. Pada tahun 1862 ia pulang ke Indonesia melalu Singapura. Ia menuju tanah kelahiranya, di Batavia.
Malang melintang mencari Ilmu, kedatangan Sayyid Utsman cukup disegani para Ulama kala itu, meskipun Sayyid Utsman meanmpilkan sikap yang merendah. Syekh Abdul Gani Bima, yang sudah sepuh, meminta ia mengganti mengajar di masjid pekojan. Berkat ketinggian Ilmunya pula, ia diangkat menjadi Mufti di tanah Betawi.
Sayyid dan Snouck
Hubungan Sayyid Utsman dengan Pemerintah Kolonial sudah terbentuk jauh sebelum Snouck datang ke Indonesia, dan menjabat sebagai kepala kantor urusan pribumi (Kantoor voor Inlandasche Zaken). Sayyid Utsman diangkat menjadi penasehat urusan Arab pada 1891.
Alasan pengangkatan Sayyid Utsman tidak lepas dari kondisi masyarakat arab di Indonesia saat itu. Awalnya, masyarakat Arab ayng digambarkan sebagai masyarakat yang mencintai baca tulis, berfokus pada urusan perdagangan, sementara dalam urusan sosial Politik, masyarakat Arab tidak memiliki rasa simpatik yang tinggi.* (BERSAMBUNG)
Penulis adalah pegiat KAMMI Kultural Solo