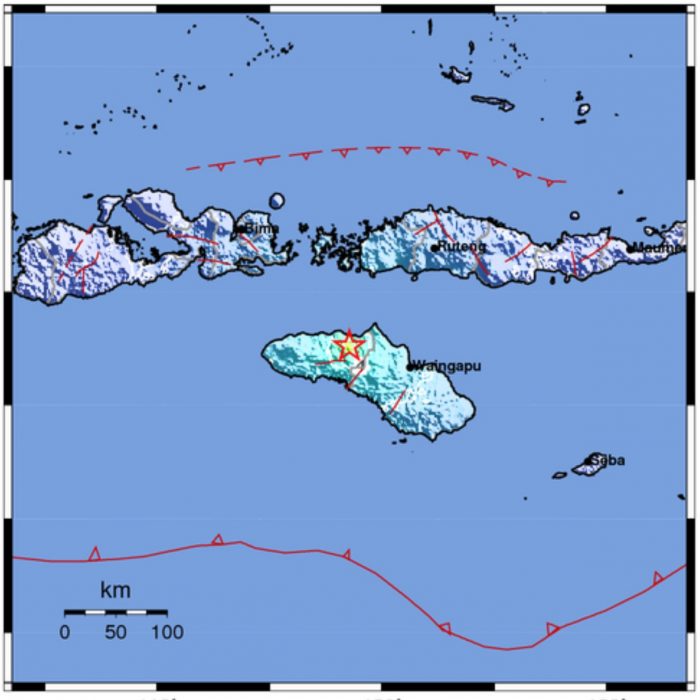Oleh: Asri Supatmiati
TRAGEDI Tajudin “cobek” rupanya masih berlanjut. Setelah bebas dari penjara, Tajudin ternyata tidak begitu saja bisa menghirup udara bebas. Ini karena setelah dinyatakan bebas atas keputusan hakim PN Tangerang, pihak kejaksaan melakukan kasasi atas vonis tersebut. Upaya kasasi Jaksa ini, menurut Tadjudin membebani dan memberikan ketidakadilan terhadap diri dan keluarganya
Tajudin tidak ada niat atau melakukan pemaksaan terhadap dua keponakannya untuk menjual cobek tersebut. Secara polos, Tajudin mengatakan, dirinya buta terhadap adanya pasal atau aturan hukum terkait eksploitasi terhadap anak (beritasumut.com, 27/1/17).
Seperti diketahui, Polres Tangsel menangkap dan menjebloskan Tajudin ke tahanan pada April 2016. Waktu itu ia dibantu CN (14), DD(15) dan MS (15) yang masih kerabat dekatnya saat berjualan. Setelah 9 bulan diproses dan Tajudin dipenjara, pada 14 Januari 2017 Tajudin divonis bebas oleh PN Tangerang.
Ambigu UU Anak
UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah yang belum genap 18 tahun. Itu merujuk pada dunia Barat melalui lembaga kepanjangan tangan ideologi kapitalis sekuler, yakni PBB-UNICEF. Entah apa dasar penetapannya, yang jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, batasan anak dan dewasa adalah baligh. Kalau sudah baligh, wajib memikul tanggung jawab seperti orang dewasa.
Batasan anak 18 tahun itu, kerap memakan korban. Misalnya, anak seorang ustad terkenal yang menikah usia 17 tahun, disorot. Dianggap masih kanak-kanak. Padahal sudah punya penghasilan sendiri. Siap lahir batin dan mental membentuk keluarga. Karena, menikah itu bukan soal usia.
Termasuk kasus Tajudin yang dianggap mempekerjakan anak-anak. Padahal ponakannya itu ikut karena membantu orangtuanya mencari nafkah. Seharusnya, yang dilakukan pemerintah bukan menangkap Tajudin, melainkan mengentaskan anak-anak itu, mengapa tak sanggup sekolah? Mengapa –jika dianggap masih kecil– ikut berjualan? Harusnya negara malu, masih ada anak-anak usia sekolah tapi malah berjualan.
Namun demikian, sejatinya, di kalangan kelas ekonomi bawah, sangat biasa anak-anak kecil ikut membantu orangtua mencari uang. Saking sulitnya hidup. Anak petani membantu di sawah, anak pedagang membantu berjualan. Anak nelayan membantu melaut. Dan masih banyak lagi. Apanya yang salah?
Lebih dari itu, ponakan Tajudin itu, sudah 14-15 tahun. Pasti sudah baligh. Sudah tepat jika diajari cara berdikari. Apalagi mereka anak laki-laki. Tidak ada salahnya diajari berusaha mencari nafkah. Sebab, kelak mereka adalah para calon pemimpin rumah tangga. Harus bisa mandiri secara ekonomi.
Memang, seharusnya mereka bisa melanjutkan sekolahnya agar kelak bisa menata masa depannya lebih baik. Mengubah nasib diri dan keluarganya. Dan ini tanggungjawab negara. Menjamin kebutuhan dan hak-hak mereka agar bisa bersekolah. Bukan malah menangkap Tajudin yang berniat membantu mereka.
Pelajaran Mandiri
Anak zaman sekarang, banyak dikeluhkan orang tua sebagai anak yang tidak mengerti pekerjaan. Sebab, sejak kecil terbiasa dengan fasilitas serba ada. Serba dibantu. Serba mudah. Serba instan. Akhirnya tidak membentuk anak menjadi mandiri. Bahkan mentalnya labil. Meminjam istilah parenting, anak-anak sekarang produk “home service” alias serba dilayani.
Maka, jika ada anak-anak yang peduli keluarganya dengan membantu secara ekonomi, itu adalah tindakan terpuji. Belajar mandiri, itu baik. Bahkan jika mungkin, anak laki-laki itu, sejak prabaligh harus diajarkan cara mendapatkan uang.
Minimal mereka mengerti dan menghargai jerih payah mendapatkan uang. Sebab, mereka adalah calon para pencari uang. Pencair nafkah. Sehingga, ketika baligh, harus bisa mandiri. Berapa banyak saat ini, anak laki-laki yang kuliah dengan biaya sendiri? Sangat sedikit.
Dengan demikian, konsep “eksploitasi anak” itu jelas menyesatkan. Tidak selamanya anak kurang dari 18 tahun itu masih kanak-kanak. Tidak selamanya pula membantu orangtua bekerja itu adalah eksploitasi.
Lagipula, definisi eksploitasi ini juga ambigu. Tebang pilih. Mengikuti paradigma hukum di negeri ini yang selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bandingkan, anak-anak cantik-ganteng, manis-manja, molek-merona dari keturunan kaya berada. Mereka, tak sedikit yang kecil-kecil sudah menghasilkan duit puluhan juta rupiah. Misalnya dari dunia model, iklan, sinetron, film, realty show, endorse selebgram, dll.
Tapi, mereka tak pernah diusik dengan palu eksploitasi. Sebaliknya, dibangga-banggakan sebagai prestasi. Bahkan ditiru ibu-ibu seantero negeri yang bermimpi punya anak yang bisa dijadikan mesin ATM seperti itu.
Demikian pula, anak-anak pengusaha kaya, yang kecil-kecil sudah diajari jadi entrepreneur dengan berjualan, disanjung-sanjung sebagai prestasi luar biasa. Kalau ada pengusaha usia 20-an sudah menjadi miliarder, sejak kapan mereka mulai merintis usaha? Pastinya usia belasan. Ada yang memulai sejak SMP atau SMA. Apa masih dibilang anak-anak juga? Kenapa dari awal tidak dilarang saja dengan alasan eksploitasi? Kalau begitu, eksploitasi anak itu untuk anak siapa? Khusus anak miskin saja?
Di sekolah-sekolah Islam terpadu, saat ini juga menjamur konsep “market day,” di mana anak-anak diajarkan berdagang mencari uang. Bahkan di level sekolah TK pun, ada yang menjadikan “entrepreneurship” sebagai konsep unggulan. Tentu ini bukan dimaksudkan untuk mengeksploitasi anak. Tetapi dengan harapan, anak-anak kelak bisa mandiri.
Maka sungguh berlebihan jika Tajudin dijadikan tumbal untuk menegakkan UU Perlindungan Anak yang ambigu dan sarat masalah. Bahkan sudah saatnya UU tersebut ditinjau ulang, agar tidak terjadi lagi tragedi cobek yang memilukan.*
Jurnalis, penulis buku-buku Islam