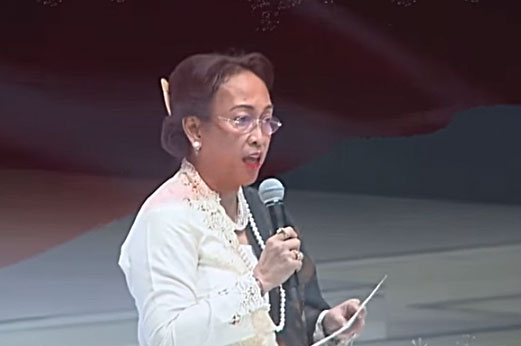ORANG-orang Barat telah semakin jauh dari fitrah mereka sebagai manusia. Oleh sebab itu, mereka menjadi sukar memahami sifat-sifat Orang Timur yang cenderung menjunjung nilai-nilai klasik. Kesulitan memahami Timur itu ditandai antara lain oleh kecenderungan mereka memberi stigma atau stempel tertentu dan dilegalisasi melalui kajian-kajian bercitra ilmiah dan disebarluaskan melalui media, sehingga menciptakan dan menularkan fobia ke seluruh pelosok dunia.
Kajian semacam ini pada dasarnya adalah produk yang didesain dalam rangka kolonialisme dengan pengetahuan sebagai alat kekuasaan, untuk memecah belah dan mengadu domba Muslim di dunia.
Kajian semacam ini pernah mendapat kritik tajam dari Edward Said dan Homi Bhabha melalui kajian antitesa terhadap Kolonialisme-Orientalisme, yang disebut dengan “Teori Poskolonial”.
Teori ini menunjuk pada segolongan kajian terhadap dampak kolonialisme terhadap masyarakat terjajah, secara fisik dan terutama mental, baik semasa maupun sesudah penjajahan berlangsung.
Di antara stigma atau stempel Barat terhadap Timur di mana Timur adalah dunia Islam, ialah stigma Wahabi. Terma ini pernah digunakan dan disebarluaskan Barat dengan sangat didukung oleh Iran (Syiah). Oleh sebagian besar masyarakat dunia yang tidak mengetahui hakikatnya, terma ini lebih dimaknai secara konotatif daripada denotatif.
Munculnya istilah “takfiri” juga makin menguat ketika munculnya kasus Syiah di Sampang, Madura. Di mana kaum Syiah menebar opini (untuk memecah kaum Sunni) dengan menyebut lawan-lawannya “Wahabi –Takfiri”.
Istilah itu mulai disampaikan Haidar Bagir, CEO Mizan dalam acara Indonesian Lawyers Club (ILC) TV One, Selasa 25 Juni 2013, saat menjadi salah satu narasumber. Belakangan, semua media Syiah (baik dari pusatnya di Iran dan Indonesia) serentak menggunakan bahasa sama, “Wahabi-Takfiri”, seolah menjadi biang anti Syiah.
Sementara kalangan NU mulai terpancing menggunakan istilah “Wahabi”. Di kalangan NU sendiri istilah ini mulai dimarakkan lagi setelah banyaknya ‘serangan-serangan’ terhadap amaliyah NU oleh seperti; ziarah kubur, tahlil dan sebagainya.
Wahabi secara konotatif awalnya diasosiasikan dengan gerakan memurnikan Islam dengan menegakkan kembali dua pedoman utama dalam Islam, ialah Al-Qur’an dan As sunnah. Sebagaimana pernah dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah di Yogya pada 1912) ia berusaha memberantas kemusyrikan berupa tahayul, bid’ah dan churafat (atau sering disingkat TBC). Juga pernah dilakukan Ahmad Hassan (Persis) di Bangil.
Namun dalam perkembangan saat ini, penyebutkan “Wahabi” saat ini lebih banyak unsur kepentingan politik. Inilah yang saat ini menjadi suatu paradoksi.
Paradoksi ini merupakan bentuk ambivalensi diametral. Berbagai bentuk sikap ambivalen seperti ini merupakan stereotip dan ciri perilaku kolonial. Akibatnya adalah tumbuhnya karakter paradoksi atau ambivalens pada si terjajah. Di mana masyarakat terjajah cenderung mengembangkan sifat terombang-ambing, gamang atau merasa serba-salah dalam sesuatu.
Paradoksi bukan hanya terjadi secara kolektif, tetapi juga menimpa individu. Nah sejatinya terdapat partentangan di sini. Apalagi pihak Barat mengnambil alih dan menghegemoni pengertian “pembaruan” Islam yang awalnya pemurnian ajaran Islam menjadi gerakan yang mengarah lebih kompromi, permisi atau baha lugasnya; liberalisme.
Ibarat pohon, sumber kekuatan itu adalah akar; ibarat bangunan, tumpuannya adalah pondasi. Sebaliknya, proses melemah menunjuk pada proses menjadi lebih rapuh, rentan atau labil, sehingga ibarat pohon, arahnya menjauh dari akar menuju pucuk daun yang mudah digoyang angin; menjauh dari pondasi menuju ujung genting yang mudah diporakporanda badai.
Berada dalam kecenderungan ini adalah gerakan-gerakan yang justru arahnya meninggalkan nilai-nilai yang mengakar atau fondasional (Barat menyebutnya nilai puritan atau konservatif), menuju nilai-nilai nilai-nilai kompromis (lugasnya: nilai-nilai liberal) yang sangat karet, dan oleh sebab itu rentan, rapuh dan labil.
Nah akhirnya jika nanti ada orang berkata imannya menguat tetapi pada saat yang sama pandangan-pandangannya cenderung liberal, boleh jadi ini merupakan stereotip karakter yang terhegemoni atau terkolonialisasi.*
Ahmad Antawirya
Penulis magister dengan konsentrasi Teori Poskolonial