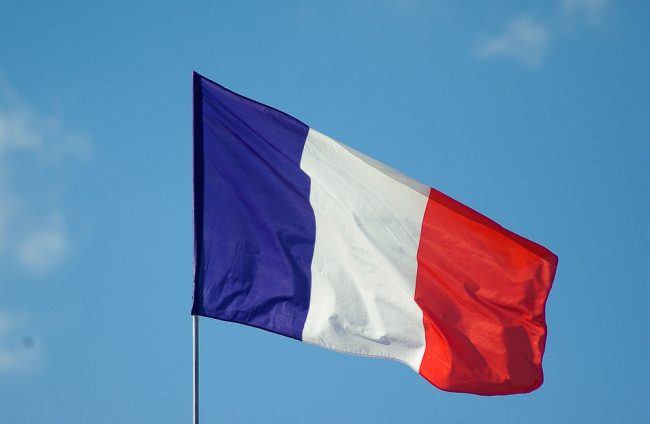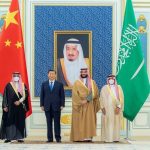Oleh: Joseph Massad
Hidayatullah.com—Prancis sedang dalam krisis. Ekstremisme radikal Prancis Kristen yang resmi dan tidak resmi, yang melegitimasi dirinya sendiri di bawah payung apa yang oleh orang Prancis disebut laicité, terus meningkatkan serangannya terhadap Muslim Prancis dan non-Prancis.
The Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) mencatat 1.043 insiden Islamofobia yang terjadi pada 2019 (meningkat 77 persen sejak 2017) – 68 serangan fisik (6,5 persen), 618 insiden diskriminasi (59,3 persen), 210 insiden ujaran kebencian dan hasutan kebencian rasial (20,1 persen), 93 insiden pencemaran nama baik (8,9 persen), 22 insiden perusakan tempat-tempat suci umat Islam (2,1 persen), dan 32 insiden diskriminasi terkait dengan pemberantasan terorisme (3,1 persen).
Orang Kristen Prancis dan apa yang disebut kebencian ‘sekuler’ terhadap Muslim adalah bagian dari pidato sehari-hari oleh pemerintah Prancis, para pakar, dan media
Orang Kristen Prancis dan apa yang disebut kebencian “sekuler” terhadap Muslim adalah bagian dari pidato sehari-hari oleh pemerintah Prancis, para pakar, dan media.
Faktanya, normalisasi ujaran kebencian terhadap Muslim tidak hanya melegitimasi diskriminasi yang dilembagakan yang dialami Muslim Prancis, tetapi juga memicu kekerasan terhadap mereka di dalam dan di luar Prancis, termasuk penembakan di masjid Brest dan penargetan terhadap imam populer Rachid Eljay pada Juni 2019 dan penyerangan Masjid Bayonne pada Oktober 2019 yang melukai empat orang.
Di luar Prancis, teroris yang melakukan pembantaian 2019 di masjid-masjid Christchurch di Selandia Baru, menewaskan 51 jamaah Muslim dan melukai 49 lainnya, menyebut teori-teori pembunuhan pemikir Islamofobia Prancis Renaud Camus yang memengaruhi tindakannya.
Pada bulan Oktober 2019, Presiden Prancis Emmanuel Macron (yang nama depannya adalah nama yang diberikan malaikat Gabriel kepada Yesus dalam Injil, yang berarti “Tuhan beserta kita”) dan Menteri Dalam Negeri saat itu Christophe Castaner (juga dinamai menurut nama Kristus sendiri) menghubungkan terorisme di Prancis untuk tanda-tanda agama dan budaya Muslim Prancis, termasuk memiliki janggut, sholat lima waktu, makan makanan halal, dll.
Ini benar-benar kebetulan bahwa presiden dan menteri dalam negerinya dinamai menurut nama Yesus Kristus, yang seharusnya tidak mengimplikasikan semua orang yang dinamai Yesus memiliki krisis dengan “Islam”, melainkan hanya beberapa dari mereka yang mengekspresikan kebencian “sekuler” anti-Muslim. .
‘Membebaskan’ Islam
Pada awal Oktober, Macron menyatakan bahwa “Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kami tidak hanya melihat ini di negara kami”. Dia menambahkan bahwa dia berusaha untuk “membebaskan” Islam di Prancis dari pengaruh asing dengan meningkatkan pengawasan pembiayaan masjid.
Tapi Macron bukanlah penguasa Prancis pertama yang ingin “membebaskan” Islam.
Ini adalah tradisi “sekuler” Prancis kuno. Ketika Napoleon Bonaparte menginvasi Mesir dan Palestina pada tahun 1798, rencana cerdiknya adalah berbohong kepada orang Mesir dengan mengumumkan bahwa dia dan pasukannya adalah “Muslim yang setia” dan bahwa mereka datang untuk membebaskan Muslim dan Islam dari tirani Mamluk.
Penipuannya tidak berhasil dan orang Mesir bangkit melawannya seperti yang dilakukan orang Palestina. Dia kembali dalam kekalahan ke Prancis setelah pasukannya melakukan kekejaman yang tak terhitung di Mesir dan Palestina.
Krisis Napoleon dan Prancis dengan Islam dua abad lalu adalah ketika mereka dikalahkan di kota Acre di Palestina. Tiga dekade kemudian, ketika Prancis menginvasi Aljazair, Prancis tidak perlu lagi berbohong kepada Muslim untuk menaklukkan, merampok, dan menghancurkan tempat ibadah mereka.
Casus belli resmi yang digunakan Raja Charles X untuk membenarkan invasi ke Aljazair pada tahun 1830 adalah penolakan Prancis untuk membayar hutangnya atas biji-bijian yang telah disuplai oleh pedagang Aljazair kepada tentara Prancis Napoleon selama Kampanye Italia di bawah Republik Pertama. Mengingat fakta bahwa para pedagang Aljazair berasal dari keluarga bankir Yahudi Livorno di Bacri dan Busnac, debat publik pada saat itu di Prancis memiliki “tenor antisemit”.
Ironisnya, ini adalah Raja Charles yang sama yang pada tahun 1825 memaksa budak-budak Haiti yang dibebaskan, yang revolusinya menggulingkan kolonialisme dan perbudakan Prancis, untuk membayar jutaan sebagai ganti rugi atas hilangnya properti mantan tuan Prancis kulit putih mereka yang telah memperbudak mereka dengan imbalan diplomatik Prancis, pengakuan dan mencabut blokade hukumannya di Haiti.
Pada tahun 1827, Hussein Dey, penguasa Ottoman Aljazair, menuntut pembayaran hutang dari konsul Perancis, Pierre Deval, yang dengan kasar menolaknya. Marah dengan penghinaan konsul, Dey memukulnya dengan kocokan lalat (apa yang orang Prancis sebut sebagai insiden kudeta) – dan menyebutnya “bajingan jahat, tidak setia, pemuja berhala”.
Menyerang Aljazair
Invasi diluncurkan pada pertengahan Juni 1830 dan Aljazair jatuh pada 5 Juli. Prancis yang berjuang secara finansial merampok harta Aljazair, mencuri lebih dari 43 juta Franc dalam bentuk emas dan perak, selain dari jumlah yang hilang dan yang dihabiskan untuk tentara pendudukan Prancis.
Mungkin negara-negara miskin Afrika Barat yang terus berhutang budi kepada Prancis saat ini harus membuktikan betapa berasimilasi mereka ke dalam bahasa Prancis dengan menginvasi Prancis untuk merampok perbendaharaannya.
Tentara Prancis yang menaklukkan mengambil alih masjid dan mengubahnya menjadi gereja dan katedral dengan todongan senjata
Tujuan langsung dari invasi itu, sebagaimana Charles menyebutkannya di majelis nasional Prancis pada tanggal 2 Maret, adalah untuk membalas dendam kepada Prancis atas penghinaan Aljazair, “mengakhiri pembajakan dan merebut kembali Aljazair untuk Kekristenan”.
Sejalan dengan komitmen Kristen Prancis, tentara Prancis yang menaklukkan mengambil alih masjid dan mengubahnya menjadi gereja dan katedral di bawah todongan senjata, termasuk masjid Utsmani Ketchaoua terbesar di Aljazair, dibangun pada 1612, yang diubah menjadi Katedral St Philippe pada Desember 1832.
Pada tahun yang sama, Prancis memusnahkan seluruh suku Ouffias, tidak menyisakan wanita atau anak-anak, dan merebut semua harta benda mereka.
Tidak seperti kebencian dan rasisme terhadap kaum Muslim, pada awal tahun 1840-an, pemikir terkenal Prancis Alexis de Toqueville menyatakan dalam hal ini bahwa “adalah mungkin dan perlu bahwa ada dua perangkat hukum di Afrika, karena kita dihadapkan pada dua masyarakat yang jelas terpisah. Ketika seseorang berurusan dengan orang Eropa [kolonial-pemukim di Afrika], sama sekali tidak ada yang menghalangi kita untuk memperlakukan mereka seolah-olah mereka sendirian; hukum yang berlaku untuk mereka harus diterapkan secara eksklusif kepada mereka.”
Dia keberatan dengan lemahnya hati yang menentang barbarisme Prancis dan penggunaan blitzkrieg (yang mereka sebut “razzias”) terhadap penduduk Aljazair. “Saya sudah sering mendengar laki-laki yang saya hormati, tetapi dengan siapa saya tidak setuju, menganggap salah bahwa kita membakar hasil panen, bahwa kita mengosongkan silo, dan akhirnya kita menangkap laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersenjata. Ini, menurut saya, adalah kebutuhan yang disesalkan, tetapi yang wajib diserahkan oleh setiap orang yang ingin berperang terhadap orang Arab. Dan, jika saya harus mengutarakan pikiran saya, tindakan-tindakan ini tidak memberontak saya lebih atau bahkan sebanyak beberapa orang lain bahwa hukum perang jelas memberi wewenang dan yang terjadi di semua perang di Eropa.”
Barbarisme Prancis
Pada tahun 1871, Muslim Aljazair memberontak lagi melawan pemerintahan Prancis, dengan 150.000 orang bergabung dengan pasukan pemimpin Kabyle setempat, Al-Muqrani.
Mesin genosida Prancis merespons dengan membunuh ratusan ribu orang, yang dikombinasikan dengan kematian akibat kelaparan yang disebabkan oleh Prancis pada akhir tahun 1860-an, mengakibatkan kematian satu juta orang Aljazair (sekitar sepertiga dari populasi).
Prancis menghancurkan lusinan kota dan desa hingga rata dengan tanah sambil membunuh masyarakat Aljazair. Tetapi bahkan itu tidak menyelesaikan “krisis” Prancis dengan Islam.
Pada tahun 1901, kekhawatiran Prancis tentang “krisis” mereka dengan Islam meningkat. Ini terutama terjadi karena Prancis, yang “sedang dan akan menjadi semakin dan tidak diragukan lagi kekuatan Muslim yang besar”, mengingat akuisisi koloni baru dengan populasi Muslim yang besar, perlu mengetahui seperti apa Islam di abad ke-20.
Hal ini menjadi keprihatinan yang begitu besar sehingga “pencarian” kolonial akan pengetahuan dikeluarkan. Editor jurnal penting kolonial Prancis Questions diplomatiques et koloniales, Edmond Fazy, mulai menyelidiki pertanyaan tentang “Masa Depan Islam” pada tahun 2000.
Masa Depan Islam
Tidak seperti banyak orang Kristen Prancis yang Islamofobia saat ini, Fazy khawatir tentang peningkatan dan jumlah Muslim yang tidak dilaporkan di seluruh dunia (dia mengutip angka 300 juta, yang merupakan seperlima dari populasi dunia) dan penyebaran agama “sederhana” mereka ke Afrika.
Prancis terus tenggelam dalam wacana dominan chauvinisme dan kebencian saat ini yang tidak berbeda dengan yang selalu mendominasi budaya Prancis. Banyak kontributor di jurnalnya memandang perlu untuk memanipulasi teologi Islam dan mengubah ulama Muslim untuk menghasilkan tidak hanya Islam modern yang dapat ditoleransi oleh modernitas Eropa, tetapi juga Islam yang, mereka harapkan, akan melemahkan Kesultanan Utsmaniyah.
Nasihat paling praktis, bagaimanapun, datang dari sekolah Arabis Prancis, yang dikelola oleh pemukim kolonial Prancis (pieds noirs) di Afrika Utara. Salah satunya, Edmond Doutte, dari ecole algerienne, seorang spesialis agama dan Islam, berbicara tentang pertemuannya dengan fanatisme dan intoleransi Muslim.
Muslim yang terpelajar secara tradisional tampaknya telah “menjauh dari kami” berbeda dengan pekerja asli, yang bersahabat dengan titik dua dan mempelajari “kebiasaan kami”. Daripada menekan “manifestasi agama yang dibesar-besarkan” dari Islam yang masih ada, tugas di hadapan orang Eropa lebih produktif.
“Sebaliknya, kita bisa mendukung lahirnya Islam baru yang lebih condong ke kompromi dan toleransi Eropa; untuk mendorong generasi muda ulama yang bekerja ke arah itu, dan untuk meningkatkan jumlah masjid, madrasah, dan Muslim. universitas, memastikan bahwa kami mempekerjakan mereka dengan penganut teori baru.”
Komentar Doutte sangat dikenal karena dapat dengan mudah diucapkan oleh setiap politikus atau pakar Prancis kontemporer – atau Barat lainnya – saat ini.
Adapun M William Marcais, direktur madrasah Tlemcen yang didirikan oleh Prancis untuk melatih para hakim Muslim Aljazair atas dasar “rasionalis”, dia berpihak pada Islam “baru” dan “modern” yang sedang dibentuk Prancis dan di mana dia berada. seorang peserta, sebuah Islam yang “terkait erat dengan takdir Prancis.”
Waktu Pengembalian
Proyek mengubah Islam menjadi sesuatu yang dapat ditoleransi oleh Kekristenan Eropa dan laicite Prancis terus berlangsung pada tahun 2020, tetapi dengan hasil yang tidak memuaskan sejauh menyangkut Macron, terutama karena pendanaan Prancis untuk kelompok-kelompok jihadis di Suriah sejauh ini belum menghasilkan yang dicari oleh Prancis.
Diskriminasi yang dilembagakan yang sedang berlangsung oleh negara Prancis terhadap warga Muslimnya tidak menunjukkan tanda-tanda pengurangan di bawah Macron. Prancis terus tenggelam dalam wacana dominan chauvinisme dan kebencian saat ini yang tidak berbeda dengan wacana yang selalu mendominasi budaya Prancis bahkan sebelum Revolusi Prancis.
Memang benar bahwa supremasi Kristen kulit putih yang tersebar luas dan budaya kebencian fasis di seluruh Eropa dan Amerika Serikat saat ini, yang mengingatkan pada budaya kebencian Eropa di tahun 1930-an, tidak eksklusif untuk Prancis, tetapi Prancis (tidak seperti orang Israel) unggul dalam hal mengekspresikannya dengan eufemisme minimal.
Krisis yang terus dihadapi Prancis dengan Muslim adalah krisis chauvinisme Prancis, dan penolakan supremasi kulit putih Kristen dan Prancis laic untuk mengakui bahwa negara mereka adalah kekuatan neokolonial kelas tiga dengan budaya retrograde yang dominan yang bersikeras untuk mempertahankannya. kejayaan masa lalu yang terlayani, ketika mereka perlu bertobat dari dosa genosida mereka yang meluas dari Karibia ke Asia Tenggara, ke Afrika, dan yang membunuh jutaan orang sejak akhir abad ke-18.
Apa yang perlu dilakukan orang Prancis adalah membayar kembali hutang yang mereka miliki kepada semua orang yang mereka rampok dan bunuh di seluruh dunia sejak saat itu. Hanya itu yang akan mengakhiri krisis Prancis dengan “Islam” dan dengan dirinya sendiri.*
Joseph Massad adalah Profesor Politik Arab Modern dan Sejarah Intelektual di Universitas Columbia di New York. Ia menulis artikel ini dalam bahasa Prancis untuk Middle East Eye France.